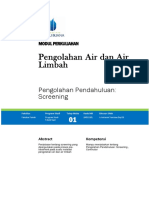Praktik Kerja Industri - SC
Praktik Kerja Industri - SC
Diunggah oleh
resa vindiJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Praktik Kerja Industri - SC
Praktik Kerja Industri - SC
Diunggah oleh
resa vindiHak Cipta:
Format Tersedia
Hak Cipta dan Hak Penerbitan dilindungi Undang-undang
Cetakan pertama, Agustus 2018
Penulis : Yulianto, S,Pd., M.Kes.
Hadi Suryono, ST. MPPM.
Pengembang Desain Intruksional : Drs. Suhartono, M.Pd.
Desain oleh Tim P2M2 :
Kover & Ilustrasi : Nursuci Leo Saputri, A.Md.
Tata Letak : Ayuningtias Nur Aisyah
Jumlah Halaman : 280
DAFTAR ISI
Halaman
BAB I: HAKIKAT PRAKTIK KERJA INDUSTRI 1
Topik 1.
Landasan Hukum Tujuan dan Ruang Lingkup ..................................................... 3
Latihan ....…………………………………………….................................................................. 6
Ringkasan ..…………………………………………................................................................... 6
Topik 2.
Bentuk Kegiatan Praktik Kerja Industri 8
Latihan ....…………………………………………….................................................................. 13
Ringkasan ..…………………………………………................................................................... 14
Topik 3.
Sistem Evaluasi dan Pelaporan …........................................................................ 15
Lampiran .…………………………………………….................................................................. 20
BAB II: PENYUSUNAN RENCANA PENGAWASAN 32
Topik 1.
Rencana Lokasi Praktik Kerja Industri ................................................................. 34
Latihan ....…………………………………………….................................................................. 37
Ringkasan ..…………………………………………................................................................... 38
Tes 1 ..……………………………..……................................................................................. 38
Topik 2.
Rencana Sasaran Praktik Sanitasi Industri 39
Latihan ....…………………………………………….................................................................. 51
Ringkasan ..…………………………………………................................................................... 52
Tes 2 ..……………………………..……................................................................................. 52
Topik 3.
Rencana Sasaran Pengawasan K3 di Industri …................................................... 53
Lampiran .…………………………………………….................................................................. 58
Praktik Kerja Industri iii
Ringkasan ..…………………………………………................................................................... 59
Tes 3 ..……………………………..……................................................................................. 59
GLOSARIUM ...................................................................................................... 60
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................. 61
BAB III: PENYUSUNAN INSTRUMEN 62
Topik 1.
Teknik Penyusunan Instrumen .......................................................................... 64
Latihan ....…………………………………………….................................................................. 76
Ringkasan ..…………………………………………................................................................... 76
Tes 1 ..……………………………..……................................................................................. 77
Topik 2.
Instrumen Pengawasan Sanitasi Industri ........................................................... 78
Latihan ....…………………………………………….................................................................. 113
Ringkasan ..…………………………………………................................................................... 113
Tes 2 ..……………………………..……................................................................................. 114
Topik 3.
Instrumen Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja …............................. 115
Lampiran .…………………………………………….................................................................. 123
Ringkasan ..…………………………………………................................................................... 123
Tes 3 ..……………………………..……................................................................................. 124
KUNCI JAWABAN TES ........................................................................................ 125
GLOSARIUM ...................................................................................................... 126
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................. 127
BAB IV: PELAKSANAAN PENGAWASAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI 129
Topik 1.
Pelaksanaan Pengawasan Sanitasi Industri ........................................................ 131
Latihan ....…………………………………………….................................................................. 147
Ringkasan ..…………………………………………................................................................... 149
Tes 1 ..……………………………..……................................................................................. 149
iv Praktik Kerja Industri
Topik 2.
Pengukuran K3 dalam Praktik Kerja Industri ...................................................... 151
Latihan ....…………………………………………….................................................................. 169
Ringkasan ..…………………………………………................................................................... 170
Tes 2 ..……………………………..……................................................................................. 171
KUNCI JAWABAN TES ........................................................................................ 172
PENILAIAN KETUNTASAN .................................................................................. 173
GLOSARIUM ...................................................................................................... 174
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................. 175
BAB V: PENGAWASAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 176
Topik 1.
Pengawasan Keselamatan Kerja ........................................................................ 177
Latihan ....…………………………………………….................................................................. 213
Ringkasan ..…………………………………………................................................................... 213
Tes 1 ..……………………………..……................................................................................. 214
Topik 2.
Pengawasan Kesehatan Kerja ............................................................................ 215
Latihan ....…………………………………………….................................................................. 223
Ringkasan ..…………………………………………................................................................... 223
Tes 2 ..……………………………..……................................................................................. 224
KUNCI JAWABAN TES ........................................................................................ 225
GLOSARIUM ...................................................................................................... 230
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................. 232
BAB VI: PELAKSANAAN EVALUASI PRAKTIK KERJA INDUSTRI 233
Topik 1.
Evaluasi Hasil Pengawasan Sanitasi Industri ....................................................... 234
Latihan ....…………………………………………….................................................................. 236
Ringkasan ..…………………………………………................................................................... 240
Tes Uraian ..............………………................................................................................. 240
Praktik Kerja Industri v
Penilaian Ketuntasan ............................................................................................... 240
Tes 1 ........................................................................................................................ 241
Topik 2.
Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko K3 Industri ............................................ 242
Latihan ....…………………………………………….................................................................. 248
Ringkasan ..…………………………………………................................................................... 249
Tes Uraian ............................................................................................................... 250
KUNCI JAWABAN TES ........................................................................................ 251
Topik 3.
Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen K3 Industri ............…............................. 253
Latihan Berpraktik .……………………………………………................................................... 266
Tes Uraian ..………………………………………................................................................... 270
KUNCI JAWABAN TES ........................................................................................ 271
GLOSARIUM ...................................................................................................... 273
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................. 274
vi Praktik Kerja Industri
Bab 1
HAKIKAT PRAKTIK KERJA INDUSTRI
Yulianto, S.Pd., M.Kes.
Hadi Suryono, ST., MPPM.
Pendahuluan
P
endidikan tenaga kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan kesehatan
secara nasional merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan Indonesia
Sehat dengan menyediakan tenaga kesehatan yang terampil. Pendidikan Tenaga
Kesehatan bertujuan menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional dalam jumlah dan jenis
yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. Untuk mewujudkan Indonesia Sehat
ditetapkan misi dan strategi yang meliputi pembangunan nasional berwawasan kesehatan
yang dilandasi pandangan baru dan paradigma sehat, profesionalisme, Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Masyarakat (JPKM) dan desentralisasi.
Keempat strategi tersebut sangat relevan dengan perkembangan yang terjadi di tanah
air kita dewasa ini. Kaitannya dengan institusi pendidikan tenaga kesehatan mempunyai
peranan yang strategis dalam menyiapkan atau mendidik tenaga kesehatan yang bermutu.
Sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pendidikan tenaga kesehatan mempunyai misi antara lain
meningkatkan kemitraan serta kemandirian institusi diknakes dalam melaksanakan
pendidikan tenaga kesehatan.
Dalam pelaksanaan pendidikan, proses pembelajaran yang terjadi tidak terbatas
didalam kelas saja. Pengajaran yang berlangsung pada pendidikan ini lebih ditekankan pada
pengajaran yang menerobos diluar kelas, bahkan diluar institusi pendidikan seperti lingkungan
kerja (industri), alam atau kehidupan masyarakat. Dalam hal ini praktik kerja industri
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem program pengajaran serta merupakan
wadah yang tepat untuk mengaplikasikan pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang diperoleh
pada proses belajar mengajar.
Industri merupakan lahan praktek sebagai sarana belajar mengajar utama untuk
mewujudkan profesionalme mahasiswa, dan juga sebagai wahana untuk meningkatkan
keterampilan secara utuh dari seorang mahasiswa yang telah mendapat pelajaran teori
dikelas atau praktek di laboratorium dan bengkel kerja.
Praktik Kerja Industri 1
Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka untuk memberikan bekal kepada Saudara
dalam upaya untuk memberikan pengalaman belajar lapangan untuk kepentingan pengajaran
keterampilan peserta didik dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah kesehatan
lingkungan di industri dalam bentuk praktIk kerja industri. Kegiatan ini diselenggarakan untuk
memenuhi tuntutan kurikulum Program Studi Diploma III Kesehatan Lingkungan. Program
tersebut tentunya akan membawa konsekuensi logis terutama dalam hal pembiayaan untuk
penyediaan lahan praktek, bahan praktek, mobilitas pembimbing akademik dan pembimbing
lapangan serta Saudara sebagai peserta program praktik kerja industri.
Bab satu yang membahas hakikat praktek kerja industri ini terdiri dari tiga topik,
meliputi:
1. Landasan hukum, tujuan dan ruang lingkup
2. Bentuk kegiatan praktek kerja industri
3. Sistim evaluasi dan pelaporan
2 Praktik Kerja Industri
Topik 1
Landasan Hukum Tujuan dan Ruang
Lingkup
S
ejalan dengan perkembangan organisasi penyelenggaraan pendidikan di bawah naungan
Badan Pengembangan dan Pendidikan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kementerian
Kesehatan RI, menimbulkan berbagai kebijakan terutama dalam upaya penyesuaian
organisasi dan tata laksana penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan. Kebijakan
tersebut antara lain adalah terbentuknya penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan
menjadi bentuk politeknik kesehatan.
Dalam kenyataannya, bentuk politeknik ini merupakan penggabungan beberapa
institusi akademi kesehatan dalam satu wadah penyelenggaraan pendidikan dengan sebutan
Politeknik Kesehatan. Dimana institusi akademi kesehatan yang semula menjadi
penyelenggara pendidikan tenaga kesehatan secara mandiri, maka dengan dibentuknya
Politeknik Kesehatan, akademi-akademi tersebut berubah statusnya menjadi sebuah jurusan
atau program studi di bawah koordinasi Direktorat Politeknik Kesehatan. Perubahan status
organisasi dan kelembagaan tersebut tentu juga akan menimbulkan perubahan dalam sistem
dan pola penyelenggaraan pendidikannya.
Satu diantara bentuk perubahan sistem dan pola penyelenggaraan pendidikan
tersebut adalah terjadinya pola penyelenggaraan praktek kerja industri, bagi semua jurusan
atau program studi termasuk Jurusan Kesehatan Lingkungan.
Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka seluruh mahasiswa Program Studi
Kesehatan Lingkungan diwajibkan mengikuti pembelajaran lapangan untuk kepentingan
pengajaran keterampilan peserta didik dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah
kesehatan lingkungan di industri dalam bentuk praktek kerja industri. Kegiatan ini
diselenggarakan untuk memenuhi tuntutan kurikulum Program Studi Diploma III Kesehatan
Lingkungan. Program tersebut tentunya akan membawa konsekuensi logis terutama dalam
hal pembiayaan untuk penyediaan lahan praktik, bahan praktik, mobilitas pembimbing
akademik dan pembimbing lapangan serta mahasiswa sebagai peserta praktik kerja industri.
Praktik Kerja Industri 3
A. LANDASAN HUKUM
Landasan hukum penyelenggaraan praktik kerja industri, disesuaikan dengan dasar
hukum yang dipakai dasar Penyusunan Kurikulum Diploma III Kesehatan Lingkungan, yaitu:
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan.
2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009, tentang Kesehatan
3. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman.Penyusunan
Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Kerja Mahasiswa.
4. Surat Keputusan Mendiknas No. 045/U/202, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 38/DIKTI/Kep/2002, tentang Rambu-Rambu
Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
6. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No 1282/D/T/2001 tanggal 27 April 2001
tentang Persetujuan Pembukaan Program studi D-III dan Pelembagaan Poltekkes di
Lingkungan Departemen Kesehatan & Kesejahteraan Sosial.
7. Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan Nomor HK.02.03/I/IV/2/04092.1/2014
tentang Kurikulum Inti Pendidikan Diploma III Kesehatan Lingkungan
B. TUJUAN
Secara umum tujuan dari praktik kerja industri adalah memberikan pengalaman
pembelajaran secara langsung kepada peserta didik untuk menerapkan bekal ilmu
pengetahuan kesehatan lingkungan sehingga dihasilkan lulusan Program Studi D-III Kesehatan
Lingkungan yang berkemampuan, mandiri dan berjiwa wirausaha, khususnya dalam upaya
pemecahan masalah sanitasi di industri dan pemecahan masalah keselamatan dan kesehatan
kerja (K3) didalam industri.
Bidang kajian mata kuliah Praktik Kerja Industri sesuai Kurikulum Inti 2014 Diploma III
Kesehatan Lingkungan, meliputi :
1. Penyusunan rencana kegiatan pengawasan kesehatan lingkungan di tempat kerja
2. Melaksanakan kegiatan kegiatan pengawasan kesehatan lingkungan di tempat kerja
3. Menganalisis dan menyimpulkan hasil pengawasan kegiatan pengawasan kesehatan
lingkungan di tempat kerja
4. Menyusun laporan kegiatan pengawasan kesehatan lingkungan di tempat kerja
Adapun tujuan secara khusus dari praktik kerja industri adalah meliputi :
1. Menyusun rencana kegiatan praktik kerja industri dalam bentuk proposal kegiatan.
2. Menyusun instrumen pengawasan praktik kerja industri.
4 Praktik Kerja Industri
3. Melakukan proses pemantauan dan penilaian di dalam dan di luar gedung pada
lingkungan kerja Industri.
4. Melakukan identifikasi terhadap bahan, peralatan, proses produksi yang memberikan
pengaruh bahaya terhadap kesehatan kerja di industri.
5. Melakukan analisis risiko terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di industri.
6. Merumuskan pengendalian faktor risiko di tempat kerja industri.
C. RUANG LINGKUP
Pengelolaan bahaya kesehatan di lingkungan kerja industri maupun pemenuhan
persyaratan kesehatan lingkungan merupakan salah satu aspek penting dalam penerapan
sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja seperti yang diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 50
Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.
Lingkungan kerja industri yang sehat merupakan salah satu faktor yang menunjang
meningkatnya kinerja dan produksi yang secara bersamaan dapat menurunkan risiko
gangguan kesehatan maupun penyakit akibat kerja. Lingkungan kerja industri harus
memenuhi standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri sebagai persyaratan
minimal yang harus dipenuhi. Standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri
terdiri atas nilai ambang batas, indikator pajanan biologi, dan persyaratan kesehatan
lingkungan kerja industri.
Standar Baku Mutu dan Persyaratan Kesehatan ditetapkan pada media lingkungan
meliputi:
1. Air,
2. Udara,
3. Tanah,
4. Pangan,
5. Sarana dan bangunan, dan
6. Vektor dan binatang pembawa penyakit.
Praktik Kerja Industri 5
Latihan
Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan
berikut!
1) Secara umum tujuan dari praktik kerja industri adalah memberikan pengalaman
pembelajaran secara langsung kepada peserta didik untuk menerapkan bekal ilmu
pengetahuan kesehatan lingkungan sehingga dihasilkan lulusan Program Studi D-III
Kesehatan Lingkungan yang berkemampuan, mandiri dan berjiwa wirausaha, khususnya
dalam bidang apa....
2) Bidang kajian mata kuliah Praktik Kerja Industri sesuai Kurikulum Inti 2014 Diploma III
Kesehatan Lingkungan, meliputi apa saja....
3) Lingkungan kerja industri yang sehat merupakan salah satu faktor yang menunjang
meningkatnya kinerja dan produksi yang secara bersamaan dapat menurunkan risiko
gangguan kesehatan maupun penyakit akibat kerja. Lingkungan kerja industri harus
memenuhi standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri sebagai
persyaratan minimal yang harus dipenuhi. Standar dan persyaratan kesehatan
lingkungan kerja industri terdiri atas apa saja....
Ringkasan
1. Salah satu perubahan sistem dan pola penyelenggaraan pendidikan pada Prodi D-III
Kesehatan Lingkungan sesuai dengan perkembangan kurikulum adalah terjadinya pola
penyelenggaraan praktik kerja industri. berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka
seluruh mahasiswa Program Studi Kesehatan Lingkungan diwajibkan mengikuti
pembelajaran lapangan untuk kepentingan pengajaran keterampilan peserta didik
dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah kesehatan lingkungan di industri
dalam bentuk praktik kerja industri. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memenuhi
tuntutan kurikulum Program Studi Diploma III Kesehatan Lingkungan. Program tersebut
tentunya akan membawa konsekuensi logis terutama dalam hal pembiayaan untuk
penyediaan lahan praktik, bahan praktik, mobilitas pembimbing akademik dan
pembimbing lapangan serta mahasiswa sebagai peserta praktik kerja industri.
2. Secara umum tujuan dari praktik kerja industri adalah memberikan pengalaman
pembelajaran secara langsung kepada peserta didik untuk menerapkan bekal ilmu
pengetahuan kesehatan lingkungan sehingga dihasilkan lulusan Program Studi D-III
6 Praktik Kerja Industri
Kesehatan Lingkungan yang berkemampuan, mandiri dan berjiwa wirausaha, khususnya
dalam upaya pemecahan masalah sanitasi di industri dan pemecahan masalah
keselamatan dan kesehatan kerja (K3) didalam industri. Adapun tujuan secara khusus
dari praktik kerja industri adalah meliputi :
a. Menyusun rencana kegiatan praktik kerja industri dalam bentuk proposal kegiatan.
b. Menyusun instrumen pengawasan praktik kerja industri.
c. Melakukan proses pemantauan dan penilaian di dalam dan di luar gedung pada
lingkungan kerja industri.
d. Melakukan identifikasi terhadap bahan, peralatan, proses produksi yang
memberikan pengaruh bahaya terhadap kesehatan kerja di industri.
e. Melakukan analisis risiko terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di
industri.
f. Merumuskan pengendalian faktor risiko di tempat kerja industri.
3. Standar Baku Mutu dan Persyaratan Kesehatan ditetapkan pada media lingkungan
meliputi:
a. Air,
b. Udara,
c. Tanah,
d. Pangan,
e. Sarana dan bangunan, dan
f. Vektor dan binatang pembawa penyakit.
Praktik Kerja Industri 7
Topik 2
Bentuk Kegiatan Praktik Kerja Industri
ata kuliah praktik kerja industri membahas tentang penyusunan rencana kegiatan
M pengawasan kesehatan lingkungan di tempat kerja, melaksanakan kegiatan
pengawasan kesehatan lingkungan di tempat kerja, menganalisis dan menyimpulkan
hasil pengawasan kegiatan pengawasan kesehatan lingkungan di tempat kerja, dan
menyusun laporan kegiatan pengawasan kesehatan lingkungan di tempat kerja.
ALUR PRAKTIK KERJA INDUSTRI
Menyiapkan kebutuhan awal:
MULAI 1. Menyiapkan tempat praktek
2. Menyiapkan surat ijin
3. Menyusun proposal
4. Menyusun instrumen
Menyampaikan Surat ijin
Diterima Ditolak
Mengikuti Pembekalan praktek
Menghadap pihak industry
komunikasi rencana pelaksanaan
praktekum
Pembimbing Proses
lapangan menilai Melakukan Pengawasan sanitasi penyusunan draf
unjuk kerja industry & K3 laporan
mahasiswa
Membandingkan hasil pengawasan dengan
standar baku mutu atau NAB
Membahas dan menyimpulkan hasil praktek
Menyelesaikan laporan akhir Nilai
akhir
8 Praktik Kerja Industri
A. BEBAN BELAJAR
Beban belajar mata kuliah praktik kerja industri sebesar 2 SKS dengan pengalaman
belajar berupa praktik lapangan, sehingga lama penyelenggaraan praktik kerja industri dapat
dihitung sebagai berikut :
2 SKS x 170 menit x 14 tatap muka = 4.760 menit = 79,33 jam
Apabila dalam satu hari menggunakan waktu efektif 7 jam, maka diperlukan 12 hari
efektif.
B. BENTUK KEGIATAN
Kegiatan praktik kerja industri terdiri dari beberapa tahap yang dilaksanakan secara
berurutan sebagai berikut:
1. Pembekalan
2. Penyusunan rencana kegiatan
3. Penyusunan instrumen
4. Pelaksanaan penilaian atau pengawasan
5. Evaluasi hasil penilaian
6. Pembuatan laporan
Adapun rincian kegiatan dari masing-masing tahapan pelaksanaan kegiatan praktik kerja
industri dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Pembekalan
Tujuan pembekalan adalah memberikan pemahaman pelaksanaan praktik kerja industri,
menyiapkan mahasiswa agar mampu bekerjasama dengan pihak tempat atau lahan praktik,
mengenal masalah sanitasi di industri, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja ditempat
praktik dan proses pemecahannya.
Materi Pembekalan dalam rangka persiapan pelaksanaan praktik kerja industri
mahasiswa Program Studi D-III Kesehatan Lingkungan meliputi :
a. Pengarahan secara umum.
b. Teknis pelaksanaan praktik.
c. Teknis penyusunan laporan.
d. Sistim evaluasi.
Praktik Kerja Industri 9
2. Penyusunan Rencana Kegiatan
Dalam penyusunan rencana kegiatan praktik kerja industri mahasiswa diwajibkan
membuat proposal kegiatan yang berisi urutan kegiatan yang terdiri dari:
a. Pendahuluan
b. Tujuan
c. Manfaat
d. Jenis kegiatan praktik kerja industri
e. Waktu atau jadwal pelaksanaan
f. Lokasi praktik
g. Peserta praktik kerja industri
h. Pembimbing praktik
i. Biaya pelaksanaan
j. Pengesahan proposal
3. Penyusunan Instrumen
Dalam kegiatan penyusunan instrumen mahasiswa diwajibkan menyusun seluruh
instrumen penilaian sanitasi industri dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai dengan
substansi materi pada mata kuliah terkait yang diperoleh selama perkuliahan termasuk
perhitungan atau skoring sehingga bisa didapatkan hasil akhir penilaian. Adapun mata kuliah
yang terkait dengan praktik kerja industri adalah :
a. Penyediaan air bersih dan air minum
b. Pengelolaaan limbah cair
c. Penyehatan tanah dan pengelolaan sampah
d. Penyehatan makanan dan minuman
e. Penyehatan udara
f. Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit
g. Sarana dan prasarana bangunan
h. Housekeeping atau tata graha
i. Penerapan K3 dan SMK3
j. Ergonomi
4. Pelaksanaan Penilaian atau Pengawasan
Pelaksanaan penilaian atau pengawasan praktik kerja industri dilakukan berdasarkan
instrumen yang telah disusun. Untuk melaksanakan kegiatan ini mahasiswa dituntut
menguasai kompetensi seluruh mata kuliah terkait khususnya yang berkaitan dengan industri
lahan praktik. Jenis kegiatan yang dilakukan menggunakan metode wawancara, observasi,
10 Praktik Kerja Industri
pengukuran terhadap objek yang dinilai. Kegiatan dalam pelaksanaan praktik kerja industri
tidak hanya melaksanakan tugas-tugas pembelajaran dari akademik saja, tetapi juga tugas-
tugas lain yang diberikan oleh industri lokasi praktik.
5. Evaluasi hasil penilaian
Hasil penilaian dan pengukuran yang sudah dilakukan, selanjutnya dilakukan evaluasi
atau analisis dengan cara membandingkan antara hasil penilaian dan pengukuran dengan
standar yang berlaku sesuai dengan bidang kajian, meliputi :
a. Penyediaan air bersih dan air minum
b. Pengelolaaan limbah cair
c. Penyehatan tanah dan pengelolaan sampah
d. Penyehatan makanan dan minuman
e. Penyehatan udara
f. Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit
g. Sarana dan prasarana bangunan
h. Housekeeping / tata graha
i. Penerapan K3 dan SMK3
j. Ergonomi
6. Pembuatan laporan
Kegiatan terakhir dari praktik kerja industri adalah berupa pembuatan laporan. Laporan
kegiatan praktik kerja industri disusun sebagai bukti bahwa seorang mahasiswa telah selesai
melaksanakan kegiatan praktik kerja industri. Sistimatika laporan kegiatan praktik kerja
industri disusun dengan sistimatika yang telah ditetapkan sebagaimana pada lampiran.
Laporan kegiatan praktik kerja industri ini selanjutnya juga akan dijadikan sebagai bahan ujian
sebagai bagian dari sistem penilaian pelaksanaan praktik kerja industri.
C. ORGANISASI PELAKSANAAN
Kegiatan praktik kerja industri dilaksanakan oleh unsur dosen dari mata kuliah praktik
kerja industri, dosen selain dari mata kuliah praktik kerja industri dan unsur akademik lain
yang tergabung dalam suatu kepanitiaan praktik kerja industri, yang dibentuk dan ditetapkan
oleh Direktur Poltekkes Kemenkes.
Praktik Kerja Industri 11
D. PESERTA PRAKTIK KERJA INDUSTRI
Peserta praktik kerja industri adalah mahasiswa Semester VI kelas Reguler dan/atau
mahasiswa Semester 2 kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau. Daftar mahasiswa yang akan
melaksanakan kegiatan praktik kerja industri dicantumkan dalam lampiran Surat Keputusan
Direktur tentang pelaksanaan kegiatan praktik kerja industri.
E. KRITERIA LAHAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI
Agar diperoleh pengalaman belajar yang komprehensif dalam melaksanakan kegiatan
praktik kerja industri, maka diperlukan kriteria lahan praktik yang dapat dijadikan sebagai
lokasi pelaksanaan praktik kerja industri sebagai berikut:
1. Memiliki organisasi P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja), atau
2. Memiliki tenaga kerja minimal 50 (lima puluh) orang, atau
3. Mempunyai tingkat risiko sedang sampai dengan tingkat risiko sangat tinggi, sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015.
F. PEMBIMBING PRAKTIK KERJA INDUSTRI
Dalam mengikuti kegiatan praktIk kerja industri, para mahasiswa memperoleh
bimbingan dari (1) Pembimbing Akademik dan (2) Pembimbing Lapangan.
1. Pembimbing Akademik
Pembimbing akademik dalam kegiatan praktIk kerja industri adalah dosen pengampu
mata kuliah praktIk kerja industri atau tenaga fungsional dosen lainnya, pengelola program
praktIk kerja industri yang ditunjuk.
Pembimbing akademik berperan sebagai supervisor dalam kegiatan praktik kerja
industri, yang mempunyai tugas :
a. Mempersiapkan kegiatan praktik kerja industri, memfasilitasi dan membimbing
mahasiswa sesuai substansi mata kuliah terkait, bersama-sama dengan tim pembimbing
lapangan memfasilitasi pemecahan masalah yang dihadapi mahasiswa di lapangan,
menyelesaikan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan praktik kerja industri.
b. Memberikan arahan dan bimbingan teknis dan administratif (Penyusunan Laporan)
kepada mahasiswa sehingga mereka mampu mencapai tujuan praktik secara optimal.
12 Praktik Kerja Industri
c. Wewenang pembimbing akademik (dosen pengampu mata kuliah) adalah memberikan
penilaian kepada mahasiswa pada ujian lisan dan laporan sesuai kriteria yang telah
ditetapkan (terlampir).
2. Pembimbing Lapangan :
Pembimbing lapangan praktik kerja industri adalah praktisi atau karyawan dari industri
lokasi praktik, yang bertanggung jawab atau menangani program atau kegiatan sanitasi
industri dan atau penanggung jawab kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja. Pembimbing
lapangan bertugas memberikan bimbingan kepada mahasiswa dan memfasilitasi praktik
dengan membuka akses data, informasi, kebijakan setempat, serta memfasilitasi kegiatan
yang berhubungan dengan karyawan industri dan lembaga setempat, sehingga mahasiswa
mampu mencapai tujuan praktek secara maksimal.
Kewenangan pembimbing lapangan adalah memberikan penilaian berbagai aspek yang
berkaitan dengan unjuk kerja atau kinerja mahasiswa di lapangan yang menyangkut aspek:
pemahaman atau prakarsa, aktivitas atau keaktifan, dan hasil kerja (capaian kegiatan).
Penilaian pelaksanaan praktik kerja industri oleh pembimbing lapangan menggunakan
formulir terlampir.
Latihan
Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan
berikut!
1) Mata kuliah praktik kerja industri membahas tentang penyusunan rencana kegiatan
pengawasan kesehatan lingkungan di tempat kerja, melaksanakan kegiatan pengawasan
kesehatan lingkungan di tempat kerja, menganalisis dan menyimpulkan hasil
pengawasan kegiatan pengawasan kesehatan lingkungan di tempat kerja, dan
menyusun laporan kegiatan pengawasan kesehatan lingkungan di tempat kerja. Apa saja
yang harus Saudara persiapkan sebelum pelaksanaan kuliah praktik kerja industri....
2) Kegiatan praktik kerja industri terdiri dari beberapa tahap yang dilaksanakan secara
berurutan. Bagaimanakah urutan kegiatan yang harus Saudara laksanakan dalam
pelaksanaan perkuliahan praktek kerja industri tersebut....
3) Sebelum melaksanakan perkuliahan praktik kerja industri mahasiswa diwajibkan
menyusun instrumen penilaian sanitasi industri dan keselamatan dan kesehatan kerja
(K3) sesuai dengan substansi materi. Adapun substansi materi yang terkait dengan
praktik kerja industri, meliputi apa saja....
Praktik Kerja Industri 13
Ringkasan
1. Salah satu perubahan sistem dan pola penyelenggaraan pendidikan pada Prodi D-III
Kesehatan Lingkungan sesuai dengan perkembangan kurikulum adalah terjadinya pola
penyelenggaraan praktik kerja industri. berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka
seluruh mahasiswa Program Studi Kesehatan Lingkungan diwajibkan mengikuti
pembelajaran lapangan untuk kepentingan pengajaran keterampilan peserta didik
dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah kesehatan lingkungan di industri
dalam bentuk praktik kerja industri. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memenuhi
tuntutan kurikulum Program Studi Diploma III Kesehatan Lingkungan. Program tersebut
tentunya akan membawa konsekuensi logis terutama dalam hal pembiayaan untuk
penyediaan lahan praktik, bahan praktik, mobilitas pembimbing akademik dan
pembimbing lapangan serta mahasiswa sebagai peserta praktik kerja industri.
2. Secara umum tujuan dari praktik kerja industri adalah memberikan pengalaman
pembelajaran secara langsung kepada peserta didik untuk menerapkan bekal ilmu
pengetahuan kesehatan lingkungan sehingga dihasilkan lulusan Program Studi D-III
Kesehatan Lingkungan yang berkemampuan, mandiri dan berjiwa wirausaha, khususnya
dalam upaya pemecahan masalah sanitasi di industri dan pemecahan masalah
keselamatan dan kesehatan kerja (K3) didalam industri. Adapun tujuan secara khusus
dari praktik kerja industri adalah meliputi :
a. Menyusun rencana kegiatan praktik kerja industri dalam bentuk proposal kegiatan.
b. Menyusun instrumen pengawasan praktik kerja industri.
c. Melakukan proses pemantauan dan penilaian di dalam dan di luar gedung pada
lingkungan kerja industri.
d. Melakukan identifikasi terhadap bahan, peralatan, proses produksi yang
memberikan pengaruh bahaya terhadap kesehatan kerja di industri.
e. Melakukan analisis risiko terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di
industri.
f. Merumuskan pengendalian faktor risiko di tempat kerja industri.
3. Standar Baku Mutu dan Persyaratan Kesehatan ditetapkan pada media lingkungan
meliputi:
a. Air,
b. Udara,
c. Tanah,
d. Pangan,
e. Sarana dan bangunan, dan
f. Vektor dan binatang pembawa penyakit.
14 Praktik Kerja Industri
Topik 3
Sistem Evaluasi dan Pelaporan
A. EVALUASI PRAKTIK KERJA INDUSTRI
Evaluasi ini bertujuan untuk menilai prestasi akademik mahasiswa terkait kompetensi
yang dimiliki setelah melakukan praktik kerja industri. Penilaian yang dilakukan terhadap
mahasiswa peserta praktik kerja industri dilakukan selama pelaksanaan kegiatan praktik,
penilaian terhadap laporan kegiatan praktik yang disusun, dan penilaian melalui ujian lisan
terhadap peserta kegiatan praktik kerja industri.
Adapun komponen dan pembobotan dalam penilaian pelaksanaan praktik kerja industri
tersebut terdiri dari:
1. Penilaian unjuk kerja (bobot 4)
2. Penilaian laporan praktek (bobot 2)
3. Penilaian ujian lisan (bobot 4)
Berdasarkan komponen penilaian di atas, maka dapat dilakukan penetapan nilai akhir
dari pelaksanaan kegiatan praktik kerja industri sebagai berikut :
(𝟒 × 𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑼𝒏𝒋𝒖𝒌 𝑲𝒆𝒓𝒋𝒂) ÷ (𝟐 × 𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑳𝒂𝒑𝒐𝒓𝒂𝒏) ÷ ( 𝟒 × 𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑼𝒋𝒊𝒂𝒏 𝑳𝒊𝒔𝒂𝒏)
𝑵𝑨 =
𝟏𝟎
Adapun rincian dari masing-masing komponen penilaian terhadap mahasiswa peserta
praktik kerja industri tersebut diatas dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:
1. Penilaian Unjuk Kerja (Bobot 4)
Tahap ini merupakan tahap penilaian prestasi mahasiswa selama pelaksanaan praktik
kerja industri. Penilaian ini diberikan oleh pembimbing lapangan yang didasarkan pada
masing-masing aspek penilaian sebagai berikut :
a. Aktivitas atau keaktifan (bobot 3)
Aspek ini dapat diindikasikan dengan kehadiran, sikap, disiplin, semangat kerja dan kerja
sama. Kisaran nilai yang digunakan adalah 40 sampai dengan 100.
b. Pemahaman atau Prakarsa (bobot 4)
Praktik Kerja Industri 15
Aspek ini memperhatikan kemampuan mahasiswa dalam mengerjakan tugas-tugas
selama melaksanakan praktik kerja industri dan komponen ini merupakan cerminan
penguasaan teori dan ketrampilan yang terintegrasi. Sehingga pemahaman atau prakarsa atas
kegiatan yang dilaksanakan dapat menggambarkan kemampuan mahasiswa dalam
melaksanakan kegiatan praktek kerja industri. Kisaran nilai yang digunakan adalah 40 sampai
dengan 100.
c. Hasil kerja (bobot 3)
Aspek hasil kerja ini dapat ditunjukkan dengan kemampuan peserta didik atau
mahasiswa dalam menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan secara tuntas, disamping juga
didasarkan atas jumlah atau volume kegiatan yang dapat diselesaikan. Kisaran nilai yang
digunakan adalah 40 sampai dengan 100.
(𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 × 𝑩𝒐𝒃𝒐𝒕)
𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑼𝒏𝒋𝒖𝒌 𝑲𝒆𝒓𝒋𝒂 = ∑
𝟏𝟎
2. Penilaian Laporan Praktik (Bobot 2)
Komponen ini memperhatikan kemampuan mahasiswa dalam mengungkapkan kembali
secara tertulis atas hasil kegiatan secara sistematis sesuai dengan kaidah tata cara
penyusunan laporan yang dibakukan oleh instititusi berupa petunjuk penyusunan laporan
praktik kerja industri. Penilaian ini diberikan oleh pembimbing akademik (Tim dosen
pengampu mata kuliah). Aspek penilaian komponen laporan terdiri dari:
a. Sistematika penulisan (bobot 3)
Kisaran nilai yang digunakan adalah 40 sampai dengan 100.
b. Kesinambungan antar alenia (bobot 3)
Kisaran nilai yang digunakan adalah 40 sampai dengan 100.
c. Kesesuaian: masalah, tujuan, jenis kegiatan, pembahasan dan kesimpulan serta saran
yang diberikan (bobot 4)
Kisaran nilai yang digunakan 40 sampai dengan 100.
(𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 × 𝑩𝒐𝒃𝒐𝒕 )
𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑳𝒂𝒑𝒐𝒓𝒂𝒏 = ∑
𝟏𝟎
16 Praktik Kerja Industri
3. Penilaian Ujian Lisan ( Bobot 4 )
Komponen penilaian ujian lisan ini memperhatikan penguasaan mahasiswa dalam
mengungkapkan kembali terhadap hasil kegiatan dan analisis atau pembahasan secara lisan
atas pertanyaan yang diajukan oleh tim penguji. Aspek penilaian terdiri dari:
a. Kemampuan dan Ketepatan menjawab pertanyaan (bobot 4)
Kisaran nilai yang digunakan 40 sampai dengan 100.
b. Kemampuan dan ketepatan beragumentasi (bobot 4)
Kisaran nilai yang digunakan 40 sampai dengan 100.
c. Sikap selama ujian (bobot 2)
Kisaran nilai yang digunakan 40 sampai dengan 100.
(𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 × 𝑩𝒐𝒃𝒐𝒕)
𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑼𝒋𝒊𝒂𝒏 𝑳𝒊𝒔𝒂𝒏 = ∑
𝟏𝟎
B. SISTEM PELAPORAN
Sistem paporan hasil praktik kerja industri terdiri dari dua komponen yang harus
diperhatikan terkait dengan ketentuan penulisan laporan dan sistimatika penulisan laporan,
dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Ketentuan Penulisan
a. Ditulis pada kertas HVS 70 gram
b. Ukuran kertas A4
c. Ukuran huruf Arial atau Times New Roman (12)
d. Ukuran marjin :
1) Marjin atas : 4 cm
2) Marjin bawah : 3 cm
3) Marjin kiri : 4 cm
4) Marjin kanan : 3 cm
d. Penulisan halaman di kanan atas, kecuali pada Bab ditulis di tengah bawah.
e. Laporan dijilid setelah disahkan oleh pembimbing.
Praktik Kerja Industri 17
2. Sistematika Penulisan
Cover (sampul) luar
Sampul dalam
Halaman persetujuan
Biodata penyusun
Kata pengantar
Daftar isi
Daftar tabel
Daftar gambar
Daftar lampiran
Bab I Pendahuluan
A. Latar belakang
B. Tujuan
C. Waktu
D. Lokasi
Bab II Hasil
A. Gambaran Umum Industri
B. Gambaran Program Sanitasi Industri
C. Gambaran Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Bab III Pembahasan
A. Pengelolaan Sampah
1. Identifikasi Masalah
2. Penentuan Prioritas Masalah
3. Analisis Alternatif Pemecahan Masalah
4. Rencana Tindakan
5. Tindakan Intervensi
B. Penyehatan Makanan Minuman
1. Identifikasi Masalah
2. Penentuan Prioritas Masalah
3. Analisis Alternatif Pemecahan Masalah
4. Rencana Tindakan
5. Tindakan Intervensi
18 Praktik Kerja Industri
C. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
1. Identifikasi Masalah
2. Penentuan Prioritas Masalah
3. Analisis Alternatif Pemecahan Masalah
4. Rencana Tindakan
5. Tindakan Intervensi
D. Dan lain-lain
Bab IV Kesimpulan dan Saran
A. Kesimpulan
B. Saran
Daftar Pustaka
Lampiran-lampiran
Praktik Kerja Industri 19
Lampiran 1
DAFTAR PESERTA PRAKTIK KERJA INDUSTRI
PROGRAM STUDI D-III KESEHATAN LINGKUNGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES ..................................
TAHUN AKADEMIK ............ / ...........
NO NAMA MAHASISWA NIM TEMPAT, TANGGAL LAHIR L/P
20 Praktik Kerja Industri
Lampiran 2
PENILAIAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI
PROGRAM STUDI D-III KESEHATAN LINGKUNGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES ..................................
TAHUN AKADEMIK ............ / ...........
Nama Mahasiswa :
Lokasi Praktik :
NO ASPEK YANG DINILAI NILAI
1 Aktivitas (kehadiran, sikap, disiplin, semangat kerja dan kerja sama) ……..
2 Prakarsa ……..
3 Hasil Kerja ……..
Nilai Akhir ……..
Kisaran nilai: 0 - 100
………………………, ……………… .....................
Pembimbing Lapangan
……………………...............……….
Praktik Kerja Industri 21
Lampiran 3
FORMAT LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI
Cover (sampul) luar
Sampul dalam
Halaman persetujuan
Biodata penyusun
Kata pengantar
Daftar isi
Daftar tabel
Daftar gambar
Daftar lampiran
Bab I Pendahuluan
A. Latar belakang
B. Tujuan
C. Waktu
D. Lokasi
Bab II Hasil
A. Gambaran Umum Industri
B. Gambaran Program Sanitasi Industri
C. Gambaran Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Bab III Pembahasan
A. Pengelolaan Sampah
1. Identifikasi Masalah
2. Penentuan Prioritas Masalah
3. Analisis Alternatif Pemecahan Masalah
4. Rencana Tindakan
5. Tindakan Intervensi
B. Penyehatan Makanan Minuman
1. Identifikasi Masalah
2. Penentuan Prioritas Masalah
22 Praktik Kerja Industri
3. Analisis Alternatif Pemecahan Masalah
4. Rencana Tindakan
5. Tindakan Intervensi
C. Kesehatan Kerja
1. Identifikasi Masalah
2. Penentuan Prioritas Masalah
3. Analisis Alternatif Pemecahan Masalah
4. Rencana Tindakan
5. Tindakan Intervensi
D. Dan lain-lain
Bab IV Kesimpulan dan Saran
Daftar Pustaka
Lampiran-lampiran
Praktik Kerja Industri 23
Lampiran 4
(CONTOH COVER BAGIAN LUAR )
LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI
PELAKSANAAN PROGRAM SANITASI INDUSTRI DAN K3
DI PT. ................................................................................
TAHUN ....................
L
LOGO
POLTEKKES
Oleh:
..............................................................
NIM : ................................
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES ..................................
JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN .........................
PRODI D-III KESEHATAN LINGKUNGAN
TAHUN 2018
24 Praktik Kerja Industri
Lampiran 5
(CONTOH COVER BAGIAN DALAM )
LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI
PELAKSANAAN PROGRAM SANITASI INDUSTRI DAN K3
DI PT. ................................................................................
TAHUN ....................
L
LOGO
POLTEKKES
Oleh:
..............................................................
NIM : ................................
Disusun sebagai persyaratan untuk menempuh mata kuliah
Praktik Kerja Industri
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES ..................................
JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN .........................
PRODI D-III KESEHATAN LINGKUNGAN
TAHUN 2018
Praktik Kerja Industri 25
Lampiran 6
LEMBAR PERSETUJUAN
Dengan ini menerangkan bahwa Laporan Praktik Kerja Industri mahasiswa Program
Studi Diploma III Kesehatan Lingkungan Jurusan Kesehatan Lingkungan ......................
Politeknik Kesehatan Kemenkes ..........................., berjudul PELAKSANAAN PROGRAM
SANITASI INDUSTRI DAN K3 DI PT. ............................................................................
TAHUN ....................
Yang disusun oleh :
Nama Mahasiswa : ................................................
NIM : .................................
Telah disetujui dan disahkan pada tanggal …………………….
Pembimbing Lapangan Pembimbing Akademik
…………………………….................. …………………………................
NIP/NIK : …………………………. NIP : ……………………………..
Mengetahui
Ketua Tim Dosen Praktik Kerja Industri
......................................................
NIP. : .........................................
26 Praktik Kerja Industri
Lampiran 7
IDENTITAS PESERTA PRAKTIK KERJA INDUSTRI
Nama Mahasiswa : ……………………………………………………
NIM : ……………………………………………………
Alamat Rumah : ……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Nomor Telepon : ……………………………………………………
Institusi Tempat Praktik : ……………………………………………………
Nama Institusi : ……………………………………………………
Unit Kerja : ……………………………………………………
……………………………………………………
Alamat Institusi : ……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Nomor Telepon : ……………………………………………………
Pembimbing Lapangan : ……………………………………………………
Pembimbing Akademik : ……………………………………………………
............................, …....................
Peserta Praktik Kerja Industri
Foto berwarna
3 x 4 cm ………………………………..............
NIM. : ……………………………..
Praktik Kerja Industri 27
Lampiran 8
DAFTAR KEGIATAN HARIAN
PESERTA PRAKTIK KERJA INDUSTRI
Judul Praktik Kerja Industri : ...........................................................................................
Tempat Praktik : ...........................................................................................
Waktu Pelaksanaan Praktik : ...........................................................................................
Pembimbing Lapangan : ...........................................................................................
Pembimbing Akademik : ...........................................................................................
NO TANGGAL KEGIATAN PARAF
1.
2.
3.
....
dst
Pembimbing Lapangan
………………………………...................
NIP/NIK. : ……………………........
28 Praktik Kerja Industri
Lampiran 9
LEMBAR BIMBINGAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN
Nama Mahasiswa : ……………………………………………………...........................
NIM : ……………………………………………………...........................
Judul PraktIk Kerja Industri : ……………………………………………………...........................
……………………………………………………............................
……………………………………………………............................
Lokasi Praktik Kerja Industri : ……………………………………………………...........................
Pembimbing Akademik : ……………………………………………………...........................
Pembimbing Lapangan : ……………………………………………………...........................
NO TANGGAL MATERI KONSULTASI PARAF
1.
2.
3.
....
dst
Pembimbing Lapangan Pembimbing Akademik
……………………………..................... …………………………........................
NIP/NIK : …………………………...... NIP : ……………………………........
Praktik Kerja Industri 29
Lampiran 10
BLANGKO SUPERVSI
PRAKTIK KERJA INDUSTRI
MAHASISWA PRODI D- III KESEHATAN LINGKUNGAN
JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN
NAMA SUPERVISOR :…………………………………………………....
NAMA INDUSTRI : ……………………………………………………
ALAMAT / LOKASI : ……………………………………………………
PEMBIMBING AKADEMIK : .......................................................
PEMBIMBING LAPANGAN : ……………………………………………………
KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN :
1. …………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………
3. …...……………………………………………………………………………………
KEGIATAN YANG SEDANG DILAKUKAN :
1. …………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………
3. …...……………………………………………………………………………………
RENCANA KEGIATAN (AKAN DATANG) :
1. …………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………
3. …...……………………………………………………………………………………
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI :
1. …………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………
3. …...……………………………………………………………………………………
SARAN PEMECAHAN MASALAH :
1. …………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………
3. …...……………………………………………………………………………………
…………………., ………………………………..
Supervisor
(……………………………………..)
30 Praktik Kerja Industri
Lampiran 11
DOKUMENTASI
KEGIATAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI
MAHASISWA PRODI D- III KESEHATAN LINGKUNGAN
JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN
Foto kegiatan
Praktik Kerja Industri 31
Bab 2
PENYUSUNAN RENCANA
PENGAWASAN
Hadi Suryono, ST., MPPM.
Yulianto, S.Pd., M.Kes.
Pendahuluan
raktik kerja industri akan menghasilkan ketrampilan yang optimal bagi mahasiswa D.III
P Kesehatan Lingkkungan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi industri
tempat kerja praktik apabila dilakukan perencanaan dengan baik. Perencanaan yang
dibuat harus melibatkan seluruh aspek yang berkaitan dengan kegiatan persiapan dan
pelaksaaan. Aspek perencanaan sangat menentukan kualitas hasil pelaksanaan praktik kerja
industri yang dilakukan mahasiswa. Dalam ilmu manajemen aspek perencanaan menjadi
rujukan dari pelaksanaan tahap-tahap selanjutnya sehingga semua kegiatan harus merupakan
implementasi dari perencanaan yang telah dibuat.
Bab ini akan membahas tentang rencana yang harus Saudara buat dalam melaksanakan
praktek kerja di industri sesuai dengan kompetensi yang harus saudara kuasai. Perencanaan
meliputi persiapan secara administrative maupun teknis. Persiapan administratif meliputi
penyiapan surat izin praktek kerja industri, pembuatan proposal, menyampaikan surat izin,
sedangkan persiapan teknis meliputi penyiapan substansi materi yang akan digunakan dalam
kegiatan pengawasan sanitasi dan K3 industri.
Pelajarilah bab ini dengan seksama agar Saudara dapat melakukan kegiatan praktik kerja
industri secara terarah sehingga kegiatan praktik akan berjalan lancar sesuai dengan tujuan
yang ditetapkan yaitu meningkatkan kualitas lulusan D.III Kesehatan Lingkungan yang
professional dan kompeten.
Setelah mempelajari bab ini diharapkan Saudara memiliki pengalaman belajar serta
ketrampilan melakukan pengawasan sanitasi dan keselamatan dan kesehatan kerja industri
serta dapat mengembangkan kemampuan tersebut dalam menjalantugas sebagai Sanitarian
nantinya.
32 Praktik Kerja Industri
Agar kegiatan perencanaan pengawasan sanitasi industri dan K3 ini berjalan dengan
lancar dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan, maka Saudara harus belajar membuat
konsep surat-menyurat dengan baik, sedangkan untuk substansi materinya Saudara harus
mempelajari lagi dengan seksama terhadap semua materi pada mata kuliah yang berkaitan
dengan Sanitasi Industri dan K3.
Praktik Kerja Industri 33
Topik 1
Rencana Lokasi Praktik Kerja Industri
A. SURAT IZIN PRAKTIK KERJA INDUSTRI
Pembuatan surat izin praktik kerja industri merupakan salah satu kegiatan awal dalam
perencanaan praktik kerja industri. Surat izin merupakan aspek legalitas yang harus dibuat
karena menyangkut komunikasi formal antar dua institusi. Surat izin dibuat oleh bagian
administrasi akademik atas usul mahasiswa dengan mengisi blanko pengajuan surat izin yang
ditandatangani oleh dosen wali mahasiswa yang bersangkutan.
Isi surat izin diawali dengan penyampaian esensi program pembelajaran yang dikaitkan
dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa untuk mencapai kualitas lulusan D.III
yang diharapkan. Selanjutnya disampaikan permohonan untuk mendapatkan izin agar
mahasiswa diberi kesempatan melakukan program pembelajaran praktik kerja industri di
industri yang dituju. Selain itu harus dicantumkan nama dan nomor induk mahasiswa,
semester yang sedang ditempuh, dan waktu pelaksanaan kerja praktik industri. Karena surat
izin merupakan alat komunikasi formal, maka sebaiknya dicantumkan pula nomor telepon
atau ponsel contak person petugas yang bisa dihubungi apabila diperlukan komunikasi lebih
lanjut.
Untuk lebih memperjelas uraian bentuk surat ijin praktek kerja industri Saudara dapat
melihat contoh berikut ini:
34 Praktik Kerja Industri
Surabaya, tgl – bln - tahun
Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Praktik Kerja Industri
Kepada Yth.
Sdr. Pimpinan PT. Sumber Bahagia
Jl. Pencak Silat 10
Surabaya
Dalam rangka pelaksanaan kurikulum pembelalajaran mahasiswa Program Diploma III
Kesehatan Lingkungan Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes ……… salah satunya
adalah pengalaman belajar Praktik Kerja Industri yang dilaksanakan.
Praktik Kerja Industri merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa
untuk meningkatkan profesionalisme lulusan yang diharapkan, khususnya dalam hal
pengawasan sanitai dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di industri.
Berkaitan dengan hal tersebut mohon bantuan Saudara berpartisipasi dalam proses
pelaksanaan pendidikan untuk memberikan izin kepada mahasiswa kami melakukan praktik
kerja industri di institusi Saudara. Kegiatan praktik ini akan dilaksanakan pada tanggal ……..
sampai dengan ….. tahun …….
Adapun peserta Praktik Perja Industri ini, yaitu:
1. Nama : ……………………………………………………………
2. NIM : …………………………………………………………..
3. Semester/Prodi : ……………………………………………………………
Bersama ini kami lampirkan proposal kegiatan Praktik Kerja Industri. Apabila memerlukan
penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Saudara …………………………………. No. HP.
………………………………………………………………..
Atas bantuan dan kerjasamanya dibidang pendidikan, kami menyampaikan terima kasih.
KETUA JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN
POLTEKKES KEMENKES ……………………………..,
…………………………………………………………………
NIP. ………………………………………………………….
Praktik Kerja Industri 35
B. PROPOSAL PRAKTIK KERJA LAPANGAN
Proposal kegiatan merupakan bagian penting dalam memberikan penjelasan kegiatan
disampaikan kepada tempat praktik kerja industri. Dengan pembuatan proposal yang baik
diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas bagi industri tempat praktik sehingga
akan memperlancar kegiatan praktik. Pihak industri akan memahami isi kegiatan sehingga
dapat menyiapkan diri untuk mendukung kelancaran program praktik kerja industri. Persiapan
yang disiapkan industri antara lain sumber daya manusia yang akan dilibatkan sebagai
pembimbing lahan selama kegiatan berlangsung serta objek-objek yang akan dijadikan
sasaran kegiatan praktik kerja industri.
Saudara diwajibkan menyusun proposal kegiatan praktik kerja industri dengan
sistematika sebagai berikut:
1. Pendahuluan, Berisi Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat
a. Latar belakang berisi tentang pentingnya program pengawasan bagi karyawan
perusahaan untuk mendapatkan hidup sehat terhindar dari penyakit yang disebabkan
oleh faktor sanitasi lingkungan, dan terhidarnya karyawan dari adanya kecelakaan kerja
serta penyakit akibat kerja akibat faktor risiko atau hazard yang terdapat di lingkungan
kerja. Sebagai dampak akhir dari program pengawasan tersebut adalah meningkatnya
produktivitas kerja karyawan dalam rangka peningkatan hasil produksi atau profit
perusahaan.
b. Tujuan dalam proposal berisi tentang peningkatan keterampilan mahasiswa khususnya
dalam bidang pengawasan sanitasi dan K3 industri dalam rangka meningkatkan
profesionalisme kemampuan dalam tugasnya sebagai sanitarian nantinya.
c. Manfaat dalam proposal ada 2 (dua) yaitu manfaat bagi perusahaan dan bagi mahasiswa
peserta praktik kerja industri.
d. Bagi perusahaan adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, sedangkan
bagi mahasiswa adalah diperolehnya pengalaman belajar praktik kerja di industri
sebagai Sanitarian.
2. Jenis Kegiatan Praktek Kerja Industri
Praktik Kerja Industri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di industri
berupa kegiatan pengawasan sanitasi dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di industri.
Selama melakukan praktik tersebut bentuk kegiatan yang dilakukan adalah mengidentifikasi
permasalahan yang ada di industri terkait dengan menggunakan instrument pengawasan yang
sudah disusun pada saat sebelum kegiatan praktik dilaksanakan di industri. Kegiatan
selanjutnya adalah mengolah hasil identifikasi atau pengawasan dengan cara penilaian yang
sudah ditetapkan dalam instrument, kemudian membandingkan hasil kegiatan dengan NAB
36 Praktik Kerja Industri
atau standar baku mutu, menganalisis hasil kegiatan dan membuat kesimpulan yang diakhiri
dengan pembuatan laporan kegiatan.
a. Waktu atau Jadwal Pelaksanaan : adalah waktu dilaksanakannya kegiatan praktik kerja
di industri.
b. Lokasi, adalah tempat atau alamat kerja praktik industri.
c. Peserta praktik: dituliskan nama dan Nomor induk mahasiswa peserta praktik.
d. Pembimbing praktik ada dua yaitui : 1) pembimbing Lokasi praktik, dan pembimbing
akademik (dosen terkait mata kuliah).
e. Biaya praktik: dijelaskan bahwa biaya praktik adalah murni swadaya oleh mahasiswa
peserta praktik.
f. Pengesahan proposal, dilakukan oleh Pembimbing mata kuliah praktik dan diketahui
oleh Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Ketua Prodi Lokasi.
Latihan
Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan
berikut!
Untuk dapat memperdalam kemampuan Saudara dalam menyusun konsep surat izin
Praktik Kerja Industri, buatlah konsep surat izin sebagaimana contoh, dengan catatan sebagai
berikut:
1) Tujuan Surat adalah PT. Aero Catering Service
2) Jumlah Peserta 2 – 3 orang mahasiswa
3) Waktu kegiatan selama 3 minggu, tanggal pelaksanaan tentukan sendiri.
Agar Saudara lebih memahami cara pembuatan proposal, maka buatlah proposal sesuai
dengan substansi yang telah dijelaskan di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Ditulis dalam kertas ukuran A4
2) Menggunakan Font Times New Roman, ukuran 12 point
3) Judul Bab ditulis berlanjut (tidak menyambung tidak dalam halaman baru)
4) Sistematika:
a) Lembar I. Cover (berlogo Poltekkes)
b) Lembar II. Kata Pengantar
c) Lembar III dan seterusnya. Berisi:
(1) Pendahuluan, berisi : latar belakang, tujuan dan manfaat praktik kerja industri
(2) Jenis kegiatan praktik kerja industri
Praktik Kerja Industri 37
(3) Waktu atau jadwal Pelaksanaan
(4) Lokasi praktik
(5) Peserta praktik kerja industri
(6) Pembimbing praktik
(7) Biaya pelaksanaan
(8) Pengesahan proposal
Ringkasan
1. Untuk mengawali kegiatan praktik kerja industri harus dilakukan pembuatan Surat izin
dan proposal kegiatan praktik kerja industri.
2. Surat izin yang dibuat harus berisi setidaknya permohonan pelaksanaan praktik kerja
industri yang didahului dengan esensi kegiatan tersebut bagi mahasiswa sehingga
industri berkontribusi memberikan persetujuan sebagai tempat kerja praktik.
3. Dalam surat izin harus dicantumkan nomor HP (contack person) petugas yang dihubungi.
4. Pembuatan proposal kegiatan praktik kerja industri harus dibuat tidak panjang isinya
tetapi dapat menjelaskan semua keperluan dalam kegiatan praktik kerja industri,
sehingga harus menggunakan sistematika yang lengkap.
Tes 1
Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar!
1) Buatlah rekaman jenis-jenis dokumen yang disiapkan sebelum Saudara menentukan
sasaran pengawasan praktik kerja industri.
2) Buatlah contoh surat izin melakukan praktik kerja industri!
3) Susunlah persyaratan pembuatan proposal dan sistematika proposal yang Saudara buat!
38 Praktik Kerja Industri
Topik 2
Rancana Sasaran Praktik Sanitasi Industri
opik ini membahas tentang jenis-jenis sasaran yang dijadikan obyek penilaian praktik
T sanitasi industri. Topik ini terdiri dari: Sasaran pengawasan Sanitasi Industri, meliputi:
(a) Penyediaan air bersih dan air minum, (b) Pengolahan limbah cair, (c) Penyehatan
tanah adan pengelolaan sampah, (d) Penyehatan makanan dan minuman, (e)
Penyehatan udara, (f) Pengendalian vector, (g) House keeping, (h) Jamban dan peturasan, dan
(i) Fasilitas cuci tangan.
Sedangkan untuk Rencana Sasaran penerapan K3, meliputi: (a) Penerapan Manajemen
Risiko K3, (b) Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), (c)
Pengendalian Resiko.
Penjelasan mengenai sasaran pengawasan sanitasi industri dapat di jabarkan sebagai
berikut.
A. PENYEDIAAN AIR BERSIH DAN AIR MINUM (AIR UNTUK KEBUTUHAN
HYGIENE SANITASI INDUSTRI)
Sub topik ini berisi tentang bagaimana perusahaan tersebut menyediaan penyediaan air
untuk keperluan hygiene sanitasi bagi seluruh karyawan di industri tempat kerja praktik,
sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di Indonesia (Permenkes No. 70 Tahun 2016
tentang Standar Kesehatan Lingkungan Kerja Industri, atau peraturan lain yang berlaku.
Sasaran penilaian meliputi kuantitas dan kualitas air minum/air bersih/air untuk
keperluan Higenis dan sanitasi di industri. Pertarutan yang digunakan untuk penilaian adalah
diutamakan peraturan daerah terkait lokasi kerja praktik misalnya Peraturan Gubernur
(Pergub), jika tidak ada peraturan daerah maka menggunakan peraturan tingkat nasional
(misalnya Permenkes No. 70 Tahun 2016, atau peraturan sejenis tentang air minum, air
bersih/air untuk Hygiene dan Sanitasi) yang masih berlaku. Jika peraturan tingkat nasional
masih tidak ditemukan, maka menggunakan peraturan internasional.
Contoh substansi materi pengawasan air untuk kebutuhan hygiene dan sanitasi industri:
1. Sistem Penyediaan Air Bersih
a. Sumber air untuk kebutuhan hygiene dan sanitasi yang digunakan di industri
b. Kuantitas dan kualitas air untuk kebutuhan hygiene dan sanitasi industri
Praktik Kerja Industri 39
c. Sistem perpipaan air bersih harus menjamin tidak terjadinya penularan penyakit,
misalnya sambungannya tidak bocor atau terbuka, warna pipa air bersih berbeda
dengan warna pipa air kotor
2. Sistem Penyediaan Air Minum
a. Konstruksi dan tipe tempat penyediaan air minum di industri
b. Minimal satu tempat untuk setiap 50 karyawan.
c. Jika menggunakan pendingin dengan es, maka tidak boleh kontak langsung dengan air
minum.
d. Tidak boleh menyediakan minuman dalam bentuk cangkir.
e. Apabila disediakan cangkir sekali pakai, harus tersedia penampung sampahnya.
f. Perusahaan tidak boleh menyediakan tempat minum yang cara pengambilannya di
masukkan ke dalamnya.
Parameter yang digunanakan untuk penilaian air minum diantaranya:
1) Parameter fisik,
2) Parameter mikrobiologi
3) Parameter Kimia
B. PENGELOLAAN LIMBAH CAIR
Sub topik ini membahas substansi yang akan saudara gunakan dalam melakukan
pengawasan air limbah di industri. Untuk mengetahui parameter apa yang akan Saudara
gunakan untuk melakukan monitoring, pertama Saudara harus mengetahui jenis produksi
yang dihasilkan oleh industri tempat Saudara melakukan praktik. Langkah selanjutnya adalah
mencari peraturan terkait jenis-jenis parameter yang akan dinilai. Untuk memperoleh jenis
parameter tersebut Saudara harus menggunakan peraturan terbaru tentang pengelolaan
limbah industri, parameter yang harus diawasi dan nilai buangan pencemar yang
diperkenankan oleh peraturan tersebut. Saudara harus mengetahui bahwa peraturan
perundangan selalu akan berkembang terus seiring dengan perkembangan teknologi dealam
pengolahan air limbah dan bahaya limbah yang dihasilkan dari industri. Dalam melakukan
penilaian Saudara harus membuat instrument penilaian berdasarkan parameter yang
ditentukan dalam peraturan perundangan terkait. Saudara dapat menggunakan peraturan
terkait limbah industri yang berlaku ditingkat regional terlebih dahulu, misalnya Peraturan
Gubernur yang dibuat berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh tingkat nasional. Pada
saat ini peraturan tingkat nasional tentang buangan limbah industri yang berlaku adalah
40 Praktik Kerja Industri
Permen LH Nomor 5 Tahun 2014, sedangkan Permenkes 70 Tahun 2016 mengatur tentang
Sanitasi Industri.
Berikut adalah contoh kegiatan praktikum yang Saudara lakukan pada kegiatan
pengawasan pengolahan limbah industri serta item-item penilaian yang diterapkan terhadap
industri Minuman Ringan:
1. Mengidentifikasi proses produksi minuman ringan apakah dengan menggunakan
pencucian botol
2. Mengidentifikasi proses produksi minuman ringan apakah termasuk pembuatan sirup
3. Mengidentifikasi apakah perusahaan memiliki instalasi pengolahan air limbah
4. Mengukukr parameter yang perlu diukur adalah BOD5, pH, TSS, minyak dan lemak, debit
limah yang dihasilkan.
Substansi materi yang dijadikan sebagai sasaran pengawasan pengolahan air limbah
industri tergantung dari jenis produksi yang dihasilkan oleh industri tempat praktik. Saudara
dapat menentukan standar baku mutu terkait jenis produksi dari industri yang dijadikan
tempat praktik kerja.
C. PENYEHATAN TANAH DAN PENGELOLAAN SAMPAH
Sub topik ini membahas sasaran substansi materi yang akan Saudara nilai pada saat
melakukan praktik kerja industri tentang penyehatan tanah dan pengelolaan sampah industri.
Untuk mendapatkan materi ini Saudara diwajibkan mempelajari kembali materi kuliah
Penyehatan Tanah dan Pengelolaan Sampah di industri. Selain itu Saudara harus mencari
peraturan terkait pengawasan penyehatan tanah dan pengelolaan sampah di industri.
1. Penyehatan Tanah
Tanah merupakan media yang perlu mendapatkan perhatian pada saat Saudara
melakukan kerja praktik industri. Tanah bisa menjadi media penularan penyakit jika
mengandung bahan berbahaya akibat aktivitas pengelolaan faktor pencemar yang kurang
baik, misalnya pencemaran tanah oleh faktor kimia, fisika baik secara mikrobiologi, kimia
maupun radioaktif. Penyakit yang dapat ditimbulkan dan ditularkan melalui tanah diantaranya
diare, cacingan, muntaber, cholera, disentri, penyakit kulit, sesak napas, dan sebagainya.
Contoh kegiatan penilaian terhadap tanah di industri tempat kerja praktik:
a. Mengidentifikasi kandungan mikrobiologi dalam tanah (misalnya telur cacing, fecal
coliform)
Praktik Kerja Industri 41
b. Mengidentifikasi kandungan zat pencemar kimia dalam tanah baik kandungan zat
anorganik maupun organic tanah. Zat anorganik misalnya kandungan timah hitam,
arsen, cadmium, chrom, mercuri, boron, tembaga, sedangkan zat kimia organik misalnya
DDT, dieldrin, PCP, diokxin, dan lain-lain.
2. Pengelolaan Sampah
Pengelolaan sampah di industri bertujuan untuk memastikan bahwa lingkungan industri
selalu dalam kondisi bersih saniter. Saudara diwajibkan mempelajari kembali sistem
pengelolaan sampah baik dalam bangunan maupun dilingkungan sekitar bangunan industri.
Tempat sampah yang terpisah antara sampah organik dan anorganik, sampah basah dan
sampah kering harus disediakan di industri. Konstruksi tempat sampah harus kuat, tertutup
dan kedap air khususnya bagi sampah basah untuk menjaga pencemaran tanah. Tempat
sampah harus diletakkan di setiap ruang untuk mendukung adanya sampah yang berceceran
di ruang kerja. Kegiatan sweeping dan pembersihan harus dimasukkan sebagai objek penilaian
dengan tujuan untuk menghindari pengotoran oleh debu, maupun mengakibatkan kecelakaan
pada tenaga kerja. Sweeping terhadap sampah dan kotoran lainnya harus dilakukan sesering
mungkin, minimal dilakukan dua kali sehari sebelum dan sesudah jam kerja. Sasaran sweeping
meliputi ruang bangunan tempat kerja, gang, koridor, halaman dan lingkungan sekitar
bangunan di lingkungan industri.
D. PENYEHATAN MAKANAN DAN MINUMAN
Makanan merupakan salah satu penyebab timbulnya penyakit pada manusia. Makanan
yang tidak sehat akan mempengaruhi langsung kesehatan manusia karena makanan masuk
secara langsung ke dalam tubuh manusia melalui mulut dan saluran pencernaan. Untuk
memperoleh makanan yang sehat diperlukan pengendalian terhadap bahan, alat, proses dan
kesehatan penjamah makanan.
Penentuan sasaran penilaian mengenai penyehatan makanan dan minuman sangat
tergantung kepada proses bagaimana perusahaan atau industri tempat Saudara melakukan
kerja praktik dalam menyediakan makanan dan minuman bagi karyawannya. Ada beberapa
cara penyediaan makanan dan minuman di industri, diantaranya:
1. Mengelola kantin bagi karyawan
2. Bekerja sama dengan usaha Catering
3. Membeli makanan & minuman jadi
42 Praktik Kerja Industri
Apabila sistem yang dilakukan pihak industri dalam menyediakan makanan dengan
mengelola kantin, maka sistem penilaiannya harus memperhatikan beberapa hal, yakni :
1. Pada proses pembelian bahan , pengolahan, penyimpanan makanan hasil pengolahan
harus dihindarkan dari adanya kontaminasi bahan pencemar dan dilakukan dengan
kondisi bersih. Pembelian bahan mentah, pemisahan bahan baku tidak bersentuhan
langsung dengan bahan yang dimasak, serta alat - alat yang digunakan harus bersih dan
saniter.
2. Sarana transportasi untuk mengangkut bahan mentah atau jadi harus bersih dan baik,
serta bahan baku atau jadi harus tertutup dengan baik agar tidak terkontaminasi.
3. Alat yang digunakan untuk distribusi harus bersih dan cara pendistribusian yang baik dan
benar sehingga tidak terkontaminasi.
4. Kantin harus menggunakan air yang bersih dari kontaminasi mikrobiologi dengan jumlah
yang cukup.
5. Pada proses konsumsi, sebelum makan tenaga kerja harus cuci tangan dulu, cuci muka
berkumur dang anti baju kerja dengan pakaian yang bersih.
Dapur yang disediakan kantin untuk memasak harus memenuhi persyaratan struktur
dan tata letak dapur, diantaranya:
1. Disediakan tempat secara khusus untuk proses memasak makanan, misalnya untuk
meracik, mewadahi, memanaskan, mendinginkan, mencampur, mencuci peralatan
mencuci tangan, menyimpan bahan dan makanan.
2. Ukuran ruangan harus memadai untuk pergerakan kegiatan memasak agas bisa leluasa
sehingga menunjang kelancaran memasak makanan.
3. Ruang kerja harus memiliki fungsi yang maksimal dan memenuhi syarat kesehatan
diantaranya memiliki ventilasi yang cukup, konstruksi dinding dan pintu harus kuat,
mudah dibersihkan dan dalam kondisi yang bersih dan saniter.
4. Bidang kerja harus dirancang agar memberikan kenyamanan saat digunakan.
Permukaan bidang kerja harus kuat dan dilapisi porselin atau keramik, rata dan bersih
5. Bidang kerja yang dapat dipindah harus terbuat dari logam yang kuat dan tahan karat
6. Pintu harus dapat menutup sendiri untuk memperlancar lintasan barang, bahannya
harus tembus udara untuk menjamin sirkulasi udara yang baik.
7. Letak Dapur harus mudah dicapai oleh tenaga kerja dan dari semua ruang makan, tidak
langsung berhubungan dengan tempat kerja, tidak dekat dengan tempat sampah,
mudah dicapai dari kendaraan dari luar.
8. Ergonomi pada bidang kerja dapur perlu dinilai khususnya jangkauan pekerja terhadap
barang-barang kebutuhan sebagai kelengkapan kerja. Tinggi bidang kerja khususnya
meja kerja setinggi 90 cm, letak kompor harus diatur sedemikian rupa sehingga pekerja
Praktik Kerja Industri 43
bisa melakukan pekerjaan sambil berdiri. Bahan yang digunakan tidak menimbulkan
alergi atau gangguan kesehatan.
9. Luas ruangan 1/7 – 1/5 dari jumlah tenaga kerja
10. Peralatan dapur dianjurkan dari bahan stainless steel.
Ventilasi atas
Ventilasi
bawah Tungku Meja Kerja
Gambar 2.1 Alur aliran udara di dapur
11. Ruang dapur harus memiliki aliran udara yang baik, terdapat ventilasi bawah dan disisi
tembok yang berlawanan ada ventilasi atas (cross ventilation)
12. Dapur pengolah makanan yang sehat juga harus menyediakan alat penangkap asap.
44 Praktik Kerja Industri
Filter/saringan asap
Kuali masakan
tungku
Conus
Lantai rapat air
Gambar 2.2 Alat Penangkap Asap
Selain persyaratan tersebut di atas fasilitas sanitasi yang ada di kantin biasanya ada air
bersih, wastafel untuk cuci tangan, pembuangan air limbah sisa masakan dan makanan, serta
adanya tempat pembuangan sampah. Sehingga tetap disarankan untuk menjaga kebersihan
dan kerapian lingkungan kerja. Dan yang paling penting untuk diperhatikan bagi pemilik
perusahaan agar karyawan mau memanfaatkan konsumsi makan di kantin adalah fasilitas
kantin (berisi TV, AC atau live music), letak kantin yang mudah dijangkau, lingkungan fisik
Praktik Kerja Industri 45
kantin yang masih bagus, serta pola penyusunan menu yang diatur agar tidak membuat tenaga
kerja merasa kebosanan.
Jika industri dalam penyediaan makanannya bekerjasama dengan pihak ketiga
(Catering), maka pengawasan makanan cukup ditujukan pada :
1. kualitas makanan atau menu yang disajikan,
2. kebersihan tempat makanan,
3. cara pengangkutan makanan, dan
4. waktu penyediaan sampai makanan siap dimakan.
E. PENYEHATAN UDARA
Sub topik ini akan membahas sasaran pengawasan media lingkungan udara di dalam
industri (indoor air quality) dan di lingkungan luar industri (ambient air quality). Kualitas udara
sangat tergantung dari bahan baku dan proses produksi di industri tempat kerja praktik. Untuk
memperdalam dan mengembangkan substansi sasaran pengawasan udara di industri Saudara
diwajibkan mempelajari kembali materi perkuliahan penyehatan udara.
Sisa hasil pembakaran pada emisi gas buang industri biasanya berupa air (H2O), gas CO
atau disebut juga karbon monooksida yang beracun, CO2 atau disebut juga karbon dioksida
yang merupakan gas rumah kaca, NOx senyawa nitrogen oksida, HC berupa senyawa Hidrat
arang sebagai akibat ketidak sempurnaan proses pembakaran serta partikel lepas.
Standar kualitas udara dalam ruang perkantoran mengacu kepada peraturan
perundang-undangan mengenai Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran,
sedangkan Standar Baku Mutu udara ambien mengacu ke peraturan Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan yang berlaku.
Terdapat beberapa parameter fisik udara yang juga diukur berkaitan dengan eksistensi
parameter pencemar dan cara pemajanan polutan udara terhadap karyawan atau masyarakat
di dalam lingkugan kerja industri, yaitu: iklim kerja (suhu, kelembaban relative, suhu radiasi,
dan kecepatan aliran udara). Faktor lain yang diukur berkaitan dengan kadar polutan
pencemar di dalam ruang kerja industri yaitu parameter kimia, diantaranya debu atau dust,
gas, uap dan sebagainya.
Dalam menentukan sasaran pengawasan sanitasi industri khususnya lingkungan udara
di dalam ruang kerja dan kualitas udara ambient Saudara juga diminta untuk mengembangkan
pengendalian yang dilakukan industri dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan kerja.
Standar baku mutu yang digunakan untuk pencemaran udara ambient adalah peraturan
daerah yang dikeluarkan oleh Gubernur. Apabila diperlukan dapat menggunakan peraturan
menteri Negara Lingkungan Hidup atau peraturan perundangan yang dikeluarkan pemerintah
lainnya dalam rangka melengkapi standar baku mutu yang diperlukan dalam pengawasan.
46 Praktik Kerja Industri
F. PENGENDALIAN VEKTOR
Masalah vector menjadi salah saru sasaran pengawasan atau penilaian sanitasi industri.
Hal tersebut disebabkan adanya dampak buruk akibat keberadaan vector pembawa penyakit
dan dapat menularkan kepada orang lainnya. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70
Tahun 2016 disampaikan bahwa yang termasuk vector adalah malariae, aedes aegypti, dan
culex. Sedangkan yang dikategorikan sebagai binatang pembawa penyakit meliputi tikus, lalat,
kecoa, dan lipas.
Untuk mengembangkan sasaran penilaian atau pengawasan vector di industri silahkan
Saudara mempelajari kembali materi kuliah Pengendalian vector dan peraturan perundangan
tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan di ruang kerja industri khususnya
tentang vector. Dalam peraturan tersebut terdapat 5 parameter yang dinilai sesuai standar
baku mutu yang disediakan untuk vector malaria, yaitu jumlah gigitan nyamuk permalam,
angka paritas, kapasitas vector, dan kemampuan menginfeksi per orang per malam, serta
indeks habitat dengan larva.
Untuk vector Aedes Aegypti menggunakan standar baku mutu indeks container, yaitu
persentase container yang mengandung larva. Jika container tidak mengandung larva
dikategorikan rendah sehingga dikatakan baik karena tidak ada larga dalam container
tersebut, begitu sebaliknya jika pada container ditemukan positif larva, maka potensi
perkembanbiakan vector. Untuk vector cules ditentukan dengan indeks larva dalam container.
Jika indeks container tersebut kurang dari 1 maka dapat dikatakan indeks container tersebut
baik, dan beresiko rendah untuk terjadinya perkembangbiakan vector Culex sp.
Standar baku untuk indeks tikus tergantung jumlah tikus yang tertangkap. Jika kurang
atau sama dengan 1 maka dikategorikan rendah atau baik. Jika lebih besar dari 1 maka
dikategorikan lingkungan industri tersebut kurang baik.
Standar untuk kecoa/lipas dikatakan baik apabila angka rata-rata populasi kecoa
permalamnya kurang atau sama dengan 1 maka dikategorikan baik. Sebaliknya jika lebih besar
dari 1 maka dikategorikan tinggi.
Untuk lalat jika ditemukan indeks populasi rata-rata lalat kurang atau sama dengan 2%
dikatakan rendah, jika lebih besar dari 2 persen maka dikategorikan tinggi. Indeks rata-rata
dihitung berdasarkan jumlah rata-rata lalat yang hinggap di flygrill.
Praktik Kerja Industri 47
G. HOUSEKEEPING (KEBERSIHAN RUMAH ATAU BANGUNAN)
Materi yang digunakan untuk menilai housekeeping ini ditujukan terhadap segala
sesuatu menyangkut kebersihan, keamanan lantai, bangunan dan ruang kerja. Perhatikan
contoh materi berikut:
1. Semua tempat pengelola, gang-gang, ruang penyimpanan (gudang) harus dijaga dalam
kondisi sanitair.
2. Atap, gang-gang, lantai, dinding, basement, gudang bawah tanah, jamban, toilet, septick
tank, saluran pembuangan, dan lain-lain setiap saat harus bersih dan aman serta dalam
kondisi yang sanitair.
3. Setiap bangunan, halaman, gang-gang dan keseluruhan wilayah milik perusahaan harus
dijaga bebas dari akumulasi debu dan sampah lainnya.
4. Setaip lantai ruang kerja harus dikelola secara bersih dan sebisa mungkin dalam kondisi
kering. Apabila ada kegiatan-kegiatan yang menggunakan air maka sistem drainase atau
pematusan harus dikelola dengan baik (dimungkinkan dalam kondisi cepat kering).
Pekerja harus menggunakan sepatu khusus untuk tempat semacam itu.
5. Lantai atau permukaan jalan lainnya harus terjaga dalam kondisi baik, bebas minyak
atau air, semua hal yang bernbahaya yang ada dijalanan harus dihilangkan.
6. Setiap lantai, tempat kerja dan jalan atau gang harus bebas dari gundukan, serpihan atau
lubang.
7. Meludah ke dinding, lantai, tempat kerja atau lantai bangunan lainnya harus dibuang.
8. Jika disediakan tempat meludah konstruksinya harus bisa dibersihkan dan di desinfeksi
serta harus dalam keadaan bersih setiap hari untuk menjaga kesehatan.
9. Jika tempat sampah digunakan untuk sampah basah atau yang dapat terurai
konstruksinya harus dibuat tidak bocor, nyaman, bersih dan dirawat dengan baik atau
sanitair.
10. Jika menggunakan mesin atau peralatan kimia di dalam mengelola sanitasi pemeriksaan
secara periodik harus dilakukan untuk menjamin efisiensi peralatan dan mencatat hasil
setiap pemeriksaan.
11. Peralatan penerangan harus sering dibersihkan untuk menjaga intensitas penerangan
agar tetap berada pada level yang memenuhi syarat. Jika menggunakan penerangan
alami pada siang hari maka jendela harus sering dibersihkan agar pencahayaan diruang
tersebut memenuhi syarat.
12. Bahan-bahan buangan yang mudah terbakar harus ditempatkan pada wadah logam
yang dapat menutup sendiri dan harus dikosongkan minimal 1 kali dalam sehari
13. Bahan-bahan yang mudah terbakar harus sebaiknya jangan disimpan dibawah tangga.
48 Praktik Kerja Industri
14. Alat pemadam kebakaran harus dijaga agar mudah dioperasikan dan terlindung dari
proses pendinginan. Jika alat pemadam kebakaran memakai tipe asam soda sebaiknya
diisi ulang minimal setahun sekali.
15. Limbah industri harus diolah dengan menggunakan metode yang sesuai sebelum
dibuang kebadan air.
16. Bahan-bahan atau material harus di tumpuk dan dihindarkan dari getaran atau vibrasi
dan sentakan agar tidak mudah jatuh.
Saudara dapat mengembangkan sasaran penilaian housekeeping ini dengan
mempelajari peraturan-peraturan terkait baik yang dikeluarkan oleh gubernur, pemerintah
pusat atau peraturan lainnya.
H. JAMBAN DAN PETURASAN
Jamban dan peturasan merupakan salah satu penyebab terjadinya penularan penyakit.
Penyakit yang dapat ditimbulkan dan ditularkan akibat pengelolaan jamban dan peturasan
yang kurang baik diantaranya adalah diare, muntaber, typhus, cholera, disentri, penyakit kulit,
gatal-gatal.
Untuk menilai jamban dan peturasan di industri Saudara diwajibkan mempelajari
kembali mata kuliah PAPLC. Standar baku mutu yang digunakan adalah Permenkes No. 70
Tahun 2016 untuk peturasan atau urinoir, yaitu :
No. Jumlah Toilet Pekerja
1. 1 15
2. 2 16-35
3. 3 66-35
4. 4 56-80
5. 5 81-110
6. 6 111-150
Ditambah satu Toilet untuk setiap Lebih dari 150
penambahan 40 orang
Praktik Kerja Industri 49
Sedangkan untuk penilaian jamban sehat harus menggunakan persyaratan jamban
sehat baik dari segi jumlah yang diperlukan maupun kualitas jamban. Untuk industri yang
memiliki lebih dari 25 orang dilarang menggunakan kakus, melainkan menggunakan jamban
sehat. Lokasi jamban tidak diperbolehkan berjarak 3.5 meter (dari ruang penyimpanan atau
pengolahan makanan).
Ruang toilet harus memiliki jendela yang dilengkapi kasa. Lantai WC harus dibuat dari
bahan yang kuat dan mudah dibersihkan, misalnya porselen atau keramik. Keamanan harus
diperhitungkan sehingga pengguna tidak mengalami kedelakaan. Penyediaan air harus cukup
untuk keperluan jamban dan urinoir. Lavatory hendaknya terpisah antara laki-laki dan
perempuan. WC harus selalu terjaga kebersihannnya. Harus disediakan tempat sampah.
Untuk lavatory perempuan tempat sampah harus selalu dalam kondisi tertutup. Sabun juga
harus disediakan di setiap WC. Setiap urinoir harus ada sistem gelontor (flushing) melalui
flushing valve (menyatu) atau yang tersedia secara terpisah.
Sistem gelontoran harus menggunakan air yang cukup yang tujuannya, agar urine bisa
mengalir dengan lancar di atas lantai urinoir serta tidak berbau.
Ketinggian dinding pemisah antar urinoir boleh lebih rendah dari dinding ruangan.
Bagian atas tidak kurang dari 6 feet (± 182 cm) dan batas dinding bawah 30 cm dari lantai.
Pintu toilet harus di buat menutup sendiri dan terdapat screen sehingga tidak kelihatan
dari ruang kerja. Semua pintu harus ada penguncinya.
I. FASILITAS CUCI TANGAN
Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan :
1. Fasilitas untuk menjaga kebersihan perorangan harus disediakan di setiap ruang kerja.
Fasilitas tersebut harus memberikan kenyamanan pekerja dan harus dijaga
kebersihannya.
2. Minimal satu lavatory dengan penyediaan air yang memadai harus disediakan untuk 10–
100 karyawan dan satu lavatory untuk setiap penambahan 15 orang. Satu buah lavatory
berukuran 55 cm+ satu buah kran, diperkirakan sama dengan sebuah baskom. Sabun
yang ditempatkan pada tempat khusus harus disediakan di setiap tempat cuci atau
lavatory.
3. Ruang cuci harus terpisah antara laki-laki dan perempuan. Jika ruang lavatory di buat
bersebelahan, maka dinding pemisah atau pembatas konstruksinya harus kokoh dan
rapat.
4. Setiap pembuatan tempat cuci baru harus terbuat dari bahan-bahan yang kuat dan
kedap air.
50 Praktik Kerja Industri
5. Misalnya : bahan dari sejenis kaca, kaca, besi galvanis, besi yang diberi lapisan sejeni
kaca, porselin, keramik dan sejenisnya.
6. Jika tempat cuci umum tidak tersedia pada lantai yang sama dan lokasi dekat toilet,
maka minimal satu tempat cuci harus disediakan di ruang toilet.
7. Semua lantai di bawah lavatory atau tempat cuci tangan atau wastafel harus mudah
penanganannya dan selalu dalam keadaan bersih.
8. Tidak boleh menggunakan handuk biasa di dekat lavatory.
9. Harus disediakan lap khusus atau kertas tissue, serta tempat sampah di dekat wastafel
atau tempat cuci.
10. Penggunaan alat lain pengering tangan boleh digunakan setelah mendapat ijin dari yang
berwenang.
11. Lavatory yang menggunakan air panas dan dingin dalam 1 kran harus disediakan untuk
setiap 5 karyawan yang terkontaminasi kulitnya dari bahan beracun, bahan yang
menyebabkan infeksi, atau yang menyebabkan iritasi.
12. Harus ada shower dengan air panas dan dingin bagi karyawan yang bekerja dengan
bahan beracun, infeksi, irritants, minimal 1 buah shower untuk 15 pekerja
13. Tidak diperbolehkan menggunakan sabun basa kuat atau yang bersifat irritant atau kuat
abrasinya.
14. Untuk kontaminan yang tidak bisa dibersihkan dengan air dan sabun, maka bisa
dibersihkan dengan minyak atau larutan tertentu dengan cara mengambil sedikit
kemudian diusap-usapkan pada kulit yang terkontaminasi
15. Air yang digunakan untuk keperluan fasilitas cuci di tempat kerja harus sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
Latihan
Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan
berikut!
1) Susunlah kembali item penilaian berkaitan dengan penyediaan air bersih di industri dan
air minum bagi tenaga atau karyawan industri....
2) Buatlah parameter-parameter yang akan digunakan dalam penilaian kualitas buangan
air limbah....
3) Susunlah kembali item penilaian yang membahas persyaratan sanitasi industri
mengenai pengelolaan air limbah....
4) Susunlah kembali sasaran atau item penilaian yang dinilai tentang penyehatan tanah....
Praktik Kerja Industri 51
5) Susunlah kembali sasaran penilaian yang terperinci tentang pengelolaan sampah
industri....
6) Susunlah kembali sasaran penilaian tentang sanitasi makanan dan minuman di industri
apabila industri mengelola kantin dan apabila bekerjasama dengan pihak ketiga dalam
penyediaan makanan dan minuman karyawan....
7) Susunlah kembali sasaran penilaian dalam pengawasan penyehatan udara ambient
termasuk pengendalian yang dilakukan oleh industri tempat kerja praktik....
8) Susunlah kembali sasaran penilaian WC dan toilet pada kegiatan praktik kerja industri....
9) Susunlah kembali sasaran penilaian praktik kerja industri dalam penyediaan fasilitas cuci
tangan....
Ringkasan
1. Dalam menentukan sasaran pengawasan sanitasi dan ruang kerja diperlukan persiapan
dengan cara mempelajari kembali materi kuliah terkait
2. Objek sasaran harus dibuat secara terperinci agar mudah disusun dalam bentuk
instrument pengawasan
3. Standar baku mutu dalam penilaian sasaran pengawasan sanitasi industri digunakan
terlebih dahulu secara berurutan yaitu standar baku mutu di tingkat regional, jika tidak
ditemukan baru menggunakan peraturan tingkat nasional atau internasional.
Tes 2
Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar!
1) Susun kembali sasaran pengawasan sanitasi dan ruang kerja....
2) Buatlah rincian masing-masing sasaran pengawasan sanitasi industri untuk
mempermudah pembuatan instrument pengawasan nantinya....
3) Susunlah kutipan standar baku mutu terkait pengawasan sanitasi industri yang akan
digunakan sebagai acuan dalam pengawasan sanitasi industri....
52 Praktik Kerja Industri
Topik 3
Rencana Sasaran Pengawasan K3 di Industri
A. IDENTIFIKASI RISIKO ATAU BAHAYA TERJADINYA KECELAKAAN KERJA
Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di industri harus mendapat perhatian
prioritas oleh pihak industri. Terdapatnya berbagai macam jenis kegiatan akan memiliki risiko
dalam berbagai tingkatan bahaya yang ditimbulkan. Identifikasi risiko dilakukan untuk
mengetahui kegiatan yang menjadi sumber penyebab terhadap timbulnya risiko dan
dampaknya terhadap terjadinya kecelakaan kerja. Saudara perhatikan contoh formulir
identifikasi berikut:
Formulir Identifikasi Risiko di Industri ……..
Unit : Bengkel atau Workshop Maintenance
Pekerjaan : Pengelasan
No. Tahapan/ Potensi Bahaya Akibat/
Jenis Kegiatan Dampak yang ditimbulkan
1. Persiapan alat & bahan Gas C2H2 Keracunan kronis
Kebakaran/peledakan
Cedera luka/memar
2. Pengelasan Material besi Cedera luka/memar
Panas Dehidrasi/ heat stress
Gas C2H2 Keracunan
Kebakaran/peledakan
Kilatan sinar Fotokeratitis
Partikek gram Pernapasan
Panas Mata
Dehidrasi/heat stress
Jadi dalam melakukan identifikasi risiko atau bahaya terhadap terjadinya kecelakaan
kerja, maka lakukanlah kegiatan sebagai berikut:
1. Identifikasi semua jenis kegiatan yang dilakukan di industri tempat praktik kerja
2. Identifikasi potensi bahaya yang ditimbulkan
Praktik Kerja Industri 53
3. Identifikasi akibat atau dampak yang ditimbulkan
4. Susunlah hasil identifikasi tersebut ke dalam tabel sebagaimana contoh di atas.
Terdapat beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja antara lain penyebab langsung
kecelakaan kerja, penyebab tidak langsung kecelakaan kerja, dan penyebab dasar kecelakaan
kerja.
1. Penyebab langsung kecelakaan kerja, yaitu :
a. Tidak dipasang pengaman (safeguard) pada mesin yang berputar, tajam atau panas
b. Terdapat instalasi kabel listrik yang kurang standar (isolasi terkelupas, tidak rapi)
c. Alat kerja /mesin/kendaraan yang tidak layak pakai
d. Tidak terdapat label pada kemasan bahan (material) berbahaya dan sebagainya.
2. Tindakan yang Tidak Aman (Unsafe Action)
a. kecerobohan
b. meninggalkan prosedur kerja
c. tidak menggunakan alat pelindung diri
d. bekerja tanpa perintah
e. mengabaikan instruksi kerja
f. tidak mematuhi rambu-rambu di tempat kerja
g. tidak melaporkan adanya kerusakan alat
h. tidak mengurus izin pekerjaan berbahaya sebelum memulai pekerjaan dengan risiko
tinggi.
Faktor pekerjaan contohnya: pekerjaan tidak sesuai dengan tenaga kerja, pekerjaan
tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, pekerjaan berisiko tinggi, tapi belum ada
pengendaliannya, beban kerja yang tidak sesuai.
Termasuk dalam faktor pribadi antara lain: mental atau pribadi tenaga kerja yang tidak
sesuai dengan pekerjaan, konsflik, stress, keahlian tidak sesuai, dan lainnya.
Termasuk penyebab dasar Kecelakaan kerja
a. Lemahnya manajemen dan pengendaliannya
b. Kurangnya sarana prasarna
c. Kurangnya sumber daya
d. Kurangnya komitmen
54 Praktik Kerja Industri
Selain penilaian risiko akibat kegiatan yang dilakukan di tempat kerja, perlu dilakukan
penilaian lingkungan kerja yang meliputi lingkungan yang bersifat fisik, kimia, maupun
bakteriologis. Peningkatan produktivitas kerja sangat dipengaruhi adanya risiko akibat kerja
dan lingkungan kerja yang dari keduanya akan mempengaruhi terjadinya kecelakaan dan
kesehatan kerja.
Parameter lingkungan kerja yang bersifat fisik diantaranya:
a. Tingkat intensitas kebisingan di tempat kerja
b. Tingkat instensitas pencahayaan (di dalam dan di luar ruang kerja)
c. Iklim kerja
d. Getaran
e. Radiasi
Parameter lingkungan yang bersifat kimia diukur menggunakan 3 kategori, yaitu :
a. TWA (Time Weighted Average) adalah pengukuran konsentrasi rata-rata pajanan bahan
kimia tertentu yang dapat diterima pekeerja tanpa mengakibatkan gangguan atau
penyakit dalam pekerjaan sehari-hari untuk waktu tidak melebihi 8 jam sehari atau 40
jam perminggu.
b. STEL (Short Time Exposure Limit) adalah konsentrasi rata tertinggi selama 15 menit yang
diperkenankan dan tidak boleh terjadi lebih dari 4 kali dengan periode antar pajanan
minimal 60 menit selama pekerja melakukan pekerjaannya dalam 8 jam perhari.
c. Ceiling adalah konsentrasi bahan kimia di tempat kerja yang tidak boleh dilampaui
selama jam kerja
Untuk mengembangkan sasaran penilaian atau pengawasan pada sub topik ini Saudara
dapat mempelajari mata kuliah K3 dan aspek yang dinilai berdasarkan standar baku mutu
Permenkes No. 70 Tahun 2016, atau peraturan lain yang masih berlaku misalnya peraturan
regional yang dikeluarkan oleh Gubernur.
B. IDENTIFIKASI PENERAPAN SMK3
Pengawasan atau penilaian penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (SMK3) bertujuan untuk memperoleh gambaran sejauh mana pelaksanaan penerapan
K3 secara manajerial di industri. Hasil penerapan SMK3 bisa diperoleh melalui audit eksternal
maupun audit internal. Dalam kegiatan praktek kerja industri ini mahasiswa diharapkan
mampu mengidentifikasi penerapan SMK3 yang dilakukan oleh pihak industri tempat kerja
praktik. Sasaran yang dinilai adalah sebagai berikut:
Praktik Kerja Industri 55
1. Bentuk organisasi K3
2. Peraturan perundangan tentang K3 dan atau SMK3 yang diterapkan di industri.
3. Pelaksanaan tahapan SMK3 yang terdiri dari :
a. Penetapan kebijakan
b. Perencanaan K3
c. Pelaksanaan Perencanaan K3
d. Pemantauan dan Evakuasi Kinerja K3
e. Peninjauan ulang dan Peningkatan Kinerja SMK3
Sasaran pelaksanaan SMK3 tidak boleh menyimpang dari peraturan yang berlaku saat
ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3.
C. SISTIM PENGENDALIAN RISIKO YANG DITERAPKAN DI INDUSTRI
Setelah Saudara mempelajari materi identifikasi risiko, evaluasi risiko dan dampak yang
ditimbulkan oleh risiko bahaya di ruang kerja dan di lingkungan kerja, maka Saudara
diwajibkan mempelajari Sistim pengendalian risiko bahaya di ruang dan lingkungan kerja.
Sistim pengendalian risiko bahaya di ruang kerja sangat menentukan status hasil penerapan
K3 di industri. Menurut ANZI Z10: 2005 pengendalian risiko bahaya di ruang kerja dapat
dilakukan melalui hierarkhi pengendalian bahaya yang meliputi:
1. Eliminasi
2. Substitusi
3. Rekayasa teknis
4. Sistem peringatan atau warning system
5. Rekayasi administrative
6. Alat pelindung diri.
Menurut ANSI Z10: 2005, hirarki pengendalian dalam sistem manajemen keselamatan,
kesehatan kerja antara lain:
1. Eliminasi
Hirarki teratas yaitu eliminasi atau menghilangkan bahaya dilakukan pada saat desain,
tujuannya adalah untuk menghilangkan kemungkinan kesalahan manusia dalam menjalankan
suatu sistem karena adanya kekurangan pada desain. Penghilangan bahaya merupakan
metode yang paling efektif sehingga tidak hanya mengandalkan prilaku pekerja dalam
menghindari resiko, namun demikian, penghapusan benar-benar terhadap bahaya tidak selalu
praktis dan ekonomis.
56 Praktik Kerja Industri
Contoh-contoh eliminasi bahaya yang dapat dilakukan misalnya: bahaya jatuh, bahaya
ergonomi, bahaya ruang terbatas, bahaya bising, bahaya kimia.
2. Substitusi
Metode pengendalian ini bertujuan untuk mengganti bahan, proses, operasi ataupun
peralatan dari yang berbahaya menjadi lebih tidak berbahaya. Dengan pengendalian ini
menurunkan bahaya dan resiko minimal melalui disain sistem ataupun desain ulang. Beberapa
contoh aplikasi substitusi misalnya: Sistem otomatisasi pada mesin untuk mengurangi
interaksi mesin-mesin berbahaya dengan operator, menggunakan bahan pembersih kimia
yang kurang berbahaya, mengurangi kecepatan, kekuatan serta arus listrik, mengganti bahan
baku padat yang menimbulkan debu menjadi bahan yang cair atau basah.
Contoh: penggunaan minyak daripada merkuri dalam barometer, penyapuan dengan
sistem basah pada debu timbal dibandingkan dengan penyapuan kering.
3. Pengendalian Teknik atau Engineering Control
Pengendalian ini dilakukan bertujuan untuk memisahkan bahaya dengan pekerja serta
untuk mencegah terjadinya kesalahan manusia. Pengendalian ini terpasang dalam suatu unit
sistem mesin atau peralatan.
Contoh-contoh implementasi metode ini misal adalah adanya penutup mesin/machine
guard, circuit breaker, interlock system, start-up alarm, ventilation system, sensor, sound
enclosure.
4. Sistem Peringatan atau Warning System
Adalah pengendian bahaya yang dilakukan dengan memberikan peringatan, instruksi,
tanda, label yang akan membuat orang waspada akan adanya bahaya dilokasi
tersebut. Sangatlah penting bagi semua orang mengetahui dan memperhatikan tanda-tanda
peringatan yang ada dilokasi kerja sehingga mereka dapat mengantisipasi adanya bahaya yang
akan memberikan dampak kepadanya. Aplikasi di dunia industri untuk pengendalian jenis ini
antara lain berupa alarm system, detektor asap, tanda peringatan (penggunaan APD spesifik,
jalur evakuasi, area listrik tegangan tinggi, dan lain-lain).
5. Pengendalian Administratif atau Administratif Control
Kontrol administratif ditujukan pengendalian dari sisi orang yang akan melakukan
pekerjaan, dengan dikendalikan metode kerja diharapkan orang akan mematuhi, memiliki
kemampuan dan keahlian cukup untuk menyelesaikan pekerjaan secara aman.
Praktik Kerja Industri 57
Jenis pengendalian ini antara lain seleksi karyawan, adanya Standar Operasi Baku (SOP),
pelatihan, pengawasan, modifikasi prilaku, jadwal kerja, rotasi kerja, pemeliharaan,
manajemen perubahan, jadwal istirahat, investigasi dan lain-lain.
6. Alat Pelindung Diri
Pemilihan dan penggunaan alat pelindung diri merupakan merupakan hal yang paling
tidak efektif dalam pengendalian bahaya, dan APD hanya berfungsi untuk mengurangi seriko
dari dampak bahaya. Karena sifatnya hanya mengurangi, perlu dihindari ketergantungan
hanya menggandalkan alat pelindung diri dalam menyelesaikan setiap pekerjaan.
Alat pelindung diri Mandatory adalah antara lain: Topi keselamatan (Helmet), kacamata
keselamatan, Masker, Sarung tangan, earplug, Pakaian (Uniform) dan Sepatu Keselamatan.
Dan APD yang lain yang dibutuhkan untuk kondisi khusus, yang membutuhkan perlindungan
lebih misalnya: faceshield, respirator, SCBA (Self Content Breathing Aparatus), dan lain-lain.
Pemeliharaan dan pelatihan menggunakan alat pelindung diripun sangat dibutuhkan
untuk meningkatkan efektifitas manfaat dari alat tersebut.
Dalam aplikasi pengendalian bahaya, selain kita berfokus pada hirarkinya tentunya
dipikirkan pula kombinasi beberapa pengendalian lainnya agar efektifitasnya tinggi sehingga
bahaya dan resiko yang ada semakin kecil untuk menimbulkan kecelakaan. Sebagi misal
adanya adanya unit mesin baru yang sebelumnya memiliki kebisingan 100 dBA dilberikan
enclosure (dengan metode engineering control) sehingga memiliki kebisingan 90 dBA, selain
itu ditambahkan pula safety sign dilokasi kerja, adanya preventive maintenance untuk
menjaga keandalaan mesin dan kebisingan terjaga, pengukuran kebisingan secara berkala,
diberikan pelatihan dan penggunaan earplug yang sesuai.
Latihan
Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan
berikut!
1) Susun Kembali rencana pengawasan terhadap penerapan manajemen Risiko di industri
atau perusahaan tempat Saudara melakukan praktik kerja.
2) Buatlah uraian sasaran penilaian atau pengawasan penerapan SMK3 di industri tempat
Sudara melakukan kerja praktik
3) Buatlah uraian materi penilaian atau pengawasan sistim pengedalian risiko yang
diterapkan oleh indsutri tempat Saudara melakukan praktik.
58 Praktik Kerja Industri
Ringkasan
1. Dalam melakukan identifikasi bahaya risiko harus didahului dengan mencatat semua
jenis kegiatan yang ada di indsustri, baru kemudian menentukan potensi bahaya yang
bisa ditimbulkan akibat kegiatan tersebut selanjutnya menentukan dampak yang
ditimbulkan
2. Penyebab terjaninya kecelakaan kerja digolongkan sebagai penyebab langsung, tidak
langsung, dan penyebab dasar kecelakaan kerja
3. Sasaran penilaian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah
lima langkah manajemen K3, peraturan perundangan yang diterapkan, organisasi K3,
pendokumentasian K3.
4. Sistem Pengendalian risiko dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja menerapkan
hierarkhi langkah-langkah pengendalian keelakaan kerja
Tes 3
Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar!
1) Susunlah kembali secara garis besar item penilaian K3 industri secara singkat!
2) Susunlah urutan kegiatan yang dinilai dalam system manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja di industri!
3) Susun kembali hierarki langkah-langkah pengendalian dalam rangka mencegah
kecelakaan kerja di industri!
4) Susunlah prosedur atau tahap-tahap persiapan rencana praktik kerja industri dan
buatlah diagram alirnya!
Praktik Kerja Industri 59
Glosarium
Eliminasi: tindakan pengendalian kecelakaan kerja dengan metoda menghilangkan
bahaya yang akan timbul dan dialami tenaga kerja baik pada peralatan/
mesin yang digunakan pada saat kerja.
Substitusi: tindakan pengendalian kecelakaan kerja dengan metoda mengganti
bahan-bahan berbahaya dengan bahan yang tidak berbahaya tetapi
memiliki manfaat yang sama.
Enginerring Control: pengendalian kecelakaan kerja secara teknis yang meliputi pengendalian
tempat kerja/lingkungan, peralatan, maupun bahan yang memiliki risiko
bahaya terhadap timbulnya kecelakaan kerja.
60 Praktik Kerja Industri
Daftar Pustaka
Direktorat Penyehatan Air dan Sanitasi, Sub Direktorat Hygiene Sanitasi Makanan& Minuman,
2004, Kumpulan Modul Khusus Hygiene Sanitasi Makanan & Minuman
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 70 Tahun 2016 tentang Persyaratan Sanitasi dan
Ruang Kerja Industri
Permen Lingkungan Hidup nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah
Peraturan Pemerintah RI np. 50 Tahun 2012 tentang system Manajemen K3
Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
OHSAS 18001:2007 Occupational Health & Safety Management System.
Praktik Kerja Industri 61
Bab 3
PENYUSUNAN INSTRUMEN
Hadi Suryono, ST., MPPM.
Yulianto, S.Pd., M.Kes.
Pendahuluan
K
egiatan praktik kerja industri yang akan Saudara lakukan, pada dasarnya tidak ubahnya
suatu kegiatan penelitian ilmiah yang dilakukan pada suatu industri. Pada setiap
kegiatan penelitian ilmiah peneliti berusaha memberikan simpulan dan saran yang
realistis dan operasional, hal ini dapat diperoleh apabila pada proses penelitian yang
dilakukan menggunakan prinsip penelitian ilmiah. Salah satu faktor yang cukup menentukan
keberhasilan suatu penelitian ilmiah adalah terkait dengan data yang dikumpulkan. Terdapat
berbagai metode pengumpulan data pada penelitian ilmiah, misalnya observasi, eksperimen,
survei, analisis isi (content analysis) dan wawancara.
Kualitas data penelitian tergantung pada kualitas instrumen serta kualitas teknik
pengumpulan datanya, Sekaran (2000). Lebih lanjut dinyatakan bahwa kualitas instrumen
penelitian tergantung pada validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Teknik
pengumpulan data berhubungan dengan penyusunan (desain) studi penelitian, jenis sumber
data serta cara pengumpulan data. Cara pengumpulan data dapat dilakukan melalui tiga cara
yaitu: wawancara, observasi dan penyebaran kuesioner kepada responden penelitian. Jenis
data meliputi data primer dan data sekunder, lebih mudah mempertanggungjawabkan data
sekunder dibandingkan dengan data primer. Desain penelitian dapat ditinjau dari desain
laboratorium, eksperimen atau lingkungan alami subyek dengan masing-masing keunggulan
maupun kelemahannya. Kualitas data primer yang dikumpulkan berdasarkan teknik survei
ditentukan oleh kualitas instrumen yang diwakili oleh pernyataan-pernyataan atau
pertanyaan-pertanyaan yang ada didalam kuesioner penelitian tersebut.
Survei merupakan alternatif metode komunikasi dengan mengajukan pertanyaan pada
responden dan merekam jawabannya untuk dianalisis lebih lanjut (Cooper dan Emory,1995).
Permasalahan dalam teknik survei lebih terkait dengan pembuatan kuesionernya karena
berhubungan langsung dengan daya tanggap responden. Di sisi lain perlu upaya tertentu
62 Praktik Kerja Industri
dalam rangka memberikan pemahaman kepada responden sehingga responden mau
menjawab dan menyelesaikan kuesioner.
Materi pada bab ini membahas tentang penyusunan instrumen yang akan digunakan
dalam kegiatan praktek kerja industri. Agar Saudara dapat menyusun instrumen dengan baik,
maka pada bab ini akan diuraikan secara rinci dalam tiga topik yaitu:
1. Teknik penyusunan instrumen.
2. Instrumen pengawasan sanitasi industri.
3. Instrumen pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja.
Praktik Kerja Industri 63
Topik 1
Teknik Penyusunan Instrumen
A. PRINSIP DASAR
Kuesioner merupakan alat pengumpulan data primer dengan metode survei untuk
memperoleh opini responden. Kuesioner dapat didistribusikan kepada responden dengan
cara: (1) Langsung oleh peneliti (mandiri); (2) Dikirim lewat pos (mailquestionair); (3) Dikirim
lewat komputer misalnya surat elektronik (e-mail). Kuesioner dikirimkan langsung oleh
peneliti apabila responden relatif dekat dan penyebarannya tidak terlalu luas. Lewat pos
ataupun e-mail memungkinkan biaya yang murah, daya jangkau responden lebih luas, dan
waktu cepat. Tidak ada prinsip khusus namun peneliti dapat mempertimbangkan efektivitas
dan efisiensinya dalam hal akan dikirim lewat pos, e-mail ataupun langsung dari peneliti.
Kuesioner dapat digunakan untuk memperoleh informasi pribadi misalnya sikap, opini,
harapan dan keinginan responden. Idealnya semua responden mau mengisi atau lebih
tepatnya memiliki motivasi untuk menyelesaiakan pertanyaan ataupun pernyataan yang ada
pada kuesioner penelitian. Apabila tingkat respon (repon rate) diharapkan 100% artinya
semua kuesioner yang dibagikan kepada responden akan diterima kembali oleh peneliti dalam
kondisi yang baik dan kemudian akan dianalisis lebih lanjut.
Jelas bahwa responden diharapkan memberikan respon sebaik-baiknya sekaligus
menyerahkan kembali kuesioner yang telah diisinya kepada peneliti. Namun demikian kadang-
kadang dalam kondisi tertentu, kuesioner tidak sampai kembali kepada peneliti. Dalam kasus
demikian tidak ada yang perlu dikahawatirkan karena tidak ada keharusan bahwa 100%
kuesioner dapat dikumpulkan kembali kepada peneliti, namun akan semakin baik apabila
tingkat respon semakin tinggi. Bahkan kuesioner yang dikirimkan lewat pos, apabila tingkat
respon sebesar 30% maka sudah dapat dikatakan, Jogiyanto (2005).
Peneliti juga harus merancang bentuk kuesionernya, yaitu pertanyaan yang sifatnya
terbuka atau tertutup. Pertanyaan terbuka memungkinkan responden menjawab bebas dan
seluas-luasnya terhadap pertanyaan namun dalam pertanyaan tertutup, responden hanya
diberi kesempatan memilih jawaban yang tersedia. Pertanyaan tertutup akan mengurangi
variabilitas tanggapan responden sehingga memudahkan analisisnya. Pilihan jawaban yang
diberikan dapat berupa pilihan dikotomis sampai dengan pertanyaan pilihan ganda yang
memungkinkan gradasi preferensi responden.
64 Praktik Kerja Industri
Tahap berikutnya perlu diketahui tentang wujud kuesioner penelitian yang baik. Untuk
itu perlu dibahas beberapa prinsip penyusunan kuesioner, yang bertitik tolak dari variabel
yang akan diteliti. Dalam hal ini terkait dengan jenis data, yaitu data kuantitatif dan kualiatif.
Data kuantitatif lebih mudah diukur, yang meliputi data diskrit dan data kontinuum. Data
kotinuum meliputi data dengan skala ordinal, skala interval dan skala rasio. Data dengan skala
nominal merupakan contoh dari data diskrit. Data kualitatif yang dominan pada penelitian
sosial akan lebih mudah dianalisis apabila data tersebut dikuantifisir lebih dulu, artinya
dikuantitatifkan lebih dulu. Salah satu cara kuantifikasi variabel sosial adalah dengan
menggunakan skala Likert.
Variabel kuantitatif lebih mudah diukur misalnya suhu badan manusia, volume suatu
barang, dan lain-lain. Namun akan lebih sulit untuk mengukur variabel-variabel sosial,
misalnya apabila ingin mengetahui motivasi karyawan, loyalitas pegawai, kinerja karyawan
dan variabel social lainnya. Pada saat mengukur kinerja karyawan, apakah peneliti benar-
benar mengukur kinerja ataukah sebenarnya dia mengukur produktivitas? Apabila ingin
mengukur variabel kinerja karyawan sebaiknya menggunakan instrumen kuesioner yang
benar-benar mengukur kinerja karyawan, dan apabila ingin mengukur variabel produktivitas
karyawan sebaiknya menggunakan instrumen kuesioner yang benar-benar mengukur
produktivitas karyawan. Diharapkan tidak akan terjadi bahwa untuk mengukur kinerja
karyawan maka peneliti sebenarnya mengukur produktivitas karyawan. Kedua konsep ini
cukup jelas perbedaannya.
Variabel penelitian pada ilmu sosial harus ditentukan oleh peneliti, yang jumlahnya
tergantung pada kedalaman dan luas tidaknya penelitian. Variabel merupakan satuan terkecil
obyek penelitian (Noeng Muhajir: 1998), lebih lanjut dinyatakan bahwa peneliti dapat
mengeliminasi variabel melalui eliminasi phisik, eliminasi dengan kontrol serta eliminasi
statistik. Sedangkan Lerbin Aritonang (2011) berpendapat bahwa variabel merupakan sesuatu
yang memiliki atribut yang bervariasi dan atribut itu dinyatakan dalam bentuk angka atau
bilangan.
Jumlah variabel penelitian menentukan jumlah instrumennya, apabila terdapat tiga
variabel penelitian maka dibuat pula tiga instrument penelitian. Misalnya variabel kualitas
produk, kepuasan konsumen dan variabel loyalitas konsumen maka perlu dibuat tiga
instrumen penelitian untuk mengukur ketiga variabel tersebut. Dengan demikian diperlukan
instrumen untuk mengukur kualitas produk, instrument untuk mengukur kepuasan serta
instrumen untuk mengukur loyalitas konsumen.
Variabel pada ilmu sosial dibuat sesuai konsep yang mendasarinya. Kadang-kadang
sesuatu konsep belum dapat diukur maka menjadi tugas peneliti untuk menguraikannya
sehingga menjadi sesuatu konsep yang terukur. Konsep yang terukur berarti sudah
Praktik Kerja Industri 65
menunjukkan variasi nilai. Konsep yang sudah mampu menunjukkan berbagai variasi nilai
dapat dianggap sebagai variabel.
Pada tahap ini peneliti berwenang untuk membentuk konsep, yang kemudian
dioperasionalkan dan diukur berdasarkan dimensi-dimensi (indikator) tertentu. Dengan
demikian variabel penelitian dibentuk berdasar kerangka pikir ilmiah, artinya baik secara
teoritis maupun empiris dapat diterima secara logis. Jelas bahwa variabel penelitian sosial
bukan merupakan hasil kegiatan asal-asalan melainkan berdasarkan kerangka pikir ilmiah.
Disinilah peran aktif peneliti terkait variabel yang akan diteliti , diperlukan pemahaman teori
serta pemahaman empiris (misalnya melalui penelitian sebelumnya).
1. Definisi Konsep
Konsep menggambarkan tingkat abstraksi yang secara kongkrit mempunyai rujukan
obyektif. Konsep ini harus ditentukan dan dibuat oleh peneliti, tahap selanjutnya peneliti
selayaknya mencari rujukan pakar sehingga konsep yang ditentukan tersebut mendapatkan
penguatan secara teoritis. Konsep yang dibuat dan dihasilkan secara sadar oleh peneliti untuk
kepentingan ilmiah yang khas dan tertentu disebut sebagai konstruk, Nazir (1998).
Dapat dikatakan bahwa konstruk adalah konsep yang abstrak. Konstruk sinonim dengan
variabel, Cooper dan Emory (1995). Konstruk akan menjadi variabel apabila dapat dinyatakan
dalam berbagai variasi nilai. Contoh konsep yang cukup mudah (nyata) untuk dibayangkan
perbedaannya, adalah antara konsep motivasi dengan konsep wanita subur. Konsep-konsep
dalam penelitian sosial (misalnya konsep motivasi) akan jauh lebih abstrak apabila
dibandingkan dengan contoh konsep wanita subur ini. Hal ini disebabkan, konsep wanita
subur akan lebih dapat dipahami dari sisi kuantitatifnya sedangkan konsep motivasi seseorang
dalam bekerja memang lebih abstrak karena lebih sulit dibayangkan aspek kuantitatifnya,
karena pada dasarnya memang kualitatif.
2. Definisi Operasional
Apabila peneliti sudah menentukan variabel dan menemukan definisi konsepnya maka
harus diikuti dengan mengoperasionalkan variabel tersebut sehingga variabel dapat diukur.
Definisi operasional diperoleh dengan cara memberi arti atau ciri tertentu sehingga dapat
diukur. Tiga hal terkait definisi operasional ini, yaitu: definisi yang ketat, dapat diuji secara
khusus, serta mempunyai rujukan empiris, Cooper dan Emory (1995).
Pada contoh diatas, wanita subur dapat dioperasionalkan sebagai wanita yang punya
anak atau wanita yang berat badannya ideal. Tentu saja masing-masing memerlukan rujukan
teoritis maupun empiris.
Operasionalisasi variabel atau pendefinisian secara operasional suatu konsep sehingga
dapat diukur, dapat dicapai dengan melihat dimensi-dimensi, permukaan, ciri yang
66 Praktik Kerja Industri
ditunjukkan oleh konsep itu, serta pengkategoriannya ke dalam unsur-unsur yang dapat
diobservasi dan dapat diukur, Lerbin Aritonang (2011).
3. Indikator Pengukuran
Pada penelitian eksakta, pengukuran variabel tidak menimbulkan masalah misalnya
tentang panjang, berat, volume, dan lain-lain. Namun pada penelitian sosial pengukuran
variabel tidak dapat dilakukan sembarangan. Setelah diperoleh rujukan empiris tentang
sesuatu konsep, dengan perkataan lain apabila sudah dapat ditentukan definisi
operasionalnya maka perlu ditentukan indikator atau dimensinya.
Sebagai contoh tentang wanita subur yang dioperasionalkan sebagai wanita yang punya
anak maka akan diukur dari jumlah anak yang dilahirkan, dengan demikian ada variasi nilai
yang dapat diperoleh. Mungkin jumlah anak nol artinya wanita yang tidak mempunyai anak
disebut wanita tidak subur. Jumlah anak 1-2 disebut wanita cukup subur dan apabila anak
yang dilahirkan adalah 3-4 disebut sebagai wanita subur dan seterusnya.
Demikian pula dengan konsep wanita subur yang dioperasionalkan sebagai wanita yang
berat badannya ideal. Dalam hal inipun dapat diukur berdasarkan berat badan wanita, yang
hasilnya adalah berat badan kurang ideal sampai dengan yang melebihi berat badan ideal. Hal
inipun mencerminkan variasi nilai sehingga dalam konteks ini dapat dianggap sebagai variabel.
Berdasarkan definisi operasional peneliti mencari indikator yang tepat, yang sesuai
dengan variabel yang seharusnya diukur. Sekaran (2000) memberikan contoh bahwa variabel
motivasi berprestasi (achievement motivation) dapat diobservasi dan diukur berdasarkan
lima dimensi sebagai berikut: (1) Digerakkan oleh pekerjaan (driven by work); (2) Tidak
mungkin rileks (unable to relax); (3) Tidak suka terhadap sesuatu yang tidak efektif (impatience
with ineffectiveness); (4) Mencari tantangan (seek moderate challenge); (5) Mencari umpan
balik (seek feedback).
Kelima dimensi tersebut masing-masing akan dicari elemen-elemen yang
mencerminkan atribut dari setiap elemen. Misalnya, Sekaran selanjutnya mengukur ke lima
atribut tersebut, masing-masing ke dalam beberapa elemen pengukuran. Misalnya untuk
dimensi pertama, yaitu digerakkan oleh pekerjaan (driven by work) diuraikan tiga elemen yang
mencerminkan perilaku tersebut. Tiga elemen yang nantinya dipakai sebagai dasar
pembuatan pertanyaan atau pernyataan tersebut meliputi: selalu bekerja (constantly
working), enggan beristirahat dari pekerjaan (very luctant to take time off for anything) dan
tetap bertahan dari berbagai penghalang (persevering despite setbacks).
Praktik Kerja Industri 67
B. PRINSIP TEKNIK
Tantangan dalam pengumpulan data primer terkait dengan motivasi responden untuk
menyelesaikan setiap pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Pernyataan atau pertanyaan
yang terlalu rumit akan menimbulkan kebingungan responden. Oleh karenanya ada beberapa
hal yang penting diperhatikan dalam menyusun kuesioner penelitian. Cara penyusunan
kuesioner dapat mengikuti beberapa saran berikut:
1. Kesesuaian antara isi dan tujuan yang ingin dicapai kuesioner. Indikator variabel
sebaiknya dimanfaatkan secara tepat, jangan sampai terjadi kesalahan dalam
pengukuran variabel, Jogiyanto (2005), Sekaran (2000). Setiap indikator minimal
terdapat satu pernyataan tetapi bila memungkinkan lebih dari satu pernyataan,
Suharsimi (1996).
2. Jumlah indikator atau dimensi cukup untuk mengukur variabel. Misalnya, Sekaran
(2000) memberikan contoh bahwa variabel motivasi berprestasi (achievement
motivation) dapat diobservasi dan diukur berdasarkan lima dimensi.
3. Skala pada kuesioner. Penggunaan skala pengukuran yang tepat, dalam hal datanya
nominal, ordinal, interval dan ratio lebih disarankan menggunakan pertanyaan tertutup.
Skala dapat berjumlah genap atau ganjil. Untuk penelitian di Indonesia disarankan
menggunakan skala Likert genap misalnya dengan 4 tingkat (berarti skala genap) yaitu:
1 (sangat setuju), 2 (setuju), 3 (kurang setuju) dan 4 (tidak setuju). Sebab terdapat
kecenderungan bahwa individu di Indonesia cenderung bersikap netral, apabila
demikian responden lebih mempunyai sikap kepada setuju atau tidak setuju. Namun
apabila menggunakan skala Likert ganjil, misalnya lima tingkat skala Likert maka individu
di Indonesia dikhawatirkan akan cenderung memilih tiga (yang mencerminkan sikap
netral). Lima tingkatan skala Likert tersebut adalah: 1 (sangat setuju), 2 (setuju), 3
(netral), 4 (kurang setuju) dan 5 (tidak setuju).
4. Jumlah pertanyaan memadai, tidak terlalu banyak. Jumlah pertanyaan yang terlalu
banyak menimbulkan keenggan responden namun apabila terlalu sedikit dikhawatirkan
kurang mencerminkan opini responden. Jogiyanto (2005) menyarankan waktu untuk
menyelesaikan kuesioner tidak melebihi 10 menit.
5. Jenis dan bentuk kuesioner: tertutup dan terbuka, disesuaikan dengan karakteristik
sampelnya. Cooper dan Emory (1995) menyatakan terdapat lima faktor yang yang
mempengaruhinnya, yaitu: pertama, dari sisi tujuannya antara sekedar klarifikasi atau
menggali informasi. Kedua, tingkat informasi responden (degree of knowledge) terkait
topik penelitian. Ketiga, derajad pemikiran responden terkait dengan derajad intensitas
ekspresi responden. Keempat, kemudahan komunikasi dan motivasi responden. Kelima,
68 Praktik Kerja Industri
derajat pemahaman peneliti sehingga semakin kurang paham semakin diperlukan
pertanyaan terbuka.
6. Bahasa yang dipakai disesuaikan dengan kemampuan berbahasa responden. Kondisi
responden terkait dengan: tingkat pendidikan, budaya, kerangka referensi. Kalau
responden kurang memahami kuesioner, selayaknya (apabila memungkinkan) peneliti
bisa membagikannya secara langsung kepada responden. Bila demikian peneliti dapat
memberikan penjelasan langsung apabila terjadi ketidakpahaman responden.
7. Untuk melihat keseriusan responden perlu dinyatakan dalam pertanyaan (pernyataan)
yang positif maupun negatif sehingga informasi bias dapat diminimalisir. Misalnya:
pertanyaan no 6 adalah: “saya sangat menikmati kegiatan lomba karya ilmiah di kampus
saya”. Responden sekali waktu perlu dicek konsistensinya, misalnya pada pernyataan
berikutnya (dibuat lagi): “saya merasa jenuh dengan kegiatan lomba karya ilmiah di
kampus saya”.
8. Pertanyaan tidak mendua supaya tidak membingungkan responden. Misalnya
pernyataan: “saya yakin bahwa kegiatan ini mudah dan dapat segera diselesaikan dalam
waktu singkat” sebaiknya dipecah menjadi dua pernyataan berikut: pertama, ”Saya
yakin bahwa kegiatan ini mudah untuk dilaksanakan”, dan yang kedua: “Saya yakin
bahwa kegiatan ini dapat segera diselesaikan dalam waktu singkat”.
9. Pernyataan sebaiknya tidak memungkinkan jawaban ya atau tidak, disarankan untuk
membuat dalam beberapa gradasi, misalnya dalam suatu kontinuum yang
memungkinkan munculnya variasi nilai.
10. Pernyataan bukan hal yang sudah lama, masa lalu cenderung bias dan sudah dilupakan.
11. Pernyataan tidak bersifat mengarahkan, tidak bersifat menggiring. Misalnya “para
pimpinan di tempat kerja saya cenderung bersikap bijaksana, apakah anda setuju? 1
(sangat setuju), 2 (setuju), 3 (kurang setuju) dan 4 (tidak setuju)”. Responden seolah
digiring untuk bersikap menyetujui pernyataan yang menjadi subyektivitas peneliti.
12. Pernyataan tidak membingungkan responden. Misalnya pernyataan: ”saya merasa
bahagia”, mungkin perlu diperjelas dengan: “saya merasa bahagia dalam kehidupan
perkawinan saya”. Ada kemungkinan responden bingung karena dia merasa bahagia
dalam kehidupan perkawinannya namun tidak bahagia dalam pekerjaannya.
13. Pernyataan tidak terlalu memberatkan responden. Seandainya berupa pernyataan
ataupun pertanyaan terbuka, perlu kronologi yang baik artinya diawali dengan hal-hal
ringan dan umum, dan seterusnya sampai kepada hal-hal yang bersifat spesifik.
14. Jumlah dan urutan pertanyaan memberikan semangat responden untuk
menyelesesaikannya sampai tuntas.
Praktik Kerja Industri 69
Disamping hal-hal tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan mutu informasi yang
diperoleh maka peneliti harus memperhatikan kemauan dan kemampuan responden untuk
bekerjasama serta tingkat pemahaman responden terhadap tema penelitian. Untuk
meningkatkan motivasi responden peneliti perlu memperhatikan pula hal-hal berikut,
Jogiyanto (2005), Sekaran (2000), Cooper (1995):
1. Pada bagian pengenalan (pendahuluan) sebaiknya diungkapkan tujuan penelitian secara
jelas namun singkat serta tidak perlu kalimat yang panjang dan lebar.
2. Pemberitahuan awal (introduction to completion) merupakan pemberitahuan lebih dulu
kepada responden. Misalnya lewat telepon atau pada saat akan membagikan kuesioner,
ungkapkan bahwa peneliti akan menunggu kuesioner.
3. Tindak lanjut diperlukan untuk mengingatkan kembali kepada responden atas kuesioner
yang telah diterima responden dan bila memungkinkan akan menelepon kembali untuk
mengingatkan pengisisan kuesioner serta pengambilan kembali oleh peneliti.
4. Survei yang disponsori oleh lembaga tertentu kadang-kadang lebih mendapat respon
yang lebih baik dibandingkan survei tanpa sponsor
5. Khususnya kuesioner yang dikirim lewat pos, akan lebih efektif apabila disertai perangko
untuk mengirimkan kembali pada peneliti sehingga tidak menimbulkan beban
tambahan bagi responden.
6. Kuesioner tanpa identitas responden kadang-kadang lebih disukai sehingga responden
lebih jujur dalam mengungkapkan opininya.
7. Pemberian insentif atau souvenir kadang-kadang juga memberikan motivasi pada
responden untuk mengisi kuesioner
8. Penentuan batas waktu atau pemberitahuan tentang ketentuan tanggal yang diberikan
peneliti, akan mempercepat respon sehingga kuesioner lebih cepat sampai ke peneliti.
9. Secara keseluruhan diatur supaya tampak tidak terlalu banyak, kalau memungkinkan
diberi warna supaya menarik.
C. PRINSIP PENGENDALIAN
Prinsip pengendalian bertujuan supaya tindakan pengukuran variabel dapat
menghasilkan data yang representatif. Kegiatan mengukur sesuatu relatif mudah dilakukan
apabila ada kejelasan objek yang diukur, disertai adanya alat ukur yang cocok untuk mengukur
objek tersebut. Misalnya mengukur berat barang akan lebih tepat bila menggunakan alat ukur
timbangan, sedangkan untuk mengukur tinggi sesuatu barang ataupun orang maka akan lebih
tepat bila menggunakan alat ukur yang berupa meteran. Untuk mengukur motivasi bekerja
seseorang akan menggunakan alat ukur apa? Adakah instrumen penelitiannya?
70 Praktik Kerja Industri
Khususnya pada penelitian sosial, pengukuran variabel cukup menentukan keberhasilan
penelitian. Variabel sosial selayaknya diukur dengan alat yang tepat, yang berupa instrumen
penelitian. Terkait dengan ketepatan alat ukur, dalam hal ini biasa disebut dengan validitas
instrumen penelitian. Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur sesuatu yang
seharusnya diukur. Instrumen untuk mengukur kinerja (karyawan) berbeda dengan instrumen
untuk mengukur produktivitas (karyawan) karena terdapat perbedaan yang jelas antara
konsep kinerja karyawan dan konsep produktivitas karyawan.
Terdapat banyak jenis validitas dan cara-cara pengukurannya, salah satunya adalah
analisis korelasi. Demikian juga banyak teknik yang dapat dipakai untuk mengukur reliabilitas
instrumen penelitian, salah satunya adalah Cronbach Alpha. Dengan bantuan spreadsheet
komputer akan sangat membantu cepatnya proses pengukuran.
Reliabilitas instrumen penelitian berhubungan dengan konsistensi hasil yang diperoleh
dari alat ukur ini. Apabila terdapat konsistensi hasil (data) maka instrumen penelitian dapat
dikatakan reliabel. Instrumen dikatakan mempunyai reliabilitas yang tinggi apabila apabila alat
ukur tersebut mantap, stabil, dapat diandalkan (dependability) dan dapat diramalkan
(predictability) Nazir (1998).
Lebih lanjut dinyatakan bahwa pengertian reliabilitas dapat dipahami dengan menjawab
tiga pertanyaan sebagai berikut:
1. Jika set objek yang sama diukur berkali-kali dengan alat ukur yang sama, apakah kita
akan memperoleh hasil yang sama?
2. Apakah ukuran yang diperoleh dengan menggunakan alat ukuran tertentu adalah
ukuran sebenarnya dari objek tersebut?
3. Berapa besar kesalahan (error) yang kita peroleh dengan menggunakan ukuran tersebut
terhadap objek lain?
Data yang baik tergantung pada validitas dan reliabilitas instrumen penelitiannya.
Instrumen yang baik selayaknya dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Instrumen yang valid
berarti instrument yang tepat. Misalnya instrumen kinerja karyawan adalah valid apabila
benar-benar mengukur kinerja karyawan, bukan mengukur produktivitas karyawan.
Instrumen yang reliabel akan menjamin konsistensi hasil (data) yang dikumpulkan. Instrumen
kinerja karyawan yang reliabel akan menghasilkan konsistensi data apabila digunakan
berulang kali untuk mengukur kinerja karyawan. Reliabilitas mencerminkan ketepatan alat
ukur sehingga hasil yang diperoleh akan stabil, artinya dapat diandalkan (dependability) dan
diramalkan (predictability), serta akurat dan konsisten.
Sugiyono (2004) menyatakan bahwa instrumen yang reliabel belum tentu valid dan
reliabilitas instrumen menjadi syarat mutlak untuk pengujian validitas. Marija J Noursis (1993)
menyatakan bahwa meskipun kondisi pengukuran mengalami perubahan maka hasil
Praktik Kerja Industri 71
pengukuran seharusnya tetap, tidak mengalami perubahan. Dengan kata lain instrumen
penelitian harus reliabel, uji reliabilitas instrument penelitian harus dilengkapi dengan uji
validitas. Sementara itu Hair dkk (1995) menyatakan bahwa validitas tidak menjamin adanya
reliabilitas dan sebaliknya, validitas dan reliabilitas merupakan dua hal yang berbeda namun
pada kondisi yang saling terkait.
Namun hal yang mungkin memudahkan peneliti adalah dengan memanfaatkan
kuesioner yang sudah ada yang pernah dipakai oleh peneliti lain. Beberapa contohnya adalah
Job Description Index (JDI), ataupun melalui modifikasi instrumen yang satu tema dengan
penelitian yang sedang dilakukan misalnya untuk bidang pemasaran dapat memanfaatkan
kuesioner bidang pemasaran yang dapat dilihat pada Burner dan Hensel (1992). Peneliti dapat
melakukan penyesuaian terhadap instrumen yang dipakainya, karena terdapat perbedaan
bahasa, budaya, tingkat pemahaman dan wilayah responden.
Instrumen pada ilmu eksakta biasanya telah diakui validitas dan reliabilitasnya kecuali
instrumen tersebut telah rusak ataupun palsu. Sedangkan pada ilmu sosial sudah ada yang
baku atau standar namun peneliti harus mampu menyusun sendiri. Kuesioner penelitian yang
dibuat sendiri oleh peneliti akan lebih layak apabila dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas.
Pada prinsipnya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Konsultasikan dengan pakar mengenai konstruk penelitian.
2. Instrumen penelitian diujicobakan kepada 30 responden, Sugiyono (2004). Sedangkan
Agus Sartono (2001) menyatakan bahwa uji coba terhadap 39 (sebesar 12,68% dari total
232 buah kuesioner) sudah memadai.
3. Dari data yang sudah terkumpul kemudian dilakukan uji reliabilitas dan uji validitas.
Validitas dapat dilihat dari berbagai segi, demikian juga dengan uji signifikansinya. Oleh
karenanya dapat dilakukan berdasarkan uji signifikansi statistik tertentu sesuai dengan
kebutuhan misalnya teknik korelasi ataupun dengan ukuran statistik tertentu misalnya
Cronbach Alpha untuk mengukur reliabilitas. Instrumen dikatakan tidak reliabel apabila
nilai Cronbach Alpha kurang dari 0,6 Sekaran (2000). Sementara itu uji validitas dapat
dilakukan antara lain dengan menghitung korelasi Pearson antara skor item dengan skor
total instrumen. Marija J Noursis (1993) menyatakan bahwa nilai korelasi negatif
dianggap melanggar atau tidak mencukupi untuk mengukur hubungan, sehingga
korelasi tersebut harus signifikan, positif dan lebih besar dari 0,2 Sedangkan Marsun
dalam Sugiyono (2004) menyatakan bahwa nilai korelasi harus lebih dari 0,3
4. Analisis lebih lanjut adalah membuang pernyataan yang tidak valid. Akhirnya kuesioner
siap disebarkan kepada responden.
72 Praktik Kerja Industri
D. TEKNIK PENYUSUNAN INSTRUMEN
Jenis kuisioner ditentukan oleh metode penelitian yang digunakan. Untuk penelitian
kualitatif, informasi yang ingin didapatkan mayoritas adalah informasi yang lebih mendalam
sehingga kuisioner yang diperlukan adalah kuisioner yang dapat mengeksplorasi jawaban
responden. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif, informasi yang ingin didapatkan
mayoritas adalah informasi yang menyebar, sehingga jumlah responden yang dibutuhkan
besar dan pertanyaan-pertanyaan dalam kuisioner dirancang agar cepat dan mudah dijawab
oleh responden.
Dalam menyusun kuisioner terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu
penampilan, jenis pertanyaan, dan item jawaban yang disediakan. Penampilan dalam
kuisioner walaupun tidak menunjang penelitian tetapi penting untuk menarik minat
responden untuk menjawab pertanyaan di dalam kuisioner. Penampilan kuisioner yang
tertata rapi, dengan struktur pertanyaan yang baik akan membuat responden mudah untuk
menjawab. Struktur jawaban sebaiknya dikelompokkan berdasarkan isi pertanyaan dan
diurutkan dari yang termudah dijawab hingga tersulit untuk dijawab, misalnya kelompok
pertanyaan demografi atau identitas responden, perilaku, pendapat. Apabila kuisioner
mempunyai banyak halaman bentuk buku dapat menjadi suatu pilihan.
Jenis pertanyaan yang ada di dalam kuisioner sangat bergantung pada variabel-variabel
yang hendak diukur dalam penelitian. Jenis pertanyaan juga sangat dipengaruhi oleh jenis
metode penelitian yang digunakan. Untuk penelitian yang kualitatif maka lebih banyak
pertanyaan-pertanyaan terbuka, bahkan hampir semua open question. Untuk penelitian yang
kuantitatif maka lebih banyak pertanyaan-pertanyaan tertutup, atau bisa gabungan terbuka
dan tertutup.
Item jawaban yang disediakan harus sesuai ukuran variabel yang sedang dicari. Apabila
skala data yang diinginkan adalah skala nominal maka item jawabannya juga harus berskala
nominal, demikian juga dengan skala ordinal. Apabila skala data yang diinginkan adalah skala
interval atau rasio maka pertanyaannya harus berbentuk pertanyaan terbuka. Hati-hati dalam
memberikan pertanyaan yang mengandung suatu ukuran frekuensi, misalnya sering, jarang,
kadang-kadang. Item yang disediakan harus netral dan balanced, sehingga tidak
mengarahkannya untuk menjawab jawaban tertentu. Pertanyaan filter bisa dipergunakan
untuk menyaring responden yang tidak masuk dalam kualifikasi. Keterangan untuk jawaban
jangan terlalu jauh dari pertanyaannya. Hindari penggunaan istilah-istilah yang tidak umum,
berbahasa asing dan membingungkan.
Kuisioner yang baik adalah kuisioner yang mampu menghubungkan antara tujuan
konsep variable kuisioner metode pengolahan data. Untuk menyusun kuisioner yang
Praktik Kerja Industri 73
baik dapat ditempuh dengan mengikuti delapan langkah. Adapun langkah-langkah dalam
menyusun kuisioner dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:
1. Langkah 1 : Spesifikasikan informasi yang diperlukan.
a. Pastikan semua informasi didapatkan seluruhnya untuk menjawab permasalahan,
permasalahan penelitian.
b. Hipotesis, karakteristik tujuan penelitian.
c. Dapatkan target populasi yang jelas.
2. Langkah 2 : Tipe metode wawancara.
Tentukan tipe wawancara yang ingin dilakukan.
3. Langkah 3 : Isi pertanyaan secara individual.
a. Apakah pertanyaan tersebut perlu.
b. Apakah ada beberapa pertanyaan yang membingungkan.
4. Langkah 4 : Memilih Kata-kata dalam pertanyaan.
a. Definisikan isu dalam bentuk Siapa, Apakah, Kapan, Dimana, dan Mengapa.
b. Gunakan kata-kata yang biasa dan mudah dipahami responden.
c. Hindari kata-kata yang membingungkan responden: biasanya, normalnya,
seringnya, selalu, kadang-kadang dst.
d. Hindari pertanyaan dengan kata-kata yang menuntun responden untuk menjawab
jawaban tertentu.
e. Hindari alternatif pilihan yang tidak jelas.
f. Hindari asumsi yang tidak jelas.
g. Responden tidak dibolehkan memberikan perkiraan secara umum.
h. Gunakan pernyataan yang positif.
5. Langkah 5 : Tentukan Urutan Pertanyaan
a. Pertanyaan pembuka harus menarik, sederhana dan mudah.
b. Pertanyaan umum harus diletakkan dimuka.
c. Informasi dasar harus didapatkan diawal, dilanjutkan dengan klasifikasi dan
diakhiri dengan identifikasi informasi.
d. Pertanyaan sulit, sensitif, dan kompleks harus diletakkan diakhir.
e. Pertanyaan umum harus mendahului pertanyaan khusus.
f. Pertanyaan harus mengikuti urutan logika.
g. Cabang-cabang pertanyaan harus dirancang secara hati-hati untuk mendapatkan
semua kemungkinan.
74 Praktik Kerja Industri
h. Pertanyaan yang menjadi cabang harus diletakkan sedekat mungkin dengan
pertanyaan penyebab adanya cabang dan pertanyaan cabang harus durutkan
sehingga memudahkan responden memberikan jawaban tambahan yang diminta.
6. Langkah 6 : Bentuk dan Tampilan
a. Pisahkan kuisioner dalam beberapa bagian.
b. Pertanyaan dalam setiap bagian harus diberi nomor.
c. Kuisioner harus diberi kode terlebih dahulu.
d. Kuisioner harus diberi nomer secara serial.
7. Langkah 7 : Memperbanyak kuisioner
a. Kuisioner harus mempunyai penampilan yang professional.
b. Format seperti buku catatan harus digunakan untuk kuisionare yang panjang.
c. Setiap pertanyaan harus diperbanyak dalam satu halaman.
d. Jawaban vertikal dapat digunakan.
e. Kisi-kisi berguna bila ada sejumlah pertanyaan yang berhubungan yang
menggunakan himpunan jawaban yang sama.
f. Kecenderungan untuk menjadikan satu pertanyaan untuk memperpendek
kuisioner harus dihindari.
g. Arahan pengisian harus diletakkan dekat pertanyaan yang diberikan arahan.
8. Langkah 8 : Pretest
a. Ujicoba atau pretest kusioner harus selalu dilakukan.
b. Semua aspek pada kuisoner harus diuji, termasuk isi pertanyaan, kata-kata,
bentuk, dan tampilan, kesulitan pertanyaan dan instruksinya.
c. Responden yang diberi ujicoba harus responden yang akan disurvai sebenarnya.
d. Awali ujicoba dengan menggunakan intervew secara personal.
e. Bila survai ingin dilakukan dengan menggunakan telepon atau email, ujicoba juga
dilakukan dengan cara yang sama.
f. Variasi dalam wawancara harus dilakukan dalam ujicoba.
g. Ukuran sampel dalam uji coba kecil minimum 30 responden.
h. Gunakan analisis awal dan lakukan identifikasi masalah.
i. Sesudah revisi secara signifikan dilakukan pada kuisioner ujicoba lain bisa dilakukan
dengan menggunakan sampel yang berbeda.
j. Respons yang didapatkan dari ujicoba harus dikoding dan dianalisis.
Praktik Kerja Industri 75
Latihan
Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan
berikut!
1) Sekaran memberikan contoh bahwa variabel motivasi berprestasi (achievement
motivation) dapat diobservasi dan diukur berdasarkan lima dimensi, sebutkan!.
2) Penggunaan skala pengukuran yang tepat dalam suatu penelitian sangat penting untuk
diperhatikan. Sebutkan jenis skala data yang biasa digunakan dalam penelitian!.
3) Jelaskan bagaimana mengukur realibilitas instrumen pengumpulan data yang baik!.
Ringkasan
1. Kuesioner merupakan alat pengumpulan data primer dengan metode survei untuk
memperoleh opini responden. Kuesioner dapat didistribusikan kepada responden
dengan cara: (1) Langsung oleh peneliti (mandiri); (2) Dikirim lewat pos
(mailquestionair); (3) Dikirim lewat komputer misalnya surat elektronik (e-mail).
2. Instrumen pada ilmu eksakta biasanya telah diakui validitas dan reliabilitasnya kecuali
instrumen tersebut telah rusak ataupun palsu. Sedangkan pada ilmu sosial sudah ada
yang baku atau standart namun peneliti harus mampu menyusun sendiri. Kuesioner
penelitian yang dibuat sendiri oleh peneliti akan lebih layak apabila dilakukan uji
validitas dan uji reliabilitas.
3. Kusioner yang baik adalah kuisioner yang mampu menghubungkan antara tujuan
konsep variable kuisioner metode pengolahan data. Untuk menyusun kuisioner
yang baik dapat ditempuh dengan mengikuti delapan langkah.
76 Praktik Kerja Industri
Tes 1
Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar!
1) Kuesioner penelitian yang dibuat sendiri oleh peneliti akan lebih layak apabila dilakukan
uji validitas dan uji reliabilitas. Pada prinsipnya uji validitas dan uji reliabilitas dapat
dilakukan dengan cara....
A. Cermati semua pertanyaan apakah sesuai dengan topik penelitian.
B. Sesuaikan pertanyaan dengan motode penelitian yang digunakan.
C. Menyesuaikan jumlah pertanyaan dengan topik penelitian.
D. Konsultasikan dengan pakar mengenai konstruk penelitian.
2) Jenis pertanyaan yang ada di dalam kuisioner sangat bergantung pada variabel-variabel
yang hendak diukur dalam penelitian. Jenis pertanyaan juga sangat dipengaruhi oleh….
A. Jumlah responden yang menjadi sasaran penelitian.
B. Jenis metode penelitian yang digunakan.
C. Topik penelitian yang akan dilakukan.
D. Luasnya cakupan wilayah penelitian.
3) Kuisioner yang baik harus memperhatikan bentuk dan tampilan, adapun yang bukan
merupakan ciri dari bentuk dan tampilan kuisioner yang baik adalah....
A. Kuisioner harus disusun dengan menggunakan bahasa yang umum.
B. Pertanyaan dalam setiap bagian harus diberi nomor.
C. Kuisioner harus diberi kode terlebih dahulu.
D. Kuisioner harus diberi nomer secara serial.
Praktik Kerja Industri 77
Topik 2
Instrumen Pengawasan Sanitasi Industri
A. SASARAN PENGAWASAN SANITASI INDUSTRI
Sebelum Saudara melakukan penyusunan instrumen pengawasan sanitasi industri,
sebaiknya Saudara sudah benar-benar memahami dan menguasai teknik penyusunan
instrumen sebagaimana dijabarkan secara lengkap pada Topik 1. Hal lain yang juga harus
dipersiapkan dalam penyusunan instrumen adalah peraturan yang berlaku terkait dengan
materi pengawasan, baik yang berlaku secara nasional seperti undang undang, peraturan
pemerintah, dan peraturan menteri, ataupun peraturan yang berlaku secara lokal misalnya
peraturan daerah, dan peraturan gubernur.
Instrumen yang akan Saudara susun tentunya sesuai dengan kebutuhan dan sasaran
dalam pengawasan sanitasi industri. Adapun sasaran pengawasan sanitasi industri
sebagaimana disebutkan dalam Bab 2 meliputi:
1. Penyediaan air bersih
2. Pengolahan limbah cair
3. Penyehatan tanah adan pengelolaan sampah
4. Penyehatan makanan dan minuman
5. Penyehatan udara
6. Pengendalian vector dan binatang pembawa penyakit
7. Housekeeping atau tata graha
8. Jamban dan peturasan
9. Fasilitas cuci tangan
Untuk mempermudah dalam penyusunan instrumen pengawasan sanitasi industri
secara lengkap, maka berikut ini akan diuraikan dan dijabarkan masing masing sasaran
pengawasan dengan memberikan contoh dalam penyusunan instrumen berdasarkan pada
peraturan yang berlaku.
B. INSTRUMEN PENGAWASAN PENYEDIAAN AIR BERSIH
Terkait dengan pengawasan penyediaan air bersih di industri terdapat peraturan
menteri kesehatan yang perlu diperhatikan, pertama Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor
70 Tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri, kedua
78 Praktik Kerja Industri
Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu
Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Hygiene Sanitasi,
Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum.
Dalam Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 70 Tahun 2016, meyebutkan bahwa
Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL) merupakan konsentrasi atau kadar dari
setiap parameter media lingkungan yang ditetapkan dalam rangka perlindungan kesehatan
pekerja sesuai satuannya berupa angka minimal yang diperlukan, atau maksimal atau kisaran
yang diperbolehkan, bergantung pada karakteristik parameter.
Media lingkungan air meliputi air minum dan air untuk keperluan higiene dan sanitasi,
baik kuantitas maupun kualitas. Kecukupan air minum untuk lingkungan kerja industri dihitung
berdasarkan jenis pekerjaan dan lamanya jam kerja setiap pekerja untuk setiap hari. Standar
Baku Mutu (SBM) di bawah ini berlaku secara umum untuk setiap pekerja setiap hari. Jika jenis
pekerjaan memerlukan lebih banyak air minum, maka kebutuhannya disesuaikan dengan jenis
pekerjaan tersebut.
Kecukupan penyediaan air minum untuk pekerja dipersyaratkan minimal sebanyak 5
liter/orang/hari. Sedangkan kecukupan air untuk keperluan higiene dan sanitasi dihitung
berdasarkan kebutuhan minimal dikaitkan dengan perlindungan kesehatan dasar dan higiene
perorangan. Ketersediaan air sebanyak 20 liter/orang/hari hanya mencukupi untuk kebutuhan
higiene dan sanitasi minimal, sehingga untuk menjaga kondisi kesehatan pekerja yang optimal
diperlukan volume air yang lebih, yang biasanya berkisar antara 50-100 liter/orang perhari.
Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 32 Tahun 2017
menyebutkan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media Air untuk Keperluan
Higiene Sanitasi meliputi parameter fisik, biologi, dan kimia yang dapat berupa parameter
wajib dan parameter tambahan. Parameter wajib merupakan parameter yang harus diperiksa
secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan
parameter tambahan hanya diwajibkan untuk diperiksa jika kondisi geohidrologi
mengindikasikan adanya potensi pencemaran berkaitan dengan parameter tambahan. Air
untuk keperluan higiene sanitasi tersebut digunakan untuk pemeliharaan kebersihan
perorangan seperti mandi dan sikat gigi, serta untuk keperluan cuci bahan pangan, peralatan
makan, dan pakaian. Selain itu air untuk keperluan higiene sanitasi dapat digunakan sebagai
air baku air minum.
Terkait dengan persyaratan kesehatan air untuk keperluan hygiene sanitasi dalam
Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 32 Tahun 2017 menyebutkan bahwa air dalam
keadaan terlindung dari sumber pencemaran, binatang pembawa penyakit, dan tempat
perkembangbiakan vektor :
Praktik Kerja Industri 79
1. Tidak menjadi tempat perkembangbiakan vektor dan binatang pembawa penyakit.
2. Jika menggunakan kontainer sebagai penampung air harus dibersihkan secara berkala
minimum 1 kali dalam seminggu.
Lebih jauh dalam peraturan diatas menyebutkan bahwa air untuk keperluan hygiene
sanitasi harus aman dari kemungkinan kontaminasi :
1. Jika air bersumber dari sarana air perpipaan, tidak boleh ada koneksi silang dengan pipa
air limbah di bawah permukaan tanah.
2. Jika sumber air tanah non perpipaan, sarananya terlindung dari sumber kontaminasi
baik limbah domestik maupun limbah industri.
3. Jika melakukan pengolahan air secara kimia, maka jenis dan dosis bahan kimia harus
tepat.
Persyaratan kesehatan lingkungan air minum untuk kepentingan di industri terdapat
beberapa ketentuan sebagai berikut:
1. Berasal dari sumber air yang improved atau terlindung (perpipaan, mata air terlindung,
sumur bor terlindung, sumur gali terlindung dan penampungan air hujan terlindung).
2. Tersedia dalam jumlah yang cukup dan kontinyu.
3. Kualitas air minum diperiksa secara berkala.
4. Memenuhi kualitas fisik.
Adapun persyaratan kesehatan lingkungan air untuk keperluan hygiene dan sanitasi
ditetapkan sebagai berikut:
1. Berasal dari sumber air yang improved atau terlindung (perpipaan, mata air terlindung,
sumur bor terlindung, sumur gali terlindung dan penampungan air hujan terlindung).
2. Tersedia dalam jumlah yang cukup dan kontinu.
3. Air yang berasal dari pengolahan air limbah atau grey water hanya digunakan untuk
menggelontor toilet dan menyiram tanaman.
4. Kualitas air harus diperiksa secara berkala.
5. Memenuhi kualitas fisik.
Selanjutnya dalam upaya pengawasan penyediaan air untuk kepentingan hygiene
industri di tempat kerja, dijelaskan bahwa setiap penyelenggara baik badan usaha, usaha
perorangan, kelompok masyarakat dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan
penyediaan air untuk keperluan hygiene sanitasi, wajib menjamin kualitas air untuk keperluan
80 Praktik Kerja Industri
hygiene sanitasi yang memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan
Kesehatan.
Untuk menjaga agar kualitas air untuk keperluan hygiene sanitasi senantiasa dalam
keadaan memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan
perlu dilakukan pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal merupakan
pengawasan yang dilakukan oleh penyelenggara melalui penilaian mandiri, pengambilan, dan
pengujian sampel air yang dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun. Sedangkan
pengawasan eksternal dilakukan oleh tenaga kesehatan lingkungan yang terlatih pada dinas
kesehatan kabupatena atau kota, atau kantor kesehatan pelabuhan untuk lingkungan wilayah
kerjanya.
Untuk melakukan pengawasan penyediaan air keperluan hygiene sanitasi di industri
dapat menggunakan contoh formulir pengawasan sebagai berikut:
Praktik Kerja Industri 81
Tabel 3.1.
INSTRUMEN PENGAWASAN PENYEDIAAN AIR
KEPERLUAN HYGIENE SANITASI INDUSTRI
Nama Perusahaan : ………………………………………………..
Alamat : ………………………………………………..
Kabupaten/Kota : ………………………………………………..
Provinsi : ………………………………………………..
Jenis Peruntukan Air : Hygiene-sanitasi
Tanggal Pengawasan : ...................................................
ADA / DIPERIKSA
NO PARAMETER TIDAK KET
ADA TIDAK
BERLAKU
1. Fisik
a. Kekeruhan
b. Warna
c. Zat padat terlarut (TDS)
d. Suhu
e. Rasa
f. Bau
2. Biologi
a. Total coliform
b. E. coli
3. Kimia wajib
a. pH
b. Besi
c. Fluorida
d. Kesadahan
e. Mangan
f. Nitrat, sebagai N
g. Nitrit, sebagai N
h. Sianida
i. Diterjen
j. Pestisida total
Kimia tambahan
a. Air raksa
b. Arsen
c. Kadmium
82 Praktik Kerja Industri
ADA / DIPERIKSA
NO PARAMETER TIDAK KET
ADA TIDAK
BERLAKU
d. Kromium (valensi 6)
e. Selenium
f. Seng
g. Sulfat
h. Timbal
i. Benzene
j. Zat organik (KMnO4)
4. Tidak ada koneksi silang dengan pipa air
limbah di bawah permukaan tanah (jika
air bersumber dari sarana air perpipaan)
5. Sumber air tanah non perpipaan,
sarananya terlindung dari sumber
kontaminasi baik limbah domestik
maupun industri.
6. Tidak menjadi tempat
berkembangbiaknya vektor dan binatang
pembawa penyakit
7. Jika melakukan pengolahan air secara
kimia, maka jenis dan dosis bahan kimia
harus tepat
8 Jika menggunakan kontainer sebagai
penampung air harus dibersihkan secara
berkala minimum 1 kali dalam seminggu.
Penanggung Jawab Petugas Pengawasan
........................................... .................................................
Praktik Kerja Industri 83
C. INSTRUMEN PENGAWASAN PENGOLAHAN LIMBAH CAIR
Manusia dan lingkungan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam sebagian
besar aktivitasnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, manusia membutuhkan
lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Interaksi antara manusia dan lingkungan
tersebut jika dilakukan dengan tidak bertanggung jawab akan mengganggu keseimbangan dan
kelestarian alam, yang pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan manusia itu sendiri.
Oleh karena itu, perlu upaya menjaga kelestarian lingkungan supaya lingkungan dapat
berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat dimanfaatkan manusia secara optimal.
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 H ayat (1) disebutkan
bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan”, sehingga lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak
konstitusional bagi setiap warga negara. Oleh karena itu pemerintah dan pemangku
kepentingan wajib untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam
melaksanakan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup tetap menjadi penunjang
hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.
Kegiatan pembangunan yang didukung ilmu pengetahuan dan teknologi, selain
meningkatkan kualitas hidup dan merubah gaya hidup manusia, juga mengandung resiko
terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan apabila tidak arif bijaksana dalam
melaksanakannya. Dalam konteks pembangunan yang sangat dinamis di berbagai daerah,
muncul beragam usaha dan kegiatan oleh manusia, diantaranya dalam bentuk industri. Jenis
kegiatan tersebut berpotensi menghasilkan air limbah. Air limbah sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air diperbolehkan dibuang ke media lingkungan dalam hal ini air sungai dengan
izin tertulis dari Bupati/Walikota dan telah memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.
Penetapan Baku Mutu Air Limbah dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab; asas
kelestarian dan berkelanjutan; dan asas manfaat. Adapun tujudan dari pengaturan penetapan
Baku Mutu Air Limbah adalah untuk:
1. Pedoman bagi Bupati/Walikota dalam mengeluarkan izin pembuangan air limbah.
2. Pedoman bagi Bupati/Walikota dalam memberikan saran, arahan, petunjuk dan
pembinaan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
3. Mencegah terjadinya pencemaran air.
4. Mewujudkan kualitas air yang sesuai dengan peruntukannya.
5. Menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup.
6. Penilaian dokumen lingkungan, rekomendasi dan izin lingkungan, dan
84 Praktik Kerja Industri
7. Instrumen pengendalian pencemaran lingkungan.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup R.I. Nomor 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air
Limbah pasal 16 menyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 ayat (1) wajib:
a. Melakukan pemantauan kualitas air limbah paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulannya
sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan dalam izin pembuangan air limbah.
b. Melaporkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-
kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada penerbit izin pembuangan air limbah, dengan
tembusan kepada Menteri dan gubernur sesuai dengan kewenangannya.
c. Laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat:
1) catatan debit air limbah harian.
2) bahan baku dan/atau produksi senyatanya harian.
3) kadar parameter baku mutu limbah cair, dan
4) penghitungan beban air limbah.
d. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c disusun berdasarkan format pelaporan
yang telah ditetapkan.
Terkait dengan pengelolaan limbah industri pada Peraturan Menteri Kesehatan R.I.
Nomor 70 Tahun 2016 tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri
menegaskan suatu industri harus memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan, termasuk
sarana pembuangan air limbah, dengan ketentuan :
1. Air limbah dari berbagai sumber dapat mengalir dengan lancar dan salurannya dalam
keadaan tertutup,
2. Tersedia instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang memadai.
Contoh instrumen pengawasan pengelolaan limbah industri sesuai dengan Peraturam
Menteri Lingkungan Hidup R.I. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.
Praktik Kerja Industri 85
Tabel 3.2.
INSTRUMEN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI
Nama Industri :
Kode Sampel :
Lokasi Pengambilan Contoh Uji :
Jam,Tanggal, Tahun Pengambilan :
Contoh Uji
Petugas Pengambil Contoh Uju :
Debit air limbah saat pengambilan : ............................ m3 / detik
contoh uji
Tanggal, Tahun penerimaan :
contoh uji
Tanggal, Tahun analisis contoh uji :
Lama waktu produksi : ....................................... jam / hari
Jumlah bahan baku waktu : ....................................... ton / hari (satuan
pengambilan contoh uji (satuan disesuaikan atau dikonversi)
bahan baku / hari)
Jumlah produksi waktu : ....................................... ton / hari (satuan
pengambilan contoh uji (satuan disesuaikan atau dikonversi)
produksi / hari)
86 Praktik Kerja Industri
Hasil Analisis Baku Mutu
Beban Beban Metode
No Kadar Kadar
Parameter Pencemaran Pencemaran Uji
(mg/L) (mg/L)
(kg/ton) (kg/ton)
1. BOD
2. COD
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
9. .....
10. pH
Kuantitas air .............................. m3/ton ............................. m3/ton
11. limbah paling produk atau bahan baku produk atau bahan baku
tinggi
..................................,.............................
Tanda tangan & Cap Lab
..................................................
Praktik Kerja Industri 87
D. INSTRUMEN PENGAWASAN PENYEHATAN TANAH DAN PENGELOLAAN
SAMPAH
Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar dan
Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri Pasal 1 menyebutkan bahwa pengaturan
standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri bertujuan untuk:
1. Mewujudkan kualitas lingkungan kerja industri yang sehat dalam rangka menciptakan
pekerja yang sehat dan produktif;
2. Mencegah timbulnya gangguan kesehatan, penyakit akibat kerja, dan kecelakaan kerja;
3. Mencegah timbulnya pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri.
Selanjutnya pada Pasal 2 disebutkan bahwa setiap industri wajib memenuhi standar dan
menerapkan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri. Standar kesehatan lingkungan
kerja industri meliputi:
1. Nilai ambang batas faktor fisik dan kimia;
2. Indikator pajanan biologi; dan
3. Standar baku mutu kesehatan lingkungan.
Sedangkan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri meliputi:
1. Persyaratan faktor fisik;
2. Persyaratan faktor biologi;
3. Persyaratan penanganan beban manual; dan
4. Persyaratan kesehatan pada media lingkungan.
Standar baku mutu media tanah yang berhubungan dengan kesehatan meliputi kualitas
tanah dari aspek biologi, kimia dan radioaktivitas.
1. Standar Baku Mutu biologi tanah meliputi angka telur cacing (Ascaris lumbricoides) dan
fecal coliform yang mengindikasikan adanya pencemaran tanah oleh tinja.
2. Standar Baku Mutu kimia tanah meliputi kimia anorganik yang terdiri dari 7 parameter
yaitu Timah hitam, Arsen, Kadmium, Krom (valensi 6), senyawa Merkuti, Boron dan
Tembaga dalam satuan mg/kg. Sedangkan parameter organik meliputi BaP, DDT,
Dieldrin, PCP, Dioksin (TCDD) dan Dioxin-like PCBs.
3. Standar Baku Mutu radioaktivitas sebagai indikator pencemaran Radon dengan satuan
Bq/m3 tanah berkisar antara 100-300, di mana 3,7 Bq/m3 adalah setara dengan 1 pCi/L
88 Praktik Kerja Industri
Persyaratan kesehatan lingkungan media tanah yang baik untuk kegiatan industri,
dipersyaratkan sebagai berikut:
1. Memenuhi persyaratan konstruksi untuk jenis tanah peruntukan industri.
2. Tidak tercemar oleh limbah domestik maupun industri baik berupa limbah padat, cair
maupun gas.
3. Tidak menjadi tempat perkembangbiakan vektor dan binatang pembawa penyakit.
4. Jika tidak memungkinkan untuk mendapatkan kualitas tanah sesuai dengan persyaratan
teknis bangunan industri maka perlu dilakukan rekayasa atau remediasi tanah agar tidak
menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan dampak kesehatan pekerja
Contoh instrumen pengawasan kualitas tanah lingkungan industri sesuai dengan
Peraturam Menteri Kesehatan R.I. Nomor 70 Tahun 2016.
Praktik Kerja Industri 89
Tabel 3.3.
INSTRUMEN PEMANTAUAN KUALITAS TANAH LINGKUNGAN INDUSTRI
Nama Industri :
Kode Sampel :
Lokasi Pengambilan Contoh Uji :
Jam, Tanggal, Tahun Pengambilan :
Contoh Uji
Petugas Pengambil Contoh Uji :
Tanggal, Tahun penerimaan :
contoh uji
Tanggal, Tahun analisis contoh uji :
Metode
No Parameter Hasil Analisis Baku Mutu Unit
Uji
Tidak ada telur /
Jumlah / 10 gr
1. Telur Cacing ......... 10 gram tanah
tanah kering
kering
CFU/10 gr
2. Fecal coliform ......... 0
tanah kering
3. Timah hitam (Pb) ......... ≤ 3300 mg/kg
4. Arsen (As) ......... ≤ 70 mg/kg
5. Kadmium (Cd) ......... ≤ 1300 mg/kg
6. Krom (CrHeksavalen) ......... ≤ 6300 mg/kg
7. Senyawa Merkuri (Hg) ......... ≤ 4200 mg/kg
8. Boron ......... Tidak ada batas mg/kg
9. Tembaga (Cu) ......... Tidak ada batas mg/kg
10. BaP ......... ≤ 35 mg/kg
11. DDT ......... ≤ 1000 mg/kg
12. Dieldrin ......... ≤ 160 mg/kg
13. PCP ......... ≤ 360 mg/kg
14. Dioxin (TCDD) ......... ≤ 1,4 µg/kg TEQ
15. Dioxin-like PCBs ......... ≤ 1,2 µg/kg TEQ
16. Radon ......... 100-300 Bq/m3
..................................,.............................
Tanda tangan & Cap Lab
..................................................
90 Praktik Kerja Industri
Kegiatan industri pada umumnya sebagaimana kegiatan yang lain akan menimbulkan
buangan padat berupa sampah baik berupa sampah bahan berbahaya dan beracun (B3)
maupun sampah non B3. Terkait dengan buangan padat berupa sampah B3 maupun non B3
pada kegiatan industri, maka diperlukan adanya sarana pengelolaan limbah B3 dan non B3
yang baik sehingga tidak menimbulkan pengaruh negatip terhadap tempat kerja, lingkungan
maupun terhadap tenaga kerja.
Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau di buang dari suatu
sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai
ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya
baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar. Sampah
adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama
dalam pembuatan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembuatan manufktur
atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan. Dalam Undang - Undang No.18 tentang
Pengelolaan Sampah dinyatakan definisi sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia
dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.
Menurut Daniel terdapat tiga jenis sampah, di antaranya:
1. Sampah organik: sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang bisa terurai secara
alamiah/biologis, seperti sisa makanan dan guguran daun. Sampah jenis ini juga biasa
disebut sampah basah.
2. Sampah anorganik: sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang sulit terurai secara
biologis. Proses penghancurannya membutuhkan penanganan lebih lanjut di tempat
khusus, misalnya plastik, kaleng dan styrofoam. Sampah jenis ini juga biasa disebut
sampah kering.
3. Sampah bahan berbahaya dan beracun (B3): limbah dari bahan-bahan berbahaya dan
beracun seperti limbah rumah sakit, limbah pabrik dan lain-lain.
Kemudian di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah, diatur beberapa jenis–jenis sampah yaitu sebagai berikut :
1. Sampah rumah tangga yaitu sampah yang berbentuk padat yang berasal dari sisa kegiatan
sehari-hari di rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik dan dari proses
alam yang berasal dari lingkungan rumah tangga. Sampah ini bersumber dari rumah atau
dari komplek perumahan.
2. Sampah sejenis sampah rumah tangga yaitu sampah rumah tangga yang bersala bukan
dari rumah tangga dan lingkungan rumah tangga melainkan berasal dari sumber lain
Praktik Kerja Industri 91
seperti pasar, pusat perdagangan, kantor, sekolah, rumah sakit, rumah makan, hotel,
terminal, pelabuhan, industri, taman kota, dan lainnya.
3. Sampah spesifik yaitu sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga yang
karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus, meliputi,
sampah yang mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun seperti baterai bekas, bekas
toner, dan sebagainya), sampah yang mengandung limbah B3 (sampah medis), sampah
akibat bencana, puing bongkaran, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah,
sampah yang timbul secara periode (sampah hasil kerja bakti).
Pengelolaan sampah juga semakin berkembang sejalan dengan perkembangan jenis
sampah yang akan dikelola. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis,
menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
1. Pengurangan sampah, yaitu kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak dari
produsen sampah (rumah tangga, pasar, dan lainnya), mengguna ulang sampah dari
sumbernya dan/atau di tempat pengolahan, dan daur ulang sampah di sumbernya dan
atau di tempat pengolahan.
2. Penanganan sampah, yaitu rangkaian kegiatan penaganan sampah yang mencakup
pemilahan (pengelompokan dan pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya),
pengumpulan (memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat
pengolahan sampah terpadu), pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari
sumber, TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu, pengolahan hasil akhir
(mengubah bentuk, komposisi, karateristik dan jumlah sampah agar diproses lebih
lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan alam dan pemprosesan aktif kegiatan
pengolahan sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya agar dapat dikembalikan
ke media lingkungan.
3. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat
pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan, dan pemrosesan akhir
sampah terpadu.
4. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan
pengumpulan, pemilahanm penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahaan, dan
pemrosesan akhir sampah.
5. Tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) adalah tempat untuk memroses dan
mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan
lingkungan.
92 Praktik Kerja Industri
Pengelolaan sampah pada kegiatan industri lebih ditekankan kepada sejauh mana
perusahaan tempat praktek kerja industri mengelola sampahnya agar tidak menimbulkan
gangguan kesehatan dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja bagi tenaga kerja.
Pengelolaan sampah industri dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai
berikut:
1. Upaya menciptakan kondisi kebersihan dalam ruang kerja dan di luar ruang kerja
misalnya di gang, koridor, halaman dan taman, serta tempat-tempat kegiatan lainnya.
2. Menyediakan tempat sampah, kesesuaiannya dengan volume sampah yang dihasilkan,
konstruksi tempat sampah, pemisahan tempat sampah untuk jenis sampah yang
memiliki karakteristik berbeda misalnya sampah organik dengan anorganik, sampah
basah dan sampah kering, sampah berbahaya/B3, sampah radiologi.
3. Melaksanakan kegiatan pembersihan sampah dan pemeliharaan kebersihan di dalam
maupun di luar ruang kerja di lingkungan perusahaan.
4. Melaksanakan upaya pengangkutan sampah.
5. Melaksanakan upaya pemusnahan sampah.
6. Menyediakan petugas sampah.
Berdasarkan hal-hal diatas, maka untuk melakukan pemantauan pengelolaan sampah
industri dapat menggunakan contoh instrumen sebagai berikut:
Praktik Kerja Industri 93
Tabel 3.4.
INSTRUMEN PEMANTAUAN PENGELOLAAN SAMPAH INDUSTRI
Nama Industri :
Alamat Industri :
Jenis Industri :
Luas Lahan Industri :
Jumlah Petugas Pengelola Sampah : Laki Laki : ......... orang, Perempuan : ....... orang
Petugas Pemantau :
Tanggal Pemantauan :
No Item Pemantauan Ya Tidak Ket.
1. Apakah ada upaya kebersihan lingkungan kerja
2. Apakah tersedia tempat sampah yang memadai
3. Apakah ada upaya pemisahan sampah
4. Apakah semua sampah dapat tertampung
5. Apakah tempat sampah yang tersedia kuat
6. Apakah tempat sampah yang tersedia dilengkapi tutup
7. Apakah tempat sampah mudah dibersihkan
8. Apakah tempat sampah kedap air
9. Apakah ada upaya pengangkutan sampah yang baik
10. Apakah ada pengolaan sampah B3 secara khusus
11. .........
..................................,.............................
Tanda tangan
..................................................
94 Praktik Kerja Industri
E. INSTRUMEN PENGAWASAN PENYEHATAN MAKANAN DAN MINUMAN
Ketersediaan makanan dan minuman di tempat kerja industri merupakan hal yang
penting untuk diperhatikan. Penyediaan makanan dan minuman di tempat kerja tentu sangat
menunjang keberlangsungan pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja, hal ini disebabkan
karena untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik setiap tenaga kerja memerlukan
tambahan kalori yang bersumber dari makanan dan minuman yang dikonsumsi.
Untuk terlaksananya penyediaan makanan dan minuman yang baik bagi tenaga kerja,
tentunya perlu dilakukan suatu usaha penyediaan makanan dan minuman yang memenuhi
persyaratan yang berlaku, diantaranya persyaratan kesehatan yang berhubungan dengan
penyelenggara pangan, penjamah pangan, waktu dan suhu pangan.
Terkait dengan persyaratan kesehatan yang berhubungan dengan penyelenggara
pangan, perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Tersedia kebijakan setempat untuk memastikan tiga hal penting diterapkan dalam
pengamanan pangan, yaitu tenaga yang professional, pengendalian waktu dan suhu
dalam penanganan pangan dan pencegahan kontaminasi silang.
2. Melakukan pencegahan kontaminasi silang agar tidak terjadi pencemaran oleh
mikroorganisme dan cemaran lain di setiap tahap penanganan pangan melalui tiga jalur
pangan ke pangan, tangan ke pangan, dan atau peralatan ke pangan.
3. Sanitasi tempat penerimaan, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian pangan
dikakukan secara rutin bukan hanya mengenai kebersihan tetapi juga ketepatan
penggunaan disinfektan untuk kebersihan.
4. Menjamin semua penjamah pangan mempunyai kemampuan dan keahlian dalam
menangani pangan, higiene dan keamanan pangan yang dapat diperoleh melalui
pelatihan formal atau pemagangan.
5. Menunjuk seorang penyelia penjamah pangan untuk mengawasi kinerja penjamah
pangan.
6. Memastikan bahwa penjamah pangan tidak menjamah pangan jika terdapat
kemungkinan kontaminasi pangan.
7. Menjaga tersedianya sarana cuci tangan yang dapat diakses dengan mudah oleh
penjamah pangan yang dilengkapi dengan air hangat yang mengalir dan sabun dan
mengeringkannya dengan lap kertas sekali pakai.
Praktik Kerja Industri 95
Adapun persyaratan kesehatan yang berhubungan dengan penjamah pangan, perlu
memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Bertanggungjawab terhadap keamanan pangan dengan cara menjaga pangan
sedemikian rupa agar pangan tersebut tetap aman dan layak dikonsumsi.
2. Harus dalam keadaan sehat dan bebas dari penyakit menular yang dibuktikan dengan
surat keterangan dokter secara berkala.
3. Jika merasakan gejala sakit dan atau didiagnosa menderita suatu penyakit, maka harus
melaporkan kepada penyelianya atau penyelenggara.
4. Jika dalam keadaan sakit dan kemungkinan dapat menyebabkan kontaminasi pangan,
maka penjamah pangan tidak diperbolehkan menangani pangan sampai sembuh
kembali.
5. Melaporkan kepada penyelianya jika merasa melakukan sesuatu yang dapat
menyebabkan kontaminasi pangan.
6. Selalu mencuci tangan dengan air hangat yang mengalir dan sabun dan
mengeringkannya dengan lap kertas sekali pakai.
7. Selalu mencuci tangan jika akan menjamah pangan setelah dari toilet, merokok, batuk
dan bersin memegang saputangan, makan, minum dan memegang rambut atau bagian
tubuh lainnya
8. Selalu mencuci tangan sebelum menangani pangan siap saji dan setelah memegang
pangan mentah.
9. Tidak makan, bersin, meniup, batuk, meludah atau merokok di dekat pangan atau
tempatnya.
10. Tidak menyentuh pangan siap saji secara langsung.
11. Mencegah terjadinya kontaminasi pangan dengan rambut dengan cara mengikat atau
memakai tutup rambut.
Persyaratan kesehatan yang berhubungan dengan waktu dan suhu pangan yang harus
diperhatikan dalam penyediaan makanan dan minuman di tempat kerja antara lain:
1. Penyelenggara atau penjamah pangan harus memperhatikan waktu dan suhu
penggunaan, pengolahan, penyimpanan bahan pangan maupun pangan siap saji sesuai
jenisnya.
2. Penjamah pangan harus memisahkan tempat penyimpanan antara bahan pangan dan
pangan siap saji.
3. Penjamah pangan harus membuang pangan sisa (left over food) jika sudah tidak
memenuhi batas waktu dan suhu penyimpanan.
4. Penjamah pangan harus melakukan pencatatan waktu dan suhu penyimpanan pangan
secara sistematis dengan sistem pelabelan dan penggunaan alat ukur.
96 Praktik Kerja Industri
Dalam penyelenggaraan penyediaan makanan dan minuman bagi tenaga kerja di tempat
kerja, agar diperoleh kualitas makanan dan minuman yang memenuhi persyaratan kesehatan
disamping harus memperhatikan persyaratan penyelenggara pangan, penjamah pangan,
waktu dan suhu pangan seperti tersebut diatas, juga harus memperhatikan persyaratan
kesehatan yang berhubungan dengan disain dan konstruksi tempat pengolahan makanan dan
minuman. Hal ini disebabkan karena disain dan konstruksi tempat pengolahan makanan dan
minuman akan menentukan kualitas makanan dan minuman yang dihasilkan.
Persyaratan kesehatan yang berhubungan dengan disain dan konstruksi tempat
pengolahan makanan dan minuman yang harus diperhatikan meliputi:
1. Persyaratan Umum
a. Disain dan konstruksi bangunan cocok untuk tempat pengolahan pangan, dilengkapi
ruang untuk pengaturan sarana dan peralatan.
b. Mudah dibersihkan dan dilakukan sanitasi apabila diperlukan.
c. Rapat vektor dan binatang pembawa penyakit.
d. Tidak dapat menjadi tempat perkembangbiakan vektor dan binatang pembawa
penyakit.
2. Sistem Penyediaan Air
a. Tersedia air yang mencukupi untuk air minum dan air untuk keperluan higiene dan
sanitasi.
b. Idealnya air yang digunakan sudah melalui proses pengolahan (air dari PDAM), bila
terpaksa harus menggunakan air dari sumber terlindung.
3. Sistem Pembuangan Air Limbah
a. Mempunyai sistem pembuangan air limbah yang berfungsi menyalurkan air limbah
dengan baik.
b. Tidak menyebabkan koneksi silang dengan pipa air minum sehingga menimbulkan
kontaminasi sumber air dan pangan.
4. Sistem Penyimpanan Sampah dan Sampah Daur Ulang
a. Mempunyai tempat penyimpanan sampah dan sampah daur ulang yang mencukupi dan
rapat vektor dan binatang pembawa penyakit.
b. Mudah dan efektif untuk dibersihkan.
Praktik Kerja Industri 97
5. Sistem Ventilasi
Tempat pengolahan makanan harus mempunyai penghawaan alami atau buatan yang
cukup dan efektif menghilangkan asap, uap dan gas lainnya yang berasal dari proses
pengolahan pangan.
6. Sistem Pencahayaan
Tempat pengolahan makanan harus mempunyai sistem pencahayaan alam atau buatan
yang mencukupi untuk menunjang kegiatannya.
Berdasar uraian di atas, maka dapat dibuat contoh instrumen yang dapat digunakan
dalam pengawasan penyediaan makanan dan minuman di tempat kerja, sebagai berikut:
98 Praktik Kerja Industri
Tabel 3.5.
INSTRUMEN PENGAWASAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DI INDUSTRI
Nama Industri :
Alamat Industri :
Jenis Industri :
Jumlah Tenaga Kerja : Laki Laki : ......... orang, Perempuan : ....... orang
Jumlah Petugas Penjaman Makanan : Laki Laki : ......... orang, Perempuan : ....... orang
Petugas Pemantau :
Tanggal Pemantauan :
No Item Pemantauan Ya Tidak Ket.
1. Tersedia kebijakan setempat terkait pengelolaan makanan
2. Dilakukan pencegahan kontaminasi pada makanan
3. Penjamah pangan mempunyai kemampuan dan keahlian
dalam menangani makanan
4. Terdapat petugas penyelia penjamah pangan
5. Tersedianya sarana cuci tangan
6.
7.
..................................,.............................
Tanda tangan
..................................................
Praktik Kerja Industri 99
F. INSTRUMEN PENGAWASAN PENYEHATAN UDARA
Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar dan
Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri menyebutkan bahwa Standar Baku Mutu
(SBM) media udara meliputi standar baku mutu udara dalam ruang (indoor air quality) dan
udara ambien (ambient air quality). Standar kualitas udara dalam ruang perkantoran mengacu
kepada peraturan perundang-undangan mengenai Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Perkantoran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016,
sedangkan SBM udara ambien mengacu ke peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan yang berlaku diantaranya adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan
Hidup Nomor : KEP-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara.
Kualitas udara dalam tempat kerja sangat dipengaruhi oleh kandungan unsur kimia
diudara tempat kerja. Nilai Ambang Batas (NAB) bahan kimia di tempat kerja meliputi 255
(duaratus limapuluh lima) parameter sebagaimana tercantunm dalam Tabel 13 Peraturan
Menteri Kesehatan R.I. Nomor 70 tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan
Lingkungan Kerja Industri. Selanjutnya untuk mengevaluasi pajanan biologi dan potensi risiko
kesehatan pekerja dapat menggunakan acuan Indikator Pajanan Biologi (IPB). Indikator
Pajanan Biologi (IPB) atau Biological Exposure Indices (BEI) merupakan nilai acuan konsentrasi
bahan kimia yang terabsorpsi, hasil metabolisme (metabolit) bahan kimia yang terabsorpsi,
atau efek yang ditimbulkan oleh bahan kimia tersebut.
Nilai indikator pajanan biologi sebanyak 45 (empat puluh lima) bahan kimia yang ada di
tempat kerja dapat dilihat pada Tabel 14 Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 70 Tahun
2016 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Perkantoran menyebutkan bahwa untuk mendapatkan tingkat kesehatan dan
kenyamanan dalam ruang perkantoran persyaratan pertukaran udara ventilasi untuk ruang
kerja adalah 0,57 m3/org/min sedangkan untuk ruang pertemuan adalah 1,05 m3/min/orang.
Sedangkan laju pergerakan udara yang disyaratkan adalah berkisar antar 0.15 – 0.50 m/detik.
Untuk ruangan kerja yang tidak menggunakan pendingin harus memiliki lubang ventilasi
minimal 15% dari luas lantai dengan menerapkan sistim ventilasi silang.
Ruang yang menggunakan AC secara periodik harus dimatikan dan diupayakan
mendapat pergantian udara secara alamiah dengan cara membukan seluruh pintu dan jendela
atau dengan kipas angin. Saringan/filter udara AC juga harus dibersihkan secara periodik
sesuai dengan ketentuan pabrik.
Sistem perancangan ventilasi pada bangunan industri harus mengacu pada SNI 03-6572-
2001. Tindakan pengendalian yang dapat dilakukan untuk memastikan ventilasi dapat
mencegah pencemar udara adalah sebagai berikut:
100 Praktik Kerja Industri
1. Ruang kerja dan sistem ventilasinya tidak berhubungan langsung dengan dapur (pantry)
ataupun area parkir;
2. Filtrasi atau penyaringan udara yang efektif;
3. Pemeliharaan unit pendingin udara dan system ventilasi lain, termasuk pembersihan
secara regular;
4. Pencegahan adanya halangan atau obstruksi pada ventilasi;
5. Menempatkan peralatan yang menggunakan bahan pelarut (solvent) pada area yang
dilengkapi dengan local exhaust ventilation (LEV);
Persyaratan minimum kualitas udara dalam ruangan perkantoran dapat dilihat pada
Tabel 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan
dan Kesehatan Kerja Perkantoran. Jika persyaratan sudah terpenuhi tetapi masih terjadi SBS
(Sick Building Syndrome), maka perlu dilakukan investigasi.
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-45/MENLH/10/1997
tentang Indeks Standar Pencemar Udara menyebutkan bahwa pencemaran udara dapat
menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup
lainnya, selanjutnya menyatakan bahwa untuk memberikan kemudahan dan keseragaman
informasi kualitas udara ambien kepada masyarakat di lokasi dan waktu tertentu serta sebagai
bahan pertimbangan dalam melakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran udara, perlu
disusun Indeks Standar Pencemar Udara.
Indeks Standar Pencemar Udara adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang
menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan
kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya.
Parameter Indeks Standar Pencemar Udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
1. Partikulat (PM10);
2. Karbon Monoksida (CO);
3. Sulfur dioksida (SO2);
4. Nitrogen dioksida (NO2);
5. Ozon (O3);
Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat dibuat contoh instrumen pemantauan
kualitas udara tempat kerja sebagai berikut:
Praktik Kerja Industri 101
Tabel 3.6.
INSTRUMEN PENGAWASAN PENYEHATAN UDARA INDUSTRI
Nama Industri :
Alamat Industri :
Jenis Industri :
Jumlah Tenaga Kerja : Laki Laki : ......... orang, Perempuan : ....... orang
Petugas Pemantau :
Tanggal Pemantauan :
No Item Pemantauan Ya Tidak Ket.
1. Ruang kerja dan sistem ventilasinya tidak berhubungan
langsung dengan dapur (pantry)
2. Ruang kerja dan sistem ventilasinya tidak berhubungan
langsung dengan area parkir
3. Terdapat filtrasi/penyaringan udara yang efektif
4. Pemeliharaan unit pendingin udara dan system ventilasi
lain, termasuk pembersihan secara regular
5. Pencegahan adanya halangan/obstruksi pada ventilasi
6. Menempatkan peralatan yang menggunakan bahan pelarut
(solvent) pada area yang dilengkapi dengan local exhaust
ventilation (LEV)
6. Dilakukan pemantauan kualitas udara tempat kerja
7. Dilakukan pemantauan kualitas udara ambien
..................................,.............................
Tanda tangan
..................................................
102 Praktik Kerja Industri
G. INSTRUMEN PENGAWASAN PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG
PEMBAWA PENYAKIT
Vektor dan binatang pembawa penyakit yang perlu di perhatikan dalam kegiatan
industri dianataranya adalah nyamuk untuk kelompok vektor, sedangkan untuk kelompok
binatang pembawa penyakit meliputi tikus, lalat dan kecoa. Standar baku mutu vektor
penyakit meliputi Anopheles spp, Aedes aegypti, dan Culex sp. Standar baku mutu vektor
tersebut selengkapnya dapat dijumpai pada Tabel 32 Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor
70 Tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri. Adapun
standar baku mutu binatang pembawa penyakit selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 33.
Terkait dengan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit maka bangunan
untuk keperluan industri diharuskan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Tersedia upaya pencegahan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit
secara terpadu dengan mendahuluan cara atau teknologi yang tidak menggunakan
bahan kimia atau insektisida, terutama di industri pangan.
2. Tersedia tenaga khusus untuk pencegahan dan pengendalian vektor dan binatang
pembawa penyakit.
3. Memastikan semua sarana dan bangunan yang ada tidak menjadi tempat
berkembangbiaknya vektor dan binatang pembawa penyakit.
Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat dibuat contoh instrumen pemantauan
pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit tempat kerja sebagai berikut:
Praktik Kerja Industri 103
Tabel 3.7.
INSTRUMEN PENGAWASAN PENGENDALIAN
VEKTOR DAN BINATANG PEMBAWA PENYAKIT DI INDUSTRI
Nama Industri :
Alamat Industri :
Jenis Industri :
Jumlah Tenaga Kerja : Laki Laki : ......... orang, Perempuan : ....... orang
Petugas Pemantau :
Tanggal Pemantauan :
No Item Pemantauan Ya Tidak Ket.
1. Tersedia upaya pencegahan pengendalian vektor terpadu
2. Tersedia upaya pencegahan pengendalian binatang
pembawa penyakit terpadu
3. Tersedia tenaga khusus untuk pencegahan dan
pengendalian vektor
4. Tersedia tenaga khusus untuk pencegahan dan
pengendalian binatang pembawa penyakit
5. Bangunan yang ada tidak menjadi tempat
berkembangbiaknya vektor
6. Bangunan yang ada tidak menjadi tempat
berkembangbiaknya binatang pembawa penyakit
Hasil Pengukuran Baku Mutu Vektor dan Binatang
No Rendah Tinggi Ket.
Pembawa Penyakit
1. Man Biting Rate (MBR) Nyamuk Anopheles
2. Angka Paritas Nyamuk Anopheles
3. Kapasitas Vektor Nyamuk Anopheles
4. Entomological Inoculation Rate (EIR) Nyamuk Anopheles
5. Indeks habitat (IH) Larva Anopheles
6. Indeks Kontainer Larva Aedes spp.
104 Praktik Kerja Industri
Hasil Pengukuran Baku Mutu Vektor dan Binatang
No Rendah Tinggi Ket.
Pembawa Penyakit
7. Indeks Kontainer Larva Culex sp.
8. Success Trap Tikus
9. Indeks Populasi Lalat
10. Indeks Populasi Kecoa/Lipas Periplaneta Americana(PA)
11. Indeks Populasi Blatella germanica (BG)
12. Indeks Populasi Supella longipalpa (SL)
13. Indeks Populasi Blatta orientalis (BO)
..................................,.............................
Tanda tangan
..................................................
Praktik Kerja Industri 105
H. INSTRUMEN PENGAWASAN HOUSEKEEPING
Semua tempat kerja yang ditujukan bagi karyawan, harus benar-benar aman dan dapat
menjamin keselamatan tenaga kerja mencakup pengaturan untuk berbagai area kerja yang
biasa dilewati ataupun sering dilakukan aktivitas kerja, dimana area kerja tersebut
mengandung berbagai potensi bahaya yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja dan kerugian
lain.
Area kerja yang kotor, penuh debu dan berantakan dapat menyebabkan karyawan
merasa tidak nyaman dan aman saat bekerja. Kondisi tersebut akan berimbas pada keselatam
kerja terganggu dan tingkat produktivitas kerja menurun. Penataan area kerja yang buruk
secara tidak langsung bisa menghambat pergerakan kerja karyawan dan kemungkinan besar
menyebabkan kecelakaan kerja, seperti terjatuh, terpeleset, atau lainnya.
Penilaian pelaksanaan housekeeping atau tata graha di industri tempat praktek dengan
menggunakan instrument penilaian yang sudah Saudara siapkan. Cek kembali apakah
instrumen yang Saudara buat sudah meliputi aspek-aspek atau substansi materi di bawah ini:
1. Tempat pengelola, gang-gang, ruang penyimpanan (gudang) harus dijaga dalam kondisi
sanitair.
2. Atap, gang-gang, lantai, dinding, basement, gudang bawah tanah, jamban, toilet, septick
tank, saluran pembuangan, dan lain-lain setiap saat harus bersih dan aman serta dalam
kondisi yang sanitair.
3. Setiap bangunan, halaman, gang-gang dan keseluruhan wilayah milik perusahaan harus
dijaga bebas dari akumulasi debu dan sampah lainnya.
4. Setaip lantai ruang kerja harus dikelola secara bersih dan sebisa mungkin dalam kondisi
kering.
5. Apabila ada kegiatan-kegiatan yang menggunakan air maka sistem drainase atau
pematusan harus dikelola dengan baik (dimungkinkan dalam kondisi cepat kering).
Pekerja harus menggunakan sepatu khusus untuk tempat semacam itu.
6. Lantai atau permukaan jalan lainnya harus terjaga dalam kondisi baik, bebas minyak
atau air, semua hal yang bernbahaya yang ada dijalanan harus dihilangkan.
7. Setiap lantai, tempat kerja dan jalan atau gang harus bebas dari gundukan, serpihan atau
lubang.
8. Dilarang meludah ke dinding, lantai, tempat kerja atau lantai bangunan lainnya.
9. Jika disediakan tempat meludah konstruksinya harus bisa dibersihkan dan di desinfeksi
serta harus dalam keadaan bersih setiap hari untuk menjaga kesehatan.
10. Jika tempat sampah digunakan untuk sampah basah atau yang dapat terurai
konstruksinya harus dibuat tidak bocor, nyaman, bersih dan dirawat dengan baik atau
sanitair.
106 Praktik Kerja Industri
11. Jika menggunakan mesin atau peralatan kimia di dalam mengelola sanitasi pemeriksaan
secara periodik harus dilakukan untuk menjamin efisiensi peralatan dan mencatat hasil
setiap pemeriksaan.
12. Peralatan penerangan harus sering dibersihkan untuk menjaga intensitas penerangan
agar tetap berada pada level yang memenuhi syarat. Jika menggunakan penerangan
alami pada siang hari maka jendela harus sering dibersihkan agar pencahayaan diruang
tersebut memenuhi syarat.
13. Bahan-bahan buangan yang mudah terbakar harus ditempatkan pada wadah logam
yang dapat menutup sendiri dan harus dikosongkan minimal 1 kali dalam sehari
14. Bahan-bahan yang mudah terbakar sebaiknya jangan disimpan dibawah tangga.
15. Alat pemadam kebakaran harus dijaga agar mudah dioperasikan dan terlindung dari
proses pendinginan. Jika alat pemadam kebakaran memakai tipe asam soda sebaiknya
diisi ulang minimal setahun sekali.
16. Bahan-bahan atau material harus di tumpuk dan dihindarkan dari getaran atau vibrasi
dan sentakan agar tidak mudah jatuh.
17. Barang-barang yang tertata baik dan bersih tidak lagi menghambat pergerakan para
karyawan.
Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat dibuat contoh instrumen pemantauan
pelaksanaan housekeeping atau tatagraha di industri sebagai berikut:
Praktik Kerja Industri 107
Tabel 3.8.
INSTRUMEN PENGAWASAN PELAKSANAAN HOUSEKEEPING
Nama Industri :
Alamat Industri :
Jenis Industri :
Jumlah Tenaga Kerja : Laki Laki : ......... orang, Perempuan : ....... orang
Petugas Pemantau :
Tanggal Pemantauan :
No Item Pemantauan Ya Tidak Ket.
1. Tempat pengelola dalam kondisi sanitair.
2. Gang-gang dalam kondisi sanitair.
3. Ruang penyimpanan dalam kondisi sanitair.
4. Atap dalam kondisi yang sanitair
5. Lantai dalam kondisi yang sanitair
6. Dinding dalam kondisi yang sanitair
7. Basement dalam kondisi yang sanitair
8. Gudang bawah tanah dalam kondisi yang sanitair
9. Jamban dalam kondisi yang sanitair
10. Toilet dalam kondisi yang sanitair
11. Septick tank dalam kondisi yang sanitair
12. Saluran pembuangan dalam kondisi yang sanitair
13. Setiap bangunan bebas dari akumulasi debu
14. Setiap bangunan bebas dari sampah
15. Halaman bebas dari akumulasi debu
16. Halaman bebas dari sampah
17. ........
..................................,.............................
Tanda tangan
..................................................
108 Praktik Kerja Industri
I. INSTRUMEN PENGAWASAN JAMBAN DAN PETURASAN
Penilaian jamban dan peturasan tidak dapat dipisahkan dengan penilaian aspek sanitasi
industri lainnya, karena tidak adanya penilaian jamban dan peturasan maka penilaian sanitasi
industri belum selesai. Adanya jamban dan peturasan yang kotor, berbau dan tidak sehat akan
mempengaruhi kesehatan karyawan dan akhirnya karyawan akan terganggu kesehatannya
dan berujung pada gangguan produktivitas kerja tenaga kerja. Jamban dan peturasan
merupakan sarana sanitasi utama yang harus disediakan perusahaan dan dikelola dengan
baik, disamping sarana sanitasi lainnya. Ketidaknyamanan yang diakibatkan adanya jamban
dan peturasan yang tidak sehat akan menimbulkan bau yang tidak sedap, lantai yang licin
menyebabkan terpeleset dan jatuh, lebih jauh lagi akan menimbulkan penyakit pada tenaga
kerja. Kondisi tersebut memerlukan pengelolaan yang baik sehingga kondisi jamban dan
peturasan menjadi bersih dan sanitair. Sanitair berarti sehat dan aman. Sehat karena dalam
jamban dan peturasan tidak terdapat bakteri penular penyakit, tidak terjangkau serangga
yang dapat mengontaminasi makanan tenaga kerja.
Yang perlu Saudara pertimbangkan dalam menilai jamban dan peturasan tidak saja
kondisi kebersihan dari sarana tersebut melainkan juga hal lain yang mempengaruhi kualitas
jamban agar tidak mempengaruhi timbulnya penyakit atau mengganggu kesehatan tenaga
kerja sehingga produktivitas kerja jadi menurun. Pertimbangan tersebut meliputi:
1. Konstruksi jamban dan peturasan
2. Jumlah jamban dan peturasan
3. Pengelolaan dan pemeliharaan jamban
4. Penyediaan air bersih
Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar dan
Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri menyebutkan bahwa Standar Baku Mutu
(SBM) sarana toilet untuk pekerja industri ditetapkan berdasarkan rasio yaitu perbandingan
jumlah toilet dengan jumlah pekerja. Rasio sarana toilet berbeda antara laki-laki dan
perempuan. Jika toilet digunakan oleh pekerja laki-laki maka harus ada peturasan atau urinoir
paling banyak 1/3 dari jumlah toilet yang disediakan.
Berdasar uraian di atas maka dapat dibuat contoh instrumen pemantauan pengelolaan
jamban dan peturasan di industri sebagai berikut:
Praktik Kerja Industri 109
Tabel 3.9.
INSTRUMEN PEMANTAUAN PENGELOLAAN
JAMBAN DAN PETURASAN DI INDUSTRI
Nama Industri :
Alamat Industri :
Jenis Industri :
Jumlah Tenaga Kerja : Laki Laki : ......... orang, Perempuan : ....... orang
Jumlah Jamban :
Jumlah Peturasan :
Petugas Pemantau :
Tanggal Pemantauan :
No Item Pemantauan Ya Tidak Ket.
1. Konstruksi jamban kokoh / kuat
2. Konstruksi peturasan kokoh / kuat
3. Jumlah jamban memenuhi kebutuhan
4. Jumlah peturan memenuhi kebutuhan
5. Dilakukan tindakan pembesihan jamban setiap hari
6. Dilakukan tindakan pembersihan peturasan setiap hari
7. Tersedia air yang cukup pada setiap jamban
8. Tersedia air yang cukup pada setiap peturasan
9. Tersedia alat pembersih jamban yang sesuai
10. Tersedia alat pembersih peturasan yang sesuai
11. Tersedia sabun untuk mencuci tangan
12. Air buangan mengalir dengan baik
13. Tidak tercium bau Ammoniak disekitar jamban
14. Penerangan di jamban dan peturasan mencukupi
15. Lantai jamban dan peturasan kedap air
16. Dinding jamban dan peturasan mudah dibersihkan
17. ........
..................................,.............................
Tanda tangan
..................................................
110 Praktik Kerja Industri
J. INSTRUMEN PENGAWASAN FASILITAS CUCI TANGAN
Fasilitas cuci tangan keberadaannya harus dibarengi dengan sejumlah persyaratan baik
persyaratan konstruksi, kebersihan, kapasitas maupun pemeliharaannya. Tempat Cuci tangan
berupa wastafel dengan ukuran setidaknya dengan diameter 50 centimeter. Dalam
melakukan penilaian terhadap tempat cuci tangan terdapat beberapa hal yang harus
diperhatikan, antara lain :
1. Penyediaan fasilitas cuci tangan di setiap ruang kerja.
2. Kapasitas dan fasilitas cuci tangan dibanding jumlah seluruh karyawan dan pengunjung
rata-rata perhari.
3. Cara penempatan ruang fasilitas cuci tangan pekerja laki-laki dan perempuan.
4. Konstruksi pemisah ruang.
5. Kualitas bahan yang digunakan untuk fasilitas cuci tangan serta persyaratannya.
6. Tempat cuci tangan tersedia minimal 1 (satu) buah di setiap lantai
7. Perlengkapan tempat cuci tangan, misalnya handuk biasa di dekat lavatory atau
wastafel.
8. Sistem penyediaan air bagi tempat cuci tangan.
9. Ketersediaan shower dengan air panas dan dingin bagi karyawan yang bekerja dengan
bahan beracun, infeksi, irritants.
10. Ketersediaan zat tertentu untuk system pembersihan yang tidak bisa dihilangkan
dengan sabun.
11. Kesesuaian penyediaan air bersih dengan peraturan yang berlaku.
Berdasar uraian di atas maka dapat dibuat contoh instrumen pemantauan pengelolaan
jamban dan peturasan di industri sebagai berikut:
Praktik Kerja Industri 111
Tabel 3.10.
INSTRUMEN PEMANTAUAN PENGELOLAAN
TEMPAT CUCI TANGAN DI INDUSTRI
Nama Industri :
Alamat Industri :
Jenis Industri :
Jumlah Tenaga Kerja : Laki Laki : ......... orang, Perempuan : ....... orang
Jumlah Tempat Cici Tangan :
Jumlah Pancuran Bilas (Shower) :
Petugas Pemantau :
Tanggal Pemantauan :
No Item Pemantauan Ya Tidak Ket.
1. Terdapat tempat cuci tangan pada setiap ruang kerja
2. Jumlah tenpat cuci tangan sesuai dengan kebutuhan
3. Tempat cuci tangan ditempatkan pada tempat yang mudah
dijangkau
4. Terdapat pemisahan tempat cuci tangan untuk laki-laki dan
perempuan
5. Terdapat dinding pemisah yang kokoh
6. Tempat cuci tangan terbuat dari bahan yang kuat
7. Terdapat fasilitas penunjang untuk cuci tangan
8. Tersedia air dalam jumlah yang cukup
9. Kualitas air untuk cuci tangan memenuhi syarat
10. Limbah dari tempat cuci tangan mengalir dengan baik
11. Terdapat pancuran bilas pada tempat kerja kimia
12. ........
..................................,.............................
Tanda tangan
..................................................
112 Praktik Kerja Industri
Latihan
Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan
berikut!
1) Lengkapi dan sempurnakanlah contoh-contoh instrumen yang diperlukan dalam
pengawasan sanitasi industri sehingga menjadi instrumen yang siap untuk digunakan!.
2) Cermatilah materi pada Topik 2 di atas, apakah sudah sesuai dengan standar-standar
dan ketentuan yang berlaku?.
3) Terkait dengan sanitasi industri apa saja yang harus mendapatkan pengawasan?
Ringkasan
1. Sasaran pengawasan sanitasi industri pada suatu tempat kerja meliputi:
a. Penyediaan air bersih
b. Pengolahan limbah cair
c. Penyehatan tanah adan pengelolaan sampah
d. Penyehatan makanan & minuman
e. Penyehatan udara
f. Pengendalian vector
g. House keeping
h. Jamban dan peturasan
i. Fasilitas cuci tangan
2. Yang perlu pertimbangkan dalam menilai jamban dan peturasan di tempat kerja tidak
saja kondisi kebersihan dari sarana tersebut melainkan juga hal lain yang mempengaruhi
kualitas jamban agar tidak mempengaruhi timbulnya penyakit atau mengganggu
kesehatan tenaga kerja sehingga produktivitas kerja jadi menurun. Pertimbangan
tersebut meliputi:
a. Konstruksi jamban dan peturasan
b. Jumlah jamban dan peturasan
c. Pengelolaan dan pemeliharaan jamban
d. Penyediaan air bersih
Praktik Kerja Industri 113
3. Terkait dengan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit maka bangunan
untuk keperluan industri diharuskan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Tersedia upaya pencegahan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit
secara terpadu dengan mendahuluan cara atau teknologi yang tidak menggunakan
bahan kimia atau insektisida, terutama di industri pangan.
b. Tersedia tenaga khusus untuk pencegahan dan pengendalian vektor dan binatang
pembawa penyakit.
c. Memastikan semua sarana dan bangunan yang ada tidak menjadi tempat
berkembangbiaknya vektor dan binatang pembawa penyakit.
Tes 2
Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar!
1) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-45/MENLH/10/1997
mengatur tentang....
A. Indeks Standar Pencemar Udara.
B. Indeks Standar Buangan Limbah Cair.
C. Indeks Standar Pengelolaan Sampah Organik.
D. Indeks Standar Pengelolaan Sampah B3.
2) Ketersediaan tempat cuci tangan dilihat dari aspek jumlah dipersyaratkan....
A. Minimal satu buah setiap 50 orang tenaga kerja.
B. Minimal satu buah setiap 25 orang tenaga kerja.
C. Minimal satu buah setiap lantai.
D. Minimal satu buah setiap ruang kerja.
3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Perkantoran menyebutkan bahwa untuk mendapatkan tingkat
kesehatan dan kenyamanan dalam ruang perkantoran persyaratan pertukaran udara
ventilasi untuk ruang kerja adalah....
A. 0,57 m3/org/min
B. 0,75 m3/org/min
C. 0,65 m3/org/min
D. 0,56 m3/org/min
114 Praktik Kerja Industri
Topik 3
Instrumen Pengawasan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
A. SASARAN PENGAWASAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Saudara mahasiswa yang berbahagia, sebelum menyusun instrumen pengawasan
keselamatan dan kesehatan kerja, terlabih dahulu Saudara harus bisa mengidentifikasi
sasaran dalam pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karena itu bacalah materi
pada bagian awal Topik 3 ini dengan cermat.
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 2 telah
menetapkan jaminan dan persyaratan keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di
darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam
wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Selain keselamatan kerja, aspek kesehatan
kerja juga harus diperhatikan sesuai dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 4
yang memberikan hak kesehatan pada setiap orang dan pada Pasal 164 dan Pasal 165
menyatakan bahwa upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup
sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh
pekerja.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan
untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya
pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Berbicara masalah keselamatan dan
kesehatan kerja, berarti membicarakan dua hal besar yaitu keselamatan kerja dan kesehatan
kerja. Keselamatan kerja bersifat teknis dengan sasaran lingkungan kerja, sedangkan
kesehatan kerja bersifat medis dengan sasaran tenaga kerja.
Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penyusunan instrumen pengawasan
keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dapat dikelompokkan menjadi :
1. Instrumen Pengawasan keselamatan kerja
2. Instrumen Pengawasan kesehatan kerja.
Praktik Kerja Industri 115
B. INSTRUMEN PENGAWASAN KESELAMATAN KERJA
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya
dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta
produktivitas Nasional; bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin
pula keselamatannya; bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara
aman dan efisien; bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan segala daya-upaya untuk
membina norma-norma perlindungan kerja; bahwa pembinaan norma-norma itu perlu
diwujudkan dalam Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang
keselamatan kerja jang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik dan
teknologi.
Lebih lanjut pada Pasal 3 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja dinyatakan bahwa untuk mewujudkan kondisi diatas, maka setiap kegiatan industri
harus memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja sebagai berikut:
1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
2. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
4. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau
kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
5. Memberi pertolongan pada kecelakaan;
6. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
7. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu,
kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;
8. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik physik maupun
psykhis, peracunan, insfeksi dan penularan;
9. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
10. Menyelenggarakan suhu dan lembah udara yang baik;
11. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
12. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
13. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan cara dan proses
kerjanya;
14. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau
barang;
15. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
116 Praktik Kerja Industri
16. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan
penyimpanan barang;
17. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
18. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya
kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.
Sebagai pelaksanaan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja, maka ditetapkan Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di
tempat kerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor PER.13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di
tempat kerja.
Faktor fisika adalah faktor di dalam tempat kerja yang bersifat fisika yang dalam
keputusan diatas terdiri dari iklim kerja, kebisingan, getaran, gelombang mikro, sinar ultra
ungu, dan medan magnet. Sedangkan faktor kimia adalah faktor di dalam tempat kerja yang
bersifat kimia yang dalam keputusan diatas meliputi bentuk padatan (partikel), cair, gas,
kabut, aerosol dan uap yang berasal dari bahan-bahan kimia. Nilai Ambang Batas faktor fisika
secara lengkap dapat dibaca pada BAB II yang kemudian dijabarkan lebih lanjut pada Lampiran
1 dari peraturan diatas. Sedangkan Nilai Ambang Batas faktor kimia secara lengkap dan rinci
dapat dilihat pada Lampiran 2 peraturan yang sama.
Nilai Ambang Batas faktor kimia dapat digunakan sebagai (pedoman) rekomendasi pada
praktek higene perusahaan dalam melakukan penatalaksanaan lingkungan kerja sebagai
upaya untuk mencegah dampaknya terhadap kesehatan. Dengan demikian NAB faktor kimia
antara lain dapat pula digunakan:
1. Sebagai kadar standar untuk perbandingan.
2. Sebagai pedoman untuk perencanaan proses produksi dan perencanaan teknologi
pengendalian bahaya-bahaya di lingkungan kerja.
3. Menentukan pengendalian bahan proses produksi terhadap bahan yang lebih beracun
dengan bahan yang sangat beracun.
4. Membantu menentukan diagnosis gangguan kesehatan, timbulnya penyakit penyakit
dan hambatan-hambatan efisiensi kerja akibat faktor kimiawi dengan bantuan
pemeriksaan biologi.
Berdasar uraian di atas maka untuk pengawasan keselamatan kerja industri, dapat
dibuat contoh instrumen pengawasan sebagai berikut :
Praktik Kerja Industri 117
Tabel 3.11.
INSTRUMEN PENGAWASAN KESELAMATAN KERJA DI INDUSTRI
Nama Industri :
Alamat Industri :
Jenis Industri :
Jumlah Tenaga Kerja : Laki Laki : ......... orang, Perempuan : ....... orang
Petugas Pemantau :
Tanggal Pemantauan :
Hasil
No Item Pemantauan Faktor Fisika Ket.
Pengukuran
1. Iklim kerja menggunakan parameter ISBB (OC)
2. Intensitas Cahaya (Lux)
3. Intensitas Suara (dBA)
4. Getaran alat kerja mengenai lengan dan tangan (m/det2)
5. Getaran yang berpengaruh terhadap seluruh tubuh (m/det2)
6. Radiasi frekuensi radio a. Kekuatan Medan listrik ( V/m )
dan gelombang mikro b. Kekuatan medan magnit ( A/m )
7. Radiasi sinar ultra ungu (mW/cm2).
8. Medan magnit statis untuk seluruh tubuh (Tesla)
118 Praktik Kerja Industri
Hasil
No Item Pemantauan Faktor Kimia Ket.
Pengukuran
A. Pengukuran Kualitas Kimia Udara Ambien
1. Partikulat (PM10)
2. Karbon Monoksida (CO)
3. Sulfur dioksida (SO2)
4. Nitrogen dioksida (NO2)
5. Ozon (O3)
B. Pengukuran Kualitas Kimia Udara di tempat kerja,
1. ......................
2. ......................
Parameter yang diukur bisa saja berbeda antara industri yang
3.
satu dengan industri yang lain.
..................................,.............................
Tanda tangan
..................................................
Praktik Kerja Industri 119
C. INSTRUMEN PENGAWASAN KESEHATAN KERJA
Kesehatan Kerja adalah upaya peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan yang
setinggi-tingginya bagi karyawan di semua jabatan, pencegahan penyimpangan kesehatan
yang disebabkan oleh kondisi karyawan, perlindungan karyawan dari risiko akibat faktor yang
merugikan kesehatan, penempatan dan pemeliharaan karyawan dalam suatu lingkungan kerja
yang mengadaptasi antara karyawan dengan manusia dan manusia dengan jabatannya. Untuk
mencegah timbulnya gangguan kesehatan dan pencemaran lingkungan di industri, lingkungan
kerja industri harus memenuhi standar dan persyaratan kesehatan agar pekerja dapat
melakukan pekerjaan sesuai jenis pekerjaannya dengan sehat dan produktif.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.02/MEN/1980 tentang
Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja,
menyebutkan bahwa keselamatan kerja yang setinggi-tingginya dapat dicapai bila antara lain
kesehatan tenaga kerja berada dalam taraf yang sebaik-baiknya. Untuk menjamin
kemampuan fisik dan kesehatan tenaga kerja yang sebaik-baiknya perlu diadakan
pemeriksaan kesehatan yang terarah. Pemeriksaan kesehatan kerja tersebut terdiri dari
pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan kesehatan berkala, dan pemeriksaan
kesehatan khusus.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :PER.15/MEN/VIII/2008
tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan, menyatakan bahwa dalam rangka
memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan di tempat kerja
perlu dilakukan pertolongan pertama secara cepat dan tepat. Berdasarkan ketentuan tersebut
diatas lebih jauh disebutkan bahwa pengusaha wajib menyediakan petugas P3K dan fasilitas
P3K di tempat kerja, serta pengurus wajib melaksanakan P3K di tempat kerja. Ketentuan lebih
rinci terkait petugas P3K, fasilitas P3K dan pelaksanaan P3K di tempat kerja dapat dilihat pada
lampiran dari peraturan diatas.
Terkait dengan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja, pemerintah dengan Keputusan
Presiden R.I. Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, menyatakan bahwa Jaminan
Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat
pemelihaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang
diberikan kepada setiap orang yang telah membayar membayar iuran atau iurannya dibayar
oleh Pemerintah. Kepesertaan Jaminan Kesehatan tersebut diharapkan adalah seluruh warga
negara Indonesia termasuk didalamnya adalah tenaga kerja yang bekerja disektor industri baik
formal maupun nonformal.
Seorang tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya di tempat kerja tidak akan
lepas dari kondisi berbahaya yang ada di tempat kerja. Oleh karena itu maka pengusaha wajib
menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kerja di tempat kerja, hal itu sesuai dengan
120 Praktik Kerja Industri
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat
Pelindung Diri. Alat Pelindung Diri (APD) adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan
untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari
potensi bahaya di tempat kerja.
Alat Pelindung Diri yang harus disediakan diantaranya adalah Pelindung kepala,
Pelindung mata dan muka, Pelindung telinga, Pelindung pernapasan beserta
perlengkapannya, Pelindung tangan, Pelindung kaki, termasuk Pakaian pelindung, Alat
pelindung jatuh perorangan, dan Pelampung.
Pelaksanaan pekerjaan sehari-hari di tempat kerja tidak dapat terhindar dari
penanganan beban secara manual. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 70 Tahun 2016
tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri menyebutkan bahwa
persyaratan penangangan beban manual merupakan hal-hal atau kondisi yang harus dipenuhi
oleh setiap tempat kerja dalam rangka mencegah atau mengurangi risiko terjadinya cedera
pada tulang belakang ataupun bagian tubuh lain akibat aktivitas penanganan beban manual.
Adapun persyaratan penanganan beban manual yang baik adalah sebagai berikut:
1. Sedapat mungkin hindari melakukan aktivitas penanganan beban secara manual di
tempat kerja yang dapat menyebabkan risiko cedera; atau
2. Apabila tidak memungkinkan, maka
a. Lakukan penilaian risiko yang sesuai dan memadai pada semua aktivitas
penanganan beban manual yang dilakukan oleh karyawan, dengan memperhatikan
faktor-faktor yang ditentukan.
b. Lakukan pengendalian yang tepat untuk mengurangi risiko cedera pada karyawan
yang mungkin timbul akibat melakukan aktivitas penanganan beban manual ke
tingkat risiko yang dapat diterima.
c. Memberikan informasi yang tepat kepada setiap karyawan yang melakukan
aktivitas penanganan beban manual berupa:
1) Berat dari setiap beban atau benda yang akan ditangani.
2) Bagian atau sisi terberat dari beban atau benda yang akan diangkat yang
menyebabkan pusat gravitasi tidak berada di sentral.
d. Ulangi penilaian risiko jika:
1) Adanya dugaan bahwa penilaian tersebut tidak lagi sesuai.
2) Terdapat perubahan bermakna pada aktivitas penanganan beban manual yang
dimaksud.
Berdasarkan uraian di atas, maka untuk melakukan pengawasan terhadap aspek
kesehatan kerja pada tenaga kerja di industri dapat menggunakan instrumen pengawasan
sebagai berikut :
Praktik Kerja Industri 121
Tabel 3.12
INSTRUMEN PENGAWASAN KESEHATAN KERJA DI INDUSTRI
Nama Industri :
Alamat Industri :
Jenis Industri :
Jumlah Tenaga Kerja : Laki Laki : ......... orang, Perempuan : ....... orang
Petugas Pemantau :
Tanggal Pemantauan :
No Item Pemantauan Ya Tidak Ket.
1. Apakah dilakukan pemeriksaan kesehatan sebelum kerja
2. Apakah dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala
3. Apakah dilakukan pemeriksaan kesehatan khusus
4. Apakah ada petugas P3K sesuai kebutuhan
5. Apakah tersedia kotak P3K sesuai kebutuhan
6. Apakah isi kotak P3K sesuai ketentuan
7. Apakah semua tenaga kerja mengikuti BPJS Kesehatan
8. Apakah semua tenaga kerja mengikuti BPJS
Ketenagakerjaan
9. Apakah tersedia APD yang diperlukan
10. Apakah jumlah APD memenuhi kebutuhan
11. Apakah ada penanganan beban secara manual
12. ......
13 ......
..................................,.............................
Tanda tangan
..................................................
122 Praktik Kerja Industri
Latihan
Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan
berikut!
1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.13/MEN/X/2011
mengatur tentang apa?
2) Faktor lingkungan fisik tempat kerja yang harus diawasi terkait dengan keselamatan
kerja mepiluti apa saja?
3) Sebutkan beberapa syarat keselamatan kerja yang harus terpenuhi pada suatu tempat
kerja!
Ringkasan
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas
keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan
produksi serta produktivitas Nasional; bahwa setiap orang lainnya yang berada di
tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya; bahwa setiap sumber produksi perlu
dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien.
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.15/MEN/VIII/2008
tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan, menyatakan bahwa dalam rangka
memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan di tempat
kerja perlu dilakukan pertolongan pertama secara cepat dan tepat. Berdasarkan
ketentuan tersebut di atas lebih jauh disebutkan bahwa pengusaha wajib menyediakan
petugas P3K dan fasilitas P3K di tempat kerja, serta pengurus wajib melaksanakan P3K
di tempat kerja.
3. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar dan
Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri menyebutkan bahwa persyaratan
penangangan beban manual merupakan hal-hal atau kondisi yang harus dipenuhi oleh
setiap tempat kerja dalam rangka mencegah atau mengurangi risiko terjadinya cedera
pada tulang belakang ataupun bagian tubuh lain akibat aktivitas penanganan beban
manual.
Praktik Kerja Industri 123
Tes 3
Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar!
1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.08/MEN/VII/2010
mengatur tentang....
A. Pengendalian Kebakaran.
B. Pemeriksaan Kesehatan.
C. Alat Pelindung Diri.
D. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.
2) Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga
kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja....
A. Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
B. Keselamatan Kerja.
C. Kesehatan Kerja.
D. Hygiene Perusahaan.
3) Salah satu parameter udara ambien yang harus diukur terkait dengan keselamatan dan
kesehatan kerja di industri adalah....
A. Partikulat (PM10).
B. Debu terendap.
C. Karbon dioksida.
D. Kadar oksigen.
124 Praktik Kerja Industri
Kunci Jawaban Tes
Test 1
1) D.
2) B.
3) A.
Test 2
1) A.
2) C.
3) A.
Test 1
1) C.
2) A.
3) A.
Praktik Kerja Industri 125
Glosarium
Total Disolved Solid (TDS) padatan terlarut yang terdapat pada limbah cair yang
biasanya digunakan sebagai indikator kandungan zat organic
dalam limbah cair.
Responden orang yang dijadikan sebagai obyek sasaran atau memiliki
keterlibatan langsung dalam penelitian terhadap suatu kasus
maupun adanya permasalahan yang sedang dikaji.
Faktor Fisik faktor fisik lingkungan di tempat kerja yang memiliki pengaruh
terhadap terjadinya kecelakaan kerja maupun terhadap
kesehatan tenaga kerja, misalnya kebisingan, pencahayaan,
iklim kerja, getaran, panas radiasi.
Biochemical Oxygen Demand jumlah oksigen yang diperlukan bakteri dalam proses
biokimia dalam mendekomposisi zat organic secara aerobic.
Chemical Oxygen Demand jumlah oksigen yang dibutuhkan bakteri dalam proses
dekomposisi/ penguraian secara kimiawi.
126 Praktik Kerja Industri
Daftar Pustaka
Agus Sartono. 2001. Long Term Financing Decision: Views and Practices of Financial Managers
of Listed Public Firms in Idonesia. Gadjah Mada International Journal Business. Januari.
Volume 5 No. 1.
Cooper, Donald R., dan Emory, William. 1995. Business Research Methods, Richard D Irwin,
Inc.
Burner Gordon C II & Hensel Paul J. 1992. Marketing Scale Handbook: A Compilation of Multi-
Item Measures, American Marketing Association, Illinois.
Hair, Joseph F., Jr., dkk. 1995. Multivariate Data Analysis with Readings. 4thedition. Prentice
Hall. New Jersey.
Jogiyanto. 2005. Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman,
BPFE, Yogyakarta.
Keputusan Presiden R.I. Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-45/MENLH/10/1997 tentang
Indeks Standar Pencemar Udara.
Lerbin, Aritonang., R., 2011. Metode Penelitian Kuantitatif. Modul Pelatihan Metodologi
Penelitian Universitas Islam “45”.
Marija J Noursis. 1993. SPSS for Windows Profesional Statistics Release 6.0. SPSS Inc. USA.
Nazir, Moh, Ph. D.1998. Metode Penelitian, Ghalia Indonesia.
Noeng Muhadjir. 1998. Metodologi Penelitian Kualitatif: Telaah Positivistik, Rasionalistik,
Phenomenologik, Realisme Metaphisik, Rake Sarasin, Yogyakarta.
Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 32 tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu
Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Hygiene
Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum.
Praktik Kerja Industri 127
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Perkantoran.
Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 70 tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan
Kesehatan Lingkungan Kerja Industri.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup R.I. Nomor 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.13/MEN/X/2011 tentang Nilai
Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di tempat kerja.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat
Pelindung Diri.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :PER.15/MEN/VIII/2008 tentang
Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.02/MEN/1980 tentang
Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air.
Sekaran, Uma. 2000. Research Methods for Business: A Skill Building Approach, 3rd ed., John
Wiley & Sons Inc, 1994.
Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Bisnis, Alfabeta, Bandung.
Suharsimi Arikunto. 1996. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi III.
Rineka Cipta. Jakarta.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
128 Praktik Kerja Industri
Bab 4
PELAKSANAAN PENGAWASAN
PRAKTIK KERJA INDUSTRI
Hadi Suryono, ST., MPPM.
Yulianto, S.Pd., M.Kes.
Pendahuluan
P
elaksanaan pengawasan atau penilaian praktik kerja industri dilaksanakan setelah
instrument selesai dibuat dan siap digunakan untuk melakukan penilaian. Untuk
melakukan penilaian, Saudara dituntut menguasai materi terkait penilaian yang
dilakukan. Yang dimaksud dengan materi terkait adalah materi-materi mata kuliah terkait
yang pernah Saudara pelajari selama kuliah Diploma III Kesehatan lingkungan meliputi
penyediaan air bersih dan pengelolaan limbah cair, penyehatan udara, penyehatan tanah,
pengelolaan sampah, penyehatan makanan dan minuman, pengendalian vektor, tatagraha,
hygiene perorangan, pengelolaan tinja. Materi yang telah Saudara pelajari tersebut digunakan
sebagai pertimbangan dalam memberikan nilai terkait kompetensi sanitasi di industri tempat
Saudara melakukan praktikum. Keterbatasan manusia dalam menguasai kompetensi yang
diterima selama perkuliahan tidaklah sama, namun dengan adanya penyeragaman instrument
yang digunakan setidaknya dapat memberikan pendekatan hasil penilaian yang lebih objektif
terhadap sasaran penilaian.
Penilaian terhadap objek atau sasaran sanitasi industri dilakukan dengan menggunakan
instrument penilaian yang telah dibuat sebelumnya. Instrument bisa berupa panduan
wawancara (questioner), lembar observasi, checklist, atau pengukuran langsung. Saudara
sebagai seorang Sanitarian harus mampu dan memiliki intuisi yang kuat dalam menetapkan
sistim pengukuran yang tepat dengan panduan instrument tersebut. Penentuan titik sampling
pada saat pengukuran menjadi hal yang perlu diperhatikan selain penguasaan penggunaan
alat dan prosedur kerja yang benar. Pelaksanaan kegiatan pengawasan sanitasi industri
memerlukan persiapan yang baik agar semua target dapat diselesaikan tepat waktu sesuai
yang ditetapkan dalam buku pedoman.
Praktik Kerja Industri 129
Persiapan yang Saudara lakukan sebelum melaksanakan penilaian atau pengukuran di
lokasi praktek kerja industri adalah sumber daya yang akan digunakan dan teknik atau strategi
pelaksanaan dalam melakukan proses penilaian atau pengawasan. Yang dimaksud sumber
daya di sini adalah jenis dan tipe peralatan yang digunakan, petugas yang melaksanakan
pengukuran. Peralatan tentunya menggunakan peralatan yang berfungsi dengan baik, layak
pakai dan sudah dikalibrasi, sedangkan yang dimaksud strategi pelaksanaan adalah
pengaturan waktu berdasarkan hasil koordinasi Saudara dengan pihak pengelola terkait
kesiapan lokasi objek pengukuran dan pada prinsipnya tidak mengganggu pelaksanaan tugas
operasi kegiatan industri.
130 Praktik Kerja Industri
Topik 1
Pelaksanaan Pengawasan Sanitasi Industri
P
elaksanaan pengawasan sanitasi industri dilakukan dengan bantuan kuesioner penilaian
yang telah dibuat sebelumnya sebagaimana Bab 3.
Instrumen penilaian yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan bisa berupa
berbagai macam bentuk tergantung dari kebutuhan data yang dibutuhkan agar diperoleh hasil
penilaian yang sesuai dengan jenis dan macam data yang diperlukan. Jenis data yang diperoleh
akan diarahkan kepada cara atau sistem evaluasi yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya.
Sebagai contoh apabila data yang diinginkan terkait dengan dokumen perusahaan, maka
instrument yang diperlukan tentu berbentuk questioner. Apabila data yang diinginkan
merupakan kualitas faktor fisik lingkungan di tempat kerja industri, sistem atau cara yang
digunakan harus melakukan pengukuran menggunakan peralatan yang sesuai kebutuhan.
Pelaksanaan pengukuran harus dilakukan pada saat yang tepat, artinya pada waktu yang
mewakili jam kerja industri. Hal itu dilakukan karena tujuan penilaian atau pengawasan
sanitasi industri adalah untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan atau terjadinya
kecelakaan kerja bagi tenaga kerja di industri. Mengurangi atau meniadakan gangguan
kesehatan dan atau terjadinya kecelakaan kerja berarti akan meningkatkan produktivitas
tenaga kerja di industri. Di sisi lainnya adalah untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kerja
itu sendiri.
A. PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYEDIAAN AIR
Yang dimaksud dengan penyediaan air bagi industri adalah penyediaan air bersih untuk
keperluan higyene dan sanitasi industri dan air minum untuk karyawan atau tenaga kerja
industri termasuk para pengunjung atau tamu di industri. Oleh sebab itu untuk mengetahui
kuantitas air yang dibutuhkan Saudara harus menghitung :
1. Seluruh tenaga kerja yang ada di industri termasuk pengunjung rata-rata perharinya.
2. Kebutuhan air bersih per orang per hari.
3. Kebutuhan air bersih di industri per orang per hari, yaitu sebesar 20 l/o/h (permenkes
70 tahun 2016).
Sedangkan untuk mengetahui kualitas air bersih Saudara harus memeriksa kualitas air
secara fisik, bakteriologis atau kimia tergantung pemeriksaan yang dibutuhkan.
Praktik Kerja Industri 131
Dalam penilaian penyediaan air minum untuk karyawan Saudara dapat menilai secara
langsung dengan melakukan observasi terhadap:
1. Jumlah atau kuantitas air minum yang disediakan oleh pihak pengelola industri,
berdasarkan kebutuhan air minum per orang per hari. Hal ini mengacu kepada peraturan
yang berlaku.
2. Cara menyediakan air minum tersebut agar aman tidak terkontaminasi oleh kotoran
atau bakteri di lingkungan kerja
3. Cara tenaga kerja mengambil minuman.
4. Mengetahui sumber air yang diminum tenaga kerja, dan mengambil sampel untuk
pemeriksaan parameter air minum tertentu jika diperlukan.
Untuk mempermudah cara pelaksanaan pengawasan, maka Saudara diwajibkan
memperhatikan sasaran pengawasan pada Bab 2 dan instrument pengawasan pada Bab 3.
Untuk memperlancar pencarian data dalam penilaian sebaiknya Saudara minta izin
dalam pengaturan waktu pengambilan data kepada pengelola, manajer, atau supervisor yang
memiliki wewenang di industri tersebut, misalnya pada jam istirahat atau waktu yang
ditentukan oleh pihak perusahaan.
Apabila diperlukan pengukuran parameter air bersih karena pertimbangan tertentu,
lakukanlah pengukuran sesuai dengan permintaan pihak industri atau mengikuti rencana
kegiatan yang sudah saudara rencanakan pada waktu persiapan.
B. PELAKSANAAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR
Pengelolaan limbah cair di industri memiliki peran yang sangat penting terutama terkait
dengan pencemaran lingkungan dan penilaian tingkat kepatuhan industri terhadap peraturan
perundangan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan atau penilaian yang dilakukan terhadap
pengelolaan limbah cair ditentukan oleh tujuan pemeriksaan atau penelitian, atau monitoring
dampaknya secara berkala berkaitan dengan pengendalian pencemaran lingkungan.
Kegiatan pengawasan yang dilakukan mahasiswa peserta praktek kerja industri adalah
bertujuan untuk memperoleh pengalaman belajar monitoring dampak kesehatan lingkungan
akibat pengelolaan limbah cair yang dilakukan oleh industri. Oleh sebab itu penilaian lebih
ditekankan untuk mengetahui karateristik limbah yang dihasilkan, dampak yang ditimbulkan
terkait pencemaran badan air, instalasi pengolahan yang ada di industri, efektifitas
pengolanan IPAL, dan kualitas efluen buangan limbah cair industri. Hal tersebut
mempengaruhi cara menentukan titik pengambilan sampel yang akan dilakukan oleh
mahasiswa.
132 Praktik Kerja Industri
Penentuan titik sampling limbah cair industri untuk berbagai tujuan tersebut dapat di
ilustrasikan sebagai berikut:
Keterangan:
1 : bak kontrol saluran air limbah
2 : input IPAL (influent)
3 : output IPAL (effluent)
4 : perairan penerima sebelum air limbah masuk ke badan air
5 : perairan penerima setelah air limbah masuk ke badan air
Gambar 4.1 Penentuan Titik Sampling Limbah Cair di Industri
Perhatikan Ilustrasi Gambar Penentuan Titik Sampling Limbah Cair Industri Di Atas
1. Titik 1 adalah titik sampling yang digunakan untuk mengetahui kualitas limbah masing-
masing jenis produksi di industri industri. Tujuannya adalah untuk mengetahui efisiensi
produksi, dengan asumsi semakin buruk kualitas limbah yang dihasilkan, maka semakin
tidak efisien hasil produksi di industri tersebut.
2. Titik 2 dan 3 adalah titik sampling yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui efektifitas
instalasi air limbah (IPAL) yang dimiliki industri. Semakin tinggi penurunan polutan
pencemar semakin efektif IPAL tersebut.
3. Titik 4 dan 5 adalah titik sampling untuk mengetahui tingkat cemaran limbah cair oleh
industri, berfungsi untuk mengambil kesimpulan pengaruh limbah industri terhadap
Praktik Kerja Industri 133
pencemaran badan air. Lebih jauh lagi sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan oleh
pihak yang berwenang terkait dengan pencemaran.
Pengambilan sampel dalam rangka penilaian atau pengawasan limbah cair industri harus
menggunakan tatacara yang benar sesuai dengan parameter yang ingin diperiksa. Untuk
parameter bakteriologis, kimia atau fisik memiliki persyaratan masing-masing yang harus
dipenuhi.
Untuk pemeriksaan secara bakteriologis prinsipnya adalah steril, baik steril
peralatannya, steril tempat sampel, maupun steril pada proses pengambilannya. Sedangkan
untuk pemeriksaan parameter kimia harus dihindari adanya aerasi saat pengambilan sampel
agar tidak terjadi oksidasi terhadap parameter kimia yang akan diperiksa sehingga tidak
berubah komposisinya. Pemberian bahan pengawet harus diperhatikan biasanya diperlukan
sesuai dengan parameter yang akan diperiksa. Jenis parameter yang akan diperiksa
tergantung dari jenis produksi yang dihasilkan industri tempat praktek.
Jenis parameter harus diukur di lapangan bersamaan dengan sampling limbah cair
diantaranya adalah pH, suhu, dan parameter yang diperlukan sesuai kebutuhan. Jangan lupa
memberi pengawet untuk pemeriksaan parameter kimia air limbah. Juga pengawet harus
diberikan berdasarkan parameter yang akan diperiksa.
Setelah dilakukan pengambilan sampel limbah cair, maka kegiatan selanjutnya adalah:
memberi label, membawa sampel ke laboratorium dengan memperhatikan prinsip agar tidak
terjadi perubahan komposisi sampel, misalnya dengan bahan pengawet dan botol gelap, serta
waktu pengiriman tidak lebih dari 12 jam.
C. PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYEHATAN TANAH DAN PENGELOLAAN
SAMPAH
1. Penyehatan Tanah
Pengawasan pencemaran tanah ditujukan untuk menjamin tidak terjadinya keracunan
akibat bahan kimia yang berasal dari polutan pencemar tanah terhadap manusia, hewan
maupun tumbuhan.
Kegiatan yang Saudara perlukan untuk pemeriksaan tanah adalah sebagai berikut:
a. Lakukan pengambilan sampel tanah pada lokasi yang sudah ditetapkan. Alat yang
digunakan adalah mata bor auger dengan batang bornya berdiameter sekitar 10 cm,
cetok, kantong praktik, label, ballpoint.
b. Untuk peralatan pengukuran parameter lapangannya adalah pengukur pH tanah,
pengukur suhu tanah.
134 Praktik Kerja Industri
c. Keduklah bagian atas permukaan tanah setebal kurang lebih 15 cm.
d. Lakukan pengambilan tanah dengan cara meletakkan mata bor tegak lurus di atas
permukaan tanah
e. Putarlah batang bor searah jarum jam sehingga mata bor masuk kedalam tanah dan
terisi penuh
f. Keluarkan tanah sampel dari mata bor dengan bantuan Cetok dan taruk di dalam
kantong plastik.
g. Ukurlah suhu dan pH tanah sampel.
h. Masukkan sampel tersebut dalam box dan bawa ke laboratorium untuk pemeriksaan
parameter kimia yang diperlukan.
2. Pengelolaan Sampah
Pelaksanaan penilaian terhadap pengelolaan sampah lebih ditekankan kepada sejauh
mana perusahaan tempat praktik kerja industri mengelola sampahnya agar tidak
menimbulkan gangguan kesehatan dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja bagi tenaga
kerja.
Kegiatan penilaian atau pengawasan yang dilakukan meliputi:
a. Mengidentifikasi kondisi kebersihan dalam ruang kerja dan di luar ruang kerja misalnya
di gang, koridor, halaman dan taman, serta tempat-tempat kegiatan lainnya.
b. Menilai tempat sampah, kesesuaiannya dengan volume sampah yang dihasilkan,
konstruksi tempat sampah, pemisahan tempat sampah untuk jenis sampah yang
memiliki karakteristik berbeda misalnya sampah organik dengan anorganik, sampah
basah dan sampah kering, sampah berbahaya/B3, sampah radiologi.
c. Menilai kegiatan pembersihan sampah dan pemeliharaan kebersihan di dalam maupun
di luar ruang kerja di lingkungan perusahaan.
d. Menilai cara pengangkutan sampah
e. Menilai cara pemusnahan sampah
f. Menilai jumlah kecukupan tempat sampah
g. Manila kecukupan petugas sampah
h. Mengolah data atau merekapitulasi data hasil pengawasan dari instrumen pengawasan
pengelolaan sampah
D. PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYEHATAN MAKANAN DAN MINUMAN
Langkah-langkah pelaksanaan penilaian pengawasan makanan dan minuman dapat
dilakukan dengan cara:
Praktik Kerja Industri 135
1. Kegiatan persiapan, misalnya:
a. Menyiapkan instrumen penilaian
b. Berkoordinasi dengan pengelola industri perihal jadwal pelaksanaan
2. Kegiatan pelaksanaan, yaitu :
a. Memetakan tempat-tempat yang akan dituju dalam melakukan penilaian,
b. Menentukan urutan kegiatan pelaksanaan terhadap objek penilaian
c. Melakukan langkah pengawasan atau penilaian, atau pengukuran bila diperlukan.
Teknik pelaksanaan langkah penilaian bisa dilakukan dengan mengorganisasi kegiatan
yang telah diurutkan tersebut agar berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
Pengorganisasian kegiatan dimaksud adalah mengelompokkan kegiatan sejenis untuk
memudahkan pelaksanaan pengawasan atau penilaian. Pengelompokan bisa didasarkan pada
tempat atau lokasi objek sasaran pemeriksaan, misalnya kelompok kegiatan pemeriksaan
yang dilakukan di dapur kantin atau kelompok pemeriksaan dengan objek pengawasan ruang
makan.
Jika dilaksanakan berdasarkan tempat atau lokasi penilian maka seluruh kegiatan
penilaian di tempat tersebut harus diselesaikan secara tuntas kemudian baru berpindah ke
lokasi lainnya. Pelaksanaan demikian dimaksudkan agar mahasiswa dalam melakukan
kegiatan tidak bolak-balik kembali ke lokasi penilaian sehingga tidak mengganggu kegiatan
operasional yang berjalan di lokasi praktik.
Untuk melaksanakan kegiatan penilaian atau pengawasan makanan dan minuman
dengan baik, Saudara dituntut menguasai di titik-titik mana harus melakukan penilaian.
Sebagai contoh pada saat menilai hygiene dan sanitasi lajur makanan. Lajur makanan
yaitu perjalanan makanandalam rangkaian proses pengolahan makanan. Titik-titik yang harus
diawasi adalah pada bagian:
1. Penerimaan bahan
2. Pencucian bahan
3. Perencaman
4. Peracikan pemasakan (cooking)
5. Pewadahan
6. Penyajian makanan, dan
7. Kondisi kenyamanan santapan makanan
136 Praktik Kerja Industri
E. PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYEHATAN UDARA
Sebagaimana disebutkan dalam sasaran pengawasan penyehatan udara di industri di
Bab II, bahwa pengawasan kualitas udara dilakukan di dalam ruang atau bangunan (indoor)
dan di udara lingkungan luar gedung (ambient air quality). Alat yang digunakan mengukur
kualitas fisik udara adalah bermacam-macam tergantung parameter yang dinilai kualitasnya.
Peralatan yang bisa digunakan untuk mengukur beberapa parameter kualitas fisik udara:
Tabel 4.1
Nama Peralatan Untuk Mengukur Faktor Lingkungan Fisik Udara :
No. parameter Nama alat Keterangan
Terdiri thermometer basah dan
1. Suhu & Kelembaban Psychrometer
kering
Globe Suhu basah, kering, dan suhu
2. Iklim Kerja
Thermometer radiasi
3. Kecepatan aliran udara Anemometer
4. Pencahayaan Lux meter Satuan Lux
5. Kebisingan Sound Level meter Satuan dBA
Kebisingan untuk
6. Noise dose meter
perorangan
Praktik Kerja Industri 137
Tabel 4.2
Peralatan Yang Umum Digunakan Untuk Mengukur Parameter Kimia Udara
No. parameter Nama alat keterangan
1. debu High volume dust sampler Udara ambient
(HVDS)
2. Debu perorangan Personal dust sampler (PDS) Dalam ruang kerja
3. Gas Midget Impinger Menangkap gas dg
absorben
4. Spektrofotometer Memeriksa kadar gas, logam,
zat organik, dan lain-lain.
Tabel 4.3
Peralatan Untuk Pengukuran Parameter Mikrobiolobi Udara
1. Mikrobiobiologi udara Mikro Air Sampler (MAS)
2. Gas detector Gas di udara Dengan tube
detector
Yang penting Saudara perhatikan bahwa cara pengambilan sampel udara harus
mengikuti prosedur pengukuran yang benar, prosedurpenggunaan alat yang digunakan untuk
pengukuran. Spesifikasi alat yang digunakan untuk pengukuran juga harus ditulis dalam
laporan hasil pengukuran karena setiap alat memiliki spesifikasi sendiri. Kesalahan yang sering
dilakukan adalah tidak dilakukan pemetaan dalam penentuan titik sampling oleh mahasiswa,
sehingga tidak mewakili lokasi yang diukur. Selain itu juga perlu diperhatikan sikap pada saat
menggunakan alat saat pengukuran. Oleh sebab itu Saudara harus mempelajari kembali
secara seksama cara pengukuran yang benar sesuai prosedur yang ditetapkan.
F. PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGENDALIAN VEKTOR
Vektor dapat menimbulkan beberapa kerugian terhadap kesehatan para tenaga kerja di
industri. Beberapa penyakit yang bisa ditimbulkan oleh vector diantaranya:
1. Penyakit malaria, diakibatkan oleh vector malariae
138 Praktik Kerja Industri
2. Penyakit demam berdarah (DHF) disebabkan oleh vector Aedes Aegyptie
3. Penyakit Kaki Gajah dan penyakit Cikungunya disebabkan oleh vector Culex.
4. Penyakit diarrhea, typhus, colera, disentri, dapat disebabkan oleh lalat dan kecoa.
5. Penyakit pes dan leptospirosis disebabkan oleh kotoran tikus.
Vector dan binatang pembawa penyakit seperti lalat, tikus, kecoa harus dicegah
keberadaannya di industri tempat tenaga kerja melakukan aktivitasnya.
Teknik Pemberantasan vector dan binatang pembawa penyakit telah Saudara pelajari di
perkuliahan. Dalam melakukan pengawasan pengendalian vector di industri Saudara harus
mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya:
1. Apakah Industri Sudah Melakukan Pengendalian Terhadap Vector Dan Binatang
Pembawa Penyakit
Tentunya pengendalian dilakukan terhadap jenis vector atau binatang pembawa
penyakit dengan mengetahui keberadaannya di lingkungan perusahaan atau industri tempat
kerja praktik. Keberadaan vector dan binatang pembawa penyakit dapat diketahui dengan
melakukan identifikasi dan pengawasan terhadap tempat perindukan atau bersarangnya
vector atau binatang pembawa penyakit tersebut.
2. Jika Telah Diketahui Adanya Vector atau Binatang Pembawa Penyakit, Apakah Teknik
Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Sudah Sesuai Dengan Prosedur, Alat, dan Bahan
Yang Digunakan
Yang Saudara lakukan dalam pengawasan ini adalah mengidentifikasi keberadaan vector
dan binatang pembawa penyakit di lingkungan dalam dan luar gedung industri tempat praktik
menggunakan instrumen yang telah Saudara buat pada tahap sebelumnya.
Identifikasi vector Aedes Aegyptie dilakukan dengan mengamati adanya larva dan
nyamuk aedes aegypti yang berada di bak mandi atau kontainer-kontainer berisi air bersih di
lingkungan industri. Sasaran yang lain adalah mengamati keberadaan larva Culex di lingkungan
industri, serta indeks lalat dan keberadaan tikus dan kecoak. Keberadaan tikus dapat diketahui
dengan melakukan identifikasi tempat bekas lalu lintas jalannya tikus yang ditandai dengan
bercak hitam atau kotor akibat gesekan tubuh tikus atau kontak kaki tikus dengan dinding
yang dilewati.
G. PELAKSANAAN PENGAWASAN HOUSEKEEPING ATAU TATA GRAHA DI
INDUSTRI
Area kerja yang kotor, penuh debu dan berantakan dapat menyebabkan karyawan
merasa tidak nyaman dan aman saat bekerja. Kondisi tersebut akan berimbas pada keselatam
Praktik Kerja Industri 139
kerja terganggu dan tingkat produktivitas kerja menurun. Penataan area kerja yang buruk
secara tidak langsung bisa menghambat pergerakan kerja karyawan dan kemungkinan besar
menyebabkan kecelakaan kerja, seperti terjatuh, terpeleset, atau lainnya. Standar OSHA
1910.22(a)(1) menyatakan, "semua tempat kerja yang ditujukan bagi karyawan, harus benar-
benar aman dan dapat menjamin keselamatan kerja para karyawan." Standar OSHA ini
tentunya mencakup pengaturan untuk berbagai area kerja yang biasa dilewati ataupun sering
dilakukan aktivitas kerja, di mana area kerja tersebut mengandung berbagai potensi bahaya
yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja dan kerugian lain.
Tanda-tanda perusahaan dengan housekeeping yang buruk:
1. Pengaturan area kerja yang buruk dan berantakan
2. Penyimpanan barang atau bahan berbahaya secara sembarangan dan tidak tertata
3. Lantai kotor dan berdebu
4. Tidak ada ruang khusus untuk penyimpanan barang hasil produksi yang berlebih dan
barang tidak diperlukan lagi
5. Banyaknya hambatan di area menuju jalan keluar atau jalan yang sering dilalui karyawan
6. Peralatan kerja yang sudah dipakai tidak dikembalikan ke tempat semula
7. Sampah pada kontainer dibiarkan menumpuk berlebihan
8. Tumpahan dan kebocoran
Yang Saudara lakukan dalam pengawasan ini adalah melakukan penilaian pelaksanaan
housekeeping atau tata graha di industri tempat praktek dengan menggunakan instrument
penilaian yang sudah Saudara siapkan. Cek kembali apakah instrumen yang Saudara buat
sudah meliputi aspek-aspek atau substansi materi di bawah ini:
1. Tempat pengelola, gang-gang, ruang penyimpanan (gudang) harus dijaga dalam kondisi
sanitair.
2. Atap, gang-gang, lantai, dinding, basement, gudang bawah tanah, jamban, toilet, septick
tank, saluran pembuangan, dan lain-lain setiap saat harus bersih dan aman serta dalam
kondisi yang sanitair.
3. Setiap bangunan, halaman, gang-gang dan keseluruhan wilayah milik perusahaan harus
dijaga bebas dari akumulasi debu dan sampah lainnya.
4. Setaip lantai ruang kerja harus dikelola secara bersih dan sebisa mungkin dalam kondisi
kering.
5. Apabila ada kegiatan-kegiatan yang menggunakan air maka sistem drainase atau
pematusan harus dikelola dengan baik (dimungkinkan dalam kondisi cepat kering).
Pekerja harus menggunakan sepatu khusus untuk tempat semacam itu.
6. Lantai atau permukaan jalan lainnya harus terjaga dalam kondisi baik, bebas minyak
atau air, semua hal yang bernbahaya yang ada dijalanan harus dihilangkan.
140 Praktik Kerja Industri
7. Setiap lantai, tempat kerja dan jalan atau gang harus bebas dari gundukan, serpihan atau
lubang.
8. Dilarang meludah ke dinding, lantai, tempat kerja atau lantai bangunan lainnya.
9. Jika disediakan tempat meludah konstruksinya harus bisa dibersihkan dan di desinfeksi
serta harus dalam keadaan bersih setiap hari untuk menjaga kesehatan.
10. Jika tempat sampah digunakan untuk sampah basah atau yang dapat terurai
konstruksinya harus dibuat tidak bocor, nyaman, bersih dan dirawat dengan baik atau
sanitair.
11. Jika menggunakan mesin atau peralatan kimia di dalam mengelola sanitasi pemeriksaan
secara periodik harus dilakukan untuk menjamin efisiensi peralatan dan mencatat hasil
setiap pemeriksaan.
12. Peralatan penerangan harus sering dibersihkan untuk menjaga intensitas penerangan
agar tetap berada pada level yang memenuhi syarat. Jika menggunakan penerangan
alami pada siang hari maka jendela harus sering dibersihkan agar pencahayaan diruang
tersebut memenuhi syarat.
13. Bahan-bahan buangan yang mudah terbakar harus ditempatkan pada wadah logam
yang dapat menutup sendiri dan harus dikosongkan minimal 1 kali dalam sehari
14. Bahan-bahan yang mudah terbakar sebaiknya jangan disimpan dibawah tangga.
15. Alat pemadam kebakaran harus dijaga agar mudah dioperasikan dan terlindung dari
proses pendinginan. Jika alat pemadam kebakaran memakai tipe asam soda sebaiknya
diisi ulang minimal setahun sekali.
16. Bahan-bahan atau material harus di tumpuk dan dihindarkan dari getaran atau vibrasi
dan sentakan agar tidak mudah jatuh.
17. Barang-barang yang tertata baik dan bersih tidak lagi menghambat pergerakan para
karyawan
Praktik Kerja Industri 141
Saudara dapat melakukan pengawasan dengan menggunakan checklist penilaian
housekeeping seperti di bawan ini:
Nama pengawas :
Tanggal :
Memenuhi syarat = V, tidak memenuhi syarat = X
No. Item Penilaian Hsl Keterangan
A. Lorong/ Akses jalan dalam ruangan
Bersih
Kosong (bebas penghalang)
Ditandai dengan baik (terdapat rambu/sign)
B. Akses masuk dan keluar
Kosong (bebas dari penghalang)
Ditandai dengan baik (terdapat rambu/sign)
C. Peralatan kerja manual dan portable
Kosong (bebas dari penghalang)
Ditandai dengan baik (terdapat rambu/sign)
D. Peralatan kerja manual dan portable
Disimpan dengan benar dan aman saat
digunakan atau tidak digunakan
E. Peralatan pemadam kebakaran
Peralatan pemadam kebakaran
Mudah diakses
F. Lantai
Bersih
142 Praktik Kerja Industri
No. Item Penilaian Hsl Keterangan
Kering
Kosong (bebas penghalang)
Dalam kondisi baik
G. Tangga (alat kerja)
Dalam kondisi baik (layak pakai)
Bebas dari minyak atau pelumas (tidak licin)
Aman ketika digunakan atau tidak digunakan
H. Penerangan
meadai
bersih
I. Sistem ventilasi
Bersih
Kosong bebas (penghalang)
J. Mesin
bersih
Kosong (tidak ada penghalang)
Dalam kondisi baik
K. Jalan raya, area parkir
Dalam kondisi baik
Ditandai dengan baik (dengan rambu)
L. Sign, Tag
Desain dan ukuran sesuai standar
Memadai
Dipasang di lokasi yg tepat dan terlihat jelas
Praktik Kerja Industri 143
No. Item Penilaian Hsl Keterangan
Bersih
M. Penyimpanan dan penumpukan barang atau
material
Di area khusus
Penumpukan barang stabil dan aman
Ditandai dengan baik (terdapat rambu atau
label)
Area bersih dan bebas dari penghalang yang
membahayakan
Di area khusus
N. Tangga (terdapat dalam ruangan atau
sebuah bangunan)
Di area khusus
Tidak licin
bersih
Bebas (tidak ada penghalang
Dalam kondisi baik
O. Area atau Tempat pembuangan limbah dan
sampah
Jumlah tempat pembuangan sampah yang
memadai
Pengelompokan dan penempatan limbah
sesuai jenisnya
Area atau Tempat pembuangan limbah dan
sampah
144 Praktik Kerja Industri
H. PELAKSANAAN PENGAWASAN JAMBAN DAN PETURASAN
Penilaian jamban dan peturasan tidak dapat dipisahkan dengan penilaian aspek sanitasi
industri lainnya, karena tidak adanya penilaian jamban dan peturasan maka penilaian sanitasi
industri belum selesai. Adanya jamban dan peturasan yang kotor, berbau dan tidak sehat akan
mempengaruhi kesehatan karyawan dan akhirnya karyawan akan terganggu kesehatannya
dan berujung pada gangguan produktivitas kerja tenaga kerja. Jamban dan peturasan
merupakan sarana sanitasi utama yang harus disediakan perusahaan dan dikelola dengan
baik, disamping sarana sanitasi lainnya. Ketidaknyamanan yang diakibatkan adanya jamban
dan peturasan yang tidak sehat akan menimbulkan bau yang tidak sedap, lantai yang licin
menyebabkan terpeleset dan jatuh, lebih jauh lagi akan menimbulkan penyakit pada tenaga
kerja. Kondisi tersebut memerlukan pengelolaan yang baik sehingga kondisi jamban dan
peturasan menjadi bersih dan sanitair. Sanitair berarti sehat dan aman. Sehat karena dalam
jamban dan peturasan tidak terdapat bakteri penular penyakit, tidak terjangkau serangga
yang dapat mengontaminasi makanan tenaga kerja.
Yang perlu Saudara pertimbangkan dalam menilai jamban dan peturasan tidak saja
kondisi kebersihan dari sarana tersebut melainkan juga hal lain yang mempengaruhi kualitas
jamban agar tidak mempengaruhi timbulnya penyakit atau mengganggu kesehatan tenaga
kerja sehingga produktivitas kerja jadi menurun. Pertimbangan tersebut meliputi:
1. Konstruksi jamban dan peturasan
2. Jumlah jamban dan peturasan
3. Pengelolaan dan pemeliharaan jamban
4. Penyediaan air bersih
Prosedur Melakukan Pengawasan Fasilitas Jamban dan Peturasan di Industri:
1. Persiapkan instrumen penilaian atau pengawasan
2. Persiapkan perlengkapan lain yang diperlukan selama pengukuran antara lain ballpoint,
buku catatan, senter.
3. Lakukan penilaian berdasarkan instrument yang Saudara buat.
4. Instrument bisa berupa lembar checklist atau lembar observasi, dan atau lembar
wawancara.
Lembar wawancara digunakan untuk memperoleh data penilaian tentang system
pengelolaan jamban dan peturasan. Data yang dibutuhkan meliputi jumlah jamban dan
peturasan yang tersedia di perusahaan, jumlah pengguna di perusahaan atau industri tempat
kerja praktik.
Praktik Kerja Industri 145
Jumlah pengguna yang dibutuhkan terdiri dari jumlah seluruh tenaga kerja perusahaan
ditambah dengan jumlah rata-rata pengunjung perhari. Data lain yang juga harus di industri
dalam melakukan penilaian jamban dan peturasan adalah jenis kelamin dan cara penempatan
lokasi jamban dan peturasan. Jenis kelamin digunakan untuk menentukan jumlah kebutuhan
jamban dan peturasan, sedangkan cara penempatan lokasi jamban dan peturasan digunakan
untuk memberikan gambaran mudah/tidaknya fasilitas tersebut dijangkau atau diakses oleh
penggunanya. Keberadaan jamban harus ada di setiap lantai untuk gedung bertingkat.
Keberadaan jamban juga harus dilengkapi dengan tempat sampah yang konstruksinya kedap
air dan tertutup.
Persyaratan jumlah jamban dan peturasan yang dinilai harus mengacu kepada peraturan
yang berlaku, misalnya Peraturan Gubernur atau peraturan Menteri Kesehatan. Peraturan
terkait persyaratan kesehatan lingkungan di industri, yang dulu menggunakan Kepmenkes
1405/MENKES/SK/IX/2002 dinyatakan sudah tidak berlakuk lagi dan diganti dengan
Permenkes No. 70 Tahun 2016 tentang Standar Kesehatan Lingkungan Kerja Industri.
Pengelolaan jamban dan perbaikan merupakan hal penting yang harus diperhatikan
dalam menilai persyaratan jamban. Pengelolaan yang baik bisa ditunjukkan dengan
ketersediaan kamar mandi dan WC yang bersih, tidak berbau, tidak terdapat seranggaa atau
binatang lainnya, tersedia cukup air bersih untuk penggunaan. Air bersih yang digunakan
untuk kebutuhan hygiene dan sanitasi kesehatan lingkungan adalah 20 liter per orang per hari
(Permenkes RI No. 70 Tahun 2016).
I. PELAKSANAAN PENGAWASAN FASILITAS CUCI
Penilaian fasilitas cuci tangan memerlukan ketelitian terhadap materi objek sasaran
penilaian. Penilaian utama adalah tersedianya tempat cuci tangan yang harus ada untuk setiap
ruang kerja. Keberadaannya harus dibarengi dengan sejumlah persyaratan baik persyaratan
konstruksi, kebersihan, kapasitas maupun pemeliharaannya. Tempat Cuci tangan berupa
wastafel dengan ukuran setidaknya dengan diameter 50 meter. Semua sasaran penilaian dan
persyaratan tempat cuci tangan sudah dibicarakan dalam Bab 2, namun jika Saudara menilai
tempat cuci harus mempertimbangkan jenis perusahaan dan kegiatan yang dilakukan oleh
tenaga kerja. Bagi tenaga kerja industri yang melibatkan bahan kimia berbahaya bagi
kesehatan harus menyediakan shower air panas dan air dingin.
Secara umum langkah penilaian dapat dilakukan sebagai berikut:
1. Siapkan terlebih dahulu instrumen penilaian
2. Koordinasi dengan pihak pengelola untuk penyiapan kegiatan penilaian (tempat dan
tenaga kerja)
146 Praktik Kerja Industri
3. Siapkan kelengkapan pendukkung, misalnya alat catat-tulis, kendaraan dan alat
pelindung diri bila diperlukan, dan lainnya.
4. Lakukan penilaian terhadap obyek yang telah ditentukan, yaitu:
a. Penyediaan fasilitas cuci di setiap ruang kerja
b. Kapasitas dan fasilitas cuci disbanding jumlah seluruh karyawan dan pengunjung
rata-rata perhari
c. Cara penempatan ruang fasilitas cuci laki-laki dan perempuan. Dan konstruksi
pemisah ruang.
d. Kualitas bahan yang digunakan untuk fasilitas cuci serta persyaratannya.
e. Misalnya: bahan dari sejenis kaca, kaca, besi galvanis, besi yang diberi lapisan
sejenis kaca, porselin, keramik dan sejenisnya.
f. Tempat cuci tersedia minimal 1 bh di setiap lantai
g. Perlengkapan tempat cuci, misalnya handuk biasa di dekat lavatory atau wastafel.
h. Sistem penyediaan air bagi tempat cuci.
i. Ketersediaan shower dengan air panas dan dingin bagi karyawan yang bekerja
dengan bahan beracun, infeksi, irritants.
j. Ketersediaan zat tertentu untuk sistem pembersihan yang tidak bisa dihilangkan
dengan sabu.
k. Kesesuaian penyediaan air bersih dengan peraturan yang berlaku.
Latihan
Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan
berikut!
Langkah-1 : Lakukan pengambilan data dengan cara mengisi instrumen sebagaimana
dicontohkan dalam Bab 3, namun instrument harus dikembangkan sesuai
kebutuhan pengawasan praktik kerja industri. Artinya parameter yang diukur
tergantung dari produksi yang dihasilkan oleh industri terkait. Metode
pengambilan data bisa melalui wawancara, atau observasi, maupun
pengambilan sampel limbah.
Langkah-2 : Lakukan pegiriman sampel ke laboratorium
Langkah-3 : Mintalah hasil pemeriksaan sampel limbah dan isikan pada instrumen
Praktik Kerja Industri 147
Contoh Pengisian instrumen:
HASIL PEMANTAUAN LIMBAH
Nama Industri : PT. Kalibata
Kode Sampel : 002/2017
Lokasi Pengambilan Contoh Uji : Outlet bagian produksi, inlet dan olutlet IPAL
Jam, Tanggal, Tahun Pengambilan : 09.00 WIB, 20 Oktober 2017
Contoh Uji
Petugas Pengambil Contoh Uju : Kartaji
Debit air limbah saat : 0.4 m3 / detik
pengambilan contoh uji
Tanggal, Tahun penerimaan : 21 Oktober 2017
contoh uji
Tanggal, Tahun analisis contoh : 22 Oktober 2017
uju
Lama waktu produksi : 7 jam / hari
Jumlah bahan baku waktu : 8 ton / hari (satuan disesuaikan atau dikonversi)
pengambilan contoh uji (satuan
bahan baku / hari)
Jumlah produksi waktu : 7.6 ton / hari (satuan disesuaikan atau dikonversi)
pengambilan contoh uji (satuan
produksi / hari)
148 Praktik Kerja Industri
Hasil Analisis Baku Mutu
Beban Beban Metode
No Kadar Kadar
Parameter Pencemaran Pencemaran Uji
(mg/L) (mg/L)
(kg/ton) (kg/ton)
1. BOD 176 87 150 85 BOD Kit
2. COD 1500 750 350 300 Titrasi
3. TSS 12 3 5 4 Uji lab
4 5 7 6 s.d. 7,5 pH Meter
4. pH
kit
Kuantitas air .100 m3/ton produk atau 30 m3/ton produk atau
11. limbah bahan baku bahan baku
paling tinggi
Ringkasan
Pada prinsipnya pelaksanaan penilaian sanitasi industri dilakukan dengan langkah:
1. Menyiapkan instrument terkait sasaran penilaian
2. Melakukan pengambilan data (wawancara, observasi, dan atau pengukuran)
3. Melakukan penilaian, bisa berupa pengisian instrument, melakukan pengukuran, baik
pengukuran langsung maupun pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium
Tes 1
Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar!
1) Pembuatan instrumen penilaian atau pengawasan sanitasi industri harus
memperhatikan hal-hal di bawah ini, kecuali….
A. Jenis industri atau perusahaan
B. Hasil produksi
C. Debit limbah
D. Keahlian tenaga kerja
E. Instalasi Pengolah Limbah (IPAL)
Praktik Kerja Industri 149
2) Dalam melakukan pengukuran parameter kebisingan, menggunakan alat ukur yang
disebut….
A. Sound Level Meter
B. Lux meter
C. Turbidy meter
D. Gas detector
E. V-Noct Weir
3) Sedangkan alat untuk mengukur intensitas pencahayaan disebut….
A. Sound Level Meter
B. Lux meter
C. Turbidy meter
D. Gas detector
E. V-Noct Weir
4) Dalam mengambil sampel air limbah industri yang bertujuan untuk mengetahui efisiensi
IPAL, maka sampel diambil pada lokasi….
A. Pada setiap pipa air limbah yang keluar dari masing-masing produksi
B. Pada badan air yang menerima limbah buangan industri
C. Titik sebelum dan sesudah IPAL (inlet dan outlet efluen IPAL)
D. Pada titik pertemuan pada berbagai pipa yang berasal dari pipa produksi
E. Pada pipa efluen keluaran IPAL
5) Alat untuk mengukur kelembaban di ruang kerja menggunakan alat yang disebut….
A. Hygrometer atau Psychrometer
B. Lux meter
C. Noise dosimeter
D. Globe thermometer
E. High Volume dust sampler
150 Praktik Kerja Industri
Topik 2
Pengukuran K3 dalam
Praktik Kerja Industri
P
engukuran dalam penilaian sanitasi Industri bertujuan memperoleh data yang
dibutuhkan untuk menilai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap higyene dan sanitasi
kesehatan lingkungan di tempat kerja, yaitui faktor fisik, kimia maupun bakteriologis.
Hasil pengukuran juga bisa dijadikan dasar untuk merencanakan pengendalian yang dilakukan
terhadap risiko bahaya yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja atau
mempengaruhi kesehatan tenaga kerja.
Alat yang digunakan dalam praktek kerja industri tergantung pada parameter yang akan
diukur atau diketahui dari industri tempat kerja praktik. Tidak semua tempat kerja praktik
memerlukan semua parameter diukur, tetapi parameter-parameter yang diperlukan saja
berdasarkan karakteristik lingkungan kerja dan pengaruhnya terhadap kesehatan tenaga kerja
atau terjadinya kecelakaan kerja.
Tabel 4.3
Parameter dan Alat Ukur yang Digunakan Pengukuran Faktor Fisik
No. Parameter Alat Ukur Keterangan
1. Iklim kerja (suhu basah, Wet-Bulb Globe
suhu kering, suhu radiasi) thermometer
Suhu Thermometer
Kelembaban udara relatif Psychrometer/ Terdapat beberapa
hygrometer jenis
Kecepatan aliran udara Anemometer
Intensitas pencahayaan/ Lux Meter
penerangan
Intensitas kebisingan udara Sound Level meter
ambient
Praktik Kerja Industri 151
No. Parameter Alat Ukur Keterangan
Kebisingan terpapar pada Noise Dosimeter
tenaga kerja
Vibrasi/ getaran Vibration meter
Tabel 4.4
Parameter dan Alat Pengukur Faktor Kimia di Industri
No. Parameter Nama alat sampling/ Keterangan
Metode yang digunakan
1. Gas polutan pencemar Midget Impinger, Gas
udara detector
2. Debu (di ruang kerja) Low Volume Dust Sampler
(LVDS)
3. Debu udara ambient High Volume Dust Sampler
(HVDS)
4. Debu perorangan Personal Dust Sampler
(PDS)
5. Kimia air limbah & air bersih Sampling menggunakan Metode
botol sampel spektrofotometri
atau tetrasi
Alat Spektrofotometer/
AAS
Tabel 4.5
Parameter Mikrobiologis dan Sasaran Pemeriksaan
No. Parameter Sasaran Keterangan
1. Mikrobiolodi air bersih Pemeriksaan Total Pengambilan sampel
Coliform dan E.coli air bersih dan
152 Praktik Kerja Industri
Menghitung total
coli dan keberadaan
bakteri E.Coli
2. Mikrobiologi Udara Menghitung angka kuman Pengambilan sampel
udara ruang udara
menggunakan Micro Air
Menghisap udara
Sampler (MAS)
dan menangkap
mikrobiologinya
pada nutrient agar
volume tertentu
3. Mikrobiologi Makanan/ Pemeriksaan bakteri pada menghitung angka
Minuman makanan kuman,
Pemeriksaan alat makan teknik usap alat
Pelaksanaan penilaian atau pengawasan praktik kerja industri dilakukan berdasarkan
instrumen yang telah disusun. Untuk melaksanakan kegiatan ini mahasiswa dituntut
menguasai kompetensi seluruh mata kuliah terkait khususnya yang berkaitan dengan industri
lahan praktik. Jenis kegiatan yang dilakukan menggunakan metode wawancara, observasi,
pengukuran terhadap objek yang dinilai. Kegiatan dalam pelaksanaan praktek kerja industri
tidak hanya melaksanakan tugas-tugas pembelajaran dari akademik saja, tetapi juga tugas-
tugas lain yang diberikan oleh industri lokasi praktik.
Pengukuran dalam praktek kerja industri mencakup:
1. Pengukuran yang dilakukan terhadap faktor fisik di lingkungan kerja, antara lain:
a. Iklim kerja
b. Suhu
c. Kelembaban relative (relative humidity/ RH) lingkungan kerja.
d. Kecepatan liran udara
e. Suhu radiasi
f. Intensitas pencahayaan atau penerangan
g. Intensitas kebisingan
h. Getaran
2. Pengukuran yang dilakukan terhadap faktor kimia, misalnya:
a. Gas polutan pencemar udara
b. Debu udara di ruang kerja dan ambient
Praktik Kerja Industri 153
c. Kimia air limbah dan air bersih
d. Kimia dalam darah tenaga kerja
e. Dan lain-lain.
3. Pengukuran faktor mikrobiologi
a. Mikrobiologi air bersih
b. Mikrobiologi udara
c. Mikrobiologi makanan atau minuman
A. PROSEDUR PENGUKURAN FAKTOR FISIK
1. Pengukuran Iklim kerja
a. Alat pengukuran yang dibutuhkan, mencakup:
1) Psychrometer
2) Termometer
3) Erlenmeyer 125 ml
4) Globe thermometer
5) Anemometer
b. Bahan:
Aquadest
c. Prosedur Pengukuran:
1) Tempatkan Globe thermometer di dekat tenaga kerja yang sedang melakukan
pekerjaan.
2) Pastikan Erlenmeyer sudah terisi aquadest dan terpasang pada ujung thermometer
basah.
3) Paparkan alat selama 30 menit
4) Baca suhu basah, suhu bole dan suhu kering
d. Rumus yang digunakan:
Tekanan Panas dipengaruhi oleh tingkat radiasi, sehingga perhitungannya ada 2 (dua)
jenis rumus ISBB), yaitu:
1) Rumus yang digunakan jika di luar ruangan (terkena panas matahari/outdoor),
yaitu:
154 Praktik Kerja Industri
2) Rumus yang digunakan untuk pengukuran di dalam gedung (indoor), rumusnya
adalah :
Keterangan :
ISBB = Indeks Suhu Basah dan Bola, dalam 0C
SBa = Suhu Basah Alami, dalam 0C
SG = Suhu Globe, dalam 0C
SK = Suhu Kering, dalam 0C
e. Menghitung Suhu Radiasi
1) Baca Suhu Globe dan Suhu Radiasi, lihat nomogram garis A selisih dari suhu globe
dengan suhu kering.
2) Plot hasil selisih suhu globe dan suhu kering dengan kecepatan angina pada line B
hingga menembus line C
3) Tarik garis dari line C menuju line D yang menunjukkan suhu globe, hingga
menembus line E
4) Baca titik potong di line E yang menunjukkan suhu radiasi.
f. Rumus yang dikembangkan berdasarkan perpindahan lokasi kerja
Adanya pekerja yang selama bekerja terpapar pada tingkat tekanan panas yang
berbeda-beda, karena harus berpindah lokasi selama jam kerja, maka harus ditetapkan tingkat
tekanan panas rata-rata yang diterima pekerja selama jam kerja (ISBB rata-rata), rumusnya:
(𝑰𝑺𝑩𝑩𝟏 )(𝒕𝟏 ) + (𝑰𝑺𝑩𝑩𝟐 ) (𝒕𝟐 ) + (𝑰𝑺𝑩𝑩𝟑 ) (𝒕𝟑 ) + ⋯ (𝑰𝑺𝑩𝑩𝑵 ) (𝒕𝒏 )
𝑰𝑺𝑩𝑩 𝒓𝒂𝒕𝒂 − 𝒓𝒂𝒕𝒂 =
𝒕 𝟏 + 𝒕𝟐 + 𝒕𝟑 … . 𝒕𝒏
Keterangan:
ISBB rata-rata = tingkat tekanan panas yang diterima rata-rata tenaga kerja
Praktik Kerja Industri 155
selama waktu tertentu, dalam oC
ISBB1 = tingkat tekanan panas pada lokasi 1
ISBB2 = tingkat tekanan panas pada lokasi 2
ISBBn = tingkat tekanan panas pada lokasi n
t1 = lama waktu pemaparan pada lokasi 1
t2 = lama pemaparan pada lokasi 2
tn = lama pemaparan pada lokasi n
Dengan mengukur iklim kerja, maka telah terukur pula parameter suhu, kelembaban
dan suhu radiasi di ruang kerja.
2. Pengukuran Instensitas Pencahayaan
a. Alat
1) Lux meter
2) Meteran
b. Prosedur Pengukuran
Prosedur pengukuran dibagi 3 (tiga) jenis:
1) Pengukuran Penerangan Setempat (Local illumination)
2) Pengukuran penerangan rata-rata (general illumination)
3) Penerangan refelksi atau daya pantul cahaya (Reflectance)
1) Prosedur pengukuran penerangan lokal
Pengukuran ini ditujukan untuk mengukur tingkat penerangan ditempat
melakukan pekerjaan.
a) Bagilah luas setempat menjadi beberapa bagian (dalam m2)
b) Ukur di tengah-tengah bagian tersebut intensitas pencahayaannya
c) Hadapkan foto cell ke sumber cahaya setinggi bidang kerja ( + 85 cm)
d) Baca dan catat intensitas cahaya pada tiap-tiap bagian tersebut.
Rumus :
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒆𝒎𝒖𝒂 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒕𝒂𝒔 𝒔𝒆𝒎𝒖𝒂 𝒕𝒊𝒕𝒊𝒌
𝑰𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒕𝒂𝒔 𝑪𝒂𝒉𝒂𝒚𝒂 𝑳𝒐𝒌𝒂𝒍 =
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒕𝒊𝒕𝒊𝒌 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒖𝒌𝒖𝒓𝒂𝒏
156 Praktik Kerja Industri
2) Prosedur pengukuran Penerangan Rata-rata (Global/General illuminationI)
a) Ruangan yang berisi perabotan
(1) Bagilah ruang ruangan menjadi bidang-bidang kecil berukuran 90 x 90 cm
(2) Ukur intensitas pencahayaan pada salah satu sudut bidang-bidang kecil
tersebut dengan Lux meter menghadap sumber cahaya. Pengukuran
dilakukan pada sudut yang sama di setiap kotak atau bidang-bidang kecil
tersebut, sehingga diperoleh jarak pengukuran yang sama. Lihat gambar
berikut:
x x x x
x x x x
x x x x
(3) Rumus:
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑆𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑇𝑖𝑡𝑖𝑘
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑆𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑅𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
3) Prosedur Pengukuran Daya Pantul (reflectance)
Objek pengukuran dilakukan pada dinding, langit-langit, perabotan, dan lantai, dengan
cara:
a) Ukur intensitas cahaya datang dengan meletakkan foto cell lux meter pada obyek
yang diukur menghadap sinar datang yang jatuh pada obyek pengukuran tersebut.
b) Ukur intensitas sinar pantul dengan cara menempelkan foto cell lux meter
menghadap objek pengukuran dengan posisi tegak lurus, gerakkan menjauh
secara tegak lurus secara perlahan sambil mengamati angka atau skala pada lux
meter hingga diperoleh angka yang tetap atau konstan kemudian baca angkanya.
c) Maka besar reflectance adalah :
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐶𝑎ℎ𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑎𝑛𝑡𝑢𝑙
× 100%
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐶𝑎ℎ𝑎𝑦𝑎 𝐷𝑎𝑡𝑎𝑛𝑔
Praktik Kerja Industri 157
3. Pengukuran Intensitas Kebisingan di Ruang Kerja
a. Alat Ukur
1) Sound Level Meter
2) Meteran
3) Stop Watch
b. Prosedur Pengukuran Kebisingan di Lingkungan Kerja
Pengukuran dilakukan di tempat kerja, dimana tenaga kerja tersebut berada dan
menghabiskan waktu kerja. Pengukuran dikakukan pada pagi, siang dan sore hari pada jam
kerja. Hasil pengukuran ini masih kasar, karena belum menunjukkan tingkat kebisingan yang
diterima secara terus menerus selama 8 jam kerja). Tetapi dengan cara tersebut merupakan
pendekatan terhadap waktu yang mewakili selama jam kerja tersebut. Pada dasarnya
pengukuran dilakukan rata-rata selama jam kerja selama 24 jam yang disebut Lsm / Leq.
1) Buatlah desain lokasi ruang kerja tenaga kerja,
2) Tentukan titik pengukuran pada lokasi kerja
3) Ukurlah tingkat kebisingan dengan sound level meter dengan cara memegang alat
tersebut setinggi bahu pengukur dan alat agar dijauhkan dari badan pengukur.
4) Hidupkan SLM dengan memilih skala pengukuran dBA
5) Baca skala hasil pengukuran
Rumus:
LSM = 10 log 1/24 [16.10 0.1 Ls + 8.10 0.1 (Lm + 10)] dBA
Keterangan:
Lsm = Leq selama 24 jam
Ls = Nilai Leq pada siang hari (16 jam)
Lm = Leq pada malam hari (8 jam)
Lm + 10 = hasil pengukuran pada malam hari harus ditambah 10 dBA sebagai pembebanan
atau koreksi.
158 Praktik Kerja Industri
Cara menentukan hasil pengukuran:
1) Kelompokkan sampel dalam 5 interval
2) Hitung nilai Li = 10 log 1/180 ∑ nk . 10 0.1 Lk
3) Ulangi untuk harga Li,j pada interfal waktu yang lain.
4) Setelah harga Li,j dihitung, maka hitung harga Lsm/ Leq, yaitu tingkat kebisingan
siang dan malam sebagai berikut:
Ls = 10 log 1/16 ∑ te 10 0.1 Le dBA (siang)
Lm = 10 log 1/8 ∑ te 10 0.1 Le dBA (malam)
Te Jumlah jam dimana tingkat kebisingan Le berlangsung
5) Hitung Lsm/ Leq
Leq = 10 log (∑ fi . 10 Li/10)
Fi = fraksi waktu untuk tingkat kebisingan tertentu
Li,j = tingkat kebisingan terukur
Catatan :
(a) Nunyi kejut yang nyata terdengan (misalnya bunyi pukulan palu dan lain-
lain) harus dibaca langsung dan tidak perlu penambahan koreksi dB.
(b) Apabila terdengan bunyi kejut namun tidak terukur (misalnya ketukan mesin
jenset), maka hasil pengukkuran harus dikoreksi (ditambah 3 dBA). Nilai
koraksi ini ditambahkan pada Li,j pada interfal i dan j dimana ketukan
tersebut terdengar.
Selain perhitungan dengan rumus dapat dilakukan perhitungan dengan menggunakan
nomogram
4. Pengukuran Getaran/ fibrasi
a. Periksa Alat
1) Sensor Getaran
2) Kabel Sensor
3) Power ON/OFF
Praktik Kerja Industri 159
4) Tombol
5) Battery Componen
6) Display/LCD
b. Hidupkan Alat dengan menekan tombol Power ON/OFF
c. Tempelkan Sensor ke sumber getaran
d. Catat angka yang muncul di display
e. Pastikan Tingkat getaran dengan cara :
a) Modus (Nilai yang sering muncul)
b) Median ( Nilai Tengah) Angka terendah + Angka Tertinggi : 2)
c) Nilai Rata-rata (Jumlah keseluruhan sampel dibagi jumlah sampel)
Gambar 4.2 Vibration Meter (Alat Ukur Getaran)
Getaran kerja adalah getaran mekanis ditemapt kerja yang berpengaruh terhaadap kerja
yang meliputi;
1. Getaran yang berpengaruh pada seluruh bagian tubuh (Whole Body Vibration / WBV)
2. Getaran yang berpengaruh pada sebagian tubuh (Hard Arm Vibartion)
160 Praktik Kerja Industri
a. lebih kurang dari 0.15 m/ det2-0.30m/det2 = getaran yang mengganggu
kenyamanan.
b. Lebih Kurang 0,30 m/det2 – 0,75 m/det2 = Getaran yang mempercepat kelelahan
c. Di atas 0,75 m/det2 = Getaran yg mengganngu kesehatan (mual, pusing, gangguan
keseimbangan, konsentrasi, gangguan saraf motorik)
B. PROSEDUR PENGUKURAN FAKTOR KIMIA
Pengukuran faktor kimia udara bisa diukur secara langsung apabila menggunakan alat
ukur portabel, namun pada umumnya pengukuran diawali dengan mengambil sampel terlebih
dahulu. Pengambilan sampel dilakukan dengan midget impinger yang pada prinsipnya
menyerap udara dilewatkan cairan absorben parameter terkait kemudian dilakukan
pemeriksaan laboratorium. Dalam praktek kerja industri bila diperlukan bisa diukur dengan
gas detector secara langsung, namun hasil yang diperoleh dengan alat tersebut masih kasar.
Tidak bisa digunakan untuk penelitian karena memerlukan ketelitian yang lebih tinggi.
Prosedur Pengambilan sampel udara:
1. Siapkan alat dan bahan
2. Buatlah pereaksi standart
3. Siapkan pereaksi penyerap atau absorben
4. Siapkan peralatan sampling:
a. Meja sampling
b. Pompa hisap (vacuum pump)
c. Alat pengukur laju alir udara (air flow meter)
d. Midget impinge
e. Slang plastic penghubung
f. Anemometer
g. Psychrometer
h. Kertas label
i. Botol absorben
j. Botol sampel
5. Cara pengambilan sampel udara:
a. Ambil peresksi penyerap sebanyak 20 ml masukkan dalam Midget Impinger 60 ml.
b. Rangkaikan dengan pompa hidap, nyalakan vacuum pump (pompa hisap) selama
30 menit dengan laju alir 0,4 liter/menit
c. Simpan contoh dalam lemari es.
d. Buat kurva kalibrasi sesuai parameter yang diukur (Sox, NOx, Pox, dan lain-lain)
Praktik Kerja Industri 161
e. Lakukan pengujian sampel dari midget impinge dan baca dalam spektrofotometer.
6. Cara pengambilan sampel air limbah secara fisika dan kimia:
a. Alat dan bahan:
1) Cool box
2) Botol pemberat
3) Botol Winkler
4) Pipet ukur
5) Botol gelap
Bahan:
1) Etiket
2) Pengawet
b. Prosedur Kerja:
1) Siapkan alat pengambil contoh sesuai dengan saluran pembuangan
2) Bilas alat dengan contoh yang akan diambil, minimal 3 kali
3) Ambil contoh sesuai dengan peruntukan analisis dan campurkan dalam
penampung sementara, kemudian homogenkan.
4) Masukkan ke dalam wadah yang sesuai peruntukan analisis.
5) Lakukan segera pengujian untuk parameter suhu, kekeruhan, dan daya
hantar listrik, pH dan Oksigen terlarut yang dapat berubah dengan cepat dan
tidak dapat diawetkan.
6) Hasil pengujian parameter lapangan dicatat
7) Pengambilan contoh untuk parameter pengujian di laboratorium dilakukan
pengawetan
Prosedur Pengukuran Faktor Bakteriologis/Mikrobiologi
Prosedur pengukuran faktor mikrobiologi air bersih.
Pengukuran faktor mikrobiologi air bersih diawali dengan pengambilan sampel air
bersih.
Pengambilan sampel air bersih secara mikrobiologi/bakteriolobis tergantung dari obyek
sumber air bersih yang akan diperiksa.
162 Praktik Kerja Industri
1. PROSEDUR PENGAMBILAN SAMPEL AIR KRAN (PDAM)
a. Bersihkan kran dari setiap benda yang menempel yang mungkin dapat mengganggu,
dengan kain bersih, bersihkan ujung kran dari setiap kotoran dan debu
b. Kran dibuka penuh dan dibiarkan mengalir selama 2-3 menit (atau dalam waktu yang
yang dianggap cukup untuk membersihkan pipa parsial), kemudian ditutup
c. Mulut kran disterilkan dengan cara membakar/melewatkan diatas nyala api.
d. Kran dibuka, kemudian tutup botol dilepas dengan tangan kiri dan botol dipegang
dengan tangan kanan, mulut dan leher botol dilewatkan nyala api.
e. Botol diisi contoh ± sampai 3/4 Volume botol
f. Mulut dan leher botol yang telah berisi contoh air sebelum ditutup kembali dilewatkan
nyala api, kemudiantutup dan ikat kembali dengan tali.
g. Tempelkan identitas contoh kemudian Letakkan botol yang berisi contoh kedalam cool
box dan dijaga temeratur cool boxnya harus dibawah 4 oC (dengan pemberian Dry
Ice/Ice Pack/ Es batu)
Catatan:
a. Air harus jelas berasal dari pipa parsial yang dihubungkan langsung dengan pipa induk.
b. Contoh sebaiknya diambil dari air kran yang sering dipakai
c. Dihindarkan pengambilan contoh air dari alat-alat tambahan yang dipasang pada kran
atau dari kran yang bocor
d. Apabila kran kotor, harus dibersihkan lebih dahulu sebelum dilakukan pengambilan
contoh
2. Pengambilan Contoh Air Sumur Gali
Contoh diambil dengan botol yang telah diberi pemberat dan bertali. Sebelum
disterilkan, botol dibungkus seluruhnya dengan dengan kertas coklat.
a. Bilas tangan dengan Alkohol 70% , buka bungkus botol yang telah disterilkan dengan
cara seperti membuka kulit pisang (Tangan tidak boleh bersentuhan dengan botol), Tarik
tali menggunakan pinset (yang sebelumnya telah dipanaskan) dan lilitkan pada tangan
kanan.
b. Buka tutup botol, mulut & leher botol lewatkan dengan nyala api, dengan posisi mulut
botol mengahadap keatas ulurkan botol tersebut kedalam sumur secara perlahan,
jangan sampai botol tersebut menyentuh dinding sumur. Celupkan seluruh permukaan
botol kedalam sumur hingga mencapai dasar.
c. Tarik botol yang telah terisi penuh dengan air secara perlahan, buang ¼ bagian dari air
yang ada dalam botol tersebut.
Praktik Kerja Industri 163
d. Mulut dan leher botol dilewatkan diatas nyala api kemudian tutup kembali dengan
kertas dan diikat tali.
e. Tempelkan identitas contoh kemudian Letakkan botol yang berisi contoh kedalam cool
box dan dijaga temeratur cool boxnya harus dibawah 4oC (dengan pemberian Dry Ice/Ice
Pack/ Es batu)
3. Pengambilan Contoh Air Yang Terbuka, Seperti Danau, Sungai Dan lain-lain
a. Contoh air dari sungai sebaiknya diambil dari bagian yang mengalir dan dekat dengan
permukaan (pengambilan contoh berlawanan dengan arus sungai)
b. Buka tutup botol, mulut & leher botol lewatkan dg nyala api, Botol dipegang pada bagian
bawah, celupkan kedalam air dengan dengan leher botol menghadap miring keatas,
celupkan botol tersebut hingga mencapai kedalaman ± 20 cm.
c. Kemudian angkat botol tersebut dari dalam air dengan mulut botol menghadap keatas.
Bila perlu mulut botol berhadapan dengan arah aliran air.
d. Setelah botol terisi air, Mulut dan leher botol dilewatkan diatas nyala api kemudian
tutup kembali dengan kertas dan diikat tali.
e. Tempelkan identitas contoh kemudian Letakkan botol yang berisi contoh kedalam cool
box dan dijaga temeratur cool boxnya harus dibawah 4 oC (dengan pemberian Dry
Ice/Ice Pack/ Es batu)
Catatan:
a. Bagian sungai yang diam sebaiknya dihindari
b. Untuk sungai yang lebar dan lurus contoh diambil dari tepi, tetapi pada jarak paling
sedikit 1 meter dari tepi sungai.
c. Pengambilan contoh air sungai yang tidak terjangkau tangan, contoh air dapat diambil
dengan botol pemberat.
C. PROSEDUR PENGUKURAN FAKTOR BAKTERIOLOGIS/MIKROBIOLOGIS
1. Prosedur Pengukuran Faktor Mikrobiologi Makanan
Objek sasaran penilaian Sanitasi industri untuk mikrobiolobi makanan biasanya
dilakukan untuk makanan yang disediakan melalui pengadaan kantin bagi karyawan. Sanitasi
kantin telah dibicarakan sebelumnya, pada pembahasan tentang pengukuran ini, maka yang
dibahas hanya pengukuran yang meliputi:
a. Pengambilan sampel makanan atau minuman di kantin
b. Pengambilan sampel Usap alat makan misalnya piring, gelas, sendok dan alat masak.
164 Praktik Kerja Industri
2. Pengambilan Sampel Makanan
a. Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan
b. Menyeterilkan tangan dengan cara menyemprotkan alkohol 70%
c. Mengunakan handscoon pada pengambilan sampel
d. Menyeterilkan kembali tangan yang sudah memakai handscoon menggunakan alcohol
70%
e. Menyiapkan Petridis steril, sendok steril dan Erlenmeyer steril.
f. Menyiapkan bahan makanan padat yaitu telur mentah yang sudah diambil secara steril.
g. Memecahkan telur dan memasukkannya ke dalam Petridis steril
h. Lalu menimbang sampel di atas timbangan dengan berat sampel telur 10 gram.
i. Menyiapkan Erlenmeyer steril, lalu memasukkan sampel telur ke dalam Erlenmeyer
steril menggunakan sendok steril
j. Melakukan kegiatan tersebut di dekat nyala api Bunsen.
k. Memflmbir mulut Erlenmeyer di atas nyala api Bunsen dan menutup mulut Erlenmeyer
menggunakan kapas.
l. Terakhir menempelkan kertas etiket sebagai keterangan pada Erlenmeyer sampel
tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :
1) Nama petugas
2) Lokasi pengambilan sampel
3) Waktu pengambilan sampel
a) Jenis sampel makanan
b) Parameter sampel makanan
3. Pengambilan Sampel Usap Alat Makanan
Alat
a. Lidi kapas steril
b. Sarung tangan
c. Spidol
d. Kertas label
e. Termos/ice box
f. Alkohol
g. Timbangan
h. Pipet steril
i. Autoclave
j. Tali kenur
k. Timbangan
l. Formulir pemeriksaan
Praktik Kerja Industri 165
m. Lampu spirtus
n. Korek api
o. Alat makan dan alat masak (sendok, piring, garpu, mangkok, gelas, cangkir, wajan, panci,
dan lain-lain)
Bahan :
a. Media transport cairan buffer dalam botol @ 10 ml
b. Alkohol 70%
c. Alat Tulis
d. Form Pengambilan Sampel
e. Kertas label
D. PROSEDUR KERJA
1. Pengambilan Sampel Usap Alat Makan atau Masak
a. Siapkan sarung tangan yang steril untuk mulai pengambilan sampel
b. Alat makan atau masak yang akan diperiksa masing-masing diambil 4-5 buah tiap jenis
yang diambil acak dari tempat penyimpanan
c. Persiapkan catatan formulir pemeriksaan dengan membagi alat masak atau makan
dalam kelompok-kelompok
d. Persiapkan lidi kapas steril, kemudian buka tutup botol dan masukkan lidi kapas steril ke
dalamnya
e. Lidi kapas steril dalam botol ditekan ke dinding botol untuk membuang airnya, baru
diangkat dan diusapkan pada setiap alat-alat yang diusapkan sampel satu kelompok
selesai diusap. Permukaan tempat alat atau perabot yang diusap yaitu :
1) Cangkir dan gelas : permukaan luar dan dalam bagian bibir setinggi 6 mm (π r 2 t)
2) Sendok : permukaan bagian luar dan dalam seluruh mangkok sendok
3) Garpu : permukaan bagian luar dan dalam alat penusuk
4) Piring : permukaan dalam tempat makanan diletakkan
f. Cara melakukan usapan pada :
1) Cangkir dan gelas dengan usapan mengelilingi bidang permukaan
2) Sendok dan garpu dengan usapan seluruh permukaan luar dan dalam
3) Piring dengan 2 (dua) usapan pada permukaan tempat makanan dengan
menyilang siku-siku antara garis usapan yang satu dengan garis usapan kedua,
dengan menggunakan bantuan jendela swab steril ukuran luas 8 inchi (50 cm2).
166 Praktik Kerja Industri
g. Setiap bidang permukaan yang diusap dilakukan tiga kali berturut-turut dan satu lidi
kapas digunakan untuk satu kelompok alat makan yang diperiksa
h. Hal yang sama dilakukan pada peralatan masak, setiap usapan seluas 8 inci persegi atau
50 cm2 dilakukan tiga kali berturut-turut dan dianggap satu kelompok setelah dilakukan
luas permukaan sebanyak 5 kali @luasnya 8 inci persegi
i. Untuk setiap habis mengusap satu alat dari satu kelompok selalu dimasukkan ke dalam
botol cairan diputar-putar dan ditekan ke dinding botol bagian dalam, demikian
dilakukan berulang-ulang sampai semua kelompok diambil usapnya
j. Pada usapan peralatan makan atau masak setiap usapan alat harus mencapai luas
sekitar 8 inci persegi atau 50 cm2 dan dilakukan lima kali (tempat) sehingga cukup
mencapai luas 40 inci persegi atau 256 cm2 permukaan (1 inci=6,4 cm2)
k. Setiap satu kelompok menggunakan satu swab yang diusapkan dengan cara seperti
butir e
l. Setelah semua kelompok alat makan atau peralatan masak selesai diusap, kapas lidi
dimasukkan ke dalam botol, kocok dengan cara lidi kapas diaduk dalam cairan media
transport, lalu lidinya dipatahkan atau digunting dan bibir botol dipanaskan dengan api
spirtus baru ditutup sekerupnya.
m. Beri kode dan tanggal pada kertas label. Tulis data-data sebagaimana yang tertera pada
formulir pengambilan sampel dan kirim ke laboratorium.
n. Adapun data yang tertera dalam formulir pengambilan sampel mencakup:
1) Nama pengirim
2) Alamat pengirim
3) Kode sampel
4) Tanggal atau jam pengambilan sampel
5) Tanggal pengiriman sampel
6) Jenis sampel
7) Lokasi pengambilan sampel
8) Jenis pemeriksaan
9) Tanda tangan pengirim
Praktik Kerja Industri 167
Adapun teknik swab yang lain pada uji mikrobiologi dapat dilakukan seperti pada
gambar berikut ini :
• Siapkan alat dan bahan yang
diperlukan, swap stick steril,
jendela swab (transek logam
steril), dan pelarut swap steril
(extraction fluid)
• Masukkan swap stick steril ke
pelarut utk diusapkan ke seluruh
permukaan dengan
menggerakkan sambil memutar
stick swap membujur dan
melintang
Keterangan :
Standart yang ditetapkan dalam Permenkes RI No. 1096/ TENTANG HIGIENE SANITASI
JASABOGA, bahwa angka kuman peralatan makanan = 0 cfu/ cm2.
Angka kuman E.coli nol koloni/ml atau 0 koloni /gr (Standar angka bakteri perabotan
makan maksimal 500 koloni untuk 50 cm2 atau 10 koloni per cm2 permukaan.)
2. Prosedur Pengukuran Faktor Mikrobiologi Udara
Pada bab ini mahasiswa hanya melakukan pengambilan contoh (sampel) udara untuk
pemeriksaan bakteriologis udara ruang kerja yang dicurigai adanya pengaruh faktor
mikrobiologis udara yang dapat mempengaruhi kesehatan tenaga kerja. Pengambilan sampel
menggunakan alat Micro Air Sampler.
Alat dan Bahan
a. Termometer
b. Psycrometer
c. Anemometer
d. Petridish
e. Mikro Air Sampler
f. Lampu spirtus
g. Stopwatch
h. Timbangan analitik
168 Praktik Kerja Industri
i. Kertas timbang
j. Autoclave
k. Erlenmeyer
l. Aluminium foil
m. Tali rami
n. Kertas coklat
o. Etiket
p. Inkubator
q. Koloni counter
r. Spatula
s. Gelas ukur
t. Meteran
u. Kapas alkohol
v. Nutrient agar
w. Aquades
Prosedur Kerja
a. Membuat media nutrient agar
b. Sterilkan semua alat dan tempat titik yang dilakukan pengukuran dengan
menggunakan alkohol
c. Memasang media nutrient agar yang sudah beku pada alt MAS dengan ketinggian
+ 1,5 meter dari lantai
d. Menutup kembali dengan penutup berpori pada badan alat
e. Menyalakan alat dan atur daya hisapnya sesuai dengan volum ruangan tersebut
f. Memberi etiket untuk menandai sampel dari titik pengukuran
g. Membungkus semua sampel dengan kertas coklat dan ditali rami
h. Mengeramkan di inkubator selama 2 x 24 jam
Latihan
Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan
berikut!
Langkah-1: datanglah ke lokasi pengukuran di industri dan buatlah sketsa ruang kerja yang
berisi titik-titik pengukuran
Praktik Kerja Industri 169
X X
X = titik pengukuran
X X
Langkah-2: Siapkan Lux Meter dan kalibrasi alat tersebut sebelum digunakan untuk mengukur.
Langkah-3: Ukurlah intensitas pencahayaan pada titik yang telah ditentukan
Langkah-4: Amatilah lingkungan ruang kerja yaitu kondisi lingkungan yang mempengaruhi
pencahayaan di ruang kerja tersebut, dan catat waktu pengukuran, hasil
pengukuran dan kondisi lingkungan meliputi: sumber cahaya, peletakan
perabotan, warna dinding dan langit-langit, jenis pencahayaan.
Ringkasan
1. Jenis parameter yang diukur pada pengukuran lapangan praktek kerja industri terdiri
dari:
a. Parameter Fisik
b. Parameter Kimia
c. Parameter mikrobiologi
2. Faktor yang perlu diperhatikan pada saat melakukan pengukuran, yaitu:
a. Mencatat waktu pada saat melakukan sampling
b. Melakukan pengukuran parameter segera yang harus dilakukan di lapangan
c. Mencatat kondisi lingkungan kerja yang memiliki pengaruh baik secara langsung
maupun tidak langsung, misalnya pada saat melakukan pengukuran pancahayaan,
memperhatikan sumber cahaya alami dan buatan, warna perabotan, jam
pengukuran, dan sebagainya.
3. Prinsip yang diperhatikan pada saat pengambilan sampel kimia adalah tidak boleh
terjadi aerasi, hal tersebut dikarenakan aerasi bisa mempengaruhi terjadinya proses
oksidasi sehingga komposisi kima dalam sampel mengalami perubahan.
170 Praktik Kerja Industri
Tes 2
Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar!
1) Susunlah parameter apa saja yang diukur pada saat pengawasan sanitasi industri!
2) Susunlah kembali faktor apa saja yang diperhatikan pada saat pengukuran!
3) Susunlah kembali prinsip yang diperhatikan pada pengukuran secara kimia dan
bakteriologis!
Praktik Kerja Industri 171
Kunci Jawaban Tes
Test 1
1) D.
2) A.
3) B.
4) C.
5) A.
172 Praktik Kerja Industri
Penilaian Ketuntasan
Penilaian ketuntasan pada Sub Topik ini adalah:
1. Mahasiswa telah melakukan pengambilan data baik melalui wawancara, observasi, dan
atau pengukuran
2. Telah mengisi instrument pengawasan dengan baik dan benar
Praktik Kerja Industri 173
Glosarium
Influent : limbah cair hasil kegiatan industri yang masuk ke isntalasi
pengolah limbah (IPAL)
Efluent : limbah hasil pengolahan yang keluar dari instalasi pengolah limbah
Reflectance : pengukuran daya pantul pada pengukuran pencahayaan
General illumination :pengukuran pencahayaan rata-rata atau umum yang biasanya
dilakukan di ruang yang tidak ada perabotannya.
174 Praktik Kerja Industri
Daftar Pustaka
Direktorat Penyehatan Air dan Sanitasi, Sub Direktorat Hygiene Sanitasi Makanan& Minuman,
2004, Kumpulan Modul Khusus Hygiene Sanitasi Makanan & Minuman.
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 70 Tahun 2016 tentang Persyaratan Sanitasi dan
Ruang Kerja Industri.
Permen Lingkungan Hidup nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.
Peraturan Pemerintah RI np. 50 Tahun 2012 tentang system Manajemen K3.
Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
OHSAS 18001:2007 Occupational Health & Safety Management System.
Praktik Kerja Industri 175
Bab 5
PENGAWASAN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
Yulianto, S.Pd., M.Kes.
Hadi Suryono, ST., MPPM.
Pendahuluan
ingkungan kerja industri yang sehat merupakan salah satu faktor yang menunjang
L meningkatnya kinerja dan produksi yang secara bersamaan dapat menurunkan risiko
gangguan kesehatan maupun penyakit akibat kerja. Lingkungan kerja industri harus
memenuhi standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri sebagai
persyaratan minimal yang harus dipenuhi. Standar dan persyaratan kesehatan lingkungan
kerja industri terdiri atas nilai ambang batas, indikator pajanan biologi, dan persyaratan
kesehatan lingkungan kerja industri. Kesehatan Lingkungan Kerja Industri adalah upaya
pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan kerja industri
yang terdiri dari faktor bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan sanitasi untuk mewujudkan
kualitas lingkungan kerja industri yang sehat.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan
kerja dan penyakit akibat kerja. Berbicara masalah keselamatan dan kesehatan kerja, berarti
membicarakan dua hal besar yaitu keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja
bersifat teknis dengan sasaran lingkungan kerja, sedangkan kesehatan kerja bersifat medis
dengan sasaran tenaga kerja.
Berdasarkan uraian diatas, maka sasaran pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja
di tempat kerja dapat dikelompokkan menjadi:
1. Pengawasan keselamatan kerja.
2. Pengawasan kesehatan kerja.
176 Praktik Kerja Industri
Topik 1
Pengawasan Keselamatan Kerja
A. KESELAMATAN KERJA
Sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan kerja, bahwa syarat-syarat Keselamatan Kerja suatu tempat kerja meliputi:
1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
2. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
4. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau
kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
5. Memberi pertolongan pada kecelakaan;
6. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
7. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu,
kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;
8. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik secara fisik maupun
psikis, peracunan, insfeksi dan penularan;
9. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
10. Menyelenggarakan suhu dan lembah udara yang baik;
11. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
12. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
13. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan cara dan proses
kerjanya;
14. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau
barang;
15. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
16. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan
penyimpanan barang;
17. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
18. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya
kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.
Praktik Kerja Industri 177
Terkait dengan hal diatas, maka untuk melihat bagaimanakah implementasi atau
pelaksanaan pemenuhan persyaratan keselamatan kerja pada suatu tempat kerja, perlu
dilakukan pengawasan terhadap faktor fisika, kimia, biologi dan ergonomi di tempat kerja.
B. PENGAWASAN FAKTOR FISIKA TEMPAT KERJA
Faktor fisika di tempat kerja yang perlu mendapatkan pengawasan terdiri dari iklim
kerja, intensitas suara, intensitas cahaya, getaran, gelombang mikro, sinar ultra ungu, dan
medan magnet.
1. Pengukuran Iklim Kerja
Iklim kerja (panas) merupakan salah satu faktor yang pengaruhnya cukup dominan
terhadap kinerja sumber daya manusia bahkan pengaruhnya tidak terbatas pada kinerja saja
melainkan dapat lebih jauh lagi, yaitu pada kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. Untuk
itu diperlukan standar mengenai pengukuran iklim kerja (panas) dengan parameter indeks
suhu basah dan bola.
Pengukuran iklim kerja berpedoman pada SNI 16-7061-2004 tentang pengukuran iklim
kerja (panas) dengan parameter indeks suhu basah dan bola. Standar pengukuran iklim kerja
(panas) dengan parameter indeks suhu basah dan bola dimaksudkan untuk mewujudkan
keseragaman dalam melakukan penilaian iklim kerja (panas) yang memakai indeks suhu basah
dan bola sebagai parameternya. Dengan menggunakan standar ini, Nilai Ambang Batas iklim
kerja (panas) dapat diterapkan dengan baik. Selain itu dengan terbitnya standar ini lebih
banyak pihak yang dapat melakukan pengukuran indeks suhu basah dan bola dengan hasil
yang dapat dipertanggungjawabkan.
Alat-alat yang dipakai harus telah dikalibrasi oleh laboratorium yang terakreditasi untuk
melakukan kalibrasi, minimal 1 tahun sekali. Peralatan ini merupakan peralatan minimal dan
tidak membatasi penggunaan alat pengukur ISBB lainnya, tetapi hasil pengukuran yang
diperoleh sama dengan hasil dari peralatan ini. Alat-alat yang digunakan terdiri dari:
a. Termometer suhu basah alami yang mempunyai kisaran –5 OC sampai dengan 50 OC dan
bergraduasi maksimal 0,5 OC.
b. Termometer suhu kering yang mempunyai kisaran –5 OC sampai dengan 50 OC dan
bergraduasi maksimal 0,5 OC.
c. Termometer suhu bola yang mempunyai kisaran –5 OC sampai dengan 100 OC dan
bergraduasi maksimal 0,5 OC.
178 Praktik Kerja Industri
Langkah-langkah prosedur kerja pengukuran indeks suhu basah dan bola adalah sebagai
berikut:
a. Letak titik pengukuran ditentukan pada lokasi tempat tenaga kerja melakukan
pekerjaan.
b. Jumlah titik pengukuran disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan dari kegiatan yang
dilakukan.
c. Rendam kain kasa putih pada termometer suhu basah alami dengan air suling, jarak
antara dasar lambung termometer dan permukaan tempat air 1 inci. Rangkaikan alat
pada statif dan paparkan selama 30 menit - 60 menit.
d. Rangkaikan termometer suhu kering pada statif dan paparkan selama 30 menit - 60
menit.
e. Pasangkan termometer suhu bola pada bola tembaga warna hitam (diameter 15 cm,
kecuali alat yang sudah dirakit dalam satu unit), lambung termometer tepat pada titik
pusat bola tembaga. Rangkaikan alat pada statif dan paparkan selama 20 menit - 30
menit.
f. Letakkan alat-alat tersebut di atas pada titik pengukuran dengan lambung termometer
setinggi 1 meter – 1,25 meter dari lantai.
g. Waktu pengukuran dilakukan 3 kali dalam 8 jam kerja yaitu pada awal shift kerja,
pertengahan shift kerja dan akhir shift kerja.
h. Hasil pengukuran parameter ISBB ditulis dalam formulir yang telah disiapkan.
Terdapat 2 (dua) jenis rumus perhitungan pengukuran indeks suhu basah dan bola
(ISBB), yaitu:
a. Rumus untuk pengukuran dengan memperhitungkan radiasi sinar matahari, yaitu
tempat kerja yang terkena radiasi sinar matahari secara langsung:
𝑰𝑺𝑩𝑩 = 𝟎. 𝟕 𝑺𝑩𝑨 + 𝟎. 𝟐 𝑺𝑩 + 𝟎. 𝟏 𝑺𝑲
b. Rumus untuk pengukuran tempat kerja tanpa pengaruh radiasi sinar matahari:
𝑰𝑺𝑩𝑩 = 𝟎. 𝟕 𝑺𝑩𝑨 + 𝟎. 𝟑 𝑺𝑩
Dalam hal pemaparan ISBB yang berbeda-beda karena lokasi kerja yang berpindah-
pindah menurut waktu, maka berlaku ISBB rata-rata dengan rumus sebagai berikut:
(𝑰𝑺𝑩𝑩𝟏 )(𝒕𝟏 ) + (𝑰𝑺𝑩𝑩𝟐 )(𝒕𝟐 ) + ⋯ + (𝑰𝑺𝑩𝑩𝒏 )(𝒕𝒏 )
𝑰𝑺𝑩𝑩 𝒓𝒂𝒕𝒂 𝒓𝒂𝒕𝒂 =
𝒕𝟏 + 𝒕𝟐 + ⋯ + 𝒕𝒏
Praktik Kerja Industri 179
Tabel 5.1.
HASIL PENGUKURAN PARAMETER ISBB
Nama Industri :
Alamat Industri :
Jenis Industri :
Jumlah Tenaga Kerja : Laki Laki : ....... orang, Perempuan : ....... orang
Petugas Pemantau :
Tanggal Pemantauan :
Lokasi / Sumber
No Jam SBA OC SB OC SK OC ISBB OC Ket
Tempat Panas
Keterangan :
Cuaca : .............................................. Kelembaban : .....................
Mengetahui,
Penanggung Jawab Unit Kerja Petugas Pemantau
.................................................. ..........................................
180 Praktik Kerja Industri
2. Pengukuran Intensitas Kebisingan
Parameter fisika di tempat kerja yang perlu diukur terkait dengan keselamatan kerja
salah satunya adalah kebisingan. Pengukuran kebisingan di tempat kerja menggunakan
standar SNI 7231:2009. Pengukuran kebisingan pada dasarnya meliputi pengukuran intensitas
kebisingan, frekuensi dan dosis kebisingan. Tujuan pengukuran kebisingan juga bervariasi,
antara lain untuk keperluan pengendalian, penyesuaian, penetapan nilai ambang batas dan
tujuan lain.
Prinsip yang digunakan dalam pengukuran kebisingan, bahwa tingkat tekanan bunyi
diukur dengan alat sound level meter yang mempunyai kelengkapan Leq A dengan rentang
waktu tertentu pada pembobotan waktu slow (S). Tingkat bunyi menyentuh membran
mikropon pada alat, sinyal bunyi diubah menjadi sinyal listrik dilewatkan pada filter
pembobotan (weighting network), sinyal dikuatkan oleh amplifier diteruskan pada layar
hingga dapat dibaca tingkat bunyi yang terukur.
Prosedur pengukuran intensitas kebisingan di tempat kerja:
a. Hidupkan alat ukur intensitas kebisingan.
b. Periksa kondisi baterai, pastikan bahwa keadaan power dalam kondisi baik.
c. Pastikan skala pembobotan, pada A.
d. Sesuaikan pembobotan waktu respon alat ukur dengan karakteristik sumber bunyi yang
diukur, yaitu pada posisi slow (S) untuk sumber bunyi relatif konstan, atau fast (F) untuk
sumber bunyi kejut.
e. Posisikan mikropon alat ukur setinggi posisi telinga manusia yang ada di tempat kerja.
Hindari terjadinya refleksi bunyi dari tubuh atau penghalang sumber bunyai.
f. Arahkan mikropon alat ukur dengan sumber bunyi sesuai dengan karakteristik mikropon
(mikropon tegak lurus dengan sumber bunyi, 70O – 80O dari sumber bunyi).
g. Pilih tingkat tekanan bunyi (SPL) atau tingkat tekanan bunyi sinambung setara (Leq)
sesuai dengan tujuan pengukuran.
h. Catatlah hasil pengukuran intensitas kebisingan pada lembar data sampling.
i. Bila alat ukur Sound Level Meter tidak memiliki fasilitas Leq, maka dihitung secara
manual dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
𝟏 𝐋𝟏 𝐋𝟐 𝐋𝐧
𝐋𝐞𝐪 = 𝟏𝟎 𝐋𝐨𝐠{( ) ∑ [𝐭 𝟏 𝐱 𝟏𝟎 (𝟏𝟎) + 𝐭 𝟐 𝐱 𝟏𝟎(𝟏𝟎) + . . . +𝐭 𝐧 𝐱 𝟏𝟎(𝟏𝟎) ]}
𝐓
L1 : adalah tingkat tekanan punyi pada periode t1.
Ln : adalah tingkat tekanan bunyi pada periode tn.
T : adalah total waktu (t1 + t2 + ... + tn).
Praktik Kerja Industri 181
Tabel 5.2.
HASIL PENGUKURAN INTENSITAS KEBISINGAN DI TEMPAT KERJA
Nama Industri :
Alamat Industri :
Jenis Industri :
Jumlah Tenaga Kerja : Laki Laki : ....... orang, Perempuan : ....... orang
Lokasi Titik Pengukuran :
Tipe Alat Ukur :
Tipe Kalibrator :
Petugas Pengukur :
Tanggal Pengukuran :
Penanggung Jawab Unit Kerja :
No Lokasi Waktu Intensitas Bising Leq
Mengetahui, Petugas Pengukur
Penanggung Jawab Unit Kerja
.................................................. ..........................................
182 Praktik Kerja Industri
3. Pengukuran Intensitas Penerangan
Intensitas penerangan merupakan aspek penting di tempat kerja, karena berbagai
masalah akan timbul ketika kualitas intensitas penerangan di tempat kerja tidak memenuhi
standar yang ditetapkan. Intensitas penerangan di tempat kerja dimaksudkan untuk
menberikan penerangan kepada benda-benda yang merupakan obyek kerja, peralatan atau
mesin dan proses produksi serta lingkungan kerja. Untuk itu diperlukan intensitas penerangan
yang optimal. Selain menerangi obyek kerja, penerangan juga diharapkan cukup memadai
menerangi keadaan sekelilingnya. Kualitas penerangan yang tidak memadai berefek buruk
bagi fungsi penglihatan, juga untuk lingkungan sekeliling tempat kerja, maupun aspek
psikologis, yang dapat dirasakan sebagai kelelahan, rasa kurang nyaman, kurang kewaspadaan
sampai kepada pengaruh yang terberat seperti kecelakaan.
Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 tentang Syarat-Syarat Kesehatan,
Kebersihan serta Penerangan dalam Tempat Kerja, telah menetapkan ketentuan penting
intensitas penerangan menurut sifat pekerjaan. Selanjutnya pada Peraturan Menteri
Kesehatan R.I. Nomor 70 tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan
Kerja Industri, mengatur persyaratan faktor fisik sebagai persyaratan kesehatan lingkungan
kerja industri diantaranya menyangkut persyaratan faktor pencahayaan. Dalam peraturan
tersbut dikemukakan bahwa persyaratan pencahayaan lingkungan kerja industri merupakan
nilai tingkat pencahayaan yang disarankan berdasarkan jenis area, pekerjaan atau aktivitas
tertentu. Persyaratan pencahayaan lingkungan kerja dikelompokkan menjadi:
a. Persyaratan pencahayaan dalam gedung industri;
b. Persyaratan pencahayaan di luar gedung industri.
Persyaratan pencahayaan dalam gedung lingkungan kerja industri dikelompokkan
menjadi area umum dalam gedung industri dan berdasarkan jenis area, pekerjaan atau
aktivitas pada masing-masing jenis industri. Persyaratan pencahayaan luar gedung lingkungan
kerja industri dikelompokkan menjadi area umum dan berdasarkan jenis industri.
Pengukuran intensitas penerangan di tempat kerja berdasar pada Standar Nasional
Indonesia (SNI) 16-7062-2004. Standar ini menguraikan tentang metoda pengukuran
intensitas penerangan di tempat kerja dengan menggunakan luxmeter. Pengukuran intensitas
penerangan ini memakai alat luxmeter yang hasilnya dapat langsung dibaca. Alat ini
mengubah energi cahaya menjadi energi listrik, kemudian energi listrik dalam bentuk arus
digunakan untuk menggerakkan jarum skala. Untuk alat digital, energi listrik diubah menjadi
angka yang dapat dibaca pada layar monitor.
Penentuan titik pengukuran dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama penerangan
setempat: objek kerja berupa meja kerja maupun peralatan, dan kedua penerangan umum:
titik potong garis horizontal panjang dan lebar ruangan pada setiap jarak tertentu setinggi satu
Praktik Kerja Industri 183
meter dari lantai. Pada waktu pengukuran intensitas penerangan di tempat kerja maka pintu
ruangan dalam keadaan sesuai dengan kondiisi tempat pekerjaan dilakukan, dan lampu
ruangan dalam keadaan dinyalakan sesuai dengan kondisi pekerjaan.
Pada pelaksanaan pengukuran penerangan setempat bila merupakan meja kerja,
pengukuran dapat dilakukan di atas meja yang ada. Sedangkan pada pelaksanaan pengukuran
penerangan umum pengukuran dilakukan pada titik potong garis horizontal panjang dan lebar
ruangan, yang dibedakan berdasarkan luas ruangan sebagai berikut:
a. Luas ruangan kurang dari 10 meter persegi: titik potong garis horizontal panjang dan
lebar ruangan adalah pada jarak setiap 1 (satu) meter.
b. Luas ruangan antara 10 meter persegi sampai 100 meter persegi: titik potong garis
horizontal panjang dan lebar ruangan adalah pada jarak setiap 3 (tiga) meter.
c. Luas ruangan lebih dari 100 meter persegi: titik potong horizontal panjang dan lebar
ruangan adalah pada jarak 6 meter.
Tata cara pengukuran intensitas penerangan di tempat kerja dengan menggunakan
luxmeter:
a. Hidupkan luxmeter yang telah dikalibrasi dengan membuka penutup sensor.
b. Bawa alat ke tempat titik pengukuran yang telah ditentukan, baik pengukuran untuk
intensitas penerangan setempat atau umum.
c. Baca hasil pengukuran pada layar monitor setelah menunggu beberapa saat sehingga
didapat nilai angka yang stabil.
d. Catat hasil pengukuran pada lembar hasil pencatatan.
e. Matikan luxmeter setelah selesai dilakukan pengukuran intensitas penerangan.
184 Praktik Kerja Industri
Tabel 5.3.
HASIL PENGUKURAN INTENSITAS PENERANGAN SETEMPAT
Nama Industri :
Alamat Industri :
Jenis Industri :
Jumlah Tenaga Kerja : Laki Laki : ....... orang, Perempuan : ....... orang
Lokasi Titik Pengukuran :
Tipe Alat Ukur :
Tipe Kalibrator :
Petugas Pengukur :
Tanggal Pengukuran :
Penanggung Jawab Unit Kerja :
Hasil Pengukuran (Lux)
Objek Kerja Rata Rata
Pengukuran I Pengukuran II Pengukuran III
Mengetahui,
Penanggung Jawab Unit Kerja Petugas Pengukur
.................................................. ..........................................
Praktik Kerja Industri 185
Tabel 5.4.
HASIL pengukuran intensitas penerangan UMUM
Nama Industri :
Alamat Industri :
Jenis Industri :
Jumlah Tenaga Kerja : Laki Laki : ....... orang, Perempuan : ....... orang
Lokasi Titik Pengukuran :
Tipe Alat Ukur :
Tipe Kalibrator :
Petugas Pengukur :
Tanggal Pengukuran :
Penanggung Jawab Unit Kerja :
Hasil Pengukuran (Lux)
Ruang Rata Rata
Pengukuran I Pengukuran II Pengukuran III
Mengetahui,
Penanggung Jawab Unit Kerja Petugas Pengukur
.................................................. ..........................................
186 Praktik Kerja Industri
4. Pengukuran Getaran
Parameter fisik yang juga harus mendapatkan perhatian pada waktu melakukan
pengukuran di tempat kerja adalah getaran. Jenis pajanan getaran yang dapat diterima
pekerja dapat berupa getaran tangan dan lengan serta getaran seluruh tubuh. Pajanan
getaran yang dialami tenaga kerja dapat bersumber dari peralatan atau perkakas kerja yang
digunakan dan dari mesin yang beriperasi di tempat kerja.
Arah gerakan tangan yang bergetar terdiri atas gerakan biodinamik dan gerakan
biosentrik. Kecepatan getaran atau nilai akselerasi getaran tangan dan lengan terdiri atas tiga
arah aksis (x, y, dan z). Pengukuran getaran tangan dan lengan dilakukan dengan
menggunakan vibrasi meter sesuai metode yang standar. Hasil pengukuran kemudian
dibandingkan dengan nilai ambang batas. Nilai Ambang Batas (NAB) pajanan getaran pada
tangan dan lengan sebagaimana tercantum pada Tabel 5 Peraturan Menteri Kesehatan R.I.
Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri
merupakan nilai rata-rata akselerasi pada frekuensi dominan (meter/detik2) berdasarkan
durasi pajanan 8 jam per hari kerja yang mewakili kondisi dimana hampir semua pekerja
terpajan getaran berulang-ulang tanpa menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit.
Pekerja dapat terpajan getaran tangan dan lengan pada saat menggunakan alat kerja seperti
gergaji listrik, gerinda, jack hammer dan lain-lain. NAB getaran tangan dan lengan untuk 8 jam
kerja per hari adalah sebesar 5 meter/detik2. Sedangkan NAB getaran tangan dan lengan untuk
durasi pajanan tertentu dapat dilihat pada Tabel 5 Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor
70 Tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri.
Getaran yang diterima seluruh tubuh harus dievaluasi pada masing-masing aksis (x, y
dan z) dan resultan dari 3 aksis. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 70 Tahun 2016
tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri menjelaskan Nilai
Ambang Batas pajanan getaran seluruh tubuh sebagaimana tercantum pada Tabel 6 (untuk
aksis x dan y) dan Tabel 7 (untuk aksis z) merupakan akselerasi rata-rata dalam meter/detik2
pada frekuensi (hertz) dan durasi pajanan yang mewakili kondisi dimana hampir semua
pekerja berulangkali terpajan dengan risiko minimum pada nyeri punggung, gangguan
kesehatan pada tulang belakang dan ketidakmampuan dalam mengoperasikan kendaraan
dengan benar.
Pedoman Penggunaan NAB Getaran Seluruh Tubuh untuk masing-masing Aksis (x, y, dan
z) NAB getaran seluruh tubuh digunakan dengan mengikuti tahapan berikut:
a. Perhatikan nilai hasil pengukuran getaran seluruh tubuh untuk setiap frekuensi pada
masing-masing aksis x, y, dan z.
b. Untuk perhitungan akselerasi resultan maupun yang mempertimbangkan crest factor
mengikuti formula pada pedoman.
Praktik Kerja Industri 187
Pengukuran percepatan getaran seluruh tubuh pada sikap kerja duduk dilakukan dalam
rangka penilaian potensi bahaya getaran seluruh tubuh untuk mewujudkan kesehatan dan
keselamatan kerja. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan human vibration meter,
akselerometer tiga sumbu (triaxial accelerometer) dan bantalan (pad). Pengukuran dilakukan
dengan cara :
a. Hubungkan rangkaian transducer dengan vibration meter.
b. Letakkan transducer pada area antara tubuh dengan alas duduk.
c. Nara ukur menduduki bantalan transducer.
d. Hidupkan alat dan atur pembobotan frekuensi.
e. Lakukan pengukuran sesuai dengan bku petunjuk alat, lama pengukuran satu menit
dengan tiga kali pembacaan masing masing setelah 20 detik. Untuk getaran konstan
pembacaan minimal dua kali. Sumber getaran kejut minimal empat kali sesuai frekuensi
getaran
f. Catat hasil penukuran dalam formulir yang tersedia.
g. Hitung percepatan rata rata getaran.
1) Rumus percepatan rata-rata getaran.
𝐚𝐰 = √∑(𝐖|𝐚|)𝟐
aw : percepatan getaran dengan pembobotan frekuensi
W : faktor pembobotan frekuensi.
a : percepatan kuadrat rata rata
2) Rumus total nilai percepatan rata-rata getaran.
𝐚𝐯 = √(𝐤 𝐱 𝟐 𝐚𝐰𝐱 𝟐 + 𝐤 𝐲 𝟐 𝐚𝐰𝐲 𝟐 + 𝐤 𝐳 𝟐 𝐚𝐰𝐳 𝟐 )
av : nilai total percepatan rata-rata getaran seluruh tubuh
awx, awy, awz : percepatan getaran rata-rata getaran seluruh tubuh dengan
pembobotan x, y dan z.
k : konstanta pembobotan frekuensi, yaitu:
Sumbu X : Wd2, k = 1,4
Sumbu Y : Wd1, k = 1,4
Sumbu Z : Wk, k = 1
188 Praktik Kerja Industri
h. Lakukan evaluasi paparan getaran dengan cara:
1) Evaluasi berdasarkan percepatan akar kuadrat rata rata (root mean square)
dengan pembobotan frekuensi.
2) Hasil pengukuran dibandingkan dengan standar yang berlaku.
Praktik Kerja Industri 189
Tabel 5.5.
HASIL PENGUKURAN GETARAN DI TEMPAT KERJA
JENIS GETARAN TANGAN DAN LENGAN
Nama Industri :
Alamat Industri :
Jenis Industri :
Jumlah Tenaga Kerja : Laki Laki : ....... orang, Perempuan : ....... orang
Lokasi Titik Pengukuran :
Petugas Pengukur :
Tanggal Pengukuran :
Penanggung Jawab Unit Kerja :
Tenaga Kerja Sumber Tk.
No Lokasi NAB Ket
Sampel Getaran Getaran (m/s2)
Mengetahui, Petugas Pengukur
Penanggung Jawab Unit Kerja
.................................................. ..........................................
190 Praktik Kerja Industri
Tabel 5.6.
HASIL PENGUKURAN GETARAN DI TEMPAT KERJA
JENIS GETARAN SELURUH TUBUH
Nama Industri :
Alamat Industri :
Jenis Industri :
Jumlah Tenaga Kerja : Laki Laki : ....... orang, Perempuan : ....... orang
Lokasi Titik Pengukuran :
Petugas Pengukur :
Tanggal Pengukuran :
Penanggung Jawab Unit Kerja :
Tenaga Kerja Sikap Sumber Tk. Getaran Katagori
No Lokasi Ket
Sampel Kerja Getaran (m/s2) Getaran
Mengetahui, Petugas Pengukur
Penanggung Jawab Unit Kerja
.................................................. ..........................................
Praktik Kerja Industri 191
Tabel 5.7.
HASIL PENGUKURAN GETARAN DI TEMPAT KERJA
JENIS GETARAN MESIN
Nama Industri :
Alamat Industri :
Jenis Industri :
Jumlah Tenaga Kerja : Laki Laki : ....... orang, Perempuan : ....... orang
Lokasi Titik Pengukuran :
Petugas Pengukur :
Tanggal Pengukuran :
Penanggung Jawab Unit Kerja :
Tk. Getaran Katagori
No Lokasi Mesin Sampel Daya Mesin Ket
(mm/det) Getaran
Mengetahui, Petugas Pengukur
Penanggung Jawab Unit Kerja
.................................................. ..........................................
192 Praktik Kerja Industri
Tabel 5.8.
HASIL PENGUKURAN GETARAN LINGKUNGAN
JENIS GETARAN UNTUK KENYAMANAN DAN KESEHATAN
Nama Industri :
Alamat Industri :
Jenis Industri :
Jumlah Tenaga Kerja : Laki Laki : ....... orang, Perempuan : ....... orang
Lokasi Titik Pengukuran :
Petugas Pengukur :
Tanggal Pengukuran :
Penanggung Jawab Unit Kerja :
Sumber Getaran :
Frekuensi Tingkat Getaran
No Katagori Getaran Keterangan
(Hz) (µm)
1. 4
2. 5
3. 6,3
4. 8
5. 10
6. 15,5
7. 16
8. 20
9. 25
10. 31,5
11. 40
12. 50
13. 63
Catatan : Katagori Getaran berdasarkan Kepmeneg LH No. 49 Tahun 1996
Mengetahui,
Penanggung Jawab Unit Kerja Petugas Pengukur
.................................................. ..........................................
Praktik Kerja Industri 193
Tabel 5.9.
HASIL PENGUKURAN GETARAN LINGKUNGAN
JENIS GETARAN UNTUK KERUSAKAN BANGUNAN
Nama Industri :
Alamat Industri :
Jenis Industri :
Jumlah Tenaga Kerja : Laki Laki : ....... orang, Perempuan : ....... orang
Lokasi Titik Pengukuran :
Petugas Pengukur :
Tanggal Pengukuran :
Penanggung Jawab Unit Kerja :
Sumber Getaran :
Frekuensi Tingkat Getaran
No Katagori Getaran Keterangan
(Hz) (µm)
1. 4
2. 5
3. 6,3
4. 8
5. 10
6. 15,5
7. 16
8. 20
9. 25
10. 31,5
11. 40
12. 50
13. 63
Catatan : Katagori Getaran berdasarkan Kepmeneg LH No. 49 Tahun 1996
Mengetahui, Petugas Pengukur
Penanggung Jawab Unit Kerja
.................................................. ..........................................
194 Praktik Kerja Industri
5. Pengukuran Gelombang Mikro
Radiasi adalah perambatan atau pemancaran energi dari suatu sumber energi ke
lingkungannya tanpa membutuhkan media atau bahan penghantar tertentu. Sesuai dengan
tingkat energi yang dipancarkannya, radiasi dapat dibedakan menjadi radiasi bukan peng-ion
dan radiasi peng-ion. Radiasi bukan peng-ion memancarkan energi dengan tingkat yang relatif
rendah sehingga tidak mampu mengionisasi media yang dilaluinya. Radiasi jenis ini biasanya
merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang lebih besar
daripada 1 x 10-9 meter. Sebagai contoh jenis radiasi ini adalah gelombang radio, microwave
dan cahaya tampak. Sebaliknya, radiasi peng-ion memancarkan energi dengan tingkat yang
sudah mampu mengionisasi media yang dilaluinya. Proses ionisasi ini dapat menimbulkan
kerusakan pada sel tubuh, maka radiasi peng-ion dikategorikan sebagai sesuatu yang
berbahaya. Radiasi jenis ini dapat berupa gelombang elektromagnetik, dengan panjang
gelombang lebih kecil daripada 1 x 10-9 meter, ataupun partikel yang berasal dari transformasi
inti atom. Sebagai contoh adalah sinar-X, sinar gamma, partikel alpha dan beta.
Pembahasan lebih lanjut pada modul ini hanya membahas radiasi non pengion. Radiasi
yang memiliki energi yang cukup untuk bergerak atom dalam suatu molekul sekitar atau
menyebabkan mereka bergetar, tetapi tidak cukup untuk menghilangkan elektron. Sangat
rendah frekuensi radiasi memiliki panjang gelombang yang sangat lama (di urutan satu juta
meter atau lebih) dan frekuensi dalam kisaran 100 Hertz atau siklus per detik atau kurang.
Frekuensi radio memiliki panjang gelombang antara 1 dan 100 meter dan frekuensi dalam
kisaran 1-1000000 Hertz. Microwave yang kita gunakan untuk memanaskan makanan
memiliki panjang gelombang yang sekitar 1 seperseratus meter panjang dan memiliki
frekuensi sekitar 2,5 milyar Hertz.
Jenis radiasi non pengion:
a. Radiasi Neutron
Radiasi Neutron adalah jenis radiasi non-ion yang terdiri dari neutron bebas. Neutron ini
bisa mengeluarkan selama baik spontan atau induksi fisi nuklir, proses fusi nuklir, atau dari
reaksi nuklir lainnya. Ia tidak mengionisasi atom dengan cara yang sama bahwa partikel
bermuatan seperti proton dan elektron tidak (menarik elektron), karena neutron tidak
memiliki muatan. Namun, neutron mudah bereaksi dengan inti atom dari berbagai elemen,
membuat isotop yang tidak stabil dan karena itu mendorong radioaktivitas dalam materi yang
sebelumnya non-radioaktif. Proses ini dikenal sebagai aktivasi neutron.
b. Radiasi Elektromagnetik
Radiasi elektromagnetik mengambil bentuk gelombang yang menyebar dalam udara
kosong atau dalam materi. Radiasi EM memiliki komponen medan listrik dan magnetik yang
berosilasi pada fase saling tegak lurus dan ke arah propagasi energi. Radiasi elektromagnetik
Praktik Kerja Industri 195
diklasifikasikan ke dalam jenis menurut frekuensi gelombang, jenis ini termasuk (dalam rangka
peningkatan frekuensi): gelombang radio, gelombang mikro, radiasi terahertz, radiasi
inframerah, cahaya yang terlihat, radiasi ultraviolet, sinar-X dan sinar gamma. Dari jumlah
tersebut, gelombang radio memiliki panjang gelombang terpanjang dan sinar gamma memiliki
terpendek. Sebuah jendela kecil frekuensi, yang disebut spektrum yang dapat dilihat atau
cahaya, yang dilihat dengan mata berbagai organisme, dengan variasi batas spektrum sempit
ini.
c. Radiasi Cahaya
Cahaya adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang yang terlihat oleh mata
manusia (sekitar 400-700 nm), atau sampai 380-750 nm. Lebih luas lagi, fisikawan
menganggap cahaya sebagai radiasi elektromagnetik dari semua panjang gelombang, baik
yang terlihat maupun tidak terlihat.
d. Radiasi Thermal
Radiasi termal adalah proses dimana permukaan benda memancarkan energi panas
dalam bentuk gelombang elektromagnetik. radiasi infra merah dari radiator rumah tangga
biasa atau pemanas listrik adalah contoh radiasi termal, seperti panas dan cahaya yang
dikeluarkan oleh sebuah bola lampu pijar bercahaya. Radiasi termal dihasilkan ketika panas
dari pergerakan partikel bermuatan dalam atom diubah menjadi radiasi elektromagnetik.
Radiasi frekuensi radio dan gelombang mikro (Microwave) adalah radiasi elektromagnetik
dengan frekuensi 30 Kilo Hertz sampai 300 Giga Herzt. NAB radiasi frekuensi radio dan
gelombang mikro ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I nomor 4 Peraturan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang
Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja.
Radiasi elektromagnetik berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan tertentu.
Berbagai potensi gangguan kesehatan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Sistem darah, berupa leukemia dan limfoma malignum.
b. Sistem reproduksi laki-laki, berupa infertilitas.
c. Sistem saraf, berupa degeneratif saraf tepi.
d. Sistem kardiovaskular, berupa perubahan ritme jantung.
e. Sistem endokrin, berupa perubahan metabolisme hormon melatonin.
f. Psikologis, berupa neurosis dan gangguan irama sirkadian.
g. Hipersensitivitas.
196 Praktik Kerja Industri
Potensi gangguan terhadap sistem darah, kardiovaskular, reproduksi dan saraf,
memerlukan waktu yang panjang dan tidak dapat dirasakan atau diamati dalam waktu
pendek. Sedangkan potensi gangguan pada sistem hormonal, psikologis dan hipersensitivitas,
umumnya dapat terjadi dalam waktu pendek. Manifestasi gangguan dalam waktu pendek,
biasanya berupa berbagai keluhan. Keluhan yang paling banyak dikemukakan oleh penduduk
yang bertempat tinggal di bawah SUTET adalah sakit kepala, pening dan keletihan menahun.
Meskipun demikian, pajanan medan elektromagnetik bukan hanya berasal dari SUTET
saja, tetapi dapat berasal dari peralatan elektronik di rumah tangga, kantor, industri, dan
peralatan komunikasi. Bahkan dalam kehidupan modern, radiasi elektromagnetik gelombang
radio dengan energi yang sangat besar mudah dijumpai. Penggunaan telepon seluler (ponsel)
sebagai sarana komunikasi penting serta microwave oven yang sangat membantu pekerjaan
di dapur, juga merupakan contoh sumber radiasi elektromagnetik gelombang radio tersebut,
dan dapat menimbulkan berbagai keluhan seperti sakit kepala maupun keletihan tanpa sebab
yang nyata.
Prosedur kerja pengukuran radiasi elektromagnetik dengan menggunakan Detector
Radiasi Elektromagnetik DT 1130.
a. Siapkan alat
b. Siapkan bahan berupa sumber radiasi elektromagnetik yang akan diukur.
c. Lakukan pengukuran radiasi elektromagnetik
1) Tekan tombol Power (untuk menghidupkan).
2) Dekatkan pada benda yang akan diukur perlahan sampai menempel. Pada benda-
benda yang mengeluarkan tegangan cukup tinggi (kabel listrik, dan lain-lain) maka
pengukuran dilakukan dengan didekatkan saja.
3) Rubah sudut pengukuran untuk mencari data maksimum.
4) Pastikan alat yang akan diukur dalam keadaan hidup.
5) Hasil pengukuran dibaca dengan menekan tombol Hold untuk pembacaan hasil.
6) Catat hasil sebagai mW/cm2 (dibaca: mili Watt per centimeter persegi)
7) Tekan power untuk mematikan alat.
8) Lepas baterai apabila tidak digunakan dan simpan kembali pada tempatnya.
Praktik Kerja Industri 197
Tabel 5.10.
HASIL PENGUKURAN RADIASI ELEKTROMAGNETIK
Nama Industri :
Alamat Industri :
Jenis Industri :
Jumlah Tenaga Kerja : Laki Laki : ....... orang, Perempuan : ....... orang
Lokasi Titik Pengukuran :
Petugas Pengukur :
Tanggal Pengukuran :
Penanggung Jawab Unit Kerja :
Power
Frekuensi
No Sumber Radiasi Density NAB Ket
(Hz)
(mW/cm2)
Mengetahui,
Penanggung Jawab Unit Kerja Petugas Pengukur
.................................................. ..........................................
198 Praktik Kerja Industri
6. Pengukuran Sinar Ultra Violet
Pengukurann radiasi sinar ultra violet bertujuan untuk mengatahui besarnya radiasi
ultra violet dengan menggunakan alat radiometer ultra violet. Radiasi ultra violet adalah
radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 180 nano meter sampai 400 nano meter
(nm).
Ultra violet termasuk dalam spektrum radiasi elektromagnetik dengan panjang
gelombang 400 sampai 100 nanometer dan frekuensi 3,5 x 1014 – 3 x 1015 Hz. Ultra violet
banyak terpancar di tempat kerja, baik yan bersumber dari alam (sinar matahari) maupun
yang ditimbulkan oleh peralatan buatan manusia seperti lampu merkuri, halogen, las listrik,
pemotong logam, dan sebagainya.
Radiasi ultra violet dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi tenaga kerja, khususnya
pada pekerja yang melakukan pekerjaan dibawah sinar matarahi (outdoor work) dan di tempat
kerja yang menggunakan peralatan yang memancarkan sinar ultra violet. Radiasi ultra violet
umumnya berpenetrasi pada kulit dan mata, sehingga efek kesehatan yang ditimbulkan
adalah pada kulit dan mata.
Setiap alat pengukur radiasi ultra violet mempunyai spesifikasi sehingga untuk
pelaksanaan pengukuran tergantung dan petunjuk pada alat yang digunakan. Prosedur yang
umum digunakan pada pengukuran radiasi ultra violet menggunakan alat portable dengan
pembacaan langsung:
a. Pasan atau sambung setiap bagian alat, yaitu unit detector fotocel, panel radiometer dan
tempat baterai. Sebelum memasang setiap bagian, arus/power harus dimatikan.
b. Gunakan baterai sesuai dengan petunjuk pada alat (umumnya 9 volt).
c. Lakukan kalibrasi (mengukur agar skala menunjuk angka nol), caranya : tutup unit
detector fotocel dan tekan tombol untuk menghidupkan (power on). Setelah muncul
tulisal “CAL” tekan tombol “HOLD”. Bila sudah muncul 0,000 mV/cm2 (kira-kira dalam
4 detik) berarti kalibrasi selesai.
d. Matikan tombol “HOLD” setelah selesai mengkalibrasi.
e. Buka tutup detector fotocel dan lakukan pengukuran.
f. Muncul angka pengukuran radiasi ultra violet pada panel radiometer. Bila angka yang
tertera sudah stabil (tidak berkedip-kedip) lakukan pencatatan. Dengan menekan
tombol “HOLD – On” panel radiometer akan tetap menunjuk angka tersebut.
g. Untuk melakukan pengukuran selanjutnya, tombol HOLD harus dimatikan (HOLD – Off).
h. Lakukan pengukuran pada setiap titik pengukuran. Penguran dilakukan minimal pada
tiga titik :
Praktik Kerja Industri 199
1) Zona penglihatan dengan jarak maksimal 30 cm dari mata.
2) Setinggi siku (sesuai posisi kerja duduk atau berdiri) dengan jarak maksimal 30 cm
dari bagian badan paling luar.
3) Setinggi betis dengan jarak maksimal 30 cm dari betis.
i. Catat hasil pengukuran pada formulir pengisian data.
200 Praktik Kerja Industri
Tabel 5.11.
HASIL PENGUKURAN RADIASI ULTRA VIOLET
Nama Industri :
Alamat Industri :
Jenis Industri :
Jumlah Tenaga Kerja : Laki Laki : ....... orang, Perempuan : ....... orang
Lokasi Titik Pengukuran :
Tipe Alat Ukur :
Petugas Pengukur :
Tanggal Pengukuran :
Penanggung Jawab Unit Kerja :
Waktu
No Unit Kerja Radiasi (µW/cm) Keterangan
Pengukuran
Mata
Siku
Betis
Mata
Siku
Betis
Mata
Siku
Betis
Mata
Siku
Betis
Mata
Siku
Betis
Mengetahui, Petugas Pengukur
Penanggung Jawab Unit Kerja
.................................................. ..........................................
Praktik Kerja Industri 201
7. Pengukuran Medan Magnet
Listrik menjadi bagian yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Coba bayangkan
bagaimana kehidupan manusia sebelum adanya listrik. Lampu danperalat an elektronik tidak
bisa digunakan. Dunia akan gelap gulita di malam hari. Tidak ada TV, atau HP yang bisa dilihat
atau digunakan. Sebagai manusia tentu kita pantas bersyukur dengan ditemukannya listrik
dengan segala manfaat yang mengiringinya. Listrik didefinisikan sebagai aliran atau
pergerakan elektron, yakni suatu partikel bermuatan negatif yang ditemukan pada setiap
atom.
Muatan listrik ada dua yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Jika dua
benda saling bergesekan, maka elektron akan ditarik dari satu benda dan dilemparkan ke
benda lain. Hal tersebut akan menyebabkan tumpukan elektron sehingga terjadi muatan
negatif pada salah satu benda. Hilangnya elektron pada benda yang lain menyebabkan
terjadinya muatan positif. Sebagai contoh penggaris plastis yang digosok dengan rambut atau
handuk akan bermuatan negatif dan handuk bermuatan positif. Muatan yang sama jika
didekatkan akan tolak menolak dan muatan yang berbeda jika didekatkan akan tarik menarik.
Adanya gaya antara dua benda bermuatan yang berada pada jarak tertentu
memunculkan gagasan adanya medan di sekitar muatan tersebut. Ide medan pertama kali
dicetuskan oleh Michael Faraday (1791-1867). Menurut Faraday suatu medan listrik keluar
dari setiap muatan. Ketika muatan kedua di tempatkan di sekitar muatan pertama, maka
muatan kedua akan mengalami gaya yang disebabkan oleh adanya medan listrik di area
tersebut.
Gaya listrik pada sebuah benda bermuatan dikerahkan oleh medan listrik yang
diciptakan oleh benda bermuatan lainnya. Gaya adalah sebuah besaran vector, sehingga
medan listrik juga adalah besaran vector. Oleh karena medan listrik adalah besaran vector,
makan medan listrik sering disebut juga dengan medan vektor. Medan listrik divisualisasikan
dengan garis-garis medan atau garis-garis gaya. Untuk suatu muatan positif, garis-garis gaya
secara radial mengarah ke luar dari muatan sedangkan untuk muatan negatif garis-garis gaya
secara radial mengarah ke dalam muatan.
Arus listrik merupakan sumber lain untuk medan magnet, fenomena ini pertama kali
ditemukan oleh Hans Christian Oersted (1777-1851), sebuah penemuan penting yang
menyatakan bahwa arus litrik menghasilkan efek magnetik atau medan magnet. Magnet yang
dihasilkan oleh arus listrik disebut dengan elektromagnetik. Medan magnetik yang dihasilkan
oleh eletromagnetik mempunyai arah. Untuk menentukan arah medan magnetik maka dapat
digunakan aturan tangan kanan yaitu ibu jari menunjukkan arah arus listrik, sedangkan arah
lipatan jari menunjukkan arah medan magnet.
202 Praktik Kerja Industri
Medan magnet statis adalah suatu medan atau area yang ditimbulkan oleh pergerakan
arus listrik. Pengukuran medan magnet dapat menggunakan Alat Ukur Medan Magnet meter
EM-191. Alat ini diterapkan untuk mengukur medan elektromagnetik frekuensi sangat rendah
(ELF) dari 30Hz ke 300Hz. Hal ini mampu mengukur intensitas radiasi medan elektromagnetik
yang dihasilkan dari peralatan listrik transmisi, saluran listrik, oven listrik, AC, kulkas, monitor
komputer, video atau perangkat audio dan sebagainya. Unit medan magnet adalah Tesla (T),
Gauss (G), mikro–Tesla (µT) atau mili–Gauss (mg).
Gambar 5.1.
Alat Ukur Medan Magnet meter EM-191
NAB medan magnit statis untuk seluruh tubuh ditetapkan sebesar 2 Tesla. NAB medan
magnit statis untuk bagian anggota tubuh (kaki dan tangan) ditetapkan sebesar 600 milli tesla
(mT). NAB medan magnit untuk masing-masing anggota badan tercantum dalam Lampiran I
Nomor 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.13/MEN/X/2011
tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di tempat kerja.
Praktik Kerja Industri 203
Tabel 5.12.
HASIL PENGUKURAN MEDAN MAGNET STATIS
Nama Industri :
Alamat Industri :
Jenis Industri :
Jumlah Tenaga Kerja : Laki Laki : ....... orang, Perempuan : ....... orang
Lokasi Titik Pengukuran :
Tipe Alat Ukur :
Petugas Pengukur :
Tanggal Pengukuran :
Penanggung Jawab Unit Kerja :
Pemaparan Medan Magnet Statis yang Diperkenankan
Kadar Tertinggi
No. Bagian Tubuh Diperkenankan Hasil Ukur Keterangan
(Ceiling)
1 Seluruh Tubuh (tempat kerja umum) 2T
Seluruh Tubuh (pekerja khusus dan
2 8T
lingkungan kerja yang terkendali)
3 Anggota gerak (Limbs) 20 T
4 Pengguna peralatan medis elektronik 0,5 mT
Medan Magnet Statis untuk Frekuensi 1 - 30 kHz
Rentang
No. Bagian Tubuh NAB Hasil Ukur Ket.
Frekuensi
1 Seluruh tubuh 60/f mT 1 – 300 Hz
2 Lengan dan paha 300/f mT 1 – 300 Hz
3 Tangan dan kaki 600/f mT 1 – 300 Hz
Anggota tubuh dan seluruh
4 0,2 mT 300 Hz – 30 KHz
tubuh
Mengetahui, Petugas Pengukur
Penanggung Jawab Unit Kerja
.................................................. ..........................................
204 Praktik Kerja Industri
C. PENGAWASAN FAKTOR KIMIA TEMPAT KERJA
Kegiatan industri yang mengolah, menyimpan, mengedarkan, mengangkut dan
mempergunakan bahan-bahan kimia berbahaya akan terus meningkat sejalan dengan
perkembangan pembangunan sehingga berpotensi untuk menimbulkan bahaya besar bagi
industri, tenaga kerja, lingkungan maupun sumber daya lainnya. Untuk mencegah kecelakaan
dan penyakit akibat kerja, akibat penggunaan bahan kimia berbahaya di tempat kerja maka
perlu diatur pengendaliannya.
Pengusaha atau Pengurus yang menggunakan, menyimpan, memakai, memproduksi
dan mengangkut bahan kimia berbahaya di tempat kerja wajib mengendalikan bahan kimia
berbahaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Pengendalian bahan kimia berbahaya meliputi penyediaan Lembar Data Keselamatan Bahan
(LDKB) dan label, serta penunjukan petugas K3 Kimia dan Ahli K3 Kimia.
Untuk mengetahui kondisi bahan kimia di lingkungan kerja perlu dilakukan pengukuran
baik dilingkungan kerja ataupun di dalam tempat kerja.
Praktik Kerja Industri 205
Tabel 5.13.
HASIL PENGUKURAN PARAMETER KIMIA DI TEMPAT KERJA
Nama Industri :
Alamat Industri :
Jenis Industri :
Jumlah Tenaga Kerja : Laki Laki : ....... orang, Perempuan : ....... orang
Lokasi Titik Pengukuran :
Petugas Pengukur :
Tanggal Pengukuran :
Penanggung Jawab Unit Kerja :
Hasil
No Item Pemantauan Faktor Kimia Ket.
Pengukuran
A. Pengukuran Kualitas Kimia Udara Ambien :
1. Partikulat (PM10)
2. Karbon Monoksida (CO)
3. Sulfur dioksida (SO2)
4. Nitrogen dioksida (NO2)
5. Ozon (O3)
B. Pengukuran Kualitas Kimia Udara di tempat kerja :
1. ......................
2. ......................
Parameter yang diukur bisa saja berbeda antara industri yang
3.
satu dengan industri yang lain.
Mengetahui,
Penanggung Jawab Unit Kerja Petugas Pengukur
.................................................. ..........................................
206 Praktik Kerja Industri
D. PENGAWASAN FAKTOR BIOLOGI TEMPAT KERJA
Lingkungan kerja industri harus memenuhi standar dan persyaratan kesehatan
lingkungan kerja industri sebagai persyaratan minimal yang harus dipenuhi. Standar dan
persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri terdiri atas nilai ambang batas, indikator
pajanan biologi, dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri.
Persyaratan faktor biologi di lingkungan kerja mencakup nilai maksimal bakteri dan
jamur baik pada media air, udara, tanah dan bahan pangan.
Praktik Kerja Industri 207
Tabel 5.14.
HASIL PENGUKURAN PARAMETER BIOLOGI DI TEMPAT KERJA
Nama Industri :
Alamat Industri :
Jenis Industri :
Jumlah Tenaga Kerja : Laki Laki : ....... orang, Perempuan : ....... orang
Lokasi Titik Pengukuran :
Petugas Pengukur :
Tanggal Pengukuran :
Penanggung Jawab Unit Kerja :
A. Standar Baku Mutu Biologi Air Minum
No. Parameter SBM Hasil Ukur Ket.
1. E. coli 0 CFU/100 ml sampel
2. Total Bakteri Koliform 0 CFU/100 ml sampel
B. Standar Baku Mutu Biologi Air untuk Keperluan Higiene dan Sanitasi
No. Parameter SBM Hasil Ukur Ket.
1. E. coli 0 CFU/100 ml sampel
2. Total Bakteri Koliform 50 CFU/100 ml sampel
C. Standar Baku Mutu Biologi Udara Perkantoran
No. Parameter SBM Hasil Ukur Ket.
1. Angka Mikroorganisme 700 CFU/m3 udara
2. Angka Kapang/Jamur 1000 CFU/ m3 udara
D. Standar Baku Mutu Biologi Tanah
No. Parameter SBM Hasil Ukur Ket.
1. Telur Cacing 0 / 10 gr tanah kering
2. Fecal coliform 0 CFU/10 gr tanah kering
208 Praktik Kerja Industri
E. Standar Baku Mutu Biologi Pangan Siap Saji
No. Parameter SBM Hasil Ukur Ket.
1. Standard Plate Count < 104 CFU/gr
2. Enterobacteriaceae < 100 CFU/gr
3. Escherichia coli < 10 CFU/gr
4. Salmonella spp. Tidak terdeteksi /25 gr
5. Campylobacter spp. Tidak terdeteksi /25 gr
6. E.coli Tidak terdeteksi /25 gr
7. Listeria monocytogenes Tidak terdeteksi /25 gr
8. V. parahaemolyticus Tidak terdeteksi /25 gr
9. Clostridium perfringens < 10 CFU/gr
10. Coagulasepositi < 50 CFU/gr
vestaphylococci
11. Bacillus spp. < 50 CFU/gr
Mengetahui,
Penanggung Jawab Unit Kerja Petugas Pengukur
.................................................. ..........................................
Praktik Kerja Industri 209
E. PENGAWASAN FAKTOR ERGONOMI TEMPAT KERJA
Faktor ergonomi yang perlu diperhatikan dalam kegiatan di industri diantaranya adalah
volume ruang kerja untuk setiap tenaga kerja dan penangan beban manual. Standar baku
mutu ruang kerja industri bergantung pada luas lantai dan tinggi langit-langit bangunan,
sehingga menghasilkan volume ruang kerja minimal perorang sebesar 11 m3.
Persyaratan penangangan beban manual merupakan hal-hal atau kondisi yang harus
dipenuhi oleh setiap tempat kerja dalam rangka mencegah atau mengurangi risiko terjadinya
cedera pada tulang belakang ataupun bagian tubuh lain akibat aktivitas penanganan beban
manual. Persyaratan penanganan beban manual adalah sebagai berikut:
1. Sedapat mungkin hindari melakukan aktivitas penanganan beban secara manual di
tempat kerja yang dapat menyebabkan risiko cedera; atau
2. Apabila tidak memungkinkan, maka
a. lakukan penilaian risiko yang sesuai dan memadai pada semua aktivitas
penanganan beban manual yang dilakukan oleh karyawan, dengan memperhatikan
faktor-faktor yang ditentukan.
b. Lakukan pengendalian yang tepat untuk mengurangi risiko cedera pada karyawan
yang mungkin timbul akibat melakukan aktivitas penanganan beban manual ke
tingkat risiko yang dapat diterima.
c. Memberikan informasi yang tepat kepada setiap karyawan yang melakukan
aktivitas penanganan beban manual berupa:
1) Berat dari setiap beban atau benda yang akan ditangani,
2) Bagian atau sisi terberat dari beban atau benda yang akan diangkat yang
menyebabkan pusat gravitasi tidak berada di sentral,
3. Ulangi penilaian risiko jika:
a. Adanya dugaan bahwa penilaian tersebut tidak lagi sesuai,
b. Terdapat perubahan bermakna pada aktivitas penanganan beban manual yang
dimaksud.
210 Praktik Kerja Industri
Tabel 5.16.
HASIL PENGUKURAN PARAMETER ERGONOMI DI TEMPAT KERJA
Nama Industri :
Alamat Industri :
Jenis Industri :
Jumlah Tenaga Kerja : Laki Laki : ....... orang, Perempuan : ....... orang
Lokasi Titik Pengukuran :
Petugas Pengukur :
Tanggal Pengukuran :
Penanggung Jawab Unit Kerja :
Volume ruang kerja setiap pekerja :
No. Aspek yang dinilai Tidak Ya Ket.
1. Apakah beban atau benda tersebut lebih dari 3
kg untuk wanita dan lebih dari 5 kg untuk pria?
2. Apakah beban atau benda terletak jauh dari
tulang belakang?
3. Apakah ukuran beban atau benda tersebut
besar sehingga sulit untuk ditangani?
4. Apakah beban atau benda tersebut sulit untuk
dipegang?
5. Apakah beban atau benda tersebut tidak stabil
atau berisi material yang mudah berpindah
(misalnya cairan atau serbuk)?
6. Apakah beban atau benda tersebut memiliki
bagian tajam, panas atau dingin?
7. Apakah aktivitas penanganan beban manual
yang dilakukan melibatkan postur tulang
belakang tidak netral (yaitu telinga, bahu, dan
panggul tidak terletak pada satu garis lurus),
antara lain membungkuk dan memutar badan
8. Apakah terdapat aktivitas membawa beban
atau benda jarak jauh?
9. Apakah ada aktivitas mendorong atau menarik
beban secara berlebihan?
10. Apakah aktivitas penanganan beban manual
dilakukan secara berulangulang?
11. Apakah aktivitas penanganan beban manual
dilakukan secara statis?
Praktik Kerja Industri 211
No. Aspek yang dinilai Tidak Ya Ket.
12. Apakah waktu istirahat atau pemulihan tidak
memadai?
13. Apakah permukaan lantai tidak rata, licin, atau
tidak stabil?
14. Apakah ada variasi ketinggian pada lantai?
15. Apakah iklim lingkungan kerja terlalu panas
atau terlalu dingin?
16. Apakah terdapat masalah pada pertukaran
udara di lingkungan kerja?
17. Apakah penerangan tidak sesuai?
18. Apakah ruang yang ada terbatas sehingga
menyulitkan dalam melakukan aktivitas
penanganan beban manual dengan postur
yang baik?
19. Apakah aktivitas penanganan beban manual
tersebut berpotensi menimbulkan bahaya
untuk wanita hamil atau karyawan dengan
masalah kesehatan?
20. Apakah aktivitas penanganan beban manual
tersebut memerlukan kekuatan atau
kemampuan fisik tertentu?
21. Apakah aktivitas penanganan beban manual
tersebut memerlukan informasi atau pelatihan
khusus agar dapat dilakukan dengan aman?
22. Apakah alat pelindung diri atau pakaian yang
digunakan menghalangi karyawan untuk
aktivitas penanganan beban manual dengan
baik?
Mengetahui,
Penanggung Jawab Unit Kerja Petugas Pengukur
.................................................. ..........................................
212 Praktik Kerja Industri
Latihan
Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan
berikut!
1) Sebutkan parameter fisika yang harus diukur dalam pelaksanaan pengawasan
keselamatan kerja di tempat kerja!
2) Parameter kimia apa saja yang harus diukur terkait dengan udara ambient di lingkungan
industri yang harus diukur dalam pelaksanaan pengawasan keselamatan kerja ?
3) Pengamatan faktor biologi dalam pelaksanaan pengawasan keselamatan kerja di tempat
kerja harus dilakukan pada media apa saja ?
Ringkasan
1. Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja di industri, suatu industri harus
menerapkan syarat-syarat keselamatan kerja sebagaimana tercantum dalam Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Faktor fisika di tempat kerja yang perlu mendapatkan pengawasan terdiri dari iklim
kerja, intensitas suara, intensitas cahaya, getaran, gelombang mikro, sinar ultra ungu,
dan medan magnet.
3. Pengawasan faktor kimia di tempat kerja dalam pelaksanaan keselamatan kerja
mencakup kualitas udara ambien dan kualitas udara dalam tempat kerja.
4. Dalam rangka mencegah atau mengurangi risiko terjadinya cedera pada tulang belakang
ataupun bagian tubuh lain akibat aktivitas penanganan beban manual, maka dalam
penanganan beban manual perlu memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan.
Praktik Kerja Industri 213
Tes 1
Kerjakan soal di bawah ini dengan tepat dan cermat!
1) Seorang tenaga kerja melakukan pekerjaan diluar ruangan dan terkena panas matahari
langsung selama melakukan pekerjaan. Berdasarkan hasil pengukuran indek suhu basah
dan bola diperoleh hasil sebagai berikut :
A. Temperatur kering : 31 OC
B. Temperatur basah : 29 OC
C. Temperatur bola : 35 OC
Berdasarkan hasil pengukuran diatas, berapakah Indeks Suhu Basah dan Bola pada
tempat kerja tersebut ?
2) Suatu tempat kerja berukuran panjang 12 meter dan lebar 8 meter. Jika Saudara
bertugas untuk melakukan pengukuran intensitas cahaya untuk mengetahui tingkat
penerangan umum di tempat kerja tersebut, berapakah titik pengukuran yang
diperlukan? Bagaimanakah mekanisme penentuan titik pengukuran tersebut?
3) Hasil pengukuran intensitas suara pada suatu tempat kerja selama lima menit, diperoleh
hasil sebagaimana pada tabel di bawah ini :
Pembacaan Hasil Pengukuran Intensitas Suara Menit Ke
5 detik ke 1 2 3 4 5
1 80 86 87 88 89
2 84 88 79 86 90
3 82 89 84 85 85
4 89 90 86 89 83
5 90 86 88 90 88
6 87 85 86 84 89
7 85 87 89 87 90
8 86 88 90 89 85
9 87 87 83 79 84
10 88 89 76 87 89
11 89 86 78 82 87
12 90 89 88 87 86
Hitung intensitas sinambung setara dari hasil pengukuran tersebut diatas!
214 Praktik Kerja Industri
Topik 2
Pengawasan Kesehatan Kerja
esehatan Kerja adalah upaya peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan yang
K setinggi-tingginya bagi karyawan di semua jabatan, pencegahan penyimpangan
kesehatan yang disebabkan oleh kondisi karyawan, perlindungan karyawan dari risiko
akibat faktor yang merugikan kesehatan, penempatan dan pemeliharaan karyawan
dalam suatu lingkungan kerja yang mengadaptasi antara karyawan dengan manusia dan
manusia dengan jabatannya. Untuk mencegah timbulnya gangguan kesehatan dan
pencemaran lingkungan di industri, lingkungan kerja industri harus memenuhi standar dan
persyaratan kesehatan agar pekerja dapat melakukan pekerjaan sesuai jenis pekerjaannya
dengan sehat dan produktif.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.02/MEN/1980 tentang
Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja,
menyebutkan bahwa keselamatan kerja yang setinggi-tingginya dapat dicapai bila antara lain
kesehatan tenaga kerja berada dalam taraf yang sebaik-baiknya. Untuk menjamin
kemampuan fisik dan kesehatan tenaga kerja yang sebaik-baiknya perlu diadakan
pemeriksaan kesehatan yang terarah. Pemeriksaan kesehatan kerja tersebut terdiri dari
pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan kesehatan berkala, dan pemeriksaan
kesehatan khusus. Pengurus bertanggung jawab atas biaya yang diperlukan terhadap
pemeriksaan kesehatan berkala atau pemeriksaan kesehatan khusus yang dilaksanakan atas
perintah baik oleh Pertimbangan Kesehatan Daerah ataupun oleh Majelis Pertimbangan
Kesehatan Pusat.
Pemeriksaan Kesehatan sebelum bekerja ditujukan agar tenaga kerja yang diterima
berada dalam kondisi kesehatan yang setinggi-tingginya, tidak mempunyai penyakit menular
yang akan mengenai tenaga kerja lainnya, dan cocok untuk pekerjaan yang akan dilakukan
sehingga keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang bersangkutan dan tenaga kerja yang
lain-lainnya dapat dijamin. Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Kerja meliputi pemeriksaan fisik
lengkap, kesegaran jasmani, rontgen paru-paru (bilamana mungkin) dan laboratorium rutin,
serta pemeriksaan lain yang dianggap perlu.
Pemeriksaan Kesehatan Berkala dimaksudkan untuk mempertahankan derajat
kesehatan tenaga kerja sesudah berada dalam pekerjaannya, serta menilai kemungkinan
adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan seawal mungkin yang perlu dikendalikan dengan
usaha-usaha pencegahan. Pemeriksaan kesehatan berkala bagi tenaga kerja sekurang-
kurangnya 1 tahun sekali kecuali ditentukan lain oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Praktik Kerja Industri 215
Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja. Pemeriksaan Kesehatan Berkala meliputi
pemeriksaan fisik lengkap, kesegaran jasmani, rontgen paru-paru (bilamana mungkin) dan
laboratoriuin rutin serta pemeriksaan lain yang dianggap perlu.
Pemeriksaan Kesehatan khusus dimaksudkan untuk menilai adanya pengaruh-pengaruh
dari pekerjaan tertentu terhadap tenaga kerja atau golongan-golongan tenaga kerja tertentu.
Pemeriksaan Kesehatan Khusus dilakukan pula terhadap:
1. Tenaga kerja yang telah mengalami kecelakaan atau penyakit yang memerlukan
perawatan yang lebih dari 2 (dua minggu).
2. Tenaga kerja yang berusia diatas 40 (empat puluh) tahun atau tenaga kerja wanita dan
tenaga kerja cacat, serta tenaga kerja muda yang melakukan pekerjaan tertentu.
3. Tenaga kerja yang terdapat dugaan-dugaan tertentu mengenai gangguan-gangguan
kesehatannya perlu dilakukan pemeriksaan khusus sesuai dengan kebutuhan.
4. Pemeriksaan Kesehatan Khusus diadakan pula apabila terdapat keluhan-keluhan
diantara tenaga kerja, atau atas pengamatan pegawai pengawas keselamatan dan
kesehatan kerja, atau atas penilaian Pusat Bina Hyperkes dan Keselamatan dan
Balaibalainya atau atas pendapat umum dimasyarakat.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.15/MEN/VIII/2008
tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan, menyatakan bahwa dalam rangka
memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan di tempat kerja
perlu dilakukan pertolongan pertama secara cepat dan tepat. Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan di tempat kerja selanjutnya disebut dengan P3K di tempat kerja, adalah upaya
memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja/buruh dan/atau
orang lain yang berada di tempat kerja, yang mengalami sakit atau cidera di tempat kerja.
Berdasarkan ketentuan tersebut diatas lebih jauh disebutkan bahwa pengusaha wajib
menyediakan petugas P3K dan fasilitas P3K di tempat kerja, serta pengurus wajib
melaksanakan P3K di tempat kerja. Ketentuan lebih rinci terkait petugas P3K, fasilitas P3K dan
pelaksanaan P3K di tempat kerja dapat dilihat pada lampiran dari peraturan diatas.
Petugas P3K di tempat kerja harus memiliki lisensi dan buku kegiatan P3K dari Kepala
Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Petugas P3K dalam
melaksanakan tugasnya dapat meninggalkan pekerjaan utamanya untuk memberikan
pertolongan bagi pekerja/buruh dan/atau orang lain yang mengalami sakit atau cidera di
tempat kerja. Untuk mendapatkan lisensi sebagaimana tersebut diatas seorang petugas P3K
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Bekerja pada perusahaan yang bersangkutan;
Sehat jasmani dan rohani; Bersedia ditunjuk menjadi petugas P3K; dan Memiliki pengetahuan
dan ketrampilan dasar di bidang P3K di tempat kerja yang dibuktikan dengan sertifikat
216 Praktik Kerja Industri
pelatihan. Petugas P3K di tempat kerja mempunyai tugas : Melaksanakan tindakan P3K di
tempat kerja; Merawat fasilitas P3K di tempat kerja; Mencatat setiap kegiatan P3K dalam
buku kegiatan; dan Melaporkan kegiatan P3K kepada pengurus.
Pengurus wajib mengatur tersedianya Petugas P3K pada:
1. Tempat kerja dengan unit kerja berjarak 500 meter lebih sesuai jumlah pekerja/buruh
dan potensi bahaya di tempat kerja;
2. Tempat kerja di setiap lantai yang berbeda di gedung bertingkat sesuai jumlah
pekerja/buruh dan potensi bahaya di tempat kerja;
3. Tempat kerja dengan jadwal kerja shift sesuai jumlah pekerja/buruh dan potensi bahaya
di tempat kerja.
Fasilitas P3K yang harus tersedia pada tempat kerja meliputi :
1. Ruang P3K;
2. Kotak P3K dan isi;
3. Alat evakuasi dan alat transportasi; dan
4. Fasilitas tambahan berupa alat pelindung diri dan/atau peralatan khusus di tempat kerja
yang memiliki potensi bahaya yang bersifat khusus.
Terkait dengan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja, pemerintah dengan Keputusan
Presiden R.I. Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, menyatakan bahwa Jaminan
Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat
pemelihaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang
diberikan kepada setiap orang yang telah membayar membayar iuran atau iurannya dibayar
oleh Pemerintah. Kepesertaan Jaminan Kesehatan tersebut diharapkan adalah seluruh warga
negara Indonesia termasuk didalamnya adalah tenaga kerja yang bekerja disektor industri baik
formal maupun nonformal.
Penyelenggaraan jaminan kesehatan dilaksanakan oleh lembaga berbadan hukum yang
dibentuk oleh pemerintah yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Kepesertaan jaminan kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap sehingga
mencakup seluruh penduduk, tentunya termasuk tenaga kerja di industri. Ditegaskan dalam
Peraturan Presiden diatas, bahwa setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan
pekerjanya sebagai peserta jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar
iuran. Pemberi kerja wajib membayar iuran jaminan kesehatan seluruh peserta yang menjadi
tanggung jawabnya pada setiap bulan.
Setiap peserta dan keluarganya berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang
bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif
dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan
Praktik Kerja Industri 217
kebutuhan medis yang diperlukan. Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas : pelayanan
kesehatan tingkat pertama meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik; pelayanan
kesehatan rujukan tingkat lanjutan; dan pelayanan kesehatan lain.
Pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik
mencakup:
1. Administrasi pelayanan;
2. Pelayanan propotif dan preventif;
3. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
4. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;
5. Pelayanan obet dan bahan medis habis pakai;
6. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;
7. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan
8. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi.
Adapun pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang dapat diperoleh oleh
peserta, mencakup pelayanan rawat jalan dan pelayanan rawat inap mencakup perawatan
inap non intensif, dan perawatan inap di ruang intensif. Pelayanan rawat jalan yang dapat
diterima oleh peserta dan keluarganya mencakup:
1. Administrasi pelayanan;
2. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan
subspesialis;
3. Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis;
4. Pelayanan obat dab bahan medis habis pakai;
5. Pelayanan kesehatan implan;
6. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
7. Rehabilitasi medis;
8. Pelayanan darah;
9. Pelayanan kedokteran forensik; dan
10. Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan.
Seorang tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya di tempat kerja tidak akan
lepas dari kondisi berbahaya yang ada di tempat kerja. Oleh karena itu maka pengusaha wajib
menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kerja di tempat kerja, hal itu sesuai dengan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat
Pelindung Diri. Alat Pelindung Diri (APD) adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan
untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari
potensi bahaya di tempat kerja.
218 Praktik Kerja Industri
Alat Pelindung Diri yang harus disediakan diantaranya adalah Pelindung kepala,
Pelindung mata dan muka, Pelindung telinga, Pelindung pernapasan beserta
perlengkapannya, Pelindung tangan, Pelindung kaki, termasuk Pakaian pelindung, Alat
pelindung jatuh perorangan, dan Pelampung.
Alat pelindung kepala adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi kepala dari
benturan, terantuk, kejatuhan atau terpukul benda tajam atau benda keras yang melayang
atau meluncur di udara, terpapar oleh radiasi panas, api, percikan bahan-bahan kimia, jasad
renik (mikro organisme) dan suhu yang ekstrim. Jenis alat pelindung kepala terdiri dari helm
pengaman (safety helmet), topi atau tudung kepala, penutup atau pengaman rambut, dan
lain-lain.
Alat pelindung mata dan muka adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi
mata dan muka dari paparan bahan kimia berbahaya, paparan partikel-partikel yang melayang
di udara dan di badan air, percikan benda-benda kecil, panas, atau uap panas, radiasi
gelombang elektromagnetik yang mengion maupun yang tidak mengion, pancaran cahaya,
benturan atau pukulan benda keras atau benda tajam. Jenis alat pelindung mata dan muka
terdiri dari kacamata pengaman (spectacles), goggles, tameng muka (face shield), masker
selam, tameng muka dan kacamata pengaman dalam kesatuan (full face masker).
Alat pelindung telinga adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi alat
pendengaran terhadap kebisingan atau tekanan. Jenis alat pelindung telinga terdiri dari
sumbat telinga (ear plug) dan penutup telinga (ear muff).
Alat pelindung pernapasan beserta perlengkapannya adalah alat pelindung yang
berfungsi untuk melindungi organ pernapasan dengan cara menyalurkan udara bersih dan
sehat dan/atau menyaring cemaran bahan kimia, mikro-organisme, partikel yang berupa
debu, kabut (aerosol, uap, asap, gas/fume, dan sebagainya). Jenis alat pelindung pernapasan
dan perlengkapannya terdiri dari masker, respirator, katrit, kanister, Re-breather, Airline
respirator, Continues Air Supply Machine = Air Hose Mask Respirator, tangki selam dan
regulator Self-Contained Underwater Breathing Apparatus (SCUBA), Self-Contained Breathing
Apparatus (SCBA), dan emergency breathing apparatus.
Pelindung tangan (sarung tangan) adalah alat pelindung yang berfungsi untuk
melindungi tangan dan jari-jari tangan dari pajanan api, suhu panas, suhu dingin, radiasi
elektromagnetik, radiasi mengion, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan dan tergores,
terinfeksi zat patogen (virus, bakteri) dan jasad renik. Jenis pelindung tangan terdiri dari
sarung tangan yang terbuat dari logam, kulit, kain kanvas, kain atau kain berpelapis, karet, dan
sarung tangan yang tahan bahan kimia.
Alat pelindung kaki berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa atau berbenturan
dengan benda-benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap
panas, terpajan suhu yang ekstrim, terkena bahan kimia berbahaya dan jasad renik,
Praktik Kerja Industri 219
tergelincir. Jenis Pelindung kaki berupa sepatu keselamatan pada pekerjaan peleburan,
pengecoran logam, industri, kontruksi bangunan, pekerjaan yang berpotensi bahaya
peledakan, bahaya listrik, tempat kerja yang basah atau licin, bahan kimia dan jasad renik,
dan/atau bahaya binatang dan lain-lain.
Pakaian pelindung berfungsi untuk melindungi badan sebagian atau seluruh bagian
badan dari bahaya temperature panas atau dingin yang ekstrim, pajanan api dan benda-benda
panas, percikan bahan-bahan kimia, cairan dan logam panas, uap panas, benturan (impact)
dengan mesin, peralatan dan bahan, tergores, radiasi, binatang, mikro-organisme patogen
dari manusia, binatang, tumbuhan dan lingkungan seperti virus, bakteri dan jamur. Jenis
pakaian pelindung terdiri dari rompi (Vests), celemek (Apron/Coveralls), Jaket, dan pakaian
pelindung yang menutupi sebagian atau seluruh bagian badan.
Alat pelindung jatuh perorangan berfungsi membatasi gerak pekerja agar tidak masuk
ke tempat yang mempunyai potensi jatuh atau menjaga pekerja berada pada posisi kerja yang
diinginkan dalam keadaan miring maupun tergantung dan menahan serta membatasi pekerja
jatuh sehingga tidak membentur lantai dasar. Jenis alat pelindung jatuh perorangan terdiri
dari sabuk pengaman tubuh (harness), karabiner, tali koneksi (lanyard), tali pengaman (safety
rope), alat penjepit tali (rope clamp), alat penurun (decender), alat penahan jatuh bergerak
(mobile fall arrester), dan lain-lain.
Pelampung berfungsi melindungi pengguna yang bekerja di atas air atau dipermukaan
air agar terhindar dari bahaya tenggelam dan atau mengatur keterapungan (buoyancy)
pengguna agar dapat berada pada posisi tenggelam (negative buoyant) atau melayang
(neutral buoyant) di dalam air. Jenis pelampung terdiri dari jaket keselamatan (life jacket),
rompi keselamatan (life vest), rompi pengatur keterapungan (Bouyancy Control Device).
Alat Pelindung Diri wajib digunakan di tempat kerja di mana :
1. Dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan atau
instalasi yang berbahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau
peledakan;
2. Dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau disimpan bahan
atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar, korosif, beracun, menimbulkan
infeksi, bersuhu tinggi atau bersuhu rendah;
3. Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran
rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan perairan, saluran atau
terowongan di bawah tanah dan sebagainya atau di mana dilakukan pekerjaan
persiapan;
4. Dilakukan usaha pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan,
pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan dan lapangan
kesehatan;
220 Praktik Kerja Industri
5. Dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan batu-batuan, gas, minyak, panas bumi,
atau mineral lainnya, baik di permukaan, di dalam bumi maupun di dasar perairan;
6. Dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik di daratan, melalui
terowongan, di permukaan air, dalam air maupun di udara;
7. Dikerjakan bongkar muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun,
bandar udara dan gudang;
8. Dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam air;
9. Dilakukan pekerjaan pada ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan;
10. Dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah;
11. Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena
pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting;
12. Dilakukan pekerjaan dalam ruang terbatas tangki, sumur atau lubang;
13. Terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, gas, hembusan
angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran;
14. Dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah;
15. Dilakukan pemancaran, penyiaran atau penerimaan telekomunikasi radio, radar,
televisi, atau telepon;
16. Dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset yang
menggunakan alat teknis;
17. Dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau disalurkan listrik,
gas, minyak atau air; dan
18. diselenggarakan rekreasi yang memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik.
Pengawasan aspek kesehatan kerja pada pekerja dengan cara memperhatikan aspek
pelayanan kesehatan yang dialami oleh tenaga kerja, sejak tenaga kerja mulai kerja sampai
dengan saat pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja.
Praktik Kerja Industri 221
Tabel 5.17.
PEMANTAUAN PENGAWASAN KESEHATAN KERJA
Nama Industri :
Alamat Industri :
Jenis Industri :
Jumlah Tenaga Kerja : Laki Laki : ......... orang, Perempuan : ....... orang
Petugas Pemantau :
Tanggal Pemantauan :
No Item Pemantauan Ya Tidak Ket.
1. Apakah dilakukan pemeriksaan kesehatan sebelum kerja
2. Apakah dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala
3. Apakah dilakukan pemeriksaan kesehatan khusus
4. Apakah ada petugas P3K sesuai kebutuhan
5. Apakah tersedia kotak P3K sesuai kebutuhan
6. Apakah isi kotak P3K sesuai ketentuan
7. Apakah semua tenaga kerja mengikuti BPJS Kesehatan
8. Apakah semua tenaga kerja mengikuti BPJS
Ketenagakerjaan
9. Apakah tersedia APD yang diperlukan
10. Apakah jumlah APD memenuhi kebutuhan
Mengetahui, Petugas Pengukur
Penanggung Jawab Unit Kerja
.................................................. ..........................................
222 Praktik Kerja Industri
Latihan
Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan
berikut!
1) Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
berpedoman pada apa?
2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.15/MEN/VIII/2008
mengatur tentang apa terkait dengan kesehatan kerja?
3) Apakah yang dimaksud dengan jaminan kesehatan?
Ringkasan
1. Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja terdiri
dari pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan kesehatan berkala, dan
pemeriksaan kesehatan khusus.
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.15/MEN/VIII/2008
tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan, menyatakan bahwa dalam rangka
memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan di tempat
kerja perlu dilakukan pertolongan pertama secara cepat dan tepat. Pertolongan
Pertama Pada Kecelakaan di tempat kerja selanjutnya disebut dengan P3K di tempat
kerja, adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada
pekerja/buruh/ dan/atau orang lain yang berada di tempat kerja, yang mengalami sakit
atau cidera di tempat kerja.
3. Alat Pelindung Diri yang harus disediakan diantaranya adalah Pelindung kepala,
Pelindung mata dan muka, Pelindung telinga, Pelindung pernapasan beserta
perlengkapannya, Pelindung tangan, Pelindung kaki, termasuk Pakaian pelindung, Alat
pelindung jatuh perorangan, dan Pelampung.
Praktik Kerja Industri 223
Tes 2
Kerjakan soal di bawah ini dengan tepat dan cermat!
1) Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja terdiri
dari pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan kesehatan berkala, dan
pemeriksaan kesehatan khusus. Pemeriksaan Kesehatan khusus dimaksudkan untuk
menilai adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan tertentu terhadap tenaga kerja atau
golongan-golongan tenaga kerja tertentu. Pemeriksaan Kesehatan Khusus dilakukan
pula terhadap tenaga kerja dengan kondisi bagaimana ?
2) Berdasarkan ketentuan pengusaha wajib menyediakan petugas P3K dan fasilitas P3K di
tempat kerja, serta pengurus wajib melaksanakan P3K di tempat kerja. Petugas P3K
dalam melaksanakan tugasnya dapat meninggalkan pekerjaan utamanya untuk
memberikan pertolongan bagi pekerja/buruh dan/atau orang lain yang mengalami sakit
atau cidera di tempat kerja. Jelaskan bagaimanakah ketentuan yang mengatur
penempatan petugas P3K di tempat kerja?
3) Setiap peserta BPJS Kesehatan dan keluarganya berhak memperoleh manfaat jaminan
kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis
habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. Pelayanan kesehatan yang
dijamin terdiri atas : pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi pelayanan
kesehatan non spesialistik; pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan; dan
pelayanan kesehatan lain. Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang dapat diterima
meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik mencakup apa saja ?
224 Praktik Kerja Industri
Kunci Jawaban Tes
Test 1
1) Hasil pengukuran indek suhu basah dan bola diperoleh hasil sebagai berikut :
A. Temperatur kering : 31 OC
B. Temperatur basah : 29 OC
C. Temperatur bola : 35 OC
Karena pekerjaan dilakukan pada tempat yang terkena panas matahari secara
terus menerus, maka berarti pekerja pada tempat kerja tersebut terpapar oleh panas
radiasi. Oleh karena itu maka untuk menghitung Indeks Suhu Basan dan Bola
berdasarkan hasil pengukuran diatas menggunakan rumus :
ISBB = 0,7 SBA + 0,2 SB + 0,1 SK
= (0,7 x 29 ) + (0,2 x 35 ) + (0,1 x 31)
= 20,3 + 7 + 3,1
ISBB = 30,4 OC
Jadi Indeks Suhu Basah dan Bola (ISBB) berdasarkan hasil pengukuran diatas
adalah sebesar 30,4OC. Hasil perhitungan ini selanjutnya dibandingkan dengan Nilai
Ambang Batas yang berlaku.
2) Sesuai dengan ukuran ruang tempat kerja yang akan diukur intensitas cahayanya yaitu
panjang 12 meter dan lebar 8 meter, maka luas ruang tempat kerja tersebut adalah 92
m2. Sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pengukuran penerangan umum pengukuran
dilakukan pada titik potong garis horizontal panjang dan lebar ruangan, yang dibedakan
berdasarkan luas ruangan sebagai berikut:
A. Luas ruangan kurang dari 10 meter persegi: titik potong garis horizontal panjang
dan lebar ruangan adalah pada jarak setiap 1 (satu) meter.
B. Luas ruangan antara 10 meter persegi sampai 100 meter persegi: titik potong garis
horizontal panjang dan lebar ruangan adalah pada jarak setiap 3 (tiga) meter.
C. Luas ruangan lebih dari 100 meter persegi: titik potong horizontal panjang dan
lebar ruangan adalah pada jarak 6 meter.
Praktik Kerja Industri 225
Berdasarkan ketentuan di atas, maka untuk menentukan banyaknya titik
pengukuran intensitas pencahayaan guna menghitung penerangan umum, maka
dengan melihat luas ruang tempat kerja 92 m2 maka pedoman yang digunakan adalah
poin b yaitu untuk luas ruangan antara 10 m2 sampai 100 m2.
Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :
A. Buatlah gambar ruang dengan ukuran panjang 12 m dan lebar 8 m
3m 3m 3m 3m
2,5 m
3m
2,5 m
B. Buatlah garis horizontal dan garis vertikal dengan jarak 3 m.
C. Tentukan titik potong antara garis horizontal dengan garis vertikal.
D. Berdasar gambar diatas, maka titik potong yang ditemukan sebanyak 6 (enam).
E. Jadi titik pengukuran intensitas pencahayaan untuk mengukur penerangan umum
pada ruang kerja tersebut ada sebanyak 6 (enam) titik pengukuran, dengan skema
seperti pada diagram di atas.
3) Untuk menghitung intensitas suara sinambung setara berdasarkan hasil pengukuran
sebagaimana tercantum pada soal tes 1 nomor 3, rumus yang digunakan adalah :
1 L1 L2 Ln
Leq = 10 Log{( ) ∑ [ 10 (10) + 10(10) + . . . + 10( 10 ) ]}
T
226 Praktik Kerja Industri
Intensitas suara sinambung untuk hasil pengukuran menit yang ke 1.
5 80 84 82 89 90 87 85
Leq = 10 Log{( ) ∑ [ 10 (10) + 10(10) + 10(10) + 10(10) + 10(10) + 10(10) + 10(10)
60
86 87 88 89 90
+ 10(10) + 10(10) + 10(10) + 10(10) + 10(10) ]}
Leq = 87,3 dB.
Dengan menggunakan rumus yang sama seperti tersebut diatas, untuk hasil
pengukuran menit ke 2, menit ke 3, menit ke 4 dan menit ke 5 diperoleh hasil sebagai
berikut :
Leq menit ke 2 = 87,76 dB
Leq menit ke 3 = 86,19 dB
Leq menit ke 4 = 86,94 dB
Leq menit ke 5 = 87,66 dB
Selanjutnya untuk menghitung intensitas uara sinambung untuk hasil pengukuran
selama 5 (lima) menit, dihitung dengan menggunakan rumus :
1 87,3 87,76 86,19 86,94 87,66
Leq = 10 Log{( ) ∑ [ 10 ( 10 ) + 10( 10 ) + 10( 10 ) + 10( 10 ) + 10( 10 ) ]}
5
Leq = 87,20 dB
Jadi intensitas suara hasil pengukuran selama 5 (lima) menit sebagaimana pada
tabel hasil pengukuran pada tes 1 soal nomor 3, setara dengan 87,20 dB. Hasil
penghitungan ini selanjutnya dibandingkan dengan Nilai Ambang Batas yang berlaku.
Test 2
1) Pemeriksaan Kesehatan khusus dimaksudkan untuk menilai adanya pengaruh-pengaruh
dari pekerjaan tertentu terhadap tenaga kerja atau golongan-golongan tenaga kerja
tertentu. Pemeriksaan Kesehatan Khusus dilakukan pula terhadap tenaga kerja dengan
kondisi :
A. Tenaga kerja yang telah mengalami kecelakaan atau penyakit yang memerlukan
perawatan yang lebih dari 2 (dua minggu).
Praktik Kerja Industri 227
B. Tenaga kerja yang berusia diatas 40 (empat puluh) tahun atau tenaga kerja wanita
dan tenaga kerja cacat, serta tenaga kerja muda yang melakukan pekerjaan
tertentu.
C. Tenaga kerja yang terdapat dugaan-dugaan tertentu mengenai gangguan-
gangguan kesehatannya perlu dilakukan pemeriksaan khusus sesuai dengan
kebutuhan.
D. Pemeriksaan Kesehatan Khusus diadakan pula apabila terdapat keluhan-keluhan
diantara tenaga kerja, atau atas pengamatan pegawai pengawas keselamatan dan
kesehatan kerja, atau atas penilaian Pusat Bina Hyperkes dan Keselamatan dan
Balai-balainya atau atas pendapat umum dimasyarakat.
2) Dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh yang mengalami
kecelakaan di tempat kerja perlu dilakukan pertolongan pertama secara cepat dan
tepat. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di tempat kerja selanjutnya disebut
dengan P3K di tempat kerja, adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara
cepat dan tepat kepada pekerja/buruh dan/atau orang lain yang berada di tempat kerja,
yang mengalami sakit atau cidera di tempat kerja. Penempatan petugas P3K di tempat
kerja diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
A. Tempat kerja dengan unit kerja berjarak 500 meter lebih sesuai jumlah
pekerja/buruh dan potensi bahaya di tempat kerja;
B. Tempat kerja di setiap lantai yang berbeda di gedung bertingkat sesuai jumlah
pekerja/buruh dan potensi bahaya di tempat kerja;
C. Tempat kerja dengan jadwal kerja shift sesuai jumlah pekerja/buruh dan potensi
bahaya di tempat kerja.
Adapun fasilitas P3K yang harus tersedia pada tempat kerja meliputi :
A. Ruang P3K;
B. Kotak P3K dan isi;
C. Alat evakuasi dan alat transportasi; dan
D. Fasilitas tambahan berupa alat pelindung diri dan/atau peralatan khusus di tempat
kerja yang memiliki potensi bahaya yang bersifat khusus.
228 Praktik Kerja Industri
3) Pelayanan kesehatan yang dijamin bagi peserta BPJS Kesehatan terdiri atas : pelayanan
kesehatan tingkat pertama meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik; pelayanan
kesehatan rujukan tingkat lanjutan; dan pelayanan kesehatan lain. Pelayanan kesehatan
tingkat pertama yang dapat diterima meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik
mencakup :
A. Administrasi pelayanan;
B. Pelayanan propotif dan preventif;
C. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
D. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;
E. Pelayanan obet dan bahan medis habis pakai;
F. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;
G. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan
H. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi.
Praktik Kerja Industri 229
Glossary
Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja adalah nilai atau pedoman yang harus dipenuhi dan
dilaksanakan di tempat kerja.
Nilai Ambang Batas (NAB) adalah standar faktor bahaya di tempat kerja sebagai
kadar/intensitas rata-rata tertimbang waktu (time weighted
average) yang dapat diterima tenaga kerja tanpa
mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan, dalam
pekerjaan sehari-hari untuk waktu tidak melebihi 8 jam
sehari atau 40 jam seminggu.
Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka,
bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang
sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha
dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
Faktor fisika adalah faktor di dalam tempat kerja yang bersifat fisika yang
terdiri dari iklim kerja, kebisingan, getaran, gelombang
mikro, sinar ultra ungu, dan medan magnet.
Faktor kimia adalah faktor di dalam tempat kerja yang bersifat kimia yang
meliputi bentuk padatan (partikel), cair, gas, kabut, aerosol
dan uap yang berasal dari bahan-bahan kimia.
Faktor biologi adalah nilai maksimal bakteri dan jamur yang disyaratkan
yang terdapat di udara ruang kantor industri.
230 Praktik Kerja Industri
Iklim kerja adalah hasil perpaduan antara suhu, kelembaban,
kecepatan gerakan udara dan panas radiasi dengan tingkat
pengeluaran panas dari tubuh tenaga kerja sebagai akibat
pekerjaannya, yang dimaksudkan dalam peraturan ini
adalah iklim kerja panas.
Kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber
dari alatalat proses produksi dan/atau alat-alat kerja yang
pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan
pendengaran.
Indikator Pajanan Biologi (IPB) adalah nilai acuan konsentrasi bahan kimia yang
terabsorpsi, hasil metabolisme (metabolit) bahan kimia
yang terabsorpsi, atau efek yang ditimbulkan oleh bahan
kimia tersebut yang digunakan untuk mengevaluasi pajanan
biologi dan potensi risiko kesehatan pekerja.
Praktik Kerja Industri 231
Daftar Pustaka
Keputusan Presiden R.I. Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan
Kesehatan Lingkungan Kerja Industri.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.15/MEN/VIII/2008 tentang
Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat
Pelindung Diri.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.02/MEN/1980 tentang
Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.13/MEN/X/2011 tentang Nilai
Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di tempat kerja.
Standar Nasional Indonesia 16-7061-2004 tentang pengukuran iklim kerja (panas) dengan
parameter indeks suhu basah dan bola.
Standar Nasional Indonesia 16-7062-2004 tentang Pengukuran intensitas penerangan di
tempat kerja.
Standar Nasional Indonesia 7231:2009 tentang Pengukuran kebisingan di tempat kerja..
Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
232 Praktik Kerja Industri
Bab 6
PELAKSANAAN EVALUASI PRAKTIK
KERJA INDUSTRI
Hadi Suryono, ST., MPPM.
Yulianto, S.Pd., M.Kes.
Pendahuluan
elaksanaan evaluasi praktek kerja industri dilaksanakan setelah dilakukan kegiatan
P pengawasan atau penilaian sanitasi industri dan K3. Untuk melakukan evaluasi, Saudara
harus meninjau kembali metoda penilaian untuk memperoleh hasil pengukuran. Untuk
melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian yang diperoleh dengan cara pengukuran
melalui instrument (observasi, wawancara), evaluasi dilakukan dengan menghitung skor
penilaian sesuai metoda yang tertera dalam instrument penilaian. Apabila hasil data yang
diperoleh dilakukan dengan pengukuran menggunakan alat, maka Saudara harus mengolah
data sesuai dengan prosedur yang ditentukan, kemudian hasilnya dibandingkan dengan stanar
baku mutu.
Hasil akhir dari evaluasi adalah:
1. Kesimpulan kondisi hasil pemeriksaan baik yang dilakukan melalui inspeksi dengan
instrument, atau melalui pengukuran menggunakan alat ukur terkait. Isi kesimpulan
menggambarkan kondisi lingkungan industri yang diukur baik secara fisik, kimia,
ataupun bakteriologis untuk parameter polutan pencemar yang ingin diperiksa.
2. Untuk hasil penilaian secara manajerial, kesimpulan berisi kriteria-kriteria yang dibuat
berdasarkan pedoman atau peraturan perundangan yang berlaku.
3. Membuat rekomendasi bagi perusahaan atau industri tempat kerja praktik untuk
melakukan perbaikan-perbaikan terkait hasil temuan selama praktik kerja industri.
Praktik Kerja Industri 233
Topik 1
Evaluasi Hasil Pengawasan Sanitasi Industri
valuasi hasil pengawasan Sanitasi Industri bertujuan untuk mengukur tingkat bahaya
E risiko yang diakibatkan kegiatan sanitasi di industri tempat praktek. Tingkat bahaya risiko
diukur dengan membandingkan hasl pengukuran dengan standar baku mutu faktor
lingkungan yang diukur. Jika didapatkan hasil yang melebihi standar maka diperlukan
tindakan pengendalian lebih ketat terkait proses, polutan pencemar, atau menajemen
pengelolaan terkait isu yang diperoleh selama pengukuran. Kegiatan evaluasi terhadap
sanitasi industri dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan, yaitu:
A. PENGOLAHAN HASIL PENGAWASAN
Kegiatan pengawasan yang berbentuk penilaian dengan instrumen dilakukan skoring
berdasarkan metode skoring yang ditentukan.
Metode skoring bisa dilakukan dengan memberi bobot dan nilai terhadap item-item
penilaian, kemudian membuat kriteria penilaian berdasarkan jumlah skor penilaian yang
diperoleh dengan mengalikan bobot dan nilai yang ditentukan. Kriteria penilaian bisa terdiri
dari tiga kategori, misalnya baik, sedang dan kurang.
Metode skoring yang lain dan lebih sederhana adalah dengan membuat kriteria
penilaian berdasarkan persentase nilai yang diperoleh dari menghitung jumlah item yang
memenuhi syarat dibagi dengan total item penilaian dikalikan 100%. Kategori penilaian bisa
dibuat tiga jenis, yaitu baik, sedang, dan kurang. Tidak ada teori yang menentukan jumlah
persentase untuk kategori baik, sedang, atau kurang, namun dapat menggunakan pendekatan
bahwa persentase untuk item penilaian yang langsung berhubungan dengan bahaya terhadap
kesehatan sampai meninggalnya seseorang harus dibuat lebih ketat.
B. MEMBANDINGKAN DENGAN STANDAR BAKU MUTU ATAU NAB
Sistem ini digunakan untuk pengukuran polutan pencemar baik yang diukur terhadap
faktor lingkungan fisik, kimia, bakteriologis, maupun radiologis.
Sebagaimana telah disampaikan pada bab sebelumnya penggunaan bahwa standar baku
mutu yang digunakan harus dilakukan secara hierarkis, yaitu bila ada peraturan regional
misalnya perda setempat atau misalnya Peraturan Gubernur harus digunakan terlebih dahulu.
234 Praktik Kerja Industri
Jika tidak ada peraturan daerah yang bisa digunakan untuk parameter pencemar yang diukur
baru menggunakan peraturan nasional, misalnya Permenkes, Kepmenkes, Permenaker,
Permen LH, dan sebagainya. Apabilan masih tidak ditemukan peraturan tingkat nasional baru
bisa menggunakan peraturan yang berlaku secara internasional. Beberapa Peraturan tingkat
nasional yang bisa digunakan sebagai Standar Baku Mutu untuk aspek Sanitasi Industri,
misalnya:
1. Permenkes No. 70 Tahun 2016 Standar Tentang Persyaratan Lingkungan Kerja Industri.
2. Permen LH No. 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah
3. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracum
4. Dan lain-lain.
Di bagian akhir bab eveluasi ini Saudara harus menyusun tindak lanjut yang akan
dijadikan pedoman perusahaan dalam memperbaiki kekurangan atau kelemahan yang
menjadi temuan selama Saudara melakukan praktik kerja industri. Hal tersebut merupakan
masukan bagi perusahaan yang merupakan manfaat yang diperoleh atas pelaksanaan praktik
kerja industri yang Saudara lakukan.
Tindak lanjut yang dibuat berupa rekomendasi yang tertuang dalam laporan hasil
kegiatan praktik kerja industri. Sudah barang tentu perusahaan akan melakukan rekomendasi
yang Saudara berikan sesuai dengan sumber daya yang ada di perusahaan tersebut. Namun
setidaknya Saudara telah melakukan tindakan pencegahan atau pengendalian terhadap
kecelakaan kerja baik yang diakibatkan oleh kondisi sanitasi yang tidak memenuhi syarat
maupun akibat kondisi lingkungan kerja yang tidak mendukung.
Rekomendasi yang dibuat disusun secara sequence atau berurutan sebagaimana
rencana sasaran pengawasan sanitasi industri dan K3 yang tersusun dalam Bab 2, yaitu sebagai
berikut:
C. SASARAN PENGAWASAN SANITASI INDUSTRI
1. Penyediaan air bersih
2. Pengolahan limbah cair
3. Penyehatan tanah adan
4. Pengelolaan sampah
5. Penyehatan makanan dan minuman
6. Penyehatan udara
7. Pengendalian vector
8. Housekeeping
Praktik Kerja Industri 235
9. Jamban dan peturasan
10. Fasilitas cuci tangan
D. RENCANA SASARAN PENERAPAN K3
1. Identifikasi risiko atau bahaya terjadinya kecelakaan kerja
2. Identifikasi faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja
3. Penerapan manajemen risiko di industri tempat kerja praktik
Latihan
Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan
berikut!
Lakukan evaluasi terhadap penyediaan air bersih di tempat praktik kerja industri sehingga
diperoleh hasil akhir evaluasi tentang variabel tersebut!
Langkah 1 : Lakukan pengisian formulir pengawasan penyediaan air bersih dengan teknik
pengisian yang telah ditentukan sebagaimana tercantum di Bab 3 sebagai
berikut:
236 Praktik Kerja Industri
LEMBAR CHECKLIST
PENGAWASAN PENYEDIAAN AIR BERSIH
Nama Perusahaan : PT. JASA TIRTA
Alamat : Jl. ciliwung
Kabupaten/Kota : Surabaya
Provinsi : Jawa Timur
Jenis Peruntukan Air : Hygiene-sanitasi
Tanggal Pengawasan : 22 Januari 208
ADA / DIPERIKSA
NO PARAMETER TIDAK KET
ADA TIDAK
BERLAKU
1. Fisik
a. Kekeruhan V MS
b. Warna V MS
c. Zat padat terlarut (TDS) V
d. Suhu V MS
e. Rasa V MS
f. Bau V MS
2. Biologi
a. Total coliform V MS
b. E. coli V MS
3. Kimia wajib
a. pH V MS
b. Besi V MS
c. Fluorida V MS
d. Kesadahan V MS
Praktik Kerja Industri 237
ADA / DIPERIKSA
NO PARAMETER TIDAK KET
ADA TIDAK
BERLAKU
e. Mangan V MS
f. Nitrat, sebagai N V MS
g. Nitrit, sebagai N V MS
h. Sianida V MS
i. Diterjen V MS
j. Pestisida total V MS
Kimia tambahan
a. Air raksa V MS
b. Arsen V MS
c. Kadmium V MS
d. Kromium (valensi 6) V MS
e. Selenium V MS
f. Seng V MS
g. Sulfat V MS
h. Timbal V TMS
i. Benzene V MS
j. Zat organik (KMnO4) V MS
4. Tidak ada koneksi silang dengan pipa air
limbah di bawah permukaan tanah (jika air V MS
bersumber dari sarana air perpipaan)
5. Sumber air tanah non perpipaan,
sarananya terlindung dari sumber
V MS
kontaminasi baik limbah domestik maupun
industri.
238 Praktik Kerja Industri
ADA / DIPERIKSA
NO PARAMETER TIDAK KET
ADA TIDAK
BERLAKU
6. Tidak menjadi tempat berkembangbiaknya
V MS
vektor dan binatang pembawa penyakit
7. Jika melakukan pengolahan air secara
kimia, maka jenis dan dosis bahan kimia V MS
harus tepat
8 Jika menggunakan kontainer sebagai
penampung air harus dibersihkan secara V
berkala minimum 1 kali dalam seminggu.
Penanggung Jawab Petugas Pengawasan
........................................... .................................................
Langkah 2 : Buat kesimpulan hasil evaluasi dengan membandingkan standar baku mutu untuk
parameter yang diukur, atau membandingkan dengan teori jika penilaian
dilakukan secara observasi atau pengamatan kondisi objek yang diamati.
Untuk hasil penilaian yang dilakukan berdasarkan check list di atas maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1) Hampir semua variabel yang diperiksa secara fisik, kimia maupun bakteriologis sudah
memenuhi persyaratan standar baku mutu.
2) Beberapa parameter tidak dilakukan pemeriksaan karena parameter tersebut tidak
dilaksanakan dalam sistem penyediaan air bersih di industri lokasi praktik.
3) Sumber air non perpipaan di lokasi kerja praktek berasal dari sumur gali, tidak
terkontaminasi oleh polutan pencemar.
4) Sarana sumber air bersih berasal dari PDAM sehingga tidak dilakukan pemeriksaan
perpipaan silang dengan air limbah.
Praktik Kerja Industri 239
Ringkasan
Pada prinsipnya pelaksanaan evaluasi praktek kerja industri dilakukan melalui 2 (dua)
metode, yaitu:
1. Penilaian menggunakan instrument inspeksi sanitasi dilakukan melalui metode skoring,
untuk materi penilaian yang dilakukan dengan wawancara atau observasi.
2. Penilaian dengan metode pengukuran dilakukan dengan membandingkan terhadap NAB
atau Standar Baku Mutu menggunakan NAB atau Standar Baku Mutu baik yang
dikeluarkan oleh Pemda atau regional, Peraturan tingkat nasional dan atau tingkat
internasional.
3.
Tes Uraian
Susunlah secara singkat langkah-langkah evaluasi pengawasan terhadap hasil penilaian
Sanitasi pada kegitan praktik kerja Industri !
Penilaian Ketuntasan
A. PENILAIAN KETUNTASAN TERHADAP INDUSTRI TEMPAT PRAKTIK
Penilaian ketuntasan dilakukan dengan membuat kriteria penilaian terhadap semua
aspek yang dinilai. Untuk penilaian yang didapat dari hasil wawancara atau observasi bisa
dibuat kriteria penilaian, misalnya Kriteria Baik, apabila skor penilaian = >75%, SEDANG, bila
skor penilaian = 60-74%, KURANG, apabila skor < 60%. Sedangkan untuk penilaian parameter
yang diperoleh dengan cara mengukur, hasilnya langsung dibandingkan dengan standar baku
mutu. Langkah terakhit adalah dengan membuat kesimpulan.
B. PENILAIAN KETUNTASAN TERHADAP PESERTA DIDIK
Penilaian yang diperoleh dari hasil evaluasi Topik 1 ini dikatakan tuntas, apabila :
1. Saudara telah menyelesaikan penilaian terhadap semua aspek penilaian
2. Telah membuat kesimpulan hasil evaluasi berdasarkan teori-teori terkait atau dengan
membandingkan dengan standar baku mutu terhadap parameter yang diukur.
240 Praktik Kerja Industri
Tes 1
Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar!
1) Metode evaluasi penilaian sanitasi industri dilakukan dengan 2 langkah, yaitu....
A. Melakukan penilaian dan membuat kesimpulan.
B. Melakukan perhitungan dan memberikan rekomendasi
C. Menilai sikap dan tindakan karyawan di industri
D. Menilai dengan kuesioner dan membandingkan dengan standar baku mutu
E. Menghitung dengan skoring dan membandingkan dengan teori terkait
2) Bagaimanakah cara melakukan evaluasi terhadap aspek manajerial, misalnya sistem
pengelolaan sanitasi industri?
A. Dengan membandingkan standar baku mutu
B. Menghitung skor penilaian kemudian memasukkan kedalam kriteria yang dibuat,
kemudian membuat kesimpulan.
C. Membandingkan dengan standar bakumutu, kemudian membuat kesimpulan
D. Menganalisis hasil dan membuat rekomendasi
E. Membuat rekomendasi hasil pengukuran
Praktik Kerja Industri 241
Topik 2
Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko
K3 Industri
U
ntuk memahami Evaluasi terhadap manajemen Risiko K3, Saudara harus mempelajari
lagi Manajemen Risiko pada mata Kuliah K3 pada Sub Bab Manajemen Risiko.
Tahapan penilaian manajemen risiko dilakukan terhadap 4 (empat) kegiatan, yaitu:
1. Identifikasi Risiko
2. Analisa Risiko
3. Penilaian/Penanganan risiko
4. Pengendalian Risiko
Penilaian Risiko dapat dilakukan oleh:
1. Pengawas ketenagakerjaan, manajer/Supervisor/Ahli K3 di perusahaan
2. Dapat dilakukan oleh pihak ketiga
3. Kualifaikasi yang dipenuhi adalah:
a. Memahami MSDS/Label/Informasi di tempat kerja
b. Memaqhami perudangan-undangan K3
c. Memiliki keahlian dibidang K3
Pemantapan Konteks dalam manajemen risiko adalah sebagai berikut:
1. Konteks Strategik : Assesmen Internal dan eksternal unit
2. Konteks Organisasi : Assesmen Terhadap Manajemen dan Organisasi
a. Manajemen melibatkan dalam pengambilan keputusan
b. Terkait dengan kebijakan organisasi secara keseluruhan
c. Terkait dengan alokasi sumber daya (personil, finansial, dan lain-lain)
3. Konteks Pengelolaan Risiko : Assesmen Terhadap ruang lingkup yang lebih besar sampai
dengan pemerintah
Untuk memperoleh gambaran lebih jelas Saudara perhatikan aspek-aspek pengelolaan
manajemen risiko, lihat diagram berikut:
242 Praktik Kerja Industri
Tahapan Manajemen Risiko
Konteks PEMANTAUAN KONTEKS
Strategis
Konteks
Organisasi
Konteks Identifikasi Bahaya Risiko
Pengelolaan MONITOR &
REVIEW
Analisis Risiko
Penilaian Risiko
Pengendalian Risiko
A. IDENTIFIKASI RISIKO
Tahap pertama dalam kegiatan manajemen risiko dimana kita melakukan identifikasi
bahaya yang terdapat dalam suatu kegiatan atau proses.
Ada tiga pertanyaan yang dapat dipakai sebagai panduan :
1. Apakah ada sumber untuk menimbulkan cedera atau loss ?
2. Target apa saja yang terkena atau terpengaruh bahaya ?
3. Bagaimana mekanisme cedera atau loss dapat timbul?
1. Sumber bahaya di tempat kerja berasal dari:
a. Bahan atau material
b. Alat atau mesin
c. Metode atau cara kerja
d. Lingkungan kerja
Praktik Kerja Industri 243
Jenis bahaya risiko di tempat Kerja:
a. FISIKA: Bising, radiasi, laser, cahaya dan lain-lain;
b. KIMIA: bahan-bahan kimia, limbah B3 dan lain-lain;
c. ERGONOMI: Sistem kerja, angkat barang dan lain-lain;
d. PSIKOSOSIAL; stress, kerja shift;
e. BIOLOGI: serangga, bakteri, virus, dan lain-lain.
2. Target yang mungkin terkena atau terpengaruh sumber bahaya:
a. Manusia
b. Produk
c. Peralatan atau fasilitas
d. Lingkungan
e. Proses
f. Reputasi
g. Sarana atau prasarana
3. Teknik Identifikasi bahaya:
a. Inspeksi
b. Pemantauan atau survei
c. Audit
d. Kuesioner
e. Data-data statistik
B. ANALISIS RISIKO
Dalam analisa risiko dikenal 2 (dua) istilah:
1. Peluang (Probability)
Yaitu kemungkinan terjadinya suatu kecelakaan atau kerugian ketika terpajan dengan
suatu bahaya, misalnya:
a. Peluang orang jatuh karena melewati jalan licin
b. Peluang untuk tertusuk jarum
c. Peluang tersengat listrik
d. Peluang supir menabrak
244 Praktik Kerja Industri
2. Akibat (Consequences)
yaitu tingkat keparahan atau kerugian yang mungkin terjadi dari suatu kecelakaan atau
loss akibat bahaya yang ada. Hal ini bisa terkait dengan manusia, properti, proses, lingkungan,
dan lain-lain. Contohnya Fatality atau kematian, Cacat, Perawatan medis, P3K.
Lebih jelasnya dalam menyusun klasifikasi risiko yang ditemukan terkait cara
penanganan risiko, perhatikan tabel di bawah ini:
Matriks probability dan consequences bagi risiko yang ditemukan di industri
Consequeces First Aid Lost time Several Fatality /
Injury days off Disability
Probability work
Very likely +++ M H VH VH
Could happen regularly
Likely ++ L M H VH
Could
happenOccasionaly
Unlikely + VL L M H
Could happen but
Very unlikely VL VL L M
Could happen but prob.
Never will
VH : very high/ekstrim : Stop, perbaiki saat itu juga
H : high / tinggi : Perlu perbaikan dalam 24 jam
M : medium : Perlu perbaikan dalam 3 hari
L : low / rendah : Perlu perbaikan dalam 7 hari
VL : very low / dapat diabaikan : Tidak perlu tindakan khusus
Praktik Kerja Industri 245
Ada 3 Cara Dalam Penilaian Risiko Yaitu :
a. Kualitatif, metode ini menganalisa dan menilai suatu risiko dengan cara
membandingkan terhadap suatu diskripsi atau uraian dari parameter (peluang dan
akibat) yang digunakan. Umumnya metode matriks dipakai
b. Semi kuantitatif (contoh: pembobotan atau rangking), metode ini pada prinsipnya
hampir sama dengan analisa kualitatif, perbedaannya pada metode ini uraian atau
deskripsi dari parameter yang ada dinyatakan dengan nilai atau skore tertentu
c. Kuantitatif, metode ini dilakukan dengan menentukan nilai dari masing-masing
parameter yang didapat dari hasil analisa data-data yang representatif
C. PENILAIAN ATAU PENANGANAN RISIKO
1. Risiko yang Dapat Diterima
Menentukan suatu risiko dapat diterima akan tergantung kepada penilaian atau
pertimbangan dari suatu organisasi berdasarkan :
a. Tindakan pengendalian yang telah ada
b. Sumber daya (finansial, SDM, fasilitas, dan lain-lain)
c. Regulasi atau standar yang berlaku
d. Rencana keadaan darurat
e. Catatan atau data kecelakaan terdahulu, dan lain-lain
Catatan: walau suatu risiko masih dapat diterima tapi tetap harus dipantau atau dimonitor.
2. Risiko yang Tidak Dapat Diterima
Bila suatu risiko tidak dapat diterima maka harus dilakukan upaya penanganan risiko
agar tidak menimbulkan kecelakaan atau kerugian. Bentuk tindakan penanganan risiko dapat
dilakukan sebagai berikut :
a. Hindari risiko
b. Kurangi atau minimalkan risiko
c. Transfer risiko
d. Terima risiko
D. PENGENDALIAN RISIKO K3
Secara hierarki pengendalian terhadap risiko dapat dibagi ke dalam beberapa tahap
sebagai berikut:
246 Praktik Kerja Industri
1. Eliminasi
Menghilangkan suatu bahan atau tahapan proses berbahaya
2. Substitusi
a. Mengganti bahan bentuk serbuk dengan bentuk pasta
b. Proses menyapu diganti dengan vakum
c. Bahan solvent diganti dengan bahan deterjen
d. Proses pengecatan spray diganti dengan pencelupan
3. Rekayasa Teknik
a. Pemasangan alat pelindung mesin (mechin guarding)
b. Pemasangan general dan local ventilation
c. Pemasangan alat sensor otomatis
4. Pengendalian Administratif, meliputi:
a. Pemisahan lokasi
b. Pergantian shift kerja
c. Pembentukan sistem kerja
d. Pelatihan karyawan
5. Alat Pelindung Diri, terdiri dari:
a. Helmet
b. Safety Shoes
c. Ear plug atau muff
d. Safety goggles
e. Masker
f. Breathing apparatus dan lainnya.
Setelah Saudara memahami tahapan-tahapan penilaian atau evaluasi manajemen risiko
selanjutnya lakukan urutan tahapan evaluasi sebagai berikut:
1. Teliti apakah perusahaan atau industri melakukan identifikasi risiko dengan baik. Yang
dimaksud identifikasi risiko dengan baik adalah melalkukan identifikasi risiko bahaya
terhadap semua jenis risiko dari pelaksanaan kegiatan mulai dari penyiaapan alat,
bahan, penggunaan alat atau bahan, proses produksi, packing, sampai dengan
pendistribusian.
2. Apakah perusahaan telah menganalisis risiko yang ditemukan dan menyusun sasaran
prioritas terhadap penanganan risiko. Sasaran prioritas disusun untuk menyesuaikan
Praktik Kerja Industri 247
sumber daya yang mampu disediakan perusahaan setelah dilakukan dilakukan analisis
risiko dan telah dilakukan klasifikasi risiko bahaya di industri atau perusahaan tempat
kerja magang.
3. Apakah perusahaan melakukan pengendalian risiko berdasarkan prioritas yang disusun
atau melaksanakan pengendalian semua risiko yang timbul dan dapat mempengaruhi
turunnya produktivitas kerja.
4. Apakah perusahaan melakukan tinjauan terhadap aspek pengendalian dan
memperbaruinya jika terjadi perubahan akibat adanya kamjuan teknologi atau akibat
lainnya.
Latihan
Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan
berikut!
1) Mengevaluasi Manajemen Risiko pada industri
a. Langkah-1 : Mengevaluasi hasil penilaian atau pengawasan manajemen risiko
Jika berdasarkan identifikasi dan analisis risiko (yang telah dilakukan di Bab 5) ternyata
industri memiliki tingkat bahaya yang tinggi atau relatif tinggi, maka harus ada pengendalian
risiko sebaik-baiknya oleh pihak manajemen K3. Evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen
risiko dapat dilakukan dengan meninjau kembali hasil penilaian akhir terhadap manajemen
risiko. Kemudian membuat kriteria keberhasilan terhadap hasil yang diperoleh tersebut.
Kriteria dapat dibuat sebagai berikut:
a) Baik, apabila skor penilaian > 75%
b) Sedang, apabila skor penilaian 65-74%
c) Kurang, bila skor penilaqian < 65%
Persentase nilai diperoleh dengan menghitung jumlah pernyataan-pernyataan yang
benar tentang manajemen risiko, dibagi dengan total pernyataan dikalikan dengan 100%
∑ 𝐵𝐸𝑁𝐴𝑅
𝑅𝑢𝑚𝑢𝑠 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛 = × 100%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑡𝑒𝑚 𝑃𝑒𝑟𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛
248 Praktik Kerja Industri
b. Langkah-2 : Membuat kesimpulan berdasarkan kriteria yang telah dibuat.
Cara membuat kesimpulan dengan cara memasukkan skor penilaian terhadap kriteria
yang telah dibuat seperti di atas. Misalnya hasil skor penilaian = 82%, maka dapat disimpulkan
bahwa pelaksanaan Manajemen Risiko di PT Kalibata dikategorikan BAIK. Beberapa
rekomendasi dapat dibuat berdasarkan hasil temuan yang kurang dalam penilaian.
Ringkasan
Tahapan penilaian manajemen risiko dilakukan terhadap 4 (empat) kegiatan, yaitu:
1. Identifikasi Risiko
2. Analisa Risiko
3. Penilaian/Penanganan risiko
4. Pengendalian Risiko
Penilaian Risiko dapat dilakukan oleh:
1. Pengawas ketenagakerjaan, manajer/Supervisor/Ahli K3 di perusahaan
2. Dapat dilakukan oleh pihak ketiga
3. Kualifaikasi yang dipenuhi adalah:
a. Memahami MSDS/ Label/ Informasi di tempat kerja
b. Memahami perudangan-undangan K3
c. Memiliki keahlian dibidang K3
Pengendalian Risiko K3
Secara hierarki pengendalian terhadap risiko dapat dibagi ke dalam beberapa tahap
sebagai berikut:
1. Eliminasi
Menghilangkan suatu bahan atau tahapan proses berbahaya
2. Substitusi
a. Mengganti bahan bentuk serbuk dengan bentuk pasta
b. Proses menyapu diganti dengan vakum
c. Bahan solvent diganti dengan bahan deterjen
d. Proses pengecatan spray diganti dengan pencelupan
Praktik Kerja Industri 249
3. Rekayasa Teknik
a. Pemasangan alat pelindung mesin (mechin guarding)
b. Pemasangan general dan local ventilation
c. Pemasangan alat sensor otomatis
4. Pengendalian Administratif, meliputi:
a. Pemisahan lokasi
b. Pergantian shift kerja
c. Pembentukan sistem kerja
d. Pelatihan karyawan
5. Alat Pelindung Diri, terdiri dari:
a. Helmet
b. Safety Shoes
c. Ear plug atau muff
d. Safety goggles
e. Masker
f. Breathing apparatus dan lainnya.
Tes Uraian
1) Sebutkan 4 (empat) tahapan dalam mengevaluasi manajemen risiko !
2) Siapakah yang dapat menilai penerapan manajemen risiko, dan jelaskan kualifikasinya!
3) Jelaskan bagaimanakah tindak lanjut setelah dilakukan kegiatan evaluasi atau penilaian
risiko oleh indsutri ?
250 Praktik Kerja Industri
Kunci Jawaban Tes
Tes Uraian 1
Langkah 1 : Melakukan pengisian formulir pengawasan penyediaan air bersih dengan teknik
pengisian yang telah ditetapkan.
Langkah 2 : Membuat kesimpulan hasil evaluasi dengan membandingkan standar baku mutu
untuk parameter yang diukur, atau membandingkan dengan teori jika penilaian
dilakukan secara observasi atau pengamatan kondisi objek yang diamati.
Tes Uraian 2
1) Tahapan penilaian manajemen risiko dilakukan terhadap 4 (empat) kegiatan, yaitu:
a) Identifikasi Risiko
b) Analisa Risiko
c) Penilaian atau Penanganan risiko
d) Pengendalian Risiko
2) Yang dapat menilai manajemen risiko adalah
a) Pengawas ketenagakerjaan, manajer/Supervisor/Ahli K3 di perusahaan
b) Dapat dilakukan oleh pihak ketiga
c) Kualifaikasi yang dipenuhi adalah:
(1) Memahami MSDS/ Label/ Informasi di tempat kerja
(2) Memahami perudangan-undangan K3
(3) Memiliki keahlian dibidang K3
3) Tindak lanjut setelah dilakukan penilaian manajemen risiko adalah melakukan
pengendalian risiko berdasarkan tingkat risiko yang ditemukan.
Secara hierarki pengendalian terhadap risiko dapat dibagi ke dalam beberapa tahap,
sebagai berikut:
a) Eliminasi
Menghilangkan suatu bahan/tahapan proses berbahaya
b) Substitusi
(a) Mengganti bahan bentuk serbuk dengan bentuk pasta
(b) Proses menyapu diganti dengan vakum
(c) Bahan solvent diganti dengan bahan deterjen
(d) Proses pengecatan spray diganti dengan pencelupan
Praktik Kerja Industri 251
c) Rekayasa Teknik
(a) Pemasangan alat pelindung mesin (mechin guarding)
(b) Pemasangan general dan local ventilation
(c) Pemasangan alat sensor otomatis
d) Pengendalian Administratif, meliputi:
(a) Pemisahan lokasi
(b) Pergantian shift kerja
(c) Pembentukan sistem kerja
(d) Pelatihan karyawan
e) Alat Pelindung Diri, terdiri dari:
(a) Helmet
(b) Safety Shoes
(c) Ear plug atau muff
(d) Safety goggles
(e) Masker
252 Praktik Kerja Industri
Topik 3
Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen
K3 Industri
P ada topik ini Saudara akan melakukan evaluasi terhadap penerapan System Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang dilaksanakan berdasarkan PP No. 50
Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Untuk dapat mengevaluasi penerapan SMK3 di industri atau perusahaan, Saudara harus
mempelajari prinsip-prinsip dasar penerapan system manajemen K3, yaitu :
1. Penetapan kebijakan K3 dan menjamin komitmen
2. Perencanaan K3
3. Penerapan K3
4. Pengukuran dan Evaluasi
5. Peninjauan Ulang dan Peningkatan SMK3 oleh manajemen
Kelima aspek tersebut merupakan tahapan prinsip-prinsip penerapan yang dilaksanakan
secara berurutan atau sequence yang bertujuan untuk peningkatan sistem manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja di industri tersebut.
A. PENETAPAN KEBIJAKAN K3 DAN MENJAMIN KOMITMEN
Perusahaan perlu mendefinisikan kebijakan K3 dan menjamin komitmennya terhadap
Sistem manajemen K3 di perusahaannya.
Pengusaha dan atau pengurus menunjukkan komitmennya melalui:
1. Membentuk Organisasi K3
2. Menyediakan anggaran, sarana dan tenaga kerja yang diperlukan dalam bidang K3
3. Menetapkan personel yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang yang jelas
dalam penanganan K3
4. Melakukan perencanaan dan penilaian kinerja K3
Praktik Kerja Industri 253
Bentuk organisasi di perusahaan adalah Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (P2K3), dengan komponen organisasi terdiri:
1. Ketua (dari Pengusaha atau salah satu Pimpinan perusahaan}
2. Sekretaris (ahli K3 Umum)
3. Anggota (perwakilan pekerja)
Kegiatan K3 perusahaan diawali dengan tinjauan awal (initial review) yang dilakukan
setiap awal tahun. Dari kegiatan tersebut kemudian baru dilanjutkan dengan kegiatan-
kegiatan lain mulai dari kebijakan K3 sampai dengan peninjauan ulang dan perbaikan SMK3.
Tinjauan awal atau initial review dilaksanakan dengan kegiatan:
1. Identifikasi potensi bahaya berkaitan dengan kegiatan atau proses perusahaan
2. Penilaian kesesuaian dengan peraturan perundangan, standar dan pedoman K3
3. Melakukan studi banding/benchmark
4. Menganalisa data-data K3 yang sudah ada
Penetapan kebijakan dan penjaminan komitmen K3 harus :
1. Tertulis
2. Diandatangani oleh pengusana dan atau pengurus
3. Memuat pernyataan komitmen dan tujuan K3 perusahaan
4. Disosialisasikan kepada semua pihak baik internal maupun eksternal
5. Bersifat dinamik dan ditinjau ulang agar tetap update
Contoh di bawah memperlihatkan kebijakan dan komitmen Macmahon industries yang
memenuhi persyaratan tersebut di atas:
254 Praktik Kerja Industri
Praktik Kerja Industri 255
B. PERENCANAAN K3
Perusahaan harus membuat perencanaan K3 untuk memenuhi kebijakan, sasaran, dan
tujuan K3 yang telah ditetapkan. Untuk membuat perencanaan K3 harus diawali dengan
kegiatan “Manajemen Risiko” yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu:
1. Identifikasi bahaya atau risiko
2. Penilaian risiko
3. Pengendalian risiko
Setelah kegiatan tersebut dilakukan, maka dengan disertai pengkajian terhadap
peraturan perudangan terkait K3, dapat dilakukan penyusunan :
1. Tujuan
2. Sasaran, dan
3. Indikator
Setelah tersusun tujuan, sasaran, dan indikator, maka dapat disusun program K3 di
perusahaan yang bersaangkutan.
Program K3 di Perusahaan Dapat Berupa:
1. Adanya program atau kegiatan terhadap bahan-bahan berbahaya, misalnya: komunikasi
B3, Spill atau leak control, labelling system, alat pelindung diri, MSDS, dan
penatalaksanaan limbah B3.
Contoh pelabelan terhadap bahan berbahaya:
Bahan Explosive Flamabl
e
256 Praktik Kerja Industri
Radioacti Bahan
ve Beracun
Bhn Biohazard Bhn Korosif
Oxidizing NFPA Standard
2. Adanya program peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan kerja.
a. Program peningkatan Sumber Daya Manusia:
1) Pelatihan dan awareness K3
2) Peningkatan prosedur kerja yang aman
3) Peningkatan tanggung jawab
Praktik Kerja Industri 257
4) Program job safety analysis
5) On the job training
6) Rapat K3
7) P2K3
8) Pemeriksaan kesehatan
9) Program keadaan darurat dan P3K
b. Program untuk lingkungan kerja
1) Housekeeping
2) Program pemantauan lingkungan
3) Pemantauan NAB Kimia
4) Inspeksi tempat kerja
5) Hygiene perusahaan
6) Pencahayaan ruang kerja
7) 5R (ringkas, rapi, resik, rawat, rajin)
c. Program terhadap alat/mesin perusahaan:
1) Pemeliharaan alat
2) Inspeksi alat
3) Rekayasa teknik
4) Tag out dan Log out
5) Program ijin kerja
C. PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
Agar penerapan berjalan secara efektif, maka perusahaan harus mengembangkan
kemampuan dan kegiatan penunjang atau pendukung untuk mencapai kebijakan, tujuan, dan
sasaran K3.
1. Jaminan Kemampuan yang Dikembangkan Antara Lain:
a. Sumber daya yang terintegrasi
b. Sumber daya sebagai penanggung jawab dan penanggung gugat
c. Peningkatan motivasi dan kesadaran K3.
2. Kegiatan Penunjang, Misalnya:
a. Komunikasi K3
258 Praktik Kerja Industri
b. Pelaporan K3
c. Pendokumentasian K3
d. Pencatatan K3
Contoh kegiatan komunikasi (Safety Poster), misalnya membuat poster-poster
tentang safety:
Praktik Kerja Industri 259
260 Praktik Kerja Industri
Praktik Kerja Industri 261
Contoh Sign Safety (Komunikasi K3)
262 Praktik Kerja Industri
Contoh Pelaporan
a. Pelaporan Internal:
1) Pelaporan insiden
2) Pelaporan ketidaksesuaian
3) Pelaporan Kinerja K3
4) Pelaporan Sumbe bahaya
b. Pelaporan Eksternal:
1) Pelaporan Kecelakaan
2) Pelaporan Kinerja P2K3
3) Pelaporan Kinerja K3 perusahaan
Dokumentasi
a. Kegiatan pendukumentasian K3 dilakukan denga cara :
1) Manual (buku petunjuk)
2) Prosedur kerja (pedoman)
3) Instruksi kerja (IK)
4) Formulir kerja/inspeksi
b. Pengendalian dokumen:
1) Identifikasi dokumen atau mempu telusur
2) Persetujuan dokumen
3) Ditinjau ulang atau direvisi
4) Dokumen versi terbaru
5) Dokumen lama dibuang
Praktik Kerja Industri 263
Jalur evakuasi dan aktivitas lain untuk kejadian gawat darurat atau emergency juga
diperlukan, misalnya:
D. PENGUKURAN DAN EVALUASI
Perusahaan perlu mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja K3 serta melakukan
tindakan pencegahan dan pengendalian.
Kegiatan pengukuran dan evaluasi terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Inspeksi, pemantauan, dan pengujian K3
2. Audit system Manajemen K3 (SMK3)
3. Tindakan perbaikan dan pencegahan
264 Praktik Kerja Industri
1. Inspeksi, Pemantauan, dan Pengujian K3:
Perusahaan menetapkan dan memelihara prosedur inspeksi, pemantauan dan
pengujian K3 yang meliputi;
a. Kompetensi personil pelaksana
b. Pemeliharaan catatan kegiatan
c. Metode dan pencatatan yang memadai
d. Rekomendasi tindakan perbaikan
e. Pemantauan tindakan perbaikan
2. Audit Sistem Manajemen K3
a. Kegiatan dilakukan berkala
b. Penentuan personil pelaksana
c. Audit harus indipenden dan sistematik
d. Frekuensi audit berdasarkan hasil audit sebelumnya dan identifikasi bahaya
e. Hasil audit dipakai untuk tinjauan manajemen K3
3. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
a. Melakukan perbaikan pada system manajemen K3 berdasarkan hasil audit SMK3
b. Melakukan tindakan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja melalui penatalaksanaan
administrasi atau tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan
c. Meningkatkan pengawasan terhadap kinerja K3.
E. PENINJAUAN ULANG DAN PENINGKATAN SMK3 OLEH PIHAK
MANAJAMEN
Industri atau perusahaan perlu meninjau ulang dan terus melakukan peningkatan SMK3
yang tujuannya adalah untuk miningkatkan kinerja K3 secara keseluruhan.
Tinjauan ulang dilakukan oleh pihak manajemen K3 meliputi kegiatan:
1. Evaluasi penerapan SMK3
2. Tujuan, sasaran, dan kinerja K3
3. Hasil audit SMK3
4. Evaluasi kebutuhan untuk peningkatan SMK3
Setelah Saudara mengetahui teori tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (SMK3) di perusahaan atau industri tempat kerja praktek, maka Saudara
Praktik Kerja Industri 265
harus melakukan Evaluasi terhadap hasil penilaian yang telah Saudara buat dengan tahap-
tahap kegiatan sebagai berikut:
1. Lakukan evaluasi hasil kerja praktik penilaian Sistem manajemen K3 industri dengan
menghitung skor yang diperoleh dari instrument penilaian.
2. Buat kesimpulan hasil evaluasi dengan cara membandingkan hasil penilaian terhadap
kriteria penilaian yang telah dibuat pada Bab 3.
3. Buat laporan kerja praktIk penilaian atau pengawasan Sistem Manajemen K3 industri
sesuai dengan sistematika penyusunan laporan pada Bab 1
Latihan Berpraktik
Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, perhatikan contoh
Latihan Evaluasi Penilaian SMK3 berikut berikut!
Misalkan hasil pengawasan SMK3 adalah sebagai berikut, bagaimanakah cara
evaluasinya?
Hasil Pengawasan berdasarkan instrument SMK3:
Nama Industri : PT. Kalibata
Alamat Industri : Jl. Kalibata 1297, Jakarta
Jenis Industri : Pembuatan Kapal
Jumlah Tenaga Kerja : Laki Laki : ......... orang, Perempuan : ....... orang
Petugas Pemantau : Harry Cane
Tanggal Pemantauan : 23 Januari 2017
266 Praktik Kerja Industri
No Item Pemantauan Ya Tidak Ket.
A. Komitmen dan Kebijakan:
1. Membentuk Organisasi K3 V
2. Menyediakan anggaran, sarana dan tenaga kerja yang V
diperlukan dalam bidang K3
3. Menetapkan personel yang mempunyai tanggung jawab V
dan wewenang yang jelas dalam penanganan K3
Melakukan perencanaan dan penilaian kinerja K3 V
Penetapan kebijakan K3 harus:
4 a. Tertulis V
5 b. Diandatangani oleh pengusana dan atau pengurus V
6 c. Memuat pernyataan komitmen dan tujuan K3 V
perusahaan
7. d. Disosialisasikan kepada semua pihak baik internal V
maupun eksternal
8 e. Bersifat dinamik dan ditinjau ulang agar tetap update V
B. Perencanaan
9. Adanya program/ kegiatan terhadap bahan-bahan V
berbahaya, misalnya: komunikasi B3, Spill/leak control,
labelling system, alat pelindung diri, MSDS, dan
penatalaksanaan limbah B3.
10. Adanya program peningkatan kualitas sumber daya V
manusia dan lingkungan kerja
11 Ada Program untuk lingkungan kerja, misalnya house V
keeping,
a) Program pemantauan lingkungan
b) Pemantauan NAB Kimia
c) Inspeksi tempat kerja
d) Hygiene perusahaan
Praktik Kerja Industri 267
No Item Pemantauan Ya Tidak Ket.
e) Pencahayaan ruang kerja
f) 5R (ringkas, rapi, resik, rawat, rajin)
12 Ada Program terhadap alat/mesin perusahaan: V
a) Pemeliharaan alat
b) Inspeksi alat
c) Rekayasa teknik
d) Tag out dan Log out
e) Program izin kerja
C. Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
13 Adanya Jaminan kemampuan yang dikembangkan antara V
lain:
1). Sumber daya yang terintegrasi
2). Sumber daya sebagai penanggung jawab dan
penanggung gugat
3). Peningkatan motivasi dan kesadaran K3.
14 Adsanya Kegiatan Penunjang, misalnya: V
a. Komunikasi K3
b. Pelaporan K3
c. Pendokumentasian K3
d. Pencatatan K3
D. Pengukuran dan Evaluasi
15 Ada kegiatan pengukuran dan evaluasi terdiri dari kegiatan- V
kegiatan sebagai berikut:
a) Inspeksi, pemantauan, dan pengujian K3
16 b) Audit system Manajemen K3 (SMK3) V
17 c) Tindakan perbaikan dan pencegahan V
268 Praktik Kerja Industri
No Item Pemantauan Ya Tidak Ket.
E. Peninjauan Ulang dan Peningkatan SMK3 oleh Pihak
Manajamen
18 a) Adanya Evaluasi penerapan SMK3 V
19 b) Terdapat Tujuan, sasaran, dan kinerja K3 V
20 c) Ada Hasil audit SMK3 V
21 d) Terdapat Evaluasi kebutuhan untuk peningkatan SMK3 V
Mengevaluasi penerapan Manajemen K3 industri
1. Langkah-1 : Mengevaluasi langkah-langkah manajemen K3 industri.
Untuk mengevaluasi manajemen K3 Industri Saudara harus telah selesai
melakukan penulaian manajemen K3 industri dengan menggunakan instrument yang
telkah dilengkapi dengan cara penghitungan skor penilaian.
2. Langkah-2 : Saudara membuat kriteria penilaian sebagaimana penghitungan skor pada
manajemen risiko, yaitu:
a. Baik, apabila skor penilaian > 75%
b. Sedang, apabila skor penilaian 65-74%
c. Kurang, bila skor penilaqian < 65%
Untuk contoh hasil penilaian tersebut di atas, maka dilakukan perhitungan skor sebagai
berikut:
𝟏𝟖
𝑺𝑲𝑶𝑹 𝑵𝑰𝑳𝑨𝑰 = × 𝟏𝟎𝟎% = 𝟖𝟓, 𝟖%
𝟐𝟏
Maka Hasil evaluasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Kalibata
termasuk dalam kriteria “Baik”
Praktik Kerja Industri 269
Tes Uraian
1) Sebutkan prinsip-prinsip penerapan sistem manajemen K3 (SMK3) !
2) Jelaskan cara menetapkan kebijakan dan komitmen K3 di perusahaan !
3) Sebutkan kegiatan apa saja yang dilakukan dalam mengawali kegiatan perencanaan K3!
4) Sebutkan program-program yang diterapkan dalam kegiatan penerapan K3
di perusahaan!
5) Sebutkan jenis kegiatan yang dilakukan dalam program pengukuran dan evaluasi K3
di perusahaan!
6) Sebutkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tinjauan ulang dan perbaikan SMK3!
270 Praktik Kerja Industri
Kunci Jawaban Tes
Test Uraian
1) Prinsip-prinsip dasar penerapan sistem manajemen K3, yaitu :
a) Penetapan kebijakan K3 dan menjamin komitmen
b) Perencanaan K3
c) Penerapan K3
d) Pengukuran dan Evaluasi
e) Peninjauan Ulang dan Peningkatan SMK3 oleh manajemen
2) Cara menetapkan kebijakan & komitmen K3, harus:
a) Tertulis
b) Diandatangani oleh pengusana dan atau pengurus
c) Memuat pernyataan komitmen dan tujuan K3 perusahaan
d) Disosialisasikan kepada semua pihak baik internal maupun eksternal
e) Bersifat dinamik dan ditinjau ulang agar tetap update
3) Perencanaan K3 diawali dengan kegiatan berikut:
a) Identifikasi bahaya atau risiko
b) Penilaian risiko
c) Pengendalian risiko
Setelah kegiatan tersebut dilakukan, maka dengan disertai pengkajian terhadap
peraturan perudangan terkait K3, dapat dilakukan penyusunan:
a) Tujuan
b) Sasaran, dan
c) Indikator
Setelah tersusun tujuan, sasaran, dan indikator, maka dapat disusun program K3 di
perusahaan yang bersaangkutan.
Program K3 berupa:
a) program terhadap bahan berbahaya,
b) program peningkatan Sumber daya manusia
c) program terhadap lingkungan
d) program terhadap alat atau mesin
Praktik Kerja Industri 271
4) Kegiatan pada penerapan K3 adalah:
a) Mengembangkan kemampuan dalam kegiatan K3
b) Mengembangkan kegiatan penunjang, misalnya Safety hazard, Safety
5) Kegiatan Pengukuran dan evaluasi K3:
a) Inspeksi, pemantauan, dan pengujian K3
b) Audit system Manajemen K3 (SMK3)
c) Tindakan perbaikan dan pencegahan
6) Kegiatan pada kegiatan Tinjauan Ulang dan perbaikan system manajemen K3
a) Evaluasi penerapan SMK3
b) Tujuan, sasaran, dan kinerja K3
c) Hasil audit SMK3
d) Evaluasi kebutuhan untuk peningkatan SMK3
272 Praktik Kerja Industri
Glosarium
Housekeeping :salah satu penilaian aspek sanitasi industri yang menitikberatkan pada
kebersihan bangunan dalam dan luar gedung industri terdiri dari
dinding, lantai, perbotan, langit-langit, armature/penerangan, koridor,
halaman, taman.
Fasilitas cuci tangan : fasilitas cuci tangan yang disediakan perusahaan bagi karyawannya,
baik dalam bentuk wastafel, maupun kamar mandi.
Lost time injury : kehilangan waktu pada saat kejadian luka karena kecelakaan
Several days of work : kehilangan waktu kerja beberapa hari yang diakibatkan oleh adanya
kecelakaan kerja.
Fatality/ disability : kecelakaan fatal atau cacat permanen yang diakibatkan kecelakaan
kerja
Labeling system : sistim pelabelan terhadap barang berhahaya agar tidak menyebabkan
kecelakaan kerja
Sign safety : gambar tanda bahaya biasanya diletakkan pada barang-barang di
sekitar lokasi kerja
Safety poster : poster untuk keamanan kerja agar diikuti oleh para tenaga kerja untuk
mencegah terjadinya kecelakaan kerja
Praktik Kerja Industri 273
Daftar Pustaka
Peraturan Pemerintah RI np. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan System Manajemen K3
OHSAS 18001:2007 Occupational Health & Safety Management System.
Rudi Suwardi, 2005. “Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja” Edisi I. PPM
Jakarta
274 Praktik Kerja Industri
Anda mungkin juga menyukai
- Laporan Inspeksi SalonDokumen13 halamanLaporan Inspeksi SalonSukMaBelum ada peringkat
- Sanitasi Pasar (Pertanyaan)Dokumen1 halamanSanitasi Pasar (Pertanyaan)Asti MilaBelum ada peringkat
- Makalah Tata GrahaDokumen16 halamanMakalah Tata GrahaGyzka salwaBelum ada peringkat
- BAB I Pendahuluan Laporan STTUDokumen4 halamanBAB I Pendahuluan Laporan STTUCita Widiya SariBelum ada peringkat
- Konsep Dasar Pengawasan Kualitas AirDokumen13 halamanKonsep Dasar Pengawasan Kualitas AirNindya FeliyantiBelum ada peringkat
- Laporan Praktikum Pengendalian Vektor Dan Binatang Pengganggu Di Kereta ApiDokumen5 halamanLaporan Praktikum Pengendalian Vektor Dan Binatang Pengganggu Di Kereta ApiYusniaBelum ada peringkat
- Laporan Praktek Kerja Institusi Sanitasi IndustriDokumen35 halamanLaporan Praktek Kerja Institusi Sanitasi IndustriWeldo Amando SulaimanBelum ada peringkat
- Kelompok 2 PBL BaturajaDokumen85 halamanKelompok 2 PBL BaturajaAldi SanjayaBelum ada peringkat
- Teknologi Inovasi Penyehatan UdaraDokumen12 halamanTeknologi Inovasi Penyehatan UdarasilmaBelum ada peringkat
- LKP 8 - Pengukuran DebitDokumen16 halamanLKP 8 - Pengukuran DebitUlfah FaoziahBelum ada peringkat
- Laporan Praktik Belajar Lapangan BTKLPP Fix-1Dokumen35 halamanLaporan Praktik Belajar Lapangan BTKLPP Fix-1kiran AdeliaBelum ada peringkat
- Hasil Pembahasan Penilaian Kebun BinatangDokumen6 halamanHasil Pembahasan Penilaian Kebun BinatangD. RandaBelum ada peringkat
- Tugas Adkl IndustriDokumen43 halamanTugas Adkl IndustriKadek Ayang Cendana PrahayuBelum ada peringkat
- Elemen-Elemen Sistem Pembuanagn Kotoran ManusiaDokumen13 halamanElemen-Elemen Sistem Pembuanagn Kotoran ManusiaAnjas Samad0% (1)
- Modul 1 PaalDokumen9 halamanModul 1 PaalDeaLailaniBelum ada peringkat
- Laporan DPMKL Kelompok 4Dokumen38 halamanLaporan DPMKL Kelompok 4Rany AmeliaBelum ada peringkat
- Muhammad Fausy (Sttu)Dokumen11 halamanMuhammad Fausy (Sttu)Muh FausyBelum ada peringkat
- Laporan Inspeksi Sanitasi PermukimanDokumen82 halamanLaporan Inspeksi Sanitasi PermukimanFebriyanti RamadhaniBelum ada peringkat
- Gambaran Pengetahuan, Sikap Dan Tindakan Masyarakat Tentang Sanitasi Dan Rumah Sehat Di Wilayah Kerja Puskesmas TuntunganDokumen77 halamanGambaran Pengetahuan, Sikap Dan Tindakan Masyarakat Tentang Sanitasi Dan Rumah Sehat Di Wilayah Kerja Puskesmas TuntunganclaudyBelum ada peringkat
- KTI Kontruksi Sumur GaliDokumen27 halamanKTI Kontruksi Sumur Galibayu permadi utomo100% (1)
- Bab 3 - Sanitasi RMH SakitDokumen48 halamanBab 3 - Sanitasi RMH SakitAnisa Dwi PutriBelum ada peringkat
- Laporan Klinik SanitasiDokumen39 halamanLaporan Klinik SanitasiPutri Oktayanti Go'oBelum ada peringkat
- Skripsi - Khaerul Anwar - P23133114032 PDFDokumen137 halamanSkripsi - Khaerul Anwar - P23133114032 PDFscasintra auliaBelum ada peringkat
- Teknik Pengendalian Pencemaran Tanah Oleh SampahDokumen19 halamanTeknik Pengendalian Pencemaran Tanah Oleh SampahRaufita HeriyahBelum ada peringkat
- Esai PSDA (Melly Nesilyia 170702127)Dokumen9 halamanEsai PSDA (Melly Nesilyia 170702127)MELLY NESILYIABelum ada peringkat
- Laporan Penyehatan Udara - A GetaranDokumen22 halamanLaporan Penyehatan Udara - A GetaranImelda TumuloBelum ada peringkat
- Proposal Lanjutan Bab 1-3Dokumen66 halamanProposal Lanjutan Bab 1-3Fahmi FirmansyahBelum ada peringkat
- Udara Bersih Dan KarakteristiknyaDokumen6 halamanUdara Bersih Dan KarakteristiknyaIndah PermatasariBelum ada peringkat
- Skenario C Blok 25 SementaraDokumen44 halamanSkenario C Blok 25 SementaraJim Christover NiqBelum ada peringkat
- Kelompok 5 - Open DumpingDokumen11 halamanKelompok 5 - Open Dumpingdinda retnoBelum ada peringkat
- 1) Makalah Pengawasan Kualitas Udara Kel 4-RevisiDokumen19 halaman1) Makalah Pengawasan Kualitas Udara Kel 4-RevisiIky SulteraaBelum ada peringkat
- Syarat TTUDokumen15 halamanSyarat TTULena TindaonBelum ada peringkat
- Proposal Fogging AmyDokumen8 halamanProposal Fogging AmySitti Fauziah SuhardiBelum ada peringkat
- Persyaratan Kesehatan Lingkungan BioskopDokumen6 halamanPersyaratan Kesehatan Lingkungan BioskopnusagrahenipBelum ada peringkat
- HASIL DISKUSI Sanitasi PemukimanDokumen9 halamanHASIL DISKUSI Sanitasi PemukimanTina.D.LestariBelum ada peringkat
- Instrumen Penilaian Salon SpaDokumen38 halamanInstrumen Penilaian Salon SpaNahda Ruce TriyantiBelum ada peringkat
- Instrumen Kapal LautDokumen10 halamanInstrumen Kapal LautraraBelum ada peringkat
- Laporan Sanitasi RSUP DR Sardjito 2013 PDFDokumen76 halamanLaporan Sanitasi RSUP DR Sardjito 2013 PDFMITRA TEHNIKBelum ada peringkat
- Kel 8 - Instrument Bahaya Faktor Fisik Di IndustriDokumen16 halamanKel 8 - Instrument Bahaya Faktor Fisik Di IndustriAmanda Nadia PutriBelum ada peringkat
- Jawaban UAS Klinik Sanitasi Arend TondatuonDokumen5 halamanJawaban UAS Klinik Sanitasi Arend TondatuonCelin GracelaBelum ada peringkat
- Kebijakan Nasional Sanitasi PermukimanDokumen6 halamanKebijakan Nasional Sanitasi PermukimanWahyuni EfridaBelum ada peringkat
- MAKALAH KEL.2 IRTS - Teknologi Sanitasi - 3D4Dokumen16 halamanMAKALAH KEL.2 IRTS - Teknologi Sanitasi - 3D4AINUNDITA PARAMANANDA mhsD4KL20190Belum ada peringkat
- Makanan MinumanDokumen12 halamanMakanan MinumanDian SoumenaBelum ada peringkat
- Laporan Praktikum PMM Kel.5Dokumen20 halamanLaporan Praktikum PMM Kel.5Umi Faridhotul umahBelum ada peringkat
- Instrumen Dan Ceklist Standar Faktor Biologi Di IndustriDokumen9 halamanInstrumen Dan Ceklist Standar Faktor Biologi Di IndustriSalma LestariBelum ada peringkat
- Kuesioner Pengendalian Vektor RsDokumen4 halamanKuesioner Pengendalian Vektor Rsadistya_adiBelum ada peringkat
- Makalah Kode Etik Profesi Kesehatan SanitarianDokumen8 halamanMakalah Kode Etik Profesi Kesehatan SanitarianMrizki febrianBelum ada peringkat
- Desinfektan Dan Teknik SamplingnyaDokumen6 halamanDesinfektan Dan Teknik SamplingnyaRizkyahBelum ada peringkat
- Aku Seorang SanitarianDokumen5 halamanAku Seorang SanitarianUlfah FaoziahBelum ada peringkat
- Makalah Penjernihan AirDokumen10 halamanMakalah Penjernihan AirDalang AjaBelum ada peringkat
- Konsep Standar Dan Penerapan Standar Etika Profesi Sanitarian - Kel7Dokumen9 halamanKonsep Standar Dan Penerapan Standar Etika Profesi Sanitarian - Kel7Adinda SavitriBelum ada peringkat
- Sttu Gereja FixDokumen4 halamanSttu Gereja FixIvana Arsita HastariBelum ada peringkat
- Pertemuan Ke 13 PVT (Jessica Sarapil)Dokumen9 halamanPertemuan Ke 13 PVT (Jessica Sarapil)Calon D3Belum ada peringkat
- Perbedaan Pemikir Dan Perasa PDFDokumen3 halamanPerbedaan Pemikir Dan Perasa PDFekoBelum ada peringkat
- Teknik Minimasi Sampah 1Dokumen12 halamanTeknik Minimasi Sampah 1MIA HAMMIDAH mhsD3KL2019BBelum ada peringkat
- FORMULIR STTU KOLAM (Blank)Dokumen7 halamanFORMULIR STTU KOLAM (Blank)Ilham LensunBelum ada peringkat
- Dokumen - Tips - Laporan Sanitasi Bioskop Kel 8Dokumen70 halamanDokumen - Tips - Laporan Sanitasi Bioskop Kel 8MeiliaBelum ada peringkat
- Pengelolaan TinjaDokumen38 halamanPengelolaan TinjaMouya WahyuBelum ada peringkat
- Spray CanDokumen4 halamanSpray CanBima SuryaBelum ada peringkat
- Etika-Profesi SC PDFDokumen196 halamanEtika-Profesi SC PDFAnugrah NoviantiBelum ada peringkat
- Puskesmas Ii Purwokerto Timur: Dinas KesehatanDokumen19 halamanPuskesmas Ii Purwokerto Timur: Dinas KesehatanChoerul FajriBelum ada peringkat
- Sik3 ModulDokumen16 halamanSik3 ModulChoerul FajriBelum ada peringkat
- Persyaratan BangunanDokumen3 halamanPersyaratan BangunanChoerul FajriBelum ada peringkat
- PROPOSAL PrintDokumen41 halamanPROPOSAL PrintChoerul FajriBelum ada peringkat