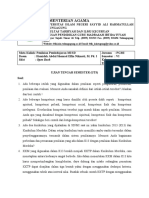Garuda 350959
Diunggah oleh
Alf NurrhmaJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Garuda 350959
Diunggah oleh
Alf NurrhmaHak Cipta:
Format Tersedia
RELASI PENGETAHUAN
ISLAM EKSOTERIS DAN ESOTERIS
Hammis Syafaq Abstract: This article scrutinizes the relationship of
hammis_syafaq@yahoo.com Islamic knowledge focusing on esoteric realm and
exoteric area or what so-called duality of life. Within
intellectual treasures of Islam this dualism have
subsequ-ently beat each other. It is sometimes in the
form of friction between the scientific and non-
scientific, rational and spiritual, the sacred and the
profane, theocentric and anthropocentric. However,
when carefully understood, the dualism shares the
Fakultas Ushuluddin
same nature, namely outer and inner aspects. The
IAIN Sunan Ampel,
outer is represented by naming, while the inner can
Surabaya
only be understood through the process of
interpretation. In other words, these two aspects are
represented by two words are name (outer aspect)
and meaning (inner aspect). Therefore, Islam is
present and it attempts to draw both together. As
can be observed in this century, the mentality of
modern humans seem to be eroded far from
religious norms as people have developed science
which leads to religious emptying from its noble
values. Therefore, it is important to bring the
esoteric realm into modern thought which tends only
to put emphasis on exoteric aspect.
Keywords: Islamic knowledge, esoteric, exoteric.
Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam
Volume 2 Nomor 2 Desember 2012
Pendahuluan
Jika diamati secara seksama, akan ditemukan dalam kehidupan ini
adanya sebuah dualisme kehidupan. Contoh konkret adalah bahwa dari
awal mula manusia diciptakan oleh Tuhan, terdapat gaya saling tarik
menarik dan bergerak ke arah dua kutub yang saling berlawanan,
negatif dan positif. Jika yang pertama diwakili oleh mereka yang
menghambat kemajuan dan melakukan perbuatan-perbuatan negatif,
jahat, dan penyelewengan dengan menegakkan tirani atas rakyat. Maka,
yang terakhir justru menentang arus awal tadi, yakni menentang tirani,
ketidakadilan serta korupsi demi tegaknya perdamaian, keadilan serta
persaudaraan di muka bumi. Untuk bisa survive dalam kehidupan ini,
kedua kubu pun harus saling mengalahkan, dan itu yang terjadi dari
masa ke masa.1
Hakikat kedua kutub yang berlawanan tersebut telah dijelaskan
dalam al-Qur’ân melalui rivalitas Qabil dan Habil. Kisah itu
mengilustrasikan secara sederhana konflik dua kubu yang berlawanan,
yang satu adalah pembunuh (subjek) dan yang lain adalah korban
(objek).2 Dalam setiap kondisi, kita menemukan dualitas dari sebuah
realitas, yang saling berlawanan, seakan-akan sulit dipersatukan.3
Seyyed Hossein Nasr, seorang pemikir Muslim dalam Traditional
Islam, juga berbicara tentang adanya dualisme, yaitu antara yang ilmiah
dan non-ilmiah, rasional dan spiritual, yang sakral dan yang profan,
teosentrisme dan antroposentrisme, dengan nilai-nilai Islam tentunya
berada di tengah-tengah persandingan itu. Maksud dari karya tersebut,
Nasr mencoba untuk mempersandingkan antara yang wilayah yang
eksoteris maupun yang esoteris, religius dan keduniawian, Barat dan
Timur, sakral dan profan, modern dan tradisional.
Menarik sekali untuk diungkap apa yang dilakukan oleh Seyyed
Hossein Nasr di atas, karena sesungguhnya antara eksoterisme dan
esoterisme dapat dipahami bahwa dalam kajian Islam itu terdapat aspek
luaran dan dalaman. Yang luaran diwakili oleh penamaan, sedang yang
dalaman hanya bisa dimengerti melalui proses pemaknaan. Pendek
1 Ali Syari’ati, Man and Islam, terj. Amien Rais (Jakarta: Srigunting, 2001), 30.
2 Syari’ati, Man and Islam, 33.
3 Ali Syari’ati, Hajj, terj. Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, Cet. Ke-8, 2009), 171-
172.
332 Hammis Syafaq—Relasi Pengetahuan
kata, dua aspek itu diwakili oleh dua kata, yaitu nama (aspek luaran)
dan makna (aspek dalaman).
Dualisme Pengetahuan Islam
Dalam diskursus keilmuan filsafat, paham dualisme dianggap
suatu varian dari paham idealisme. Idealisme sendiri seperti dilansir
Louis O. Kattsoff dari G. Watts Cunningham dalam The Idealistic
Argument in Recent British and American Philosophy menyebutkan,
“…memahami materi atau tatanan kejadian-kejadian yang terdapat
dalam ruang dan waktu sampai pada hakikatnya yang terdalam. Maka
ditinjau dari segi logika, adalah memahami adanya jiwa atau roh yang
menyertainya, dan bersifat mendasari hal-hal tersebut dalam hubungan
tertentu.”4 Dengan kata lain, jiwa (roh) merupakan istilah yang harus
ada sebagai tambahan terhadap istilah-istilah yang lain, seperti materi,
alam dan sebagainya. Pandangan tersebut berbeda dengan naturalisme
dan materialisme yang hanya menempatkan materi, alam yang dianggap
sudah cukup untuk memberikan keterangan mengenai kenyataan.
Ikhtisar dari pengertian idealisme di atas, lahirlah pandangan
dualisme sebagai konsep filsafat yang menyatakan adanya dua substansi
yang mendasari dunia. Dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa
dan raga, dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas
non-fisik. Menurut Lorens Bagus dalam Kamus Filsafat, “dualisme
adalah pandangan filosofis yang menegaskan eksistensi dari dua bidang
yang terpisah, tidak dapat direduksi, dan unik. Contoh: Allah/alam
semesta, ruh/materi, jiwa/badan, dan sebagainya.”5 Dapat dikatakan
pula bahwa dualisme memiliki ajaran bahwa segala sesuatu yang ada,
bersumber dari dua hakikat atau substansi yang berdiri sendiri-sendiri.
Sebagaimana watak dasar manusia dan alam yang dapat dibagi
menjadi dua, demikian pula pengetahuan dan pengalaman spiritualnya.
Yang terakhir ini diwakili oleh tasawuf dan senantiasa melihat segala
realitas dengan kaca mata dualistik. Rumi adalah satu dari sekian
banyak sufi yang gemar membagi kosmos secara metaforik menjadi
alam atas dan alam bawah, alam kanan dan alam kiri, serta alam putih
dan alam hitam. Dualisme itu saling bekerja sama dan membutuhkan,
4 Louis O. Kattsoff, Pengantar Filsafat, terj. Soejono Soemargono (Yogyakarta: Tiara
Wacana, 2006), 217.
5 Lorens Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 671.
Teosofi—Volume 2 Nomor 2 Desember 2012 333
3
dan bersama membentuk satu kesatuan yang utuh. Atas tidak akan ada
tanpa bawah. Bahkan Rumi pernah berujar bahwa kebaikan menjadi
tidak berarti apa-apa tanpa kejahatan karena kebaikan diketahui hanya
melalui kejahatan. Putih diketahui sebagai putih karena hitam. Tanpa
hitam, kita tidak pernah tahu warna hitam.
Corak pikir yang dualistik pun sudah menjadi gaya bagi hampir
setiap sufi dan bahkan para filsuf. Dan ini bisa jadi merupakan warisan
pemikiran Aristoteles. Ia mengajarkan bahwa setiap pemikiran yang
sistematis dimulai dengan pembagian atau kategorisasi. Dus, gaya pikir
yang dualistik dapat dikatakan sebagai kategorisasi karena ia (dualisme)
memisah-misahkan antara yang satu dengan yang lain.
Pengetahuan sufistik pun sangat kental dengan ciri dualistik ini.
Sehingga kita mengenal apa yang oleh para sufi disebut sebagai sharî‘ah
dan makrifah. Yang pertama mewakili aspek luaran Islam sedang yang
kedua mewakili aspek dalaman, demikian para sufi akan berkata.
Ibn ‘Arabî termasuk yang gemar berbicara mengenai banyak hal
mulai dari kosmologi hingga epistemologi dari sudut pandang dualistik
ini. Al-Ghazâlî pun demikian. Keduanya sepakat seperti sebuah
pandangan, bahwa realitas selalu dibagi menjadi yang nampak (seen) dan
yang tidak nampak (unseen). Yang nampak adalah realitas inderawi
sedang yang tidak nampak adalah realitas meta-inderawi.
Gaya berpikir semacam ini nampaknya tidak hanya kita temukan
dalam tradisi pemikiran Islam saja, melainkan juga di Barat dan di
pusat-pusat keilmuan lainnya. Bahkan di Barat, kategorisasi semacam
ini sangat kental sehingga istilah dualisme sementara ini lebih identik
dengan sistem pemikiran di Barat.
Sayangnya, di Barat istilah dualisme dalam perkembangannya
mengalami pergeseran. Dualisme menjadi paham yang—seperti
dikampanyekan oleh Rene Descartes di atas—meyakini bahwa realitas
memiliki dua sisi, tapi antara satu sisi dan sisi yang lain tidak saling
terkait. Manusia, misalnya, memiliki akal dan hati, pikir dan rasa, tapi
antara kedua aspek ini tidak ada hubungannya satu dengan lainnya.
Secara lebih makro, paham dualisme ala Descartes juga mengajarkan
bahwa dalam realitas Tuhan Ada dan manusia juga ada. Tapi antara
Tuhan dan manusia tidak ada keterkaitan sama sekali baik secara
ontologis maupun aksiologis. Tuhan Ada dengan sendirinya dan untuk
dirinya sendiri, dan manusia pun demikian. Manusia ada bukan karena
334 Hammis Syafaq—Relasi Pengetahuan
diciptakan oleh Tuhan tapi karena dirinya. Manusia ada bukan untuk
Tuhan atau menyembah-Nya tapi untuk kepentingan dirinya sendiri.
Pandangan dualisme semacam ini sudah menjarah ke seluruh
pelosok dunia terutama di kalangan filsuf dan pemikir termasuk di
Indonesia. Dan itu nampak dari definisi Kamus Lengkap Psikologi karya
J.D Chaplin yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh
Kartini Kartono. Definisi kamus ini adalah bahwa dualisme merupakan
“posisi falsafi dengan eksponen pokoknya Plato. Dualisme menyatakan
bahwa terdapat dua substansi asasi yang berbeda dan terpisah di dunia
ini, yaitu jiwa dan zat (mind and matter).6 Definisi itu seolah masuk
begitu saja ke dalam ranah publik di Indonesia tanpa filter, seakan
tanpa sadar kita menerimanya dan menyutujuinya.
Definisi serupa juga disampaikan oleh Lorens Bagus yang
memahami dualisme sebagai “pandangan filosofis yang menegaskan
eksistensi dari dua bidang yang terpisah, tidak dapat direduksi, unik.
Contoh: Allah/alam semesta, ruh/materi, jiwa/badan, dan
sebagainya.”7
Salah satu tujuan dari kajian tentang dualisme pengetahuan Islam
di sini adalah mempertemukan dua pemikiran dari tradisi yang berbeda,
dengan membandingkan atau mempertemukan keduanya untuk
kemudian diperoleh suatu pemaknaan yang baru, terutama dalam
melakukan kajian Islam eksoteris dan esoteris.
Pengetahuan Islam Eksoteris dan Esoteris
Secara etimologis, kata “eksoterisme” berasal dari bahasa Yunani
kuno (έκ:ek dan τηρικος–terikos). Artinya sesuatu yang di luar, bentuk
eksternal dan dapat dimengerti oleh publik, bukan oleh segelintir
kelompok. Sedangkan “esoteric” berasal dari bahasa Yunani Kuno
(εις:eis dan ηρικος-terikos). Artinya merujuk kepada sesuatu yang internal,
hanya dapat dimengerti oleh orang-orang tertentu. Lawan kata dari
eksoteris.8
6 J.D Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, terj. Kartini Kartono (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2005), 308.
7 Lorens Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 671.
8 Lihat catatan kaki nomor 24 dan 28 dalam Adnin Arnis, “Gagasan Frithjof Schoun
Tentang Titik Temu Agama-Agama” dalam Islamia, Tahun I, No. 3, Sepetember-
November 2004, 14-15.
Teosofi—Volume 2 Nomor 2 Desember 2012 335
3
Menurut Frithjof Schoun, “eksoteris” adalah aspek eksternal,
formal, hukum, dogmatis, ritual, etika dan moral pada sebuah agama.
Sedangkan “esoteris” adalah aspek metafisis dan dimensi internal
agama.9 Dalam penjelasan Schoun, eksoteris berada sepenuhnya di
dalam Maya, kosmos yang tercipta. Katagori menempatkan Tuhan
dipersepsikan sebagai Pencipta dan Pembuat Hukum bukan Tuhan
sebagai Esensi karena eksoterisme berada di dalam Maya, yang relatif
dalam hubungannya dengan Atma. Menurut Schuon, pandangan
eksoteris, bukan saja benar dan sah bahkan juga keharusan mutlak bagi
keselamatan (salvation) individu. Bagaimanapun, kebenaran eksoteris
adalah relatif.10 Inti dari eksoteris adalah ‘kepercayaan’ kepada
“huruf”,—sebuah dogma esklusifistik (formalistik)—dan kepatuhan
terhadap hukum ritual dan moral.11 Di sisi lain, dalam pandangan
esoterisme, manusia akan menemukan dirinya yang benar. Lebih lanjut
esoteris menolak ego manusia dan mengganti ego tersebut menjadi ego
yang diwarnai dengan nilai-nilai ketuhanan.12
Kolerasi dua konsep tersebut ibarat dunia bentuk (a world form)
dalam eksoteris namun ia bersumber pada Esensi yang tak berbentuk
(the Formless Essence) yaitu Esoteris. Dalam membangun dikotomi
makna tersebut Schoun menjustifikasinya melalui ajaran tasawuf yang
mengekspresikan keindahan pandangan metafisika yang terkandung
dalam makna wah}dat al-wujûd Ibn ‘Arabî dan sufi lainnya. Karena Islam
merupakan bagian dari Tuhan yang menjadi substansi nisbi.
Sudah dijelaskan di atas bahwa dalam realitasnya ada dua hal
yang selalu terpisah, antara Tuhan dengan alam, antara Pencipta dan
yang dicipta, ruh dan materi, jiwa dan badan, pengetahuan Islam murni
(pure Islamic science) dan pengetahuan Islam terapan (apllied Islamic science),
pengetahuan ilmiah dan non-ilmiah, rasional dan spiritual, yang sakral
dan yang profan, teosentrisme dan antroposentirsme, pengalaman
batin (inward experience) dan perilaku eksternal (outward behaviour),
pengalaman objektif (objective experience) pengalaman subjektif (subjective
9 Frithjof Schuon, The Transcendent Unity of Religions (Wheaton: Theosophical Publising
House, 1984), 15.
10 Frithjof Schuon, The Transcendent Unity, 15.
11 Frithjof Schuon, Spiritual Perspectives & Human Facts, Pen. P. N. Townsend
(Middlesex: Perennial Books Limited, 1987), 79-80
12 Arnis, “Gagasan Frithjof Schoun”, 16.
336 Hammis Syafaq—Relasi Pengetahuan
experience),13 insider dan outsider dan sebagainya. Keduanya terpisah secara
ontologis. Antara jiwa dan zat (mind and matter), seakan-akan antara
keduanya tidak dapat disatukan. Tetapi idealnya, keduanya harus
dipertemukan dengan membandingkan atau mempertemukan keduanya
untuk kemudian diperoleh suatu pemaknaan yang baru, terutama dalam
melakukan kajian Islam eksoteris dan esoteris.
Seorang sejarawan, Arnold Toynbee, mengatakan bahwa
modernitas telah dimulai menjelang akhir abad ke-15 M, ketika orang
Barat tidak lagi mengingat peran Tuhan dalam kehidupan dunia. Tentu
hal ini berdampak pada krisis spiritualitas, karena manusia modern
lebih mengedepankan aspek rasionalitas daripada aspek-aspek metafisis
dan eskatologis. Terkait dengan pembahasan tentang posisi relasional
antara pengetahaun Islam eksoteris dan esoteris ini perlu dilakukan
karena jika dikaitkan dengan problem keilmuan yang berkembang saat
ini, setidaknya terdapat tiga persoalan keilmuan paling krusial, antara
lain:
1. Dampak negatif perkembangan ilmu pengetahuan modern.1
2.
Kerangka epistemologis2 yang menjadi dasar tumbuh kembangnya
ilmu, yaitu rasionalitas melebihi wahyu, kritik lebih dari sikap adaptif
terhadap tradisi dan sejarah, progresivitas lebih dari sekedar
13 Frederick J. Streng, Understanding Religious Life (California: Wadswprth Publishing
Company, 1985), 1-2.
1 Menurut Armahedi, dampak pertama terkait potensi destruktif yang ditemukan sains
yang secara serta merta dimanfaatkan langsung sebagai senjata pemusnah massal oleh
kekuatan-kekuatan militer dunia. Dampak kedua adalah dampak tak langsung berupa
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup manusia oleh industry sebagai
penerapan teknologi untuk kepentingan ekonomi. Dampak ketiga adalah keretakan
sosial, keterbelahan personal, dan keter-asingan mental yang dibawa oleh pola hidup
urban yang mengikuti industralisasi ekonomi. Dampak keempat yang paling parah,
adalah penyalahgunaan obat-obat hasil industri kimia. Lihat Armahedi Mahzar,
Merumuskan Paradigma Sains dan Teknologi Islam: Revolusi Integralisme Islam (Bandung:
Mizan, 2004), 221-222.
2 Episteme merupakan keseluruhan ruang makna dan prapengandaian yang mendasari
kehidupan yang memungkinkan pengetahuan bisa terlahir. Maka episteme berisi hal-hal
yang bisa dipikirkan dan dipahami pada suatu masa. Michel Foucault lebih jauh
melihat, episteme merupakan ‘medan’ penelusuran epistomologi dari kelahiran
pengetahuan. Lihat Michel Foucault, The Order of Think: An Archeology of Human Science
(New York: Vintage Books, 1994), xxii.
Teosofi—Volume 2 Nomor 2 Desember 2012 337
3
konservasi tradisi, dan universalisme yang melandasi tiga elemen
sebelumnya.3
3. Seiring dengan universalisme itu, elemen-elemen episteme tersebut
lalu menjadi kekuatan hegemonik, sehingga tidak tersedia lagi ruang
tafsir lain atas realitas.4
Persoalan bangunan keilmuan itulah, menurut banyak orang,
yang menyebabkan terjadinya krisis peradaban modern. Keprihatinan
mendalam para agamawan khususnya dan pemeluk agama pada
umumnya, terkait problem pengetahuan ini, adalah karena dominasi
rasionalitas itu telah jauh meninggalkan agama. Keyakinan adanya
Tuhan dan peran-Nya, sama sekali tidak disentuh, bahkan dinafikan
dalam proses pengetahuan. Persoalan seperti ini sebenarnya bukanlah
hal baru dalam tradisi agama-agama. Kontribusi seperti itu bisa jadi
memberikan jalan keluar atas kebutuhan epistemologi modern saat ini
atau paling tidak, menjadi model pengetahuan alternatif semacam
“second opinion”.
Dalam upaya menjelaskan tentang relasi antara pengetahuan
Islam eksoteris dan esoteris, ada teori dari Nasr tentang rim (lingkaran)
dan axis (poros). Ia menyatakan bahwa hakikat (realitas) dunia ini
terdiri dari dua aspek: al-z}âhir (lahir, outward) dan al-bât}in (batin, inward),
ini sesuai dengan sifat Tuhan; di dalam al-Qur’ân Ia menyebut diri-Nya
sebagai al-Z}âhir dan al-Bât}in. Dalam kerangka ini, bentuk lahiriah
benda-benda tidaklah ilusi belaka; mereka mempunyai hakikat pada
level mereka sendiri. Tetapi, secara langsung menyatakan adanya
gerakan ke arah pemisahan dan pengunduran dari principle yang berada
di pusat yang dapat diidentifikasi sebagai yang batin. Hidup pada
tataran lahir berarti sekedar menyukuri eksistensi, tetapi merasa puas
semata-mata dengan yang lahir berarti menghianati watak manusia itu
sendiri, karena tujuan eksistensi manusia adalah perjalanan dari outward
ke inward, dari pinggiran (periferi) lingkaran eksistensi ke pusat
transenden. Sehingga dengan cara tersebut, makhluk dapat kembali
kepada asal muasalnya.14
3 Lihat F. Budi Hardiman, Melampaui Positivisme dan Problem Modernitas (Yogyakarta:
Penerbit Kanisius, 2003), 194.
4 Lihat buku penulis, Filsafat Ilmu, Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma, dan Kerangka
Dasar Ilmu Pengetahuan (Yogyakarta: Belukar Budaya, 2003)
14 Nasr, Islam and Plight, 45-47.
338 Hammis Syafaq—Relasi Pengetahuan
Menurut Nasr, Tuhan telah membantu manusia untuk
melakukan perjalanan dari outward ke inward dengan menurunkan
wahyu; dimana wahyu pun dalam Islam mempunyai dimensi lahir dan
dimensi batin. Dimensi batin atau esoterik ini sebagian besarnya
berkaitan dengan sufisme.15 Dengan demikian, relasi antara eksoterisme
dan esoterisme adalah mempraktikkan esoterisme dengan berpijak pada
ajaran eksoterisme. Esoterisme tanpa eksoterisme ibarat menanam
pohon di awang-awang. Orang bisa melakukan perjalanan menuju
Tuhan hanya sebagai bagian dari kemanusiaan sakral (ummah) yang
telah dibentuk dan disucikan Tuhan melalui wahyu.16
Ajaran esoterisme pada garis besarnya meliputi dua ajaran dasar:
tentang kesatuan transenden wujud (wah}dah al-wujûd) dan manusia
universal atau manusia sempurna (al-insân al-kâmil). Segala kejadian
adalah ayat yang memuat nama-nama juga sifat-sifat Tuhan dan
memperoleh wujudnya dari wujud tunggal sebagai satu-satunya yang
ada. Manusia adalah satu-satunya makhluk di bumi ini yang
berkedudukan sentral dan diciptakan dengan maksud supaya ia
menunjukkan nama-nama dan sifat-sifat Tuhan dengan cara yang
menyeluruh dan sadar. Menjadi seorang wali dalam Islam adalah
dengan melaksanakan semua kemungkinan dari keadaan manusia
menjadi insan kamil, karena insan kamil adalah cermin yang
memancarkan semua nama-nama dan sifat-sifat Tuhan. Melalui Insan
Kamil Tuhan merenungi diri-Nya dan segala hal yang telah Ia jelmakan
ke dalam wujud.17
Relasi eksoteris dan esoteris ini juga bisa dijelaskan di dunia
filsafat Islam dan tasawuf, di mana keduanya membahas tentang
teodisi, antropologi, eskatologi dan alam. Teodosi menyangkut
kenyataan bahwa Allah itu Ada, Kekal, Maha Kuasa, Tunggal, Pencipta
langit dan bumi, Pengasih, Maha Tahu. Kehendak-Nya bersifat kreatif.
Walaupun Ia transenden, tetapi Ia tidak jauh dari manusia yang
15 Nasr, Islam and Plight, 48.
16 Seyyed Hosein Nasr, Islamic Life and Thought (London: George Allen Unwin, 1981),
193.
17 Seyyed Hosein Nasr, Tasawuf: Dulu dan Sekarang, terj. M Thoyibi (Jakarta: Pustaka
Firdaus, 1991), 18.
Teosofi—Volume 2 Nomor 2 Desember 2012 339
3
bermohon kepadaNya.18 Antropologi menyangkut kenyataan bahwa
manusia diciptakan langsung oleh Allah. Adam dan Hawa telah
membangkang, tetapi dosanya tidak temurun kepada anak turun
mereka. Masing-masing jiwa bertanggung jawab atas perbuatannya
sendiri; manusia telah diciptakan agar menyembah kepada Allah dan
mengabdi kepada-Nya.19 Maka seorang Muslim adalah yang hidup di
bawah ajaran Allah, dan masyarakat Islam adalah masyarakat yang
teosentris. Eskatologi menyangkut kenyataan bahwa manusia di atas
bumi ini adalah pengembara. Takdirnya di alam baka. Maut ada di
tangan Allah dan jika waktunya tiba tidak dapat ditawar.20 Raganya akan
hancur, tetapi suatu hari akan dihidupkan kembali dan ikut menikmati
kenikmatan surga atau menanggung azab neraka.
Filsafat Islam yang teoretis juga menggabungkan antara unsur
agama dan akal, di mana secara historis, filsafat Islam adalah hasil
pertemuan umat Islam dengan filsafat Yunani di Baghdad, yaitu pada
masa pemerintahan khalifah Makmun pada abad ke-9. Filsafat Yunani
yang diterima masyarakat Islam pada saat itu tidak saja yang dari Plato
dan Aristoteles, tetapi dari para penerusnya yang sudah
mengembangkan atau menafsirkannya. Di samping Platonisme dan
Aristotelianisme, terdapat juga Stoiksime, Pitogorisme dan Neo-
Platonisme dari Plotinus dan Proclus. Dengan demikian, filsafat Islam
itu berpangkal dari al-Qur’ân dan ajaran Islam, serta basis rasional dari
filsafat Yunani, bertujuan untuk menggapai kebijaksanaan yang biasa
disebut dengan hikmah.
Al-Fârâbî, Ibn Sînâ, Ibn Rushd yakin akan ketunggalan
pengetahuan yang dimahkotai dengan metafisika atau ilâhiyyât. Dalam
karyanya Ih}s}â’ al-‘Ulûm, al-Fârâbî mendaftar aneka ragam ilmu,
menguraikan masing-masing dan akhirnya menyebutkan filsafat sebagai
mahkotanya, karena filsafat dianggap dapat menjamin kepastian
pengetahuan seperti yang didapat melalui penalaran apodeistik. Dalam
18 Dalam H}adîth disebutkan bahwa Allah berfirman; Aku sebagaimana prasangka
hambaKu kepadaKu. Jika ia meningatKu dalam dirinya, Aku pun akan Mengingatnya
dalam diriKu. Jika ia mendekat kepadaKu satu jengkal, Aku akan mendekat
kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaKu satu hasta, maka Aku akan
mendekat padanya satu depa. Jika ia mendatangiKu dengan berjalan kaki, maka Aku
akan mendatanginya dengan berlari.
19 Dan Aku tidak Menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaKu.
20 Dan jika ajal manusia datang, maka tidak bisa diundur dan tidak pula bisa ditunda.
340 Hammis Syafaq—Relasi Pengetahuan
karyanya al-Shifâ’, Ibn Sînâ merangkum seluruh ilmu pengetahuan
sebagai berikut: logika, fisika, matematika dan metafisika.
Dalam kawasan metafisika Ibn Sînâ memasukkan semua data
yang diwahyukan yang termuat dalam al-Qur’ân. Ia membuktikan
bahwa Allah adalah Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu. Ia
menguraikan masalah kejahatan dengan membedakan antara sebab-
sebab per se dan sebab-sebab per accident. Ia pun membicarakan masalah
kebangkitan daging yang peka itu. Di sini ia melakukan more philosophico
dan menghubungkannya dengan ilmu pengetahun agama yang sesuai,
dengan menempatkan prinsip-prinsip keyakinan sebagai masalah.
Selanjutnya dengan penalaran falsafi ia menunjukkan totalitas
kebijaksanaan metafisik dengan filsuf. Ibn Sînâ berusaha menemukan
kembali perintah-perintah sosial positif al-Qur’ân; kekhalifahan,
struktur keluarga, pembenaran poligami, talak dan lain-lain.
Dengan demikian, filsafat Islam lahir memberikan fungsinya
dengan memunculkan kebijaksanaan. Ia mengandung unsur-unsur
keagamaan yang diambil dari al-Qur’ân. Bersungguh-sungguh berusaha
menggabungkan agama dan akal untuk memberikan status keilmuan
pada yang pertama. Ia menerapkan struktur filsafat Yunani pada
prinsip-prinsip agama dan dengan demikian juga memberikan gema
keagamaan pada filsafat Yunani, suatu hal yang tidak terdapat pada
guru-guru Yunani itu. Dengan demikian ia bisa mendapatkan
tanggapan dari pendapat-pendapat keagamaan atau setidak-tidaknya
dari mereka yang ingin menyelaraskan kepercayaan mereka dengan akal
dan ilmu pengetahuan. Inilah dasar keberhasilan metafisika Ibn Sînâ.
Akhirnya, filsafat Islam menunjukkan kegemarannya akan masalah
pengetahuan dan dasar-dasar psikologi serta ontologinya.
Dalam risalah-risalah al-Kindî, al-Fârâbî. dan Ibn Sînâ ditemukan
analisis yang mendalam mengenai beberapa kekuasaan makhluk dan
tingkat-tingkat yang harus dilalui untuk mencapai kesatuan dengan
sumber segala makhluk, termasuk tingkat penyucian moral. Dengan
demikian, Neo-Platonisme Yunani mendapatkan dirinya diperkuat oleh
penjelasan-penjelasan tertentu yang berasal dari al-Qur’ân. Dari filsafat
Islam itulah lahir kemudian tasawuf.21 Keduanya mengantarkan umat
21Mah}mûd H}amdî Zaqzûq, al-Dîn wa al-Falsafah wa al-Tanwîr (Kairo: Dâr al-Ma‘ârif,
1996), 10.
Teosofi—Volume 2 Nomor 2 Desember 2012 341
3
Islam untuk memahami keberadaan Tuhan, sehingga bisa menjadi
semakin dekat dengan Allah bukan sebaliknya.
‘Abd al-H}alîm Mah}mûd, dalam al-Tafkîr al-Falsafî fî al-Islâm,
memunculkan sebuah pertanyaan, apakah terdapat korelasi antara
filsafat dan tasawuf? Jika ada, bagaimana bentuk korelasinya?22 Dalam
beberapa literatur dinyatakan bahwa kata filsafat (al-falsafah) berasal dari
bahasa Yunani yang sudah mengalami Arabisasi, yaitu berasal dari kata
philo yang berarti mencintai dan sophia yang berarti kebijaksanaan.23 Lalu
apa yang disebut dengan kebijaksanaan?
Mah}mûd, dengan merujuk pada pemikiran Ibn Sînâ, juga
mengatakan bahwa kebijaksanaan (h}ikmah) adalah penyempurnaan jiwa
manusia dengan cara menganalisa segala perkara yang dihadapinya dan
meyakini segala bentuk kebenaran teoritik maupun praktis sesuai
dengan kemampuan dirinya sebagai manusia, sehingga dapat
memahami dengan baik bagaimana hidup bermasyarakat, berkeluarga,
mana yang baik dan mana yang buruk. Semua itu, menurut ‘Abd. al-
H}alîm Mah}mûd dapat dilakukan oleh manusia jika ia mengetahui
keberadaan Allah (al-ma‘rifah bi Allâh), karena dengan mengetahui
keberadaan Allah, manusia akan menjauhi perbuatan yang buruk untuk
melakukan perbuatan yang baik. Maka inti daripada filsafat Islam
adalah mengungkap kebaradaan Allah. Artinya, filsafat adalah sarana
untuk mencapai pengenalan diri dengan Allah.24 Maka al-Kindî, filsuf
Muslim pertama, telah memperkenalkan relasi antara filsafat dan
agama, antara akal dan wahyu, sebagai upaya untuk mempertegas
hubungan relasional antara eksoteris dan esoteris.
Sementara tasawuf atau sufisme dapat dideskripsikan sebagai
interiosasi dan intensifikasi dari keyakinan dan praktik Islam.25 Seorang
yang mendalami tasawuf adalah mereka yang memperhatikan dengan
sungguh-sungguh seruan Allah untuk menyadari kehadiran-Nya, baik
di dunia maupun di akhirat, di mana mereka lebih menekankan hal-hal
22 ‘Abd. al-H}alîm Mah}mûd, al-Tafkîr al-Falsafî fî al-Islâm (Kairo: Dâr al-Ma‘ârif, t.th.),
163.
23 Muh}ammad Ibrâhîm al-Fayyûmî, Târîkh al-Falsafah al-Islâmîyah fî al-Mashriq (Kairo:
Dâr al-Thaqâfah, 1991), 139.
24 Mah}mûd, al-Tafkîr al-Falsafî, 163-169.
25 William C. Chittick, “Sufism” dalam Oxford Encyclopedia of Islamic Modern World, V,
207.
342 Hammis Syafaq—Relasi Pengetahuan
batiniah di atas lahiriah, kontemplasi di atas tindakan, perkembangan
spiritual di atas aturan hukum dan pembinaan jiwa di atas interaksi
sosial. Pada tingkat teologi misalnya tasawuf berbicara perihal
ampunan, keagungan dan keindahan Tuhan.26 Intinya adalah
mendekatkan diri kepada Allah sehingga dapat selalu merasakan bahwa
Allah selalu hadir bersama manusia. Keyakinan ini biasa digambarkan
dalam konsep yang biasa disebut dengan istilah ih}sân. Untuk
menumbuhkan konsep ih}sân pada diri setiap Muslim, Nabi
mengajarkannya melalui Hadithnya an ta’buda Allâh ka annaka tarâhu fa
in lam takun tarâhu fa innahu yarâka (beribadah kepada Allah seakan-akan
kita melihat-Nya, jika tidak mampu, dengan menumbuhkan keyakinan
bahwa Allah Melihat kita). Konsep ini dimunculkan berdasarkan pada
kayakinan bahwa sebab manusia melakukan keburukan adalah karena
kurang memiliki keyakinan bahwa Allah selalu melihatnya.
Jadi tasawuf dalam Islam tidak lepas dari adanya dua unsur yang
saling melengkapi, yaitu unsur lahir (outward) dan unsur batin (inward).
Unsur lahir diwakili oleh sharî‘ah (eksoteris), sementara unsur batin
diwakili oleh h}aqîqah (esoteris). Sharî‘ah merupakan pintu masuk
menuju h}aqîqah, dan h}aqîqah merupakan tujuan yang dari pelaksanaan
sharî‘ah. Perbedaan antara sharî‘ah dan h}aqîqah dapat diibaratkan seperti
kulit dan isi atau lingkaran dan titik tengahnya. Rene Guenon, seorang
tokoh ternama dalam mistisisme Kristen yang kemudian masuk Islam
melalui pendekatan sufisme mengatakan bahwa antara sharî‘ah dan
h}aqîqah tidak dapat dipisahkan. Demikian pula dengan Abû ‘Alî al-
Daqqâq yang menggambarkan bahwa ayat iyyâka na‘bud sebagai ayat
yang berkonotasi sharî‘ah, sementara iyyâka nasta’în sebagai ayat yang
berkonotasi h}aqîqah.
Dengan demikian, kajian filsafat Islam dan tasawuf sama-sama
berupaya menggabungkan dualisme antara eksoteris dan esoteris, untuk
mengantarkan manusia memahami keberadaan Allah, sehingga mau
melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Upaya untuk
melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan itulah yang dapat
mengantarkan manusia kepada kesempurnaan jiwa. Hanya saja filsafat
Islam lebih bersifat teoretis, sementara tasawuf lebih bersifat praktis.
Artinya, antara filsafat Islam dan tasawuf sama-sama berupaya untuk
26 Chittick, “Sufism”, 207.
Teosofi—Volume 2 Nomor 2 Desember 2012 343
3
mengantarkan manusia agar memahami keberadaan Allah, di mana
filsafat sebagai sarana teoretis yang dapat mengantarkan manusia
kepada keyakinan praktis. Keyakinan praktis inilah yang menjadi
wilayah tasawuf. Jadi tujuan belajar filsafat Islam adalah untuk
mencapai wilayah tasawuf.
Hubungan relasional terpenting antara pengetahuan eksoteris
dan esoteris adalah yang disumbangkan oleh al-Ghazâlî tentang
penggabungan antara dua jurusan yang berbeda; yang satu adalah arah
intelektual yang menghasilkan tasawuf, dan yang bisa disebut sebagai
arah metafisik atau gnostik, dan yang lain adalah arah populer yang
diterjemahkan ke dalam bentuk konkret sebagai lembaga-lembaga
persaudaraan keagamaan.27
Menurutnya, yang menjadi ciri bagi arah yang tersebut pertama
(wilayah intelektual) adalah keyakinan, bahwa mungkinlah orang
melewati dunia yang nyata ini, yang nampak belaka, untuk mencapai
dunia yang bisa dipahami dan kenyataan-kenyataan ruhani; dan ini
dengan melalui intuisi emosional, yaitu ma’rifat (gnosis). Di sini al-
Ghazâlî berbicara tentang hubungan antara Tuhan (khâliq) dan manusia
(makhlûq). Pada wilayah kedua (praktik keagamaan), mereka berbicara
tentang bentuk ketaatan dalam praktik ibadah, zikir. Dua hal ini
diupayakan untuk saling berpengaruh sehingga secara gnostik terjadi
relasi antara makrokosmos dengan mikrokosmos.28
Catatan Akhir
Jika di atas telah dijelaskan hubungan relasional antara eksoteris
dan esoteris, maka dapat dipahami bahwa semua ilmu memiliki sifat
dasar yang sama yaitu terdiri dari aspek luaran dan dalaman. Yang
luaran diwakili oleh penamaan, sedang yang dalaman hanya bisa
dimengerti melalui proses pemaknaan. Pendek kata, dua aspek itu
diwakili oleh dua kata, yaitu nama (aspek luaran) dan makna (aspek
dalaman).
Berangkat dari teoretisasi di atas, maka realitas-realitas samawi
atau langit adalah tak berwujud atau bersifat spiritual, dan bumi
memberinya bentuk-bentuk ragawi. Begitu pula analogi langit dalam
27 H.L. Beck & N.J.G. Kaptein, Teologi, Filsafat Islam dan Tasawuf (Jakarta: INIS, 1988),
64.
28 Beck & Kaptein, Teologi, Filsafat Islam, 64.
344 Hammis Syafaq—Relasi Pengetahuan
mikrokosmos manusia, “ruh” tidak bisa banyak berbuat apa-apa tanpa
bentuk atau raga yang berfungsi selaku wahana dan sarananya. Persis
seperti halnya Allah menciptakan alam semesta untuk
memanifestasikan berbagai kesempurnaan-Nya sendiri.
Paparan di atas mengantarkan pada pengertian bahwa seluruh
fenomena lahiriyah adalah refleksi dari noumena. Dengan demikian
segala macam bentuk dapat direduksi—dengan jalan tertentu—menjadi
satu yang termanifestasi melalui dua aspek yang diwakili oleh dua kata,
yaitu nama (aspek luaran) dan makna (aspek dalaman). Yang pertama
adalah segala sesuatu yang bersifat fenomena lahiriya (bentuk, form) dan
yang terakhir bersifat noumena (materi, matter).
Dalam formula yang lain, aspek penamaan (luaran) dan
pekmanaan (dalaman) juga bisa dijelaskan dengan meminjam istilah
signifier (penanda) dan signified (petanda) dari kombinasi Ferdinad de
Sausure dan Jacques Derida ketika meruntuhkan pandangan tradisional
tentang realitas teks—demikian juga bahasa. Dalam pandangan
tradisional, realitas teks dianggap mewakili atau menunjuk pada hal atau
benda dalam kenyataan langsung yang mengimplementsikan sebentuk
kebenaran objektif.
Pandangan tradisional tersebut berimplikasi; pertama, realitas
teks menjadi semacam wadah yang menampung “kenyataan” yang
bersifat continuum—dunia pengalaman yang pra-ilmiah dan pra-
reflektif—menjadi penggal-penggal dan dibingkai jeratan konsep dan
katagori yang kemudian diisolasi, dikenali dan pada gilirannya dikuasai.
Kedua, “kenyataan” yang di maksud menjadi kesatuan yang memiliki
kepenuhan, self-sufficient, lengkap dalam dirinya sendiri yang kemudian
menjadi absolut dan permanen.29
Pandangan tradisonal tentang realitas teks tersebut runtuh
semenjak munculnya gagasan Saussure dalam studi bahasa yang
menyatakan bahwa bahasa pada intinya terdiri dari beberapa tanda, di
mana tanda-tanda itu tidak langsung menunjuk pada kenyataan.
Kenyataan yang direpresentasikan oleh unsur penanda dari aspek
bahasa bukanlah kenyataan itu sendiri, melainkan konsep mengenainya
yang disebut unsur petanda. Unsur petanda itu sendiri bukanlah
29M. Shohibuddin, “Dekonstruksi: Pembebasan dari Kuasa Teks” dalam Hal of
Thought, No. 1, Januari-1999, 11.
Teosofi—Volume 2 Nomor 2 Desember 2012 345
3
sesuatu yang diacu oleh tanda (referen), melainkan sebuah representasi
mental dari apa yang diacu.30
Dengan demikian melalui teori itu signifier (penanda) adalah
merupakan bentuk realitas, yang dalam kaitannya dengan alam semesta
(kosmos) selalu terbuka dan memanggil-manggil untuk dibaca,
sedangkan signified (petanda) adalah representasi mental (materi) yang
telah meninggalkan jejak ke dalam bentuk ragawi. Signifier (penanda)
adalah aspek penamaan (luaran) sebagai bentuk yang menghasilkan
sifat plural, sedangkan signified (petanda) adalah pemaknaan (dalaman)
yang mengantarkan pada mental atau materi.
Penamaan dan pemaknaan di sini berangkat dari analisa terhadap
ilmu-ilmu modern yang ditemukan oleh dunia Barat rata-rata hanya
terpaku pada penamaan saja (aspek luaran yang artifisial) dan tidak
memperhatikan aspek dalaman atau pemaknaan. Sosiologi agama
contohnya. Ilmu hanya melihat agama sebagai fenomena sosial belaka
dan melupakan bahwa agama memiliki makna-makna yang jauh lebih
penting dan substansial dari sekedar aspek luarannya. Agama adalah
sistem kepercayaan, sistem ritual, sistem persaudaraan, sistem
peradaban, sistem budaya dan seterusnya. Agama juga tentang Tuhan,
hukum, etika, metafisika, estetika dan seterusnya. Sosiologi agama
melupakan itu semua dan hanya terpaku pada apa yang terjadi dalam
masyarakat atas nama agama.
Sangat mungkin bahwa mentalitas manusia modern yang terkikis
dari norma-norma agama karena ilmu pengetahuan yang mereka
kembangkan memang mengarah kepada pengosongan agama dari
muatan dan nilainya yang luhur. Pada akhirnya, kajian-kajian semacam
ini menghilangkan makna agama yang sesungguhnya sebagai sistem
kepercayaan dan ketuhanan.
Daftar Pustaka
Arnis, Adnin. “Gagasan Frithjof Schoun Tentang Titik Temu Agama-
Agama” dalam Islamia, Tahun I, No. 3, Sepetember-November,
2004.
Bagus, Lorens. Kamus Filsafat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2005.
30 Shohibuddin, “Dekonstruksi”, 11.
346 Hammis Syafaq—Relasi Pengetahuan
Beck H.L. & Kaptein, N.J.G. Teologi, Ffilsafat Islam dan Tasawuf. Jakarta:
INIS, 1988.
Chaplin, J.D. Kamus Lengkap Psikologi, terj. Kartini Kartono. Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
Chittick, William C. “Sufism” dalam Oxford Encyclopedia of Islamic Modern
World, V.
Fayyûmî (al), Muh}ammad Ibrâhîm. Târîkh al-Falsafah al-Islâmîyah fî al-
Mashriq. Kairo: Dâr al-Thaqâfah, 1991.
Foucault, Michel. The Order of Think: An Archeology of Human Science.
New York: Vintage Books, 1994.
Hardiman, Budi F. Melampaui Positivisme dan Problem Modernitas.
Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003.
Kattsoff, Louis O. Pengantar Filsafat, terj. Soejono Soemargono.
Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
Mah}mûd, ‘Abd. al-H}alîm. al-Tafkîr al-Falsafî fî al-Islâm. Kairo: Dâr al-
Ma‘ârif, t.th.
Mahzar, Armahedi. Merumuskan Paradigma Sains dan Teknologi Islam,
Revolusi Integralisme Islam. Bandung: Mizan, 2004.
Nasr, Seyyed Hosein. Islamic Life and Thought. London: George Allen
Unwin, 1981.
-----. Tasawuf: Dulu dan Sekarang. terj. M Thoyibi. Jakarta: Pustaka
Firdaus, 1991.
Schuon, Frithjof. Spiritual Perspectives & Human Facts, Pen. P. N.
Townsend. Middlesex: Perennial Books Limited, 1987.
-----. The Transcendent Unity of Religions. Wheaton: Theosophical
Publising House, 1984.
Shohibuddin, M. “Dekonstruksi; Pembebasan dari Kuasa Teks” dalam
Hal of Thought, No. 1, Januari-1999.
Streng, Frederick J. Understanding Religious Life. California: Wadswprth
Publishing Company, 1985.
Syari’ati, Ali. Hajj, terj. Anas Mahyuddin. Bandung: Pustaka, 2009.
-----. Man and Islam, terj. Amien Rais. Jakarta: Srigunting, 2001.
Zaqzûq, Mah}mûd H}amdî. al-Dîn wa al-Falsafah wa al-Tanwîr. Kairo: Dâr
al-Ma‘ârif, 1996.
Teosofi—Volume 2 Nomor 2 Desember 2012 347
3
Anda mungkin juga menyukai
- Jurnal Teologi Budaya Arkhaik OkDokumen10 halamanJurnal Teologi Budaya Arkhaik OkGURU-SMANTASA ALI MUSTOFABelum ada peringkat
- Dari Pluralitas Eksoterik Menuju Kesatuan EsoterikDokumen13 halamanDari Pluralitas Eksoterik Menuju Kesatuan EsoterikEnal Sipil TeknikBelum ada peringkat
- Edunomika - Vol. 07, No. 02, 2023: Pendidikan Jiwa Islami Menurut Syed Muhammad Naquib Al-AttasDokumen16 halamanEdunomika - Vol. 07, No. 02, 2023: Pendidikan Jiwa Islami Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attaselqudsy61Belum ada peringkat
- Eksistensialisme Religius..., Hafizh Zaskuri, FIB UI, 2009: Universitas IndonesiaDokumen9 halamanEksistensialisme Religius..., Hafizh Zaskuri, FIB UI, 2009: Universitas IndonesiaMareza SahfitriBelum ada peringkat
- Pandangan Filsafat Tentang Hakekat Manusia FixDokumen12 halamanPandangan Filsafat Tentang Hakekat Manusia FixIka SetiawatiBelum ada peringkat
- 1 SMDokumen12 halaman1 SMArdi Tfb3Belum ada peringkat
- Sejarah Perkembangan FilsafatDokumen12 halamanSejarah Perkembangan FilsafatSugi artoBelum ada peringkat
- Filsafat 8Dokumen17 halamanFilsafat 8Novia ArmaitaBelum ada peringkat
- Implikasi Neoplatonisme Dalam Pemikiran Islam DanDokumen28 halamanImplikasi Neoplatonisme Dalam Pemikiran Islam DanYamie DanchoBelum ada peringkat
- Bab IiDokumen5 halamanBab Iirahmadinakemhay428Belum ada peringkat
- PembahasanDokumen12 halamanPembahasanEndah Sekar SafitriBelum ada peringkat
- Makna Dan Tujuan Hidup Dalam Filsafat IslamDokumen11 halamanMakna Dan Tujuan Hidup Dalam Filsafat IslamPonimanBelum ada peringkat
- Teori AgamaDokumen5 halamanTeori AgamaMerlin MuskittaBelum ada peringkat
- Dasar Dasar Filosofi Pemikiran Pendidikan Islam (Dwi Dan Ria)Dokumen16 halamanDasar Dasar Filosofi Pemikiran Pendidikan Islam (Dwi Dan Ria)dwi JuliantiBelum ada peringkat
- Tugas Makalah Filsafat Pendidikan - Fajar 3 PDFDokumen7 halamanTugas Makalah Filsafat Pendidikan - Fajar 3 PDFFajar Fahmi RomdoniBelum ada peringkat
- Manusia Sebagai Makhluk BudayaDokumen31 halamanManusia Sebagai Makhluk BudayaSalsabila FebrianiBelum ada peringkat
- SuhrawardiDokumen3 halamanSuhrawardiTitisBelum ada peringkat
- IDEALISME PendidikanDokumen6 halamanIDEALISME PendidikanAhmad FathoniBelum ada peringkat
- Pemikiran Tasawuf Hazrat Inayat KhanDokumen27 halamanPemikiran Tasawuf Hazrat Inayat KhanEnal Sipil Teknik100% (1)
- UAS FPI M.juliansyahDokumen15 halamanUAS FPI M.juliansyahIKAPMI dmpBelum ada peringkat
- Firdaus NPM 227321027 (Filsafat Ilmu)Dokumen4 halamanFirdaus NPM 227321027 (Filsafat Ilmu)Widya SasmitaBelum ada peringkat
- Filsafat UmumDokumen10 halamanFilsafat UmumAlga GalvaniBelum ada peringkat
- 04 Modul Filsafat Pendidikan Islam 55 82 1axDokumen25 halaman04 Modul Filsafat Pendidikan Islam 55 82 1axUlil TokBelum ada peringkat
- Uas Sos Agama Arif Fahmi 19058044Dokumen5 halamanUas Sos Agama Arif Fahmi 19058044mr.dayBelum ada peringkat
- RMK - Epistimologi Islam FixDokumen9 halamanRMK - Epistimologi Islam FixsalsaBelum ada peringkat
- MODUL2Dokumen68 halamanMODUL2Surya SutrianaBelum ada peringkat
- Pendekatan Antropologi Terhadap AgamaDokumen35 halamanPendekatan Antropologi Terhadap AgamaMuhamad NurFauzi Hajianto 232Belum ada peringkat
- Kel.3 Pandangan Filsafat Dan Ilmu Pengetahuan Tentang ManusiaDokumen15 halamanKel.3 Pandangan Filsafat Dan Ilmu Pengetahuan Tentang ManusiaKartika MeiBelum ada peringkat
- 354 680 1 PBDokumen13 halaman354 680 1 PBpramudita nadiahBelum ada peringkat
- Makalah 1 Iad-1Dokumen12 halamanMakalah 1 Iad-1Aprilia GanestiaBelum ada peringkat
- Tugas Makalah Integrasi Ilmu Dalam IslamDokumen15 halamanTugas Makalah Integrasi Ilmu Dalam IslamYs Yn75% (12)
- 41-Article Text-126-1-10-20220118Dokumen15 halaman41-Article Text-126-1-10-20220118Nur RabbiBelum ada peringkat
- A, B, C SeptiDokumen10 halamanA, B, C SeptiSeptiNad SenagraBelum ada peringkat
- Bahasan 12 Matkul Pengantar Studi IslamDokumen8 halamanBahasan 12 Matkul Pengantar Studi IslamBismillah Iso leBelum ada peringkat
- PDF Islam Dan Budaya JawaDokumen20 halamanPDF Islam Dan Budaya JawaragabintangidBelum ada peringkat
- Pendekatan Studi IslamDokumen6 halamanPendekatan Studi IslamtitinsuhartinBelum ada peringkat
- Kebudayaan Menurut Clifford GeertzDokumen8 halamanKebudayaan Menurut Clifford Geertzkristiananus nahakBelum ada peringkat
- Bab I-1Dokumen8 halamanBab I-1Islan MuzaBelum ada peringkat
- Filsafat Timur Pendahuluan & PembahasanDokumen6 halamanFilsafat Timur Pendahuluan & PembahasannjwamalikapBelum ada peringkat
- Titik Temu Antara PegetahuanDokumen16 halamanTitik Temu Antara PegetahuanMuhammadBelum ada peringkat
- Makalah FilsafaattttDokumen12 halamanMakalah FilsafaattttKHAIRABelum ada peringkat
- Mengapa Harus BefilsafatDokumen11 halamanMengapa Harus BefilsafatcharusydahBelum ada peringkat
- Problem Solving Pengaruh Pemikiran Tokoh Atheis Terhadap Sekularisasi SainsDokumen5 halamanProblem Solving Pengaruh Pemikiran Tokoh Atheis Terhadap Sekularisasi SainsZsaffa AuliaBelum ada peringkat
- Epistimologi Islam Ada Beberapa Prinsip DasarDokumen3 halamanEpistimologi Islam Ada Beberapa Prinsip DasarMauliansyah SyachzeroBelum ada peringkat
- Ringkasan FenomDokumen55 halamanRingkasan FenomnandokabanBelum ada peringkat
- Tugas Laporan Baca 2Dokumen14 halamanTugas Laporan Baca 2winndy geaBelum ada peringkat
- Rivieu Fil Nusantara 10 JurnalDokumen20 halamanRivieu Fil Nusantara 10 JurnalDudung StarBelum ada peringkat
- Resume Ilmu Kalam Soleh Subarjah 12519.0058Dokumen13 halamanResume Ilmu Kalam Soleh Subarjah 12519.0058Soleh SubarjahBelum ada peringkat
- Materi Kelompok II Aliran Dan Cabang FlsafatDokumen10 halamanMateri Kelompok II Aliran Dan Cabang FlsafatSafiraBelum ada peringkat
- Islam Dan Budaya JawaDokumen20 halamanIslam Dan Budaya JawaRicky Hanafi100% (3)
- Sesi 5Dokumen7 halamanSesi 5YUNI NELIA ASTUTIBelum ada peringkat
- Teori Epistemologi Islam - Telaah Kritis Pemikiran Mulyadhi KartanegaraDokumen8 halamanTeori Epistemologi Islam - Telaah Kritis Pemikiran Mulyadhi KartanegaraMuhammadSaefulAnwarBelum ada peringkat
- Artike Pengantar Study Islam K15Dokumen4 halamanArtike Pengantar Study Islam K15RomzaBelum ada peringkat
- Mengapa Filsafat Pendidikan MatematikaDokumen7 halamanMengapa Filsafat Pendidikan MatematikaNur Ismiyati IdrisBelum ada peringkat
- Ymakalah Filsaf-Wps OfficeDokumen5 halamanYmakalah Filsaf-Wps OfficeUut AmbarBelum ada peringkat
- 3 Kaidah Atau Keyakinan Agama Terhadap ManusiaDokumen21 halaman3 Kaidah Atau Keyakinan Agama Terhadap ManusiaindahBelum ada peringkat
- Klasifikasi AgamaDokumen9 halamanKlasifikasi Agamalalu ahmad faisalBelum ada peringkat
- Bab IDokumen14 halamanBab Inurasia jamilBelum ada peringkat
- Filsafat Islam Kelompok 2d HCTDokumen11 halamanFilsafat Islam Kelompok 2d HCTAnaa Maghfiratul JannahBelum ada peringkat
- Hermeneutika Sunda: Simbol-Simbol Babad Pakuan/Guru GantanganDari EverandHermeneutika Sunda: Simbol-Simbol Babad Pakuan/Guru GantanganPenilaian: 3.5 dari 5 bintang3.5/5 (10)
- LangkahDokumen1 halamanLangkahAlf NurrhmaBelum ada peringkat
- Kementerian Agama Republik Indonesia: Kartu Studi MahasiswaDokumen1 halamanKementerian Agama Republik Indonesia: Kartu Studi MahasiswafitriBelum ada peringkat
- Bab Ii Pembahasan A. Landasan Teori 1. Pengertian TeoriDokumen16 halamanBab Ii Pembahasan A. Landasan Teori 1. Pengertian TeoriAlf NurrhmaBelum ada peringkat
- Deny Marliana Laela (13) - Pgmi1g - Sospend PDFDokumen3 halamanDeny Marliana Laela (13) - Pgmi1g - Sospend PDFAlf NurrhmaBelum ada peringkat
- Kementerian Agama Republik Indonesia: Institut Agama Islam Negeri TulungagungDokumen1 halamanKementerian Agama Republik Indonesia: Institut Agama Islam Negeri TulungagungAlf NurrhmaBelum ada peringkat
- Kementerian Agama Republik Indonesia: Kartu Studi MahasiswaDokumen1 halamanKementerian Agama Republik Indonesia: Kartu Studi MahasiswafitriBelum ada peringkat
- KKM Kurikulum 2013 Kelas 1Dokumen8 halamanKKM Kurikulum 2013 Kelas 1Fahmi ZeinBelum ada peringkat
- 2010 201011paiDokumen81 halaman2010 201011pailaelaBelum ada peringkat
- Penilaian PengetahuanDokumen24 halamanPenilaian PengetahuanAlf NurrhmaBelum ada peringkat
- Basic Principles of Communication in LearningDokumen10 halamanBasic Principles of Communication in LearningAlf NurrhmaBelum ada peringkat
- DIMENSI DAN ELEMEN PROFIL PELAJAR PANCASILA SalinanDokumen5 halamanDIMENSI DAN ELEMEN PROFIL PELAJAR PANCASILA SalinanAlf NurrhmaBelum ada peringkat
- Landasan Teknologi Pembelajaran MakalahDokumen34 halamanLandasan Teknologi Pembelajaran MakalahAlf NurrhmaBelum ada peringkat
- Model Pembelajaran Di Sekolah Dasar MakalahDokumen25 halamanModel Pembelajaran Di Sekolah Dasar MakalahAlf NurrhmaBelum ada peringkat
- Kementerian AgamaDokumen2 halamanKementerian AgamaAlf NurrhmaBelum ada peringkat
- Communication ComponentsDokumen8 halamanCommunication ComponentsAlf NurrhmaBelum ada peringkat
- Pendekatan, Strategi, Metode, Teknik Dan Taktik PembelajaranDokumen13 halamanPendekatan, Strategi, Metode, Teknik Dan Taktik PembelajaranAlf NurrhmaBelum ada peringkat
- Teori Komunikasi Kel. 8Dokumen13 halamanTeori Komunikasi Kel. 8Alf NurrhmaBelum ada peringkat
- Prof Ida Implementasi KurikulumDokumen25 halamanProf Ida Implementasi KurikulumAlf NurrhmaBelum ada peringkat
- Pengertian EvaluasiDokumen2 halamanPengertian EvaluasiAlf NurrhmaBelum ada peringkat
- Kawasan Teknologi Pembelajaran: Diajukan Untuk Memenuhi TugasDokumen18 halamanKawasan Teknologi Pembelajaran: Diajukan Untuk Memenuhi TugasAlf NurrhmaBelum ada peringkat
- Types and Forms of CommunicationDokumen9 halamanTypes and Forms of CommunicationAlf NurrhmaBelum ada peringkat
- PBA Revisi Kel-3Dokumen163 halamanPBA Revisi Kel-3Alf NurrhmaBelum ada peringkat
- The Concept of Communication in EducationDokumen9 halamanThe Concept of Communication in EducationAlf NurrhmaBelum ada peringkat
- A. Pengertian Pembelajaran Akidah Akhla1Dokumen2 halamanA. Pengertian Pembelajaran Akidah Akhla1Alf NurrhmaBelum ada peringkat
- Bab IDokumen14 halamanBab IAlf NurrhmaBelum ada peringkat
- Kementerian Agama Republik Indonesia: Institut Agama Islam Negeri TulungagungDokumen1 halamanKementerian Agama Republik Indonesia: Institut Agama Islam Negeri TulungagungAlf NurrhmaBelum ada peringkat
- Daftar Hadir Kuliah Mahasiswa Program S-1 Pai A / Semester Ii Stai Diponegoro Tulungagung Tahun Akademik 2020 / 2021Dokumen6 halamanDaftar Hadir Kuliah Mahasiswa Program S-1 Pai A / Semester Ii Stai Diponegoro Tulungagung Tahun Akademik 2020 / 2021Alf NurrhmaBelum ada peringkat
- Islam Dan Minyak Goreng 1Dokumen31 halamanIslam Dan Minyak Goreng 1Alf NurrhmaBelum ada peringkat
- Kementerian Agama Republik Indonesia: Kartu Hasil Studi MahasiswaDokumen1 halamanKementerian Agama Republik Indonesia: Kartu Hasil Studi MahasiswaAnik AnikkBelum ada peringkat
- Kementerian Agama Republik Indonesia: Kartu Studi MahasiswaDokumen1 halamanKementerian Agama Republik Indonesia: Kartu Studi MahasiswafitriBelum ada peringkat