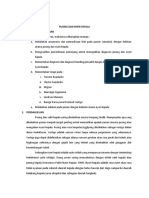Referat Final TMS
Diunggah oleh
Peter PrastDeskripsi Asli:
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Referat Final TMS
Diunggah oleh
Peter PrastHak Cipta:
Format Tersedia
1
BAB I
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang
Nyeri merupakan fenomena multidimensi yang melibatkan komponen
sensorik, afektif, lingkungan dan kognitif. The International Association for the
Study of Pain (IASP) mendefinisikan nyeri sebagai pengalaman emosi atau
sensorik yang tidak menyenangkan yang disertai atau tidak kerusakan jaringan
(Shipton, 1999).
Pengelolaan nyeri khususnya tipe kronis, sampai sekarang dapat dikatakan
belum memuaskan. Hal tersebut akibat fenomena nyeri itu sendiri yang begitu
komplek (Meliala, 2008). Dikatakan nyeri kronis jika berlangsung selama 6 bulan
atau lebih dan tidak berespon baik terhadap pengobatan yang saat ini diberikan
dan dapat berlangsung sepanjang kehidupan (Weiner, 2008).
Nyeri kronis masih menjadi masalah kesehatan umum baik di negara
bekembang maupun negara maju yang diderita oleh 17,1% lakilaki dan 20%
perempuan di Australia. Di Inggris kejadian nyeri kronis setiap tahunnya berkisar
8,3% dan prevalensi nyeri punggung sendiri di Swedia berkisar 23% . Nyeri
kronis menyebabkan masalah finansial dan disabilitas (Pridmore et al., 2005).
Di Amerika nyeri merupakan silent epidemic dan diperkirakan lebih dari
100 juta orang dewasa di Amerika sekitar 51% dari 215 juta populasi usia lebih
dari 20 tahun mengalami nyeri pada satu atau beberapa bagian tubuh termasuk
persendian, leher, punggung bawah, nyeri kepala / migrain. Lebih dari 25 % orang
dewasa berusia lebih dari 40 tahun mengalami nyeri punggung bawah dan 25 %
wanita berusia 20 hingga 39 tahun mengalami nyeri kepala atau migrain (Anonim,
2008).
Crook et al. ( 1998 ), dalam penelitian terhadap 372 keluarga di Canada
didapatkan 24% dari keluarga tersebut memiliki paling sedikit satu orang anggota
keluarga menderita nyeri yang menetap. Sebanyak 70% mengalami nyeri menetap
dan membutuhkan bantuan medis, 60% minum obat secara rutin dan
diperhitungkan bahwa rata-rata kejadian nyeri menetap menurut survei populasi
adalah sekitar 11%.
Andersen & Worm-Petersen (1988), melakukan penelitian terhadap 3.196
orang dewasa yang tinggal di Copenhagen dan menemukan prevalensi nyeri
kronis sekitar 30%.
Nyeri, terutama nyeri kronis merupakan penyebab utama penderitaan,
kecacatan dan kehilangan pekerjaan. Prevalensi nyeri kronis meningkat pada
populasi usia tua, yang berdampak secara dramatis pada sistem layanan
masyarakat dan kesehatan di seluruh dunia. Nyeri kronis saat ini juga sudah
menjadi salah satu problem kesehatan masyarakat (Peter, 2010)
Terapi dan perbaikan nyeri kronis masih menjadi tantangan yang serius
khususnya bagi negara-negara industri. Nyeri kronis tersebut memiliki dampak
negatif yang besar bagi industri terutama jika nyeri kronis diderita oleh orang
dalam usia produktif (Peter, 2010) .
Hampir setiap studi epidemiologi pada nyeri kronis dan kecacatan telah
dilakukan pada populasi pekerja, karena tingginya prevalensi gangguan nyeri
tulang belakang yang menyebabkan nyeri kronis sebagai penyebab pertama dari
kompensasi ekonomi dan kecacatan. Sebuah penemuan penting bahwa lebih dari
7,4% biaya telah di klaim untuk biaya kompensasi gangguan tulang belakang
yang menyebabkan nyeri kronis yang membuat para pekerja tersebut harus
berhenti bekerja untuk sementara waktu sekitar 6 bulan. Hal ini tentu sangat
memberi dampak yang merugikan bagi industri sehingga dibutuhkan pendekatan
terapi baru untuk deteksi dan terapi awal pada nyeri kronis ini (Ruiz-Lpez,
1995).
Telah banyak studi yang dilakukan mengenai terapi nyeri kronis tetapi
sampai saat ini pilihan terapi masih terbatas. Sementara itu lamanya gejala
cenderung membuat rasa sakit semakin resisten terhadap pengobatan (Fregni et
al., 2007). Secara farmakologi pengurangan rasa nyeri terutama nyeri kronis
kurang memuaskan. Pada beberapa individu tidak dapat mencapai pengurangan
rasa nyeri yang signifikan. Dalam beberapa penelitian dan menurut pedoman
European Federation of Neurological Societies (EFNS) hanya sekitar 3040%
pasien dengan nyeri kronis dapat mencapai target mengurangi rasa nyeri dengan
farmakoterapi (Crucu et al., 2007).
Terapi tambahan seperti terapi fisik dan terapi psikologi juga sering
digunakan tetapi terapi ini tidak cukup jika digunakan pada orang dengan nyeri
yang hebat. Selain itu beberapa terapi yang bersifat agresif seperti pembedahan
lesi yang bertujuan mengurangi rasa nyeri khususnya nyeri neuropati yang
sebelumnya banyak dilakukan kini mulai ditinggalkan.
World Health Association (WHO) telah mempublikasikan langkah-langkah
pendekatan terapi nyeri yang sederhana dan telah tervalidasi yang di kenal dengan
three-step ladder WHO yang terbukti efektif dalam mengurangi nyeri pada 90 %
pasien dengan nyeri kanker. Prinsip dasar tiga langkah menurut WHO tersebut
meliputi (1) pemilihan analgetik yang sesuai dengan intensitas nyeri, (2) titrasi
dosis analgetik opioid yang sesuai bersifat individu dan (3) penambahan terapi
adjuvant baik farmakoterapi maupun nonfarmakoterapi (Internist extra, 2010).
Salah satu terapi adjuvant non farmakologi untuk nyeri adalah dengan
teknik
noninvasive
brain
stimulation
(neurostimulasi)
seperti
repetitive
transcranial magnetic stimulation (rTMS) yang dapat membantu brain plasticity
dan modifikasi eksitabilitas neuron. Teknik ini sebenarnya bukan temuan baru
dalam terapi nyeri kronis oleh karena temuan bahwa teknik noninvasive brain
stimulation (neurostimulasi) dapat membantu memperbaiki sistem modulasi,
menyebabkan teknik ini menjadi alternatif baru dalam pengobatan terapi nyeri
kronis (Fregni et al., 2007).
Terapi neurostimulasi makin banyak digunakan. Di samping sebagai
pengganti terapi bedah yang bertujuan mengurangi nyeri, neurostimulasi ini juga
sering digunakan pada kondisi penyakit parkinson, distonia, obsesif kompulsif,
nyeri berulang, epilepsi, migrain. Teknik neurostimulasi yang bertujuan untuk
menghilangkan nyeri antara lain: transcutaneous electrical nerve stimulation
(TENS), peripheral nerve stimulation (PNS), nerve root stimulation (NRS),
spinal cord stimulation (SCS), deep brain stimulation (DBS), epidural motor
cortex stimulation (MCS), repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS),
transcranial direct cortical stimulation (tDCS).
Transcranial magnetic stimulation (TMS) pertama kali diperkenalkan oleh
Anthony Barker pada tahun 1985. Transcranial magnetic stimulation (TMS)
merupakan metode noninvasif yang aman dan tidak menimbulkan rasa nyeri
seperti pada Transcranial electrical stimulation (TES). Metode ini mengaktivasi
kortek motorik manusia dan dapat menilai keutuhan jalur motorik sentral.
Penggunaan teknik ini bertujuan untuk menghasilkan efek analgetik dengan cara
menstimulasi kortek. Teknik ini dapat diberikan dengan cara stimulasi tunggal
(single stimuli), stimulasi berpasangan atau yang dikenal dengan pairs stimulation
atau secara trains of stimuli (repetitive TMS). Repetitive transcranial magnetic
stimulation (rTMS) dapat memodifikasi eksitabilitas kortek serebral pada daerah
stimulasi dan juga pada daerah yang jauh dari tempat stimulasi sepanjang
hubungan fungsional anatomi. Teknik rTMS juga dapat menghasilkan efek terapi
yang lebih lama dibanding stimulasi tunggal (Kobayashi & Pascual-Leone, 2003).
Sejak alat ini diperkenalkan penggunaan TMS secara klinis dalam bidang
neurophysiology, neurologi, neuroscience dan psikiatri telah tersebar luas.
Sebagian besar masih dalam penelitian. Meskipun TMS telah banyak digunakan,
namun bagaimana pengaruh TMS terhadap nyeri khususnya nyeri kronis masih
menjadi perdebatan (Kobayashi & Pascual-Leone, 2003).
B. Perumusan Masalah
Dari uraian d iatas maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan
sebagai berikut:
(1.)
Nyeri kronis merupakan penyebab utama penderitaan, kecacatan, dan
(2.)
kehilangan pekerjaan.
Terapi nyeri kronis banyak pilihan, tetapi respon terapi sering tidak
(3.)
memuaskan.
Terapi nyeri kronis secara farmakologis dihadapkan pada kemungkinan
(4.)
efek samping yang ditimbulkan.
Transcranial magnetic stimulation merupakan salah satu jenis terapi non
farmakologis yang sudah banyak diterapkan dibidang neurologi, namun
peranan pada nyeri kronis masih belum banyak diketahui.
C. Tujuan Penulisan
Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transcranial
magnetic stimulation (TMS) yang diberikan secara berulang (repetitive) / rTMS
dalam terapi nyeri kronis.
D. Manfaat Penulisan
(1.)
Sebagai tambahan pengetahuan bagi para klinisi tentang penggunaan
trancranial magnetic stimulation (TMS) dengan teknik repetitive
(2.)
transranial magnetic stimulation (rTMS) dalam terapi nyeri kronis.
Menunjang penggunaan TMS di poli penyakit syaraf RS. Dr. Sardjito.
BAB II
PEMBAHASAN
A.Nyeri kronis
Nyeri kronis ditetapkan sebagai kelainan proses somatosensori yang
berkelanjutan melebihi waktu yang telah ditetapkan sebagai nyeri akut. Nyeri
kronis muncul dari disfungsi sistem saraf bersifat samar, sangat mengganggu dan
sukar untuk di lokalisir sehingga sering sulit untuk didiagnosis.
Menurut Shipton (1999), dikatakan nyeri kronis jika nyeri masih dirasakan
diluar dari batas waktu nyeri akut atau berulang setiap bulan atau tahun. Nyeri
kronis berlangsung selama 6 bulan atau lebih dan tidak berespon baik terhadap
pengobatan yang saat ini diberikan dan dapat berlangsung sepanjang kehidupan
(Weiner, 2008). PERDOSSI (2011), mendefinisikan nyeri kronis jika berlangsung
lebih dari 3 bulan.
Nyeri akut jika tidak diatasi dengan baik dapat menyebabkan perubahan
pada sistem saraf pusat misalnya perubahan pada kornu dorsalis dimana nyeri
nosiseptik yang dihasilkan dari perifer bertahan lebih lama. Lesi pada sistem saraf
dapat menghasilkan nyeri kronis dimana tidak terdapat bukti patologis pada
tempat yang nyeri misalnya pada phantom limb pain, trigeminal neuralgia. Nyeri
diketahui bersifat individual hal ini dibuktikan pada percobaan di laboratorium
yang dilakukan pada tikus menunjukkan pada beberapa tikus lebih cenderung
untuk menderita nyeri. Diperkirakan lebih dari 10% populasi umum nyeri kronis
dihasilkan dari stimulus noksius dimana pada individu normal nyeri tersebut
hanya dirasakan dalam waktu yang singkat, tetapi pada beberapa orang nyeri
berlangsung lama. Respon afektif terhadap stimulus noksius berhubungan dengan
faktor genetik, pengalaman masa lalu, mood dan interpretasi seseorang terhadap
nyeri. Faktor lingkungan juga dapat memainkan peranan yang cukup penting
terhadap nyeri (Weiner, 2008).
1. Fisiologi Nyeri
Sebelum menjadi persepsi nyeri, sinyal nosisepsi akan menjalani empat
proses yang berbeda yang dikenal sebagai transduksi, transmisi, modulasi dan
persepsi. Transduksi adalah proses dimana energi dari stimulus mekanik, suhu,
atau kimia diubah menjadi aktivitas elektrofisiologis dari perifer ke medula
spinalis. Transmisi adalah penjalaran sinyal elektrofisiologis dari perifer ke
medula spinalis, dari medula spinalis ke batang otak dan thalamus dan akhirnya
ke kortek (Serge, 2010).
Modulasi merupakan aktivitas saraf yang akan mengontrol transmisi nyeri
sebelum dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Kemampuan sel-sel saraf pada
kornu posterior medula spinalis mengontrol / memodulasi rangsang nyeri sebelum
dilanjutkan ke atas, pada gilirannya memberikan perbedaan persepsi nyeri
terhadap rangsang nyeri yang sama. Modulasi terjadi pada tingkat sistem saraf
pusat dan akan menyebabkan peningkatan atau penurunan aktivitas neuron.
Sebagaimana disebutkan pada bagian berikutnya, baik mekanisme eksitatorik dan
inhibitorik mempunyai peran penting dalam kondisi nyeri kronis (Serge, 2010).
Persepsi nyeri adalah puncak dari proses transduksi yang bersifat sementara
atau berkelanjutan yang diterima oleh nosiseptor perifer. Persepsi nyeri dimulai
dengan aktifasi nosiseptor perifer dan konduksi melalui serabut saraf A dan
serabut saraf C ke ganglion dorsalis. Dari sini sinyal berjalan ke traktus
spinotalamikus menuju thalamus dan kortek somatosensori (Shipton, 1999).
Nosiseptor dapat bersifat spesifik terhadap satu stimulus nyeri atau dapat
berespon terhadap beberapa stimulus nyeri seperti mekanik, termal, kimia atau
stimulus listrik yang disebut wide dynamic range (WDR) (Greene, 2010).
Cara yang baik untuk memahami fisiologi nyeri adalah dengan mengikuti
jaras sinyal nosisepsi dari perifer ke otak, dengan penekanan pada integrasi dan
modulasi sinyal nosisepstif pada berbagai tahap sistem saraf pusat (Serge, 2010).
Jaras nosiseptif perifer ke otak dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.
Gambar 1. Jaras nosiseptik dari perifer ke otak PAG = periaquaduktal gray
NRM = nucleus raphe magnus (Sumber :Serge, 2010).
Serabut A dan C merupakan sinaptik pertama dengan proyeksi saraf di
kornu dorsalis pada medula spinalis. Saraf kedua akan menyilang pada medula
spinalis dan menghubungkan ke nukleus thalamus. Neuron ketiga akan
diproyeksikan ke kortek somatosensoris (S1-S2) merupakan komponen sensori
diskriminatif untuk nyeri dan struktur limbik, anterior cortex cingula (ACC)
dan insula sebagai komponen afektif untuk nyeri.
10
Stimulus nosiseptif mekanis, kimia atau suhu akan diterima oleh nosiseptor
perifer yang kemudian akan melakukan konduksi sinyal nosiseptif di neuron
primary afferen menuju kornu dorsalis medula spinalis. Pada kornu dorsalis
neuron aferen primer akan melakukan kontak sinaptik dengan neuron sekunder.
Neuron sekunder dari traktus spinotalamikus lateral dan spinoretikular medial
akan menyilang di medula spinalis dan mengirimkan proyeksi eferen ke pusat
pusat yang lebih tinggi. Sebagian besar aferen akan membuat sinap kedua di
nukleus lateral dan medial thalamus yang kemudian akan membuat kontak
sinaptik dengan neuron ketiga. Penting untuk mengingat bahwa neuron sekunder
juga bersinap dengan neuron di berbagai nukleus di batang otak termasuk
periaquaductal gray (PAG) dan daerah nucleus raphe magnus (NRM) yang
terlibat dalam modulasi nyeri endogen desenden. Neuron ketiga di thalamus
mengirimkan aferen ke kortek somatosensoris primer dan sekunder (S1 dan S2).
Kortek S1 dan S2 terlibat dalam kualitas sensoris dari nyeri yang mencakup
lokasi, durasi dan intensitas. Neuron ketiga juga berproyeksi ke sistem limbik
termasuk anterior cingulated cortex (ACC) dan insula yang terlibat dalam
komponen afektif atau emosional dari nyeri. Berbagai kontak sinaptik dengan
neuron eksitatorik dan inhibitorik pada berbagai tingkat sistem saraf pusat adalah
daerah integrasi yang penting yang merupakan target untuk sebagian besar
pendekatan farmakologis (Serge, 2010).
2. Patofisiologi nyeri kronis
Lesi pada jaringan dapat berlangsung singkat dan bila lesi sembuh nyeri
akan hilang, akan tetapi jika lesi tersebut berkepanjangan dan menjadi kronis
11
menyebabkan neuron-neuron di kornu dorsalis dibanjiri potensial aksi yang
mengakibatkan terjadinya sensitisasi neuron neuron tersebut. Sensitisasi neuron
di kornu dorsalis menjadi penyebab timbulnya alodinia dan hiperalgesia sekunder
(Shipton, 1999).
Respon nosiseptor ditransmisikan dari perifer ke sistem saraf pusat (kornu
dorsalis) melalui serabut saraf bermielin (tipe A delta) maupun tanpa mielin (tipe
C). Reseptor nosiseptor di samping sebagai penerima impuls juga dapat berperan
sebagai neuroefektor yang mampu melepaskan neuropeptid seperti substansi P
dan CGRP (Calcitonin Gene Related Peptide) paska trauma atau inflamasi. Fungsi
sebagai neuroefektor ini sebenarnya berguna untuk mencegah atau mengurangi
efek merugikan dari trauma atau lesi dan mempercepat penyembuhan. Pada
beberapa keadaan patologik fungsi tersebut sebaliknya menyebabkan rasa nyeri
terutama pada nyeri kronik (Greene, 2010).
Perbedaan yang mendasar antara patofisiologi nyeri akut dan nyeri kronis
adalah keterlibatan reseptor NMDA. Pada nyeri kronis ada proses yang disebut
sebagai sensitisasi sentral yang berlangsung beberapa detik (wind-up) sampai
beberapa jam (Long Term Potentiation) atau LTP. Aktivasi reseptor NMDA akan
menyebabkan timbulnya slow excitatory post synaptic potential yang sangat
berperan dalam proses terjadinya nyeri kronis. Aktivitas NMDA yang lama juga
akan menginduksi transkripsi ekspresi gen (c-fos dan c-jun) secara cepat
menyebabkan sensitisasi nosiseptor. Plastisitas neuronal dari neuron sekunder ini
akan menyebabkan penurunan ambang stimulus atau aktifitas spontan neuron
tersebut di medula spinalis. Fenomena wind-up adalah peningkatan jumlah aksi
12
potensial progresif yang di produksi oleh neuron-neuron kornu dorsalis,
disebabkan karena banjirnya stimuli yang dihantarkan oleh serabut saraf C.
Stimuli tersebut menyebabkan kepekaan neuron kornu dorsalis meningkat
mengakibatkan terjadinya sensitisasi sentral. Aktivitas serabut saraf C
menyebabkan pelepasan glutamat yang secara langsung bereaksi terhadap reseptor
AMPA (-amino-3-hydry-5-methyl-4-isoxazole propionic acid), yang terjadi
dalam beberapa milidetik. Glutamat juga bereaksi dengan NMDA yang
membutuhkan waktu lebih banyak yaitu dalam ratusan milidetik (Meliala, 2008).
Disamping
glutamat,
serabut
juga
melepaskan
tachynin
yang
membutuhkan waktu lebih lagi yaitu puluhan detik untuk bereaksi terhadap
reseptor neurokinin. Pelepasan glutamat dan tachynin yang simultan terhadap
serabut saraf C akan menyebabkan timbulnya synaptic currents baik yang lambat
maupun yang cepat secara bersamaan. Proses ini yang disebut dengan istilah long
term potentiation (LTP) (Meliala, 2008).
Proses wind-up dan LTP mirip karena sama-sama bergantung pada aktivitas
reseptor NMDA namun lama keberadaannya berbeda. wind-up akan menyebabkan
kepekaan neuron meningkat selama input atau stimulus masih ada. Long term
potentiation (LTP) juga menambah kepekaan neuron yang masih terjadi walaupun
stimuli sudah hilang. Proses di atas menggambarkan mekanisme hiperalgesia
sekunder yang terjadi pada nyeri kronis (Meliala, 2008).
Proses sensitisasi sentral dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.
13
Gambar 2. Sensitisasi sentral (Serge, 2010).
Proses sensitisasi sentral terjadi pada saat neuron kedua di medula spinalis
mengubah pengeluaran discharge secara frekuen mengikuti rekruitment yang
menetap dari nosiseptif aferen primer. a) Pada gambar ini kita dapat melihat
discharge yang dikeluarkan oleh nosiseptif aferen primer (serabut saraf C) yang
akut akan menginduksi pelepasan peptide (substansi P, CGRP) dan glutamat yang
nantinya akan merekrut neurokinin-1 (NK 1) dan reseptor AMPA. b) Pelepasan
yang terus-menerus akan merekrut reseptor NMDA dan memproduksi sensitisasi
pada saraf
kedua yang akan mengeluarkan discharge pada frekuensi tinggi
saat direkrut oleh nosiseptif (hiperalgesia) dan stimulasi non nosiseptif (alodinia).
Secara umum kejadian ini bersifat sementara namun dapat menetap untuk jangka
waktu yang lama dan berperan dalam kejadian nyeri kronis.
14
Pada nyeri kronis, di samping
hiperalgesia sekunder
juga terdapat
alodinia yaitu nyeri yang disebabkan oleh stimulus yang secara normal tidak
menimbulkan nyeri. Prinsip terjadinya alodinia ialah impuls yang dijalarkan
oleh serabut A yang biasanya berupa sentuhan halus atau rabaan yang dalam
keadaan
normal dirasakan sebagai
rabaan
atau sentuhan akan tetapi pada
alodinia dirasakan sebagai nyeri.
Terjadinya alodinia oleh karena sensitisasi sentral (wind-up) menyebabkan
neuron di kornu dorsalis terutama WDR menjadi sangat peka dan akibatnya
daerah penerimaan impuls noksius meluas (perluasan receptive field),
peningkatan jumlah potensial aksi sebagai respon terhadap stimuli noksius dan
perlangsungannya lebih lama. Peningkatan respon terhadap stimuli ini dapat
mencapai 20 kali lipat dari normal, penurunan nilai ambang sehingga stimuli non
noksius mampu menimbulkan persepsi nyeri.
Perubahan fenotip / reorganisasi serabut A juga merupakan penyebab
terjadinya alodinia. Dalam keadaan normal serabut A tidak mengeluarkan
substansi P akan tetapi dengan adanya lesi atau inflamasi di jaringan atau sistem
saraf, serabut ini mampu mengeluarkan substansi P. Bila inflamasi sembuh maka
hiperalgesia dan alodinia juga hilang khususnya pada nyeri nosiseptif atau nyeri
inflamasi. Lain halnya dengan nyeri neuropati dimana hiperalgesia dan alodinia
bisa terus berlanjut. Hal ini terutama disebabkan sumber impuls pada nyeri
neuropati tetap ada yaitu yang datang dari perifer berupa ectopic discharge.
Serabuserabut saraf C masuk ke kornu dorsalis dan bersinapsis di lamina I dan
II.
15
Pada beberapa keadaan lesi serabut saraf aferen baik oleh karena inflamasi
maupun neuropati akan menyebabkan kematian serabut saraf
C. Hilangnya
serabut saraf C menyebabkan hubungan sinapsis kosong dan hal ini memacu
sprouting A untuk mengisi kekosongan tersebut terutama dilamina II, dengan
demikian impuls yang dibawa oleh
A (sentuhan, rabaan) yang diterima di
lamina I dan II diterjemahkan oleh neuron di kornu dorsalis sebagai nyeri atau
alodina (Meliala, 2008).
Hilangnya kontrol inhibisi juga menyebabkan terjadinya alodinia. Impuls
perifer yang datang di kornu dorsalis biasanya berupa eksitasi. Impuls tersebut
sebelum dijalarkan ke otak selalu dimodifikasi oleh serabut saraf intersegmental
atau serabut saraf desendens yang bersifat inhibisi. Neurotransmiter inhibisi
umumnya GABA atau glycin. GABA dan glycin berfungsi untuk mempertahankan
potensial
membran
mendekati
potensial
istirahat
atau
menyebabkan
hiperpolarisasi. Pada nyeri kronik khususnya nyeri neuropati terlihat adanya
penurunan aktivitas inhibisi yang diperkirakan disebabkan oleh kematian sel-sel
inibisi. Inhibisi menurun berarti eksitasi keadaan ini dapat menyebabkan alodinia
(Meliala, 2008).
Gambaran selanjutnya mengenai patofisiologi nyeri kronis adalah
dihubungkan dengan plastisitas sistem saraf dengan aktivitas yang berkelanjutan
sepanjang jalur nyeri hasil dari proses sensitisasi. Plastisitas saraf dihasilkan dari
degenerasi dan remodeling dari sinaps dan ganglia dengan kolateral sprouting di
antara sel saraf. Terapi yang agresif dan dini akan menurunkan nyeri dan
mencegah timbulnya nyeri kronis (Meliala, 2008).
16
Pada nyeri kronis diketahui juga terdapat peningkatan produksi
cholecystokinin (CCK) pada serabut saraf aferen. Peningkatan CCK menyebabkan
hipersensitifitas nosiseptor dan penurunan terhadap efektifitas opioid (Meliala,
2008).
Gambar 3. Perubahan morfologi pada serabut aferen dan kornu dorsalis
pada medula spinalis pada sindroma nyeri kronis. Perubahan ini ditunjukkan
dengan simptom klinis dari hiperalgesia dan alodinia (Greene, 2010).
3. Managemen nyeri kronis
Nyeri kronis berbeda dengan nyeri akut. Pada nyeri kronis sering
penyebab sudah berlalu tetapi nyeri tetap dirasakan dan mengganggu, seperti pada
nyeri post herpes. Terdapat perbedaan penanganan antara nyeri akut dan nyeri
kronis. Pada nyeri akut sebagian besar cukup dengan analgetik, sedangkan untuk
nyeri kronis selain analgetik juga diperlukan analgetik adjuvant maupun
intervensi lain seperti biofeedback, neurostimulasi atau pain coping lainnya
(Meliala, 2008). Berikut adalah tabel intervensi nyeri kronik yang saat ini
dilakukan.
17
Nyeri kronik : intervensi
Metode terapi
Terapi farmaka
Blok transmisi saraf
Alternatif
Analgesik
NSAID/para
setamol.
Opioid.
Reversibel
Injeksi
anastesi lokal
Adjuvan analgesik
Antidepresan.
Antikonvulsan
Stimulator
TMS,DBS,tDCS,S
CS
Akupunktur
Hipnosis
Psikologi
Ireversibel
Operasi
Destruksi saraf
Gambar 4. Intervensi nyeri kronis (Sumber McQuay and Moore, 1999 cit.
Meliala, 2008)
Memahami patofisiologi nyeri kronis dengan baik, memberikan tantangan
pada kita untuk terus mencari terapi yang efektif dan mencari metodemetode
baru sebagai tambahan terapi yang dapat digunakan untuk mengurangi nyeri
kronis. Obatobatan yang biasa digunakan untuk nyeri akut hanya sedikit atau
bahkan tidak memberikan manfaat apa apa ketika digunakan untuk nyeri kronis.
Sebaliknya obat - obatan yang memberikan efek sedikit pada nyeri akut memiliki
efikasi yang signifikan dalam terapi nyeri kronis (Meliala, 2008).
Rekomendasi terapi nyeri kronis telah dibuat oleh World Health
Organization (WHO) sebagai pedoman managemen nyeri kronis yang dikenal
sebagai WHO Ladder (Meliala, 2008; Greene, 2010).
18
Gambar 5.World Health Organization (WHO) analgesics ladder
Nyeri ringan diawali dengan terapi analgesik nonopioid (step 1) seperti
nonsteroidal
antiinflammatory
analgesic
(NSAID)
carprofen,
etodolac,
meloxicam, ketoprofen, deracoxib, tepoxalin, acetaminophen, dan aspirin.
Demikian juga analgesik yang bekerja menghambat enzim siklooksigenasi (COX1) dan lipooksigenasi (COX-2).
Obatobat tersebut dikombinasikan dengan
analgetik adjuvant. Langkah kedua dari WHO lader untuk terapi nyeri kronis bila
langkah pertama tidak adekuat, maka langkah pertama diteruskan ditambah
dengan narkotik oral dan adjuvant analgetik narkotik pilihan adalah codein.
Langkah ketiga diambil bila langkah kedua kurang efektif. Obatobatan
dilangkah kedua dihentikan, obat dilangkah pertama diteruskan, ditambah dengan
19
grup narkotik yang lebih poten. Obat pilihan adalah morfin dengan dosis dapat
dinaikkan tanpa batas, sambil diawasi respirasi, status mental dan kesiagaan.
Beberapa tipe nyeri mempunyai respon yang baik terhadap golongan opioid
lemah dibandingkan dengan opioid kuat dan juga NSAID memberikan efek
analgetik yang lebih baik dibandingkan dengan golongan opioid pada beberapa
tipe nyeri (Greene, 2010).
Sampai saat ini nyeri kronis yang diterapi secara farmakologi dengan
berbagai macam obat analgetik, secara umum masih tidak memberikan
pengurangan rasa nyeri yang adekuat pada kebanyakan pasien. Opioid dan
beberapa jenis obat obatan yang digunakan untuk mengurangi rasa nyeri yang
umumnya bekerja memblok sinyal nyeri yang berjalan sepanjang saraf, medula
spinalis dan otak seringkali tidak memberikan efek signifikan dalam mengurangi
rasa nyeri. Bahkan efek samping penggunaan obat tersebut sering muncul seperti
mengantuk, depresi respirasi, konstipasi (Greene, 2010).
Terapi non farmakologis untuk nyeri kronis termasuk massage, physical
therapy, acupuncture, dan transcutaneous electrical nerve stimulation. Modalitas
tersebut bekerja mengurangi nyeri dengan memperbaiki aliran darah ke daerah
lesi dan dengan melepaskan substansi endogen analgetik seperti beta-endorphin
dan enkephalin. Endogen opioid mempengaruhi modulasi pada desending inhibisi
pada transmisi saraf di tingkat kornu dorsalis (Greene, 2010).
Disamping terapi non farmakologis di atas dikenal juga neurostimulasi
yang saat ini sedang berkembang baik yang invasif maupun non invasif antara
lain:
20
(1). spinal cord stimulation (SCS), (2). Deep brain stimulation (DBS) atau disebut
juga electrical intracerebral stimulation, (3). Transdirect cranial stimulation
(tDCS) dan (4). Transcranial magnetic stimulation (TMS). Spinal cord
stimulation, Deep brain stimulation, merupakan metode invasif sedangkan
Transdirect cranial stimulation dan Transcranial magnetic stimulation merupakan
metode non invasif.
1). Spinal cord stimulation (SCS). Merupakan metode invasif yang dilakukan
dengan cara menanam elektrode di bawah kulit yang dihubungkan dengan pulse
generator
bertujuan untuk menstimulasi kolumna posterior medula spinalis
metode ini efektif dalam mengurangi nyeri khususnya CRPS, failed back surgery
syndrome, critical limb ischemi, post stroke pain dan berbagai nyeri kronis
lainnya. Hasil saat ini menunjukkan pada 40 sampai 70 % penderita nyeri kronis
50 % hingga 70 % nyeri berkurang signifikan bahkan mereka dapat kembali
bekerja dan hidup normal. Cara kerja SCS dalam mengurangi nyeri adalah dengan
memblok sinyal nyeri yang berjalan dari perifer ke medula spinalis sampai ke otak
(Demers, 2011).
2). Deep brain stimulation (DBS). Merupakan salah satu alat intervensi yang
digunakan dalam terapi nyeri kronis. Alat ini di tanam di daerah tertentu di otak
yang dilakukan melalui proses pembedahan yang disebut sebagai brain
pacemaker. Alat ini mengirim impuls listrik ke daerah tertentu di otak. Bekerja
secara langsung dengan merubah rangsangan di otak. Food and Drug
Administration (FDA) telah merekomendasikan alat ini sebagai terapi essential
tremor tahun 1997, Parkinson's disease tahun 2002 dan distonia pada tahun 2003.
21
Alat ini juga telah digunakan secara rutin untuk terapi nyeri kronis. Alat ini terdiri
dari tiga komponen implanted pulse generator (IPG), lead, extension. Implanted
pulse generator adalah neurostimulator bertenaga baterai yang terbungkus
titanium, yang mengirimkan arus listrik ke otak untuk merubah aktivitas saraf
pada daerah target di otak.
Lead adalah kawat melingkar yang dibungkus poliuretan dengan empat
elektroda platina iridium dan ditempatkan di salah satu dari tiga daerah otak. Lead
dihubungkan ke IPG oleh extension, sebuah kabel terisolasi yang berjalan dari
kepala turun ke leher lalu ke belakang telinga dan dihubungkan ke IPG yang
diletakkan secara subkutan di bawah klavikula atau dalam beberapa kasus
diletakkan di perut. Implanted pulse generator diletakkan sesuai gejala yang
ditunjukkan sebagai contoh untuk parkinson (rigiditas, bradikinesia/akinesia dan
tremor), lead ditempatkan pada globus pallidus atau nukleus subthalamik. Pada
nyeri IPG ini menstimulasi daerah periaqueductal gray maupun periventricular
gray untuk nyeri nosiseptik, kapsula interna, ventral posterolateral nucleus dan
ventral posteromedial nucleus untuk nyeri intractable. Meskipun DBS banyak
menolong dalam mengurangi gejala namun alat ini juga memberikan efek
samping dan komplikasi yang serius (Bittar, 2005).
3). Transdirect cranial stimulation (tDCS). Metode noninvasive brain stimulation
lainnya adalah Transdirect cranial stimulation (tDCS). Alat ini menggunakan arus
listrik yang konstan dan bertegangan lemah terdiri dari anoda dan catoda yang
diletakkan di atas scalp menembus otak dan menyebabkan perubahan pada
exitabilitas neuron. Alat ini bekerja dengan cara menstimulasi daerah target
22
dengan memberikan arus yang konstan dan bertegangan lemah melalui elektrode
yang diletakkan di daerah target. Arus yang diberikan ini diketahui dapat merubah
exitabilitas neuron pada daerah tertentu di otak berdasarkan jenis stimulasi yang
diberikan. Perubahan exitabilitas neuron menyebabkan perubahan pada fungsi
otak. Penggunaan tDCS pertama kali adalah untuk mengontrol nyeri neuropati
dan skor nyeri dapat berkurang hingga 58% pada minggu terakhir stimulasi.
Dibandingkan dengan TMS alat ini memberikan efek samping yang lebih kecil
dan mampu mengurangi nyeri lebih baik serta after effect yang lebih lama
bertahan (Fregni et al., 2006).
4). Transcranial magnetic stimulation (TMS). Salah satu terapi tambahan untuk
nyeri, khsususnya nyeri kronik. Merupakan salah satu metode non invasif yang
menyebabkan depolarisasi maupun hiperpolarisasi pada sel saraf di otak.
Transcranial magnetic stimulation menggunakan induksi elektromagnetik yang
dapat membangkitkan arus listrik dengan menggunakan perubahan medan magnet
yang cepat yang kemudian masuk menembus kulit, tengkorak dan mencapai otak.
menginduksi arus listrik sekunder pada daerah di bawah kumparan. Hal ini dapat
menyebabkan perubahan aktivitas pada daerah tertentu di otak maupun daerah
lain di otak dengan sedikit rasa tidak nyaman tanpa menimbulkan rasa sakit.
Pada single stimuli atau paired pulse stimuli akan menyebabkan saraf pada
neokortek di bawah tempat stimulasi terdepolarisasi dan membangkitkan potensial
aksi. Jika diletakkan pada kortek motorik akan menimbulkan aktivitas otot yang
disebut dengan motor evoked potential (MEP) yang dapat dicatat pada
electromyography. Pemberian TMS secara berulang dapat menghasilkan long
23
lasting after effect setelah stimulasi. Teknik ini dapat meningkatkan atau
menurunkan rangsangan pada kortek tergantung pada intensitas stimulasi,
penempatan kumparan dan frekuensi.
B. Sejarah TMS
Penggunaan gelombang magnet untuk menstimulasi jaringan saraf
didasarkan pada konsep induksi elektromagnetik oleh Faraday pada tahun 1831.
DArsonal pada tahun 1896 melaporkan penggunaan gelombang magnet pertama
kali pada manusia (Davey et al., 2002).
Pada tahun 1985 Barker pertama kali mendemonstrasikan kontraksi otot
yang dibangkitkan oleh stimulasi gelombang magnetik noninvasif melalui sistem
saraf sentral yaitu stimulasi melalui kortek motorik. Saat ini dikenal dengan
Transcranial magnetic stimulation (TMS). Sejak pertama kali ditemukan TMS
digunakan di bidang psikiatri untuk gangguan depresi yang gagal diterapi secara
farmakologi saat ini food and drug administration (FDA) telah mengakui TMS
yang diberikan secara berulang (rTMS) sebagai terapi tambahan pada major
depressive disorder. Di bidang neurologi TMS pertama kali digunakan sebagai
alat bantu diagnosis untuk penyakit-penyakit demielinisasi seperti multiple
sclerosis (Rosa, 2012).
Pada tahun 1992, Alvaro Pascual-Leone mengeksplorasi kemungkinan
penggunaan teknik ini pada pasien parkinson ternyata mereka menemukan
perbaikan kecepatan dan respon motorik pada penderita parkinson (mengurangi
akinesia). Penggunaan TMS untuk terapi nyeri kronis sendiri masih dalam
penelitian dan terus dikembangkan (Rosa, 2012).
24
C. Stimulasi TMS
Bagaimana TMS menstimulasi otak lebih lanjut diterangkan dalam gambar
enam. Gambar 6 a menjelaskan setiap gelombang TMS menghasilkan arus listrik
di otak. Hal ini menghasilkan perubahan medan magnet secara cepat yang
kemudian menembus scalp dan tengkorak hingga mencapai otak dan menginduksi
arus listrik sekunder yang dapat menstimulasi aktifitas saraf pada kortek dan
subkortek di white matter.
Seperti pada stimulasi saraf perifer, TMS pada kortek dapat mengaktivasi
axon dari beberapa saraf (rekruitmennya tergantung pada parameter stimulus).
Terdapat bukti bahwa penggunaan TMS pada kortek dengan intensitas yang
rendah menghasilkan efek inhibisi pada outcome motorik. Sebaliknya penggunaan
TMS dengan intensitas tinggi menghasilkan efek fasilitasi pada outcome motorik.
Gambar 6. Stimulasi otak oleh TMS (Sumber Ridding & Rothwell, 2008).
Gambar 6 b menjelaskan kumparan berbentuk figure of eight yang terdiri
dari beberapa kawat tembaga yang melingkar dengan diameter 7 cm. Tampak arus
mengalir di bawah kedua lingkaran dan arus terbesar terdapat pada pertemuan
kedua lingkaran. Sehingga besarnya arus pada titik tengah kumparan 2 kali
25
dibanding arus yang mengalir di bawah lingkaran. Tidak ada arus yang mengalir
di bawah pusat kumparan.
Menurut Barker (2002), terdapat tiga keterbatasan TMS yaitu (1). Besarnya
medan magnet tergantung dari jarak daerah stimulasi terhadap permukaan
kumparan sehingga stimulasi secara langsung hanya terbatas pada daerah otak
yang berada di bawah kumparan, (2). Daerah stimulasi tidak fokus sehingga salah
satu cara untuk membuat stimulasi lebih fokus adalah dengan menggunakan
kumparan berbentuk figure of eight dan (3). Penggunaan TMS mahal dan alatnya
memakan tempat.
Selajutnya menurut Rossi et al. (2009), terdapat tiga macam teknik
penggunaan TMS yaitu: (1). single- pulse TMS yaitu TMS yang diberikan dalam
satu waktu dan terdiri dari satu stimulus, teknik ini menghasilkan respon yang
baik tetapi hanya berlangsung singkat. Pengulangan stimulus dapat lebih
memperpanjang after-efect pada otak. Lamanya efek setelah single stimulus
berkisar 30-60 menit. Single-pulse TMS dapat digunakan untuk mapping output
kortek motorik, (2). Paired-pulse TMS yaitu TMS yang diberikan dalam stimulus
berpasangan / lebih dari satu stimulus dan diantara stimulus terdapat jeda
(interval), (3). Repetitive TMS yaitu TMS yang diberikan dalam stimulus yang
berurutan. Paired-pulse TMS dapat diberikan pada satu target kortikal
menggunakan satu kumparan atau pada dua daerah otak yang berbeda
menggunakan dua kumparan yang berbeda. Teknik paired- pulse TMS digunakan
untuk mengukur fasilitasi intrakortikal dan inhibisi intrakortikal. Penggunaan
TMS dengan teknik paired stimulation yang dibarengi dengan stimulus perifer
26
disebut sebagai paired associative stimulation (PAS). Pada stimulus multipel
dimana gelombang TMS diberikan secara berurutan atau dengan teknik train
stimuli atau disebut juga rTMS dibedakan menjadi conventional dan patterened
repetitive stimulation.
Pada frekuensi tertentu TMS dapat menyebabkan inhibisi yang terjadi pada
frekuensi rendah 1 Hz atau kurang dan cTBS, fasilitasi terjadi pada TMS dengan
frekuensi tinggi dan iTBS, ditemukan pada corticospinal motor outoput orang
sehat. Mekanisme yang mendasari efek inhibisi dan fasilitasi TMS belum jelas.
Salah satu mekanisme yang diduga berperan menimbulkan efek inhibisi dan
fasilitasi adalah Long term depression (LTD) atau transmisi sinaptik yang
disebabkan pemberian TMS secara berulang pada frekuensi rendah, Long term
potentiation (LTP) yang muncul pada frekuensi tinggi. Serta pergeseran
eksitabilitas jaringan dan aktivitas yang berhubungan dengan metaplastisitas
(Rossi et al., 2009).
D. Repetitive transcranial magnetic stimulation
Secara umum ada dua teknik prosedur penggunaan rTMS yaitu
conventional rTMS dan patterned rTMS. Conventional terdiri dari frekuensi
rendah dan frekuensi tinggi. Patterned menggunakan theta burst stimuli baik
intermiten theta burst stimuli (iTBS) yang meningkatkan rangsangan kortikal
maupun continous theta burst stimulation (cTBS) yang menyebabkan inhibisi
rangsangan kortikal. Pada pemberian rTMS untuk kepentingan terapi total durasi
dari satu sesi rTMS adalah sekitar 20 menit. Pengulangan pemberian rTMS dapat
memperkuat dan memperpanjang pengaruh efek single TMS yang seringkali
27
melemah dan bertahan secara singkat setelah pemberian single TMS tersebut
(cumulative effect). Gelombang single TMS dapat mendepolarisasi sel neuron
namun bersifat sementara tetapi ketika gelombang ini diberikan secara berulang
yang kita kenal dengan repetitive TMS, dapat mengubah rangsangan kortikal
(menurunkan atau menaikkan). Repetitive TMS digunakan pada frekuensi tertentu
untuk dapat menginduksi modulasi rangsangan kortikal secara persisten (Rossi et
al., 2009).
Penggunaan rTMS pada penderita nyeri kronis bertujuan memberikan efek
analgesik. Stimulasi diberikan pada scalp di atas daerah target kortikal. Stimulasi
menggunakan kumparan figure of eight lebih dianjurkan untuk mendapatkan
stimulasi yang lebih fokus. Sebagai patokan untuk menentukan intensitas,
stimulasi yang diberikan berdasarkan persentase resting motor threshold.
Umumnya stimulasi diberikan di bawah motor threshold. Frekuensi dan jumlah
total gelombang yang diberikan tergantung pada hasil studi yang dilakukan.
Dalam satu sesi paling sedikit harus terdiri dari 1000 gelombang / pulse yang
berdurasi 20 menit. Pemberian stimulus rTMS dapat diulang setiap hari selama
satu atau beberapa minggu (Crucu et al., 2007).
Keuntungan pemberian rTMS tidak menyebabkan rasa nyeri dan tidak
membutuhkan anastesi atau rawat inap selama terapi. Stimulasi rTMS dapat
mengaktifkan beberapa serabut saraf yang berjalan melewati kortek motorik dan
berproyeksi sampai ke tempat yang jauh yang terlibat pada beberapa aspek proses
nyeri kronis (komponen emosi dan komponen sensori diskriminatif). Metode ini
juga dapat digunakan pada penderita nyeri kronis yang drug resistant maupun
28
memprediksi prognosis nyeri neuropati kronis yang akan dilakukan pemasangan
implan MCS. Dari hasil studi yang melakukan stimulasi rTMS baik pada
kelompok kontrol dengan menggunakan sham rTMS, dan kelompok kasus
menggunakan rTMS aktif pada 280 pasien dengan nyeri neuropati (nyeri sentral
post stroke, lesi medula spinalis, lesi pleksus brakialis, trigeminal neuralgia, nyeri
phantom dan CRPS II) didapatkan efikasi yang berbeda antara kondisi nyeri satu
dengan lainnya, hal ini umumnya tergantung pada parameter stimulasi.
Dari beberapa RCT, yang melakukan teknik rTMS pada pasien dengan nyeri
sentral post stroke dan beberapa lesi saraf tepi yang menggunakan stimulus rTMS
pada daerah kortek motorik primer dengan frekuensi rendah (1 Hz atau kurang)
ternyata tidak efektif dalam mengurangi keluhan nyeri. Stimulasi rTMS
menggunakan kumparan yang bersifat fokal dengan frekuensi tinggi (5-20 Hz),
dengan durasi 20 menit, 1000 gelombang, dengan pemberian stimulus berulang
didapatkan pengurangan nyeri lebih dari 30% pada sekitar 50% pasien yang
menderita nyeri kronis. Dapat disimpulkan bahwa respon positif dalam
memberikan efek analgesik didapatkan pada penggunaan rTMS dengan frekuensi
tinggi. Penggunaan rTMS pada daerah non motor seperti pada dorsolateral
prefrontral cortex dalam mengurangi nyeri belum banyak diteliti (Crucu et al.,
2007).
Penggunaan rTMS pada kortek motorik menggunakan kumparan figure of
eight dan frekuensi tinggi akan menginduksi pengurangan nyeri secara signifikan
pada penderita nyeri sentral post stroke dan beberapa kondisi nyeri kronis lainnya.
Hal ini berlawanan dengan penggunaan rTMS frekuensi rendah pada kondisi nyeri
29
yang sama ternyata tidak efektif dalam mengurangi keluhan nyeri (Crucu et al.,
2007).
Pada saat rTMS diaplikasikan di atas kortek motorik dengan frekuensi yang
rendah maka akan menurunkan motor evoked potential (MEP). Sebaliknya jika
diberikan pada frekuensi tinggi akan meningkatkan MEP.
Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) dibagi menjadi
conventional rTMS dan patterened rTMS. Pada conventional rTMS dijelaskan
bahwa pemberian rTMS dengan satu stimulus yang diberikan secara berulang dan
teratur diberikan dengan frekuensi rendah 1 Hz atau kurang atau dengan frekuensi
tinggi lebih dari 1 Hz. Klasifikasi ini berdasarkan efek fisiologis dan besarnya
risiko yang ditimbulkan (Rossi et al., 2009).
Patterened rTMS diberikan sebagai stimulus yang berulang menggunakan
gelombang burst yang singkat dengan frekuensi tinggi dan diantara gelombang
tersebut terdapat jeda yang singkat tanpa stimulasi. Saat ini patterened rTMS
banyak digunakan dengan gelombang burst pendek pada frekuensi 50 Hz diulang
pada kisaran gelombang theta 5 Hz sebagai continuous theta burst stimulation
(cTBS) atau intermitten theta burst stimulation (iTBS) (Rossi et al., 2009).
Berdasarkan pedoman penggunaan keamanan dan aplikasi penggunaan
TMS dalam praktek klinis yang ditulis oleh Rossi et al. (2009), penggunaan
rTMS yang conventional pada frekuensi rendah (kurang dari 1 Hz frekuensi
stimulasi) semua gelombang diberikan secara terus menerus tanpa ada jeda.
Sementara untuk frekuensi tinggi (lebih dari 5 Hz frekuensi stimulasi) diberikan
30
dalam waktu yang lebih singkat dan diantaranya terdapat waktu istirahat tanpa
stimulus.
Patterened rTMS memiliki dua bentuk yaitu continous theta burst
stimulation (cTBS) dan Intermitten theta burst stimulation (iTBS). Protokol TBS
yang ada saat ini dibuat berdasarkan penelitian Huang et al. (2005). Untuk
continous theta burst stimulation (cTBS) diberikan dengan frekuensi 5 Hz selama
20 detik (total stimulus 300) atau 40 detik untuk total stimulus 600 yang diberikan
secara terus-menerus. Sedangkan untuk intermitten theta burst stimulation (iTBS),
diberikan stimulus dalam periode 2 detik dan dipisahkan oleh interval tanpa
stimulasi selama 8 detik. Terdapat beberapa variasi kombinasi dari protokol teknik
pengunaan TMS di atas dan perlu ditekankan efek dan keamanan dari masing
masing aplikasi penggunaan teknik tersebut. Saat ini Patterned rTMS juga dapat
diberikan dalam bentuk quadripulse stimulation (QPS) yang dapat menyebabkan
perubahan eksitabilitas kortikal jangka panjang. Quadripulse stimulation
diberikan dalam bentuk stimulasi berulang yaitu 4 pulse / gelombang monopasik
yang dipisahkan oleh interstimulus interval selama 1,51250 milidetik yang
menyebabkan fasilitasi pada interval pendek atau inhibisi pada interval yang
panjang yang kemungkinan melalui aksi modulasi sirkuit eksitatori intrakortikal
(Rossi et.al., 2009).
Kombinasi pemberian sub-motor threshold 5 Hz rTMS yang berulang pada
nervus medianus kanan dengan sub-motor threshold 5 Hz rTMS pada kortek
motorik primer (M1) pada interval yang konstan selama 2 menit teknik ini disebut
paired associated stimulation (PAS). Paired associated stimulation merupakan
31
protokol baru yang dapat meningkatkan efek rTMS pada tingkat kortikal
berdasarkan percobaan interaksi dan tes stimulus pada tingkat kortikal
sebelumnya.
Diduga
mekanisme
yang
mendasari
melalui
mekanisme
metaplastisitas (Rossi et al., 2009).
Gambar 7 menjelaskan bentuk teknik rTMS. Sebelah kiri menunjukkan
conventional rTMS. Gambar paling atas memberikan contoh 10 detik rTMS
dengan frekuensi 1 Hz pada percobaan pertama dan 5 Hz pada percobaan kedua.
Percobaan ketiga 1 detik rTMS pada frekuensi 10 Hz. Percobaan keempat untuk
tujuan terapeutik pada frekuensi 20 Hz (2 detik train rTMS yang disisipkan oleh
jeda 28 detik). Sebelah kanan gambar pertama menunjukkan pola cTBS dengan
durasi 20 detik pada frekuensi 5 Hz. Gambar kedua menunjukkan iTBS dan
intermediet theta burst (imTBS). Gambar keempat menunjukkan quadripulse
stimulation (QPS).
Gambar 7. Teknik rTMS (Rossi et al., 2009).
32
E. Prinsip Penggunaan rTMS
Telah disebutkan sebelumnya bahwa teknik ini menggunakan
prinsip
induksi elektromagnetik, dimana kumparan diletakkan di atas kepala terbanyak
pada M1. Kumparan tersebut dialiri arus dan menghasilkan medan magnet serta
menginduksi arus listrik yang dapat menembus kulit dan tengkorak kepala hingga
mencapai otak dan dapat mencetuskan depolarisasi saraf. Stimulasi diberikan
sepanjang jalannya serabut saraf, menggunakan arus yang cukup kuat untuk dapat
menimbulkan depolarisasi. Selain itu teknik rTMS dapat mengaktifasi sel sel
piramidalis secara tidak langsung (transinaptik) atau secara langsung melalui axon
hillock. Pada penggunaan rTMS operator dapat mengkontrol intensitas stimuli
dengan mengubah intensitas arus listrik yang mengalir pada kumparan sehingga
mengubah besarnya medan magnet dan medan listrik yang mengalir ke otak.
Fokus medan magnet tergantung pada bentuk kumparan (Kobayashi & Leono,
2003).
Induksi arus harus cukup kuat untuk dapat menyebabkan depolarisasi
saluran neuron kortikospinalis baik secara langsung di axon hillock atau tidak
langsung melalui transinaptik. Penggunaan TMS secara single TMS dapat
mendepolarisasi neuron bersifat sementara, sedangkan penggunaan TMS secara
berulang yang dikenal dengan repetitive transcranial magnetic stimulation
(rTMS) dapat mendepolarisasi neuron lebih lama sehingga dapat menginduksi
rangsangan modulasi kortikal secara persisten ( Rossi et al., 2009).
33
Jenis kumparan
Umumnya kumparan yang digunakan pada beberapa studi TMS terdiri dari
dua sayap yang berdekatan yang disebut figure of eight. Bentuk ini dapat
menstimulasi daerah kortikal superfisial secara fokal yang berada di bawah bagian
utama kumparan figure of eight. Serabut saraf yang diharapkan paling banyak
mendapatkan stimulasi diorientasikan secara paralel terhadap bagian sentral dari
kumparan. Sudut antara sayap kumparan akan mempengaruhi efisiensi dan
fokalitas dari kumparan. Bagian kumparan yang non-tangential terhadap kulit
kepala (scalp) menyebabkan penumpukan dari muatan permukaan, yang
mengurangi efisiensi kumparan. Sudut kumparan yang lebih kecil dari 180 0, sayap
kumparan lebih tangensial terhadap kulit kepala dan meningkatkan efisiensi
kumparan (Rossi et al., 2009).
Beberapa studi TMS menggunakan kumparan yang berbentuk lingkaran
(circular coil) dengan ukuran yang bervariasi. Diameter kumparan yang lebih
besar dari kumparan figure of eight menyebabkan stimulasi secara langsung pada
bagian otak yang lebih dalam tetapi kurang fokus. Sampai saat ini belum ada studi
yang membandingkan keamanan penggunaan antara kumparan berbentuk circular
dan figure of eight (Rossi et al., 2009).
Kumparan double cone dibentuk dari dua sayap berbentuk lingkaran yang
berdekatan bersudut 950. Kumparan besar ini menyebabkan medan listrik yang
relatif besar juga tetapi kurang fokus dibanding kumparan figure of eight, dan
dapat menyebabkan stimulasi langsung pada daerah otak yang lebih dalam.
Karena kemampuan daya tembusnya kumparan ini mampu mengaktifasi fisura
34
interhemisperik yang mewakili dasar panggul dan tungkai bawah. Stimulasi
daerah otak yang lebih dalam membutuhkan intensitas dan frekuensi yang lebih
tinggi hal ini memberikan rasa tidak nyaman pada penderita (Rossi et al., 2009).
Hal yang sering menjadi pertanyaan tentang TMS adalah mengenai
kedalaman yang mampu dicapai alat ini. Hal ini merupakan pertanyaan yang sulit
dijawab. Kedalaman penetrasi dari TMS tergantung pada faktor anatomi, ukuran
kumparan, bentuk kumparan dan intensitas stimulus yang diberikan (Barker,
2002).
F. Mekanisme rTMS
Terdapat beberapa macam mekanisme rTMS dalam memperbaiki keluhan
nyeri salah satunya stimulasi pada kortek motorik dapat memperbaiki komponen
sensori-diskriminatif. Di samping itu juga mempengaruhi perubahan komponen
fungsional motivational-affective aspek nyeri pada cingulate cortex atau
orbitofrontal cortex. Gambar 9 menunjukkan struktur saraf dan jalur yang terlibat
dalam efek analgesik pada stimulasi kortek motorik. Perangsangan rTMS pada
kortek motorik (M1) akan mempengaruhi kortek somatosensori primer (S1) dan
sekunder (S2) yang berperan dalam proses sensori-dikriminatif. Nukleus
thalamus-motor (Th-M), nukleus thalamus sensori dan nukleus thalamus assosiatif
(Th-S/A), insular cortex (Ins), anterior cingulate cortex (ACC), periaquaductal
gray (PAG), rostral ventro medial (RVM) yang berperan dalam descending
modulation dan komponen motivational affective. (Lefaucher, 2006).
35
Gambar 8. Struktur saraf dan jalur potensial yang yang terlibat dalam
stimulasi kortek motorik. (Lefaucher, 2006).
Beberapa serabut saraf yang turun dari brainstem menuju medula spinalis
dapat memodulasi impuls nyeri yang datang. Jalur desending yang dapat
memodulasi impuls nyeri diterangkan sebagai berikut stimulus nyeri yang datang
di kornu dorsalis akan diteruskan ke PAG dari sini diteruskan ke nukleus raphe
magnus di medula bagian atas, impuls akan dikembalikan ke kornu dorsalis
melalui serabut reticulospinalis. Pemberian rTMS pada M1 akan meningkatkan
pelepasan neurotransmiter serotonin di PAG dan noradrenalin di locus cerolus
disamping itu juga memicu pelepasan opioid endogen pada CNS yang juga
terletak di PAG dan nukleus raphe magnus dan dapat menekan impuls nyeri
(Renin & Dorsey, 2005).
Selain
itu
stimulasi
menggunakan
rTMS
memiliki
kemampuan
memperbaiki plastisitas sinaptik, dimana pada nyeri kronis diketahui terjadi
malplasticity. Plastisitas sinaptik adalah kemampuan sinap antara dua neuron
untuk memperkuat modulasi. Plastisitas sinaptik yang terjadi dalam bentuk long
term potentiation (LTP) terjadi jika diberikan stimulus dengan frekuensi tinggi
atau menggunakan iTBS yang dapat membangkitkan aktivitas sinap, dan long
36
term depression (LTD) yang terjadi pada stimulasi dengan frekuensi rendah atau
menggunakan cTBS yang menurunkan aktivitas sinap. Mekanisme molekuler
yang mendasari proses LTP dan LTD bergantung pada calsium influx dan reseptor
glutamat yang memiliki dua jenis reseptor yaitu AMPA (alpha-amino-3-hydroxy5-methyl-isoxazolepropionic acid) dan NMDA (N-methyl-D-aspartat) (Andrade et
al., 2011).
Pada saat sinap glutamanergik melepaskan glutamat, maka glutamat akan
berikatan pada reseptor AMPA dan reseptor NMDA. Reseptor AMPA merupakan
reseptor ionotropik yang bertanggung jawab terhadap transmisi sinap yang cepat.
Reseptor NMDA sebagai coincidence detector. Aktivitas reseptor NMDA
membutuhkan pelepasan glutamat yang cukup dari presinap yang akan
mencetuskan depolarisasi membran dan mengaktifkan reseptor NMDA.
Depolarisasi membran postsynaptic yang cukup akan membuka kanal ion
magnesium sehingga terjadi calsium influx, proses ini yang menginduksi
terjadinya LTP (Cooke & Bilis, 2006).
Gambar 9 menunjukkan membran glutamatergic
postsynaptic
yang
mengandung reseptor AMPA dan NMDA (A). Dalam kondisi istirahat atau
aktivitas input yang rendah, saluran reseptor NMDA ini diblok oleh ion
magnesium bermuatan positif (Mg2+) (B). Glutamat dilepaskan dari terminal dan
memasuki celah sinap dan berikatan dengan kedua reseptor, yang kemudian akan
membuka saluran reseptor AMPA. Aliran arus ke dalam sel yang dibawa oleh Na+
akan mendepolarisasi membran post sinap dan menyebabkan exitatory postsynaptic potential (EPSP). Pelepasan glutamat dalam jumlah yang sedikit tidak
37
akan cukup mendepolarisasi membran postsynaptic (C). Konsentrasi glutamat
yang tinggi menghasilkan depolarisasi membran post-sinaptik, sehingga membuka
blok ion magnesium dari saluran reseptor NMDA, menyebabkan masuknya ion
Na+ dan ion Ca2+. Reseptor NMDA bertindak sebagai aktivitas coincidence
detektor pra dan postsinaptik. (D). Menggambarkan rekaman intraseluler dari
rangsang sinaptik dengan kondisi magnesium yang rendah atau depolarisasi
membran (Cooke & Bliss, 2006).
Gambar 9. Aktivitas reseptor glutamat (Cooke & Bliss, 2006)
Kemampuan plastisitas sinaptik pada tingkat seluler melalui percobaan
dengan otak tikus yang dilakukan oleh Pridmore et al. (2005), stimulasi kortek
motorik menggunakan TMS menunjukkan perubahan densitas reseptor betaadrenergik pada kortek, korpus striatum, region-specific monoamine levels,
second messenger cyclic AMP, densitas NMDA binding site di hipotalamus,
38
amygdala, kortek parietal, dan densitas 5-HT1A binding site di frontal, cingulate
cortex dan nukleus olfaktori anterior, ekspresi glial fibrillary acidic protein
mRNA di girus dentata dan kortek. Dengan kata lain TMS memiliki kemampuan
mempengaruhi neurotransmiter, reseptor, second messengers systems dan gen,
pada saraf dan jaringan penyokong yang penting dalam regulasi nyeri.
Perbedaan efek plastisitas yang dihasikan oleh stimulasi TMS pada
tingkat sistem dan seluler berada pada rangsangan kortikal. Pada tingkat sistem
menjelaskan bahwa pada stimulasi yang rendah (1 Hz atau kurang) akan
menyebabkan penurunan rangsangan kortikal. Pada frekuensi tinggi akan
meningkatkan rangsangan kortikal. Fenomena di atas banyak dipelajari pada
penggunaan TMS yang diletakkan pada kortek motorik. Perubahan rangsangan
kortikal yang dihasilkan oleh TMS memiliki efek yang singkat dengan durasi
menit hingga jam. Sementara pengulangan TMS akan menghasilkan efek
kumulatif perubahan plastisitas. Percobaan yang dilakukan oleh Baumer et al.
(2001), pada kortek premotor menggunakan TMS selama 5 hari berturut turut
pada frekuensi tinggi, menunjukkan bahwa pada hari pertama penurunan
rangsangan kortikal bertahan 30 menit, pada hari kedua dapat bertahan 6 jam, hari
kelima menunjukkan hasil efek TMS dapat bertahan 4 minggu dari stimulasi
terakhir. Dari percobaan ini juga menunjukkan bahwa stimulasi menggunakan
TMS pada satu daerah juga dapat berpengaruh pada daerah lainnya yang secara
fungsional berhubungan dengan daerah tersebut.
Studi brain imaging dan neurofisologi menunjukkan bahwa pada nyeri
kronis terjadi perubahan pada struktur dan fungsi otak. Stimulasi TMS
39
menghasilkan perubahan sementara neuroplastisitas di otak. Hal ini memberikan
keuntungan pada kondisi nyeri kronis (Pridmore et al., 2005).
Mekanisme lain yang dimiliki oleh rTMS adalah kemampuannya
mengaktifkan sistem opioid endogen yang diketahui berperan dalam proses
modulasi nyeri, dimana pada nyeri kronis terdapat penurunan reseptor opiod pada
beberapa daerah otak.
Pada dasarnya pengaruh analgetik stimulasi rTMS pada M1 melibatkan
inhibisi langsung sinyal nosiseptik dari transmisi spinal. Studi elektrofisiologis
pada hewan menunjukkan keterlibatan kortek motorik dalam modulasi proses
informasi sensorik. Dengan kata lain rTMS memperbaiki descending modulasi
pada penderita nyeri kronis yang terpusat pada brainstem dan diencephalon
sampai medula spinalis dimana aktivitas modulasi kortikal bergantung pada jalur
GABAergic dan glutamat.
G. Variabilitas yang mempengaruhi efek rTMS
Efek rTMS dalam mempengaruhi modulasi rangsang kortikal dipengaruhi
oleh banyak faktor antara lain dipengaruhi oleh variabilitas inter-subjek dan
inter-session.
Berbagai
parameter
yang
telah
diteliti
dan
diperkirakan
mempengaruhi efek rTMS yaitu bentuk kumparan, amplitudo stimulus, frekuensi
dan durasi juga berkontribusi terhadap pengaruh TMS. Secara umum parameter
yang mempengaruhi derajat dan polaritas rTMS dapat dibagi menjadi dua kategori
utama yaitu kategori geometri (misalnya bentuk kumparan TMS) dan waktu
(misalnya frekuensi, durasi stimulus).
a).
Geometri. Berbagai parameter TMS mampu mempengaruhi interaksi
induksi medan listrik dengan neuron kortikal. Interaksi ini menyebabkan eksitasi
40
selektif pada kumpulan saraf tertentu oleh gelombang TMS sementara kumpulan
neuron
lainnya
tidak
terpengaruh.
Terdapat
beberapa
parameter
yang
mempengaruhi ruang lingkup stimulasi yang diyakini memainkan peran penting
dalam interaksi ini. Parameter ini meliputi bentuk geometri dari kumparan TMS,
dan karakteristik gelombang seperti bentuk dan orientasi (Pell et al., 2011).
b) Bentuk kumparan dan penempatannya. Repetitive Transcranial magnetic
stimulation dapat menginduksi arus listrik dalam media apapun tanpa
penghubung. Pada otak, media penghubung tersusun dari jaringan dengan
karakteristik listrik yang beragam. Bentuk kumparan dan lokasi penempatan
kumparan akan mempengaruhi efek TMS terhadap neuron kortikal (Pell et al.,
2011).
c) Interaksi antara medan listrik induksi dengan jaringan saraf. Tujuan stimulasi
listrik atau magnetik pada jaringan adalah memicu terjadinya potensial aksi pada
jaringan saraf. Hal ini membutuhkan depolarisasi neuron pada ambang batas
tertentu. Jika kumparan kita letakkan di atas kepala subjek, medan magnet akan
menembus kulit kepala dan tulang, dan menginduksi medan listrik di otak. Medan
listrik induksi menyebabkan ion mengalir di otak sehingga dapat menstimulasi
kortek. Transcranial magnetic stimulation dapat menstimulasi saraf kortikal tanpa
menimbulkan nyeri bila dibandingkan dengan TES (Pell et al., 2011).
d) Pengaruh bentuk pulse / gelombang dan orientasi. Pada umumnya ada dua
bentuk gelombang TMS yaitu bentuk monopasik dan bipasik. Dengan prinsip arus
osilasi, secara umum gelombang berbentuk sinusoid. Bentuk gelombang dan
orientasi TMS dapat mempengaruhi efek eksitabilitas modulasi kortikal (Pell et
al., 2011).
41
f) Frekuensi. Frekuensi diyakini merupakan penentu kekuatan rangsangan kortikal.
Frekuensi yang tinggi pada penggunaan rTMS > 5 Hz dapat
meningkatkan
rangsangan kortikal, sementara frekuensi yang rendah menurunkan rangsangan
kortikal.
g) Durasi Stimulasi. Lama stimulasi berhubungan dengan bentuk teknik rTMS yang
akan digunakan, secara umum total durasi rTMS yang diberikan tiap sesi adalah
20 menit. rTMS dengan frekuensi rendah menggunakan continous trains,
sementara rTMS dengan frekuensi tinggi menggunakan bursts stimuli berlangsung
5 10 detik. Tabel 1 menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi derajat
eksitabilitas modulasi yang diinduksi rTMS secara lengkap.
Tabel 1. Faktor faktor yang mempengaruhi derajat eksitabilitas modulasi yang
diinduksi oleh rTMS. Dengan faktor-faktor eksperimental yang dibagi subdivisi
klasifikasi waktu (timing) dan geometri.
Timing/Waktu
Frekuensi stimulasi
Durasi train stimulus
Interval inter-train
Total durasi stimulus
Total jumlah pulse
42
Geometri
Posisi kumparan
Intensitas stimulasi
Jarak antara tulang tengkorak dan kortek
Ketepatan posisi
Stabilitas penempatan kumparan
Target kortikal
Susunan dan interaksi dari sirkuit inhibisi dan eksitasi
Karakteristik saraf individu contoh : diameter serabut saraf
Jarak antara kortek dan tulang tengkorak.
Perangkat keras : pemilihan stimulator dan kumparan
Bentuk pulse dan karakteristik
Pengaruh dari daerah yang berhubungan secara fungsional.
Faktor lain
Tergantung pada kondisi dasar dan riwayat sinaptik
Kondisi rangsangan (khususnya inhibisi)
Aktivitas fisiologi
Kesadaran
Perhatian
Pengaruh genetik
Interaksi dengan neurokimia
Monoamin neuromodulator seperti dopamin
Growth factor seperti BDNF
Obat-obatan
Jens kelamin
Usia
Hormonal
Irama sirkardian
Stres
(Pell et al., 2011)
H. Aplikasi Klinis rTMS
Salah satu aplikasi klinis teknik rTMS dibidang neurologi adalah sebagai
terapi tambahan untuk nyeri khususnya nyeri kronis, drug resistant dan nyeri
sentral (nyeri post stroke, complex regional pain syndrome, fibromyalgia,
neuralgia trigeminal, nyeri pantom). Teknik ini memiliki kemampuan
mengaktivasi pelepasan neurotransmiter seperti GABA-ergic yang berperan
43
sebagai pemeran intracortical inhibisi selain plastisitas sinaptik. Hal ini menjadi
salah satu dasar mekanisme penggunaan TMS untuk membantu mengurangi nyeri
terutama nyeri kronis (Lefaucher, 2008).
Disamping itu Transcranial Magnetic Stimulation juga digunakan sebagai
tambahan terapi pada parkinson, distonia, tics, stuttering, tinnitus, spastisitas,
epilepsy, aphasia, hemiparesis post stroke. Transcranial Magnetic Stimulation
mampu memicu pelepasan neuromodulator lainnya seperti dopamin dan growth
factor seperti brain derived neurotrophic factor (BDNF). Kemampuan rTMS
memodulasi fungsi kortikal secara persisten telah membuka pintu penggunaan
rTMS sebagai terapi yang potensial pada beberapa kelainan saraf (Pell et al.,
2011).
Penelitian yang dilakukan oleh Lefaucher et al. (2001) menggunakan
teknik rTMS pada 18 pasien dengan intractable nyeri neuropati pada kortek
motorik dengan frekuensi 10 Hertz (Hz) dan 0,5 Hertz (Hz) dengan durasi 20
menit. Pengurangan nyeri secara signifikan didapatkan pada penggunaan rTMS
dengan frekuensi 10 Hertz (Hz). Leufacher et al. (2004) menggunakan rTMS
untuk nyeri sentral post stroke pada 24 subjek dengan frekuensi 10 Hz dan durasi
20 menit, nyeri dapat berkurang secara signifikan.
Penelitian lain yang dilakukan oleh Pleger et al. (2003) menggunakan
rTMS dengan cTBS yang diletakkan di kortek motorik pada 10 penderita CRPS
tipe 1 ternyata dapat mengurangi intensitas nyeri yang terjadi 30 detik setelah
stimulasi dan efek maksimal didapatkan 15 menit setelah stimulasi.
44
Mhala et al. (2010) meneliti efek analgesik TMS yang diletakkan di atas
kortek motorik pada 40 pasien yang menderita chronic widespread pain yang
disebabkan fybromyalgia. Sebanyak 20 pasien mendapatkan rTMS secara aktif
dan 20 pasien lainnya menerima sham rTMS, intensitas nyeri dapat berkurang
pada pasien yang mendapatkan rTMS aktif pada hari ke 5 stimulasi bertahan
sampai minggu ke 25. Efek analgesik rTMS pada penderita fibromyalgia
berhubungan dengan perbaikan jangka panjang pada kualitas hidup dan secara
langsung berhubungan dengan perubahan intrakortikal inhibisi.
Studi meta analisis Leung et al. (2009) meneliti efek analgesik rTMS pada
beberapa kondisi nyeri neuropatik. Ternyata didapatkan bahwa visual analog
scale (VAS) berkurang secara signifikan pada penderita yang diterapi
menggunakan rTMS aktif dibanding sham rTMS. Begitu pula dengan penggunaan
rTMS dengan frekuensi rendah dengan sesi terapi yang lebih frekuen menurunkan
skor VAS pada penderita nyeri neuropati. Menurut Leung et al. (2009) rTMS lebih
efektif bila digunakan pada penderita nyeri neuropati sentral dibanding nyeri
neuropati perifer.
O'Connell et al. (2010) mengevaluasi efikasi teknik noninvasive brain
stimulation pada 368 penderita nyeri kronik. Mendapatkan hasil ternyata TMS
frekuensi rendah tidak efektif dalam mengurangi nyeri. Efek yang singkat dalam
mengurangi rasa nyeri didapatkan pada pemberian TMS single dose dengan
frekuensi tinggi pada kortek motorik nyeri berkurang sebanyak 15 %.
I. Keamanan dan efek samping
45
Meskipun TMS dikenal sebagai terapi adjuvant yang relatif aman, namun
penggunaan alat ini juga memiliki beberapa efek samping. Efek samping TMS
yang utama adalah dapat menginduksi seizure. Meningkatkan ambang
pendengaran, mempengaruhi fungsi kognitif yang bersifat sementara hal ini
terlihat pada beberapa hasil test kognitif yang dilakukan setelah pemberian TMS,
syncope juga pernah terjadi setelah pemberian TMS. Nyeri kepala, nyeri lokal,
rasa panas pada kepala dan ketidaknyamanan juga dirasakan pada beberapa pasien
setelah pemberian rTMS. Berikut rangkuman tabel mengenai efek samping
penggunaan TMS (Rossi et al., 2009).
Tabel 2. Efek samping penggunaan TMS
Efek
samping
Single-pulse
TMS
Paired-pulse
TMS
Low
frequency
rTMS
Jarang
(biasaya
bersifat
protektif)
Kejang
Jarang
Tidak ada
laporan
Perubahan
pendengaran
sementara
Perubahan
fungsi
kognitif
Possible
Tidak ada
laporan
Tidak ada
laporan
Tidak ada
laporan
Nyeri
kepala, nyeri
lokal, nyeri
leher.
Syncope
Heat burn
Mungkin
Tidak ada
laporan
Tidak ada
laporan
Tidak ada
laporan
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
High
frequency
rTMS
Possible
terutama pada
pendeita
epilepsi 1,4%
kejadian. Pada
orang normal
kurang dari 1
%.
Possible
Theta burst
Possible ( satu
serangan pada
individu
normal)
Tidak ada
laporan.
Perubahan
sementara
pada working
memory
Possible
Possible
(Rossi et al.,2009 )
46
Ada empat parameter yang harus ditetapkan dalam penggunaan dosis TMS
antara lain intensitas, frekuensi, train duration, dan inter-train interval. Hal ini
juga digunakan untuk menentukan jumlah total gelombang per sesi, jumlah sesi
per hari, jumlah sesi hari per minggu.
Berdasarkan Safety, ethical considerations, and application guidelines for
the use of transcranial magnetic stimulation in clinical practice and research
(2009): (1). Intensitas stimulasi, intensitas stimulasi yang diberikan umumnya
berdasarkan motor threshold (MT) bersifat individual. Intensitas stimulasi
bervariasi antara satu pasien dengan lainnya. Intensitas stimulasi merupakan
persentase dari MT, yang biasa digunakan dan telah terbukti aman serta efektif
berkisar 80%, 100%, dan 120% MT. Semakin tinggi intensitas stimulasi semakin
banyak neuron yang dapat direkrut, (2). Train duration.
Berdasarkan alasan
keamanan dan karena keterbatasan fisik alat TMS tersebut (kumparan menjadi
panas dan keterbatasan kemampuan dari alat tersebut) maka terapi diberikan
dalam bentuk trains stimuli pada setiap sesi dan bukan dalam bentuk stimulasi
yang terus-menerus (continous stimulation). Pengecualian pada pemakaian TMS
dengan frekuensi rendah biasanya diberikan secara continous tanpa interval. Hal
ini dikarenakan risiko kejang dengan pemakaian frekuensi rendah dapat
diabaikan. Saat menggunakan intensitas 100% MT, train duration maksimum
untuk masing-masing frekuensi adalah 5 Hz : 10 detik, 10 Hz : 5 detik, 20 Hz :
detik. Saat menggunakan intensitas 120% MT train duration maksimal adalah 5
Hz : 10 detik, 10 Hz : 4 detik, 20 Hz :1 detik, (3). intertrain interval. Tidak ada
konsensus atau ketetapan berapa intertrain interval yang harus digunakan minimal
47
2 detik yang disarankan untuk frekuensi lebih dari 5 Hz dan minimal 5 detik
untuk frekuensi 20 Hz. Dalam praktek klinik, intertrain interval dihitung dengan
cara mengurangi train duration dengan 30 detik, sebagai contoh untuk intensitas
100% MT maka : 5 Hz untuk 10 detik maka intertrain interval 20, 10 Hz untuk 5
detik maka intertrain interval 25 detik, 20 Hz untuk 2 detik intertrain interval 28
detik. Telah ditetapkan bahwa stimulasi dengan frekuensi 1 Hz diberikan secara
terus menerus (continous) tanpa ada intertrain interval, (4). Frekuensi. Frekuensi
menjelaskan pengulangan gelombang perdetik. Diukur dengan hertz (HZ).
Umumnya frekuensi yang ditetapkan adalah 1 Hz, 5 Hz, 10 Hz, dan 20 Hz.
Berikut ini tabel yang menggambarkan dosis penggunaan TBS pada orang normal
yang tidak menimbulkan efek samping.
Tabel 3. Protokol Theta burst stimulation pada orang normal, tidak ada efek
samping yang dilaporkan.
Pulse in the Total train pulse
Tempat stimulasi
Intensitas
burst
Standar cTBS
(Huang et al.
2005)
Protokol
Standar iTBS
(Huang et al.
2005)
Sylvanto et
al.,2007 cTBS
3 pulse pada 600 (40 detik)
frekuensi 50
Hz, diulang
pada 5 Hz
3 pulse pada 600
frekuensi 50 Hz
diulang pada 5
Hz.
8 pulse pada
frekuensi 40 Hz
diulang
setiap
1,8 detik
200
80 % aktif MT
Motor cortex
80 % aktif MT
Motor cortex
80 % aktif MT
Motor cortex
(Rossi et al., 2009)
pada penggunaan cTBS, intensitas yang digunakan adalah 90 % resting
motor threshold (RMT), setara dengan 120 % active motor threshold (AMT).
48
BAB III
RINGKASAN
Repetitive Transcranial magnetic stimulation (rTMS) merupakan metode
stimulasi kortek noninvasif, painless dapat digunakan sebagai terapi tambahan
pada beberapa kasus dalam bidang neurologi. Salah satunya sebagai terapi
tambahan pada nyeri kronis seperti drug resistant dan nyeri sentral (nyeri post
stroke, complex regional pain syndrome, fibromyalgia, neuralgia trigeminal, nyeri
pantom).
Ada tiga macam teknik TMS yang digunakan, antara lain (1). Single-pulse
TMS, (2). Paired pulse TMS, dan (3). Repetitive TMS yang dibagi conventional
dan patterened rTMS. Stimulasi rTMS mampu menghasikan efek analgesik
dengan cara (a). mempengaruhi perubahan komponen sensori-discriminative dan
motivasional afektif yang terlibat dalam proses nyeri, (b). memperbaiki plastisitas
sinaptik melalui long term potentiation (LTP) dan long term depression (LTD) dan
(c). sistem opioid endogen sehingga dapat membantu memperbaiki descending
modulasi
Disamping dapat mengurangi nyeri, TMS juga memiliki efek samping.
Efek samping yang paling berat adalah kejang. Efek TMS juga dipengaruhi oleh
beberapa variabilitas seperti geometri, penempatan kumparan, frekuensi, durasi
stimulasi, bentuk gelombang, interaksi antara medan listrik induksi dengan
jaringan saraf. Secara umum dibagi menjadi dua kategori utama yaitu faktor
waktu dan geometri.
49
Daftar Pustaka
Andersen S., Worm-Petersen, J., 1988. The prevalence of persisten pain on Danish
Population. Pain , 332.
Andrade D. C., Mhalla, A., Adam, F., Texeira, M. J., & Bouhassira, D., 2011.
Neuropharmacological basis of rTMS-induced analgesia: The role of
endogenous opioids. Pain , 320-326.
Anonim 2008. The Burden of Pain Among Adult in United State. United State:
Pfizer medical division.
Baumer T., Lange, R., Liepert, J., 2003. Repeated premotor rTMS leads to
cumulative plastic changes of motor cortex excitability in humans.
Neuroimage; 20: 5505.
Barker A., 2002. The history and basic principles of magnetic nerve stimulation
dalam. Handbook of transcranial magnetic stimulation, hal. 15-17.
Bittar G.R., Purkayastha K.I.,Owen L.S., Bear R.E., Green A.,Wang Y.S., 2005.
Deep brain stimulation for pain relief, Journal clinical of neuroscience.
Cooke S. F., Bliss T. V., 2006. Plasticity in the human central nervous system.
Brain , 16591673.
Crucu G., Azis T.Z., Garcia-Larrea L., Hansson P., Jensen T.S., Lefaucher J.P.,
2007. EFNS guidelines on neurostimulation therapy for neuropathic pain.
European Journal of Neurology, 14: 952970.
Davey., 2002. Handbook of transcranial magnetic stimulation. A Hodder Arnold
Publication.
Demers D., 2011. Spinal cord stimulation. Biomedical engineering, 281.
Extra I., 2010. Chronic Pain Management. USA.
Fregni F., Freedman S., Pascual-Leone A., 2007. Recent advances in the treatment
of chronic pain with non-invasif brain stimulation techniques. Lancet
Neurol , 1881-91.
Fregni F., Boggio P.S., Lima M.C., 2006. New insight into the therapeutic
potential of noninvasif transcranial cortical stimulation in chronic
neurophatic pain. Pain, 11-13.
Greene S. A., 2010. Chronic pain : pathophysiology and treatment implications.
Washington: Elsevier Inc. Neurology. Neurology , 145-158.
Lefaucher J.P., Drout X., Nguyen J.P., 2001. Interventional neurophysiology for
pain control. Duration of pain relief following of repeti tive transcranial
magnetic stimulation of the motor cortex . Neurophysiol clin, 31, 247-249.
Lefaucher J.P., Drout X., Menar-Lefaicher I., Nguyen J.P., 2004. Neurophatic pain
control for more than a year by monhtly session by repetitive transcranial
magnetic stimulation. Neurophysiol clin, 34, 91-95.
Lefaucher J.P., 2006. The use of Repetitive transcranial magnetic stimulation in
chronic neuropathic pain. Neurophysiologie Clinique, 36,177-124.
Lefaucher J.P., 2008. Use of repetitive transcranial magnetic stimulation in pain
relief. Expert Rev Neurotherapeutics 8(5), , 799-808.
50
Loeser J., 1999. The physiology, biochemistry, classification and assesment of
pain. Dalam E. A. Shipon., Pain Acute and Chronic (hal. 1-5). London:
Oxford University.
Leung A., Donohue M, Xu, R., 2009. rTMS for suppressing neuropathic pain: a
meta-analysis. Journal of Pain. 10(12): 1205-1216
Mhala A., Benedict S., Andrade D.C., Gantron M., Perrot S., 2010. Long-Term
Maintanance of Analgesic Effects of rTMS in Fibromyalgia, Pain, 14781485.
Meliala K.L., 2008. Patofisiologi nyeri. Dalam Nyeri neuropatik (hal. 1-9).
Yogyakarta: Medikagama press.
Noordhout A.M., 2006. General principle for clinical use of repetitive transcranial
magnetic stimulation (rTMS). Neurophysiologie clinique 36 , 97-103.
O'Connell N.E., Wand B.M., Marston L., Spencer S., Desouza L.H., 2010. Noninvasif brain stimulation techniques for chronic pain. Cochrane Database
Syst Rev.
Pell G.S., Roth Y., Zangen A., 2011. Modulation of cortical excitability induced
by repetitive transcranial magnetic : Influence of timing and geometrical
parameters and underlying. Progress in Neurobiology , 59-98.
Peter Croft F.M., 2010. Chronic Pain Epidemiology. USA: Oxford University
Press.
Perdossi., 2011. Diagnosis dan penatalaksanaan nyeri neuropatik. Konsensus
Nasional 1. Airlangga University Press.
Pleger B., Jansen F., Schwenkreis P., Volker B., 2003. Repetitive transcranial
magnetic stimulation on the motor cortex attenuates pain perseption in
CRPS Type 1, Neuroscience Letter, 87-90.
Pridmore S., Oberoi G., Transcranial magnetic stimulation (TMS) in chronic pain,
2005. studies in waiting. Journal of the Neurological Sciences; 182: 14.
Renin C.L., Dorsey S.G., 2005. The Physiology and Processing of Pain , AACN
clinical issues, vol 3, 277 - 290.
Ridding M.C., Rothwell J.C., 2007. Is there a future for therapeutic use of
transcranial magnetic stimulation?. Perspective, vol 8, 559-565.
Rosa A.M., 2012. History of Transcranial magnetic stimulation, Transcranial
magnetic stimulation, Neurosoft.
Rossi S., Hallet M., Rossini P. M., Leono A.P., 2009. Safety, ethical
considerations, and application guidelines for the use of transcranial
magnetic stimulation in clinical practice and research. Clinical
Neurophysyiology , 2011-2012.
Ruiz-Lpez R.,1995. The epidemiology of chronic pain. Pain digest , 76-78.
Serge M., 2010. Applied pain neurophysiology. Dalam P. Beaulieu,
Pharmacology of pain (hal. 3-19). Seattle: IASP Press.
Shipton E. A., 1999. The physiology, biochemistry, classification and assesment of
pain. Dalam Pain Acute and Chronic (hal. 1-3). London: Oxford
University.
Weiner K., 2008. Pain Is An Epidemic. American Academy of Pain Management.
51
52
Anda mungkin juga menyukai
- Stimulasi Magnetik TranskranialDokumen24 halamanStimulasi Magnetik TranskranialEdwinSitorusBelum ada peringkat
- Panduan Pemeriksaan Transmagnetik StimulationDokumen15 halamanPanduan Pemeriksaan Transmagnetik StimulationNadia Sani amaliaBelum ada peringkat
- Tutorial Klinik: Disusun Untuk Memenuhi Syarat Kelulusan Kepaniteraan Klinik Bagian Ilmu Saraf RSUD Kota SalatigaDokumen45 halamanTutorial Klinik: Disusun Untuk Memenuhi Syarat Kelulusan Kepaniteraan Klinik Bagian Ilmu Saraf RSUD Kota SalatigaRima Nur AnnisaBelum ada peringkat
- Frontal Assessment BatteryDokumen3 halamanFrontal Assessment Batteryalvin100% (1)
- Tatalaksana Nyeri Kanker Pada Pasien DewasaDokumen39 halamanTatalaksana Nyeri Kanker Pada Pasien DewasaKelas A 2016 Kedokteran TropisBelum ada peringkat
- EkstrapiramidalDokumen8 halamanEkstrapiramidalJustisia PadmiyatiBelum ada peringkat
- Pembahasan Neurologi PDFDokumen361 halamanPembahasan Neurologi PDFKlemensius DevinBelum ada peringkat
- Neurotrauma PDFDokumen43 halamanNeurotrauma PDFCepti JuandaBelum ada peringkat
- TCDDokumen30 halamanTCDOktaria LutfianiBelum ada peringkat
- Referat Saraf TCD WordDokumen22 halamanReferat Saraf TCD WordVivi Anggelia AngBelum ada peringkat
- Penyuluhan EpilepsiDokumen16 halamanPenyuluhan EpilepsiNaurah Al-HaddadBelum ada peringkat
- Instrumen Pemeriksaan Moca-InaDokumen1 halamanInstrumen Pemeriksaan Moca-InaNadha Noedha Eno WitaroliBelum ada peringkat
- NeurorestorasiDokumen15 halamanNeurorestorasiPutri RahmawatiBelum ada peringkat
- Pemeriksaan Status Mental Strub Dan Black Versi IndonesiaDokumen1 halamanPemeriksaan Status Mental Strub Dan Black Versi IndonesiaNastiti WidyariniBelum ada peringkat
- Tutorial Klinik - TmsDokumen24 halamanTutorial Klinik - TmsMaulana Iman SaputraBelum ada peringkat
- Demensia VaskularDokumen38 halamanDemensia VaskularJamaludin CrbBelum ada peringkat
- Abe's BPSD ScoreDokumen1 halamanAbe's BPSD Scorezefri suhendarBelum ada peringkat
- Bab 2 NeurogeriatriDokumen56 halamanBab 2 NeurogeriatriRanintha Surbakti100% (1)
- PENYULUHAN Parkinson Edit PDFDokumen15 halamanPENYULUHAN Parkinson Edit PDFAb RamadhanBelum ada peringkat
- Laporan Kasus AthetosisDokumen31 halamanLaporan Kasus AthetosisMekki Lazir IlhdafBelum ada peringkat
- Transcranial Magnetic StimulationDokumen24 halamanTranscranial Magnetic StimulationhendrikusBelum ada peringkat
- Klinik Pikun Dini Atau EDokumen4 halamanKlinik Pikun Dini Atau Efajarrudy qimindraBelum ada peringkat
- 5 MODUL Neuro ONKOLOGI MODUL INDUKDokumen22 halaman5 MODUL Neuro ONKOLOGI MODUL INDUKPriscilla Christina NatanBelum ada peringkat
- Presentasi Capsula InternaDokumen38 halamanPresentasi Capsula InternaevaBelum ada peringkat
- Glasgow Outcome Scale AnesthesiologDokumen18 halamanGlasgow Outcome Scale AnesthesiologNidyBelum ada peringkat
- Neurotrauma SDH UGMDokumen12 halamanNeurotrauma SDH UGMAnonymous A9R0aLsBelum ada peringkat
- CATATAN EMG by Sep 2nd EditionDokumen93 halamanCATATAN EMG by Sep 2nd Editionkonsultasi IRNA 1Belum ada peringkat
- Makalah Word Adam Victor Bab 1 Dan 2Dokumen69 halamanMakalah Word Adam Victor Bab 1 Dan 2Rumah Penginapan Candi YogyakartaBelum ada peringkat
- EEG 2 - Abnormalitas Non-Epileptiform-Ppt - HelenDokumen52 halamanEEG 2 - Abnormalitas Non-Epileptiform-Ppt - HelenOvariadi AnwarBelum ada peringkat
- Trauma ANLS Semarang eDokumen130 halamanTrauma ANLS Semarang ePrima MaulanaBelum ada peringkat
- Intermittent Rhythmic Delta ActivityDokumen32 halamanIntermittent Rhythmic Delta ActivitymariaBelum ada peringkat
- Modul Neuro Infeksi Panduan Peserta PDFDokumen158 halamanModul Neuro Infeksi Panduan Peserta PDFAmeldaBelum ada peringkat
- Tentang TMS (Transcranial Magnetic Stimulation)Dokumen8 halamanTentang TMS (Transcranial Magnetic Stimulation)Aditya Kusuma100% (1)
- Pemeriksaan HachinskiDokumen5 halamanPemeriksaan Hachinskirido rhomaBelum ada peringkat
- Status Coass Bagian NeurologiDokumen1 halamanStatus Coass Bagian NeurologiFahri Dwi PermanaBelum ada peringkat
- Space Occupying Lesion Intrakranial Dan Halusinasi OrganikDokumen12 halamanSpace Occupying Lesion Intrakranial Dan Halusinasi OrganikJane MillerBelum ada peringkat
- Therapeutic Plasma ExchangeDokumen109 halamanTherapeutic Plasma ExchangeNysia PriscillaBelum ada peringkat
- Soal NeurologiDokumen48 halamanSoal NeurologiFitri Nur DiniBelum ada peringkat
- Modul Neurobehavior Buku AcuanDokumen49 halamanModul Neurobehavior Buku AcuanJuliet Christy100% (1)
- RehabMedik - Dr. Lidwina S. Sengkey, SPKFR - ASPEK REHABILITASI MEDIK PADA PARKINSONDokumen41 halamanRehabMedik - Dr. Lidwina S. Sengkey, SPKFR - ASPEK REHABILITASI MEDIK PADA PARKINSONRiscky Lauw100% (2)
- TBR Analgesik Pada NeurologiDokumen18 halamanTBR Analgesik Pada NeurologifitraniaputriBelum ada peringkat
- Pemeriksaan Fisik Koordinasi Dan Keseimbangan ULYDokumen22 halamanPemeriksaan Fisik Koordinasi Dan Keseimbangan ULYClara ShintaBelum ada peringkat
- Imanuel R. Patty Jurnal Vestibular MigraineDokumen18 halamanImanuel R. Patty Jurnal Vestibular MigraineDita LewaherillaBelum ada peringkat
- Penyuluhan EpilepsiDokumen12 halamanPenyuluhan EpilepsiGaluh Maharani SukmaBelum ada peringkat
- Neuro Neurogenic BladderDokumen4 halamanNeuro Neurogenic BladderKia SikembarBelum ada peringkat
- Neuro OnkologiDokumen20 halamanNeuro Onkologidian_c87Belum ada peringkat
- Referat Neurobehavior Pada EpilepsiDokumen15 halamanReferat Neurobehavior Pada EpilepsiIndra SilaenBelum ada peringkat
- Mati Otak - A MawuntuDokumen60 halamanMati Otak - A MawuntuBernie BernardusBelum ada peringkat
- Pemeriksaan Klinis NeurologiDokumen52 halamanPemeriksaan Klinis NeurologithyadinarBelum ada peringkat
- Stimulasi Magnetik Transcranial - Belajar Neurofisiologi Motorik Dari Gangguan KejiwaanDokumen25 halamanStimulasi Magnetik Transcranial - Belajar Neurofisiologi Motorik Dari Gangguan KejiwaanDwijayanti HutapeaBelum ada peringkat
- Mati Batang OtakDokumen17 halamanMati Batang OtakRakha buchoriBelum ada peringkat
- Kompilasi MCQ Multicenter SDH Di Bahas Nyerinya Osce 21-9-2016Dokumen85 halamanKompilasi MCQ Multicenter SDH Di Bahas Nyerinya Osce 21-9-2016Aditya KurniantoBelum ada peringkat
- Soal Unsri MCQDokumen16 halamanSoal Unsri MCQAditya KurniantoBelum ada peringkat
- Referat BPSDDokumen18 halamanReferat BPSDmissbunawan90Belum ada peringkat
- Tumor Medula Spinalis Intradural ExtramedulaDokumen7 halamanTumor Medula Spinalis Intradural ExtramedulaGrace PraingBelum ada peringkat
- Nyeri NeuropatikDokumen8 halamanNyeri NeuropatikfaridahakimlBelum ada peringkat
- Referat Final TMSDokumen52 halamanReferat Final TMSAnsyah EdisonBelum ada peringkat
- Pengaruh Muscle Energy Technique Dan Strain Counterstrain Terhadap Nyeri Tengkuk Pada Penderita Myofacialis Upper TrapeziusDokumen9 halamanPengaruh Muscle Energy Technique Dan Strain Counterstrain Terhadap Nyeri Tengkuk Pada Penderita Myofacialis Upper Trapeziusmuhammad yaminBelum ada peringkat
- Jurnal Nyeri TengkukDokumen9 halamanJurnal Nyeri TengkukNaella HafidhahBelum ada peringkat
- Manajemen NyeriDokumen5 halamanManajemen NyeriBaby RoseBelum ada peringkat
- Know Pain in Daily Practice - Role of Celecoxib and Pregabalin-1Dokumen40 halamanKnow Pain in Daily Practice - Role of Celecoxib and Pregabalin-1Peter PrastBelum ada peringkat
- Proposal PIR 2022 Revisi BaruDokumen15 halamanProposal PIR 2022 Revisi BaruPeter PrastBelum ada peringkat
- Presentasi Kasus Infeksi September 2015Dokumen16 halamanPresentasi Kasus Infeksi September 2015Peter PrastBelum ada peringkat
- Panduan Koass NeurologiDokumen30 halamanPanduan Koass NeurologiPeter PrastBelum ada peringkat
- Buku Program Semnas UNSOED 2021Dokumen86 halamanBuku Program Semnas UNSOED 2021Peter PrastBelum ada peringkat
- Pemeriksaan Elektrokardiogram Patologis +daftar TiliknyaDokumen54 halamanPemeriksaan Elektrokardiogram Patologis +daftar TiliknyaPeter PrastBelum ada peringkat
- Skill Lab Pemeriksaan Mammae PatologiDokumen14 halamanSkill Lab Pemeriksaan Mammae PatologikemalBelum ada peringkat
- 10 Pemeriksaan Keseimbangan Dan KoordinasiDokumen6 halaman10 Pemeriksaan Keseimbangan Dan KoordinasiPeter PrastBelum ada peringkat
- Skill Lab Pemeriksaan Spirometri Modul 3 April 2017Dokumen11 halamanSkill Lab Pemeriksaan Spirometri Modul 3 April 2017Peter PrastBelum ada peringkat
- TBR Pemeriksaan Neurobehavior-Balqis Amatulloh-G1A016024Dokumen11 halamanTBR Pemeriksaan Neurobehavior-Balqis Amatulloh-G1A016024Peter PrastBelum ada peringkat
- PPK 14 VertigoDokumen4 halamanPPK 14 VertigoPeter PrastBelum ada peringkat
- Pemeriksaan Saraf Kranial 1.6 2019Dokumen21 halamanPemeriksaan Saraf Kranial 1.6 2019Peter PrastBelum ada peringkat
- TBR Neurobehaviour - Rizki Agung Nugraha - G1A016036Dokumen22 halamanTBR Neurobehaviour - Rizki Agung Nugraha - G1A016036Peter PrastBelum ada peringkat
- PPK 13 EpilepsiDokumen5 halamanPPK 13 EpilepsiPeter PrastBelum ada peringkat
- Panduan Dokter Muda Saraf New NormalDokumen28 halamanPanduan Dokter Muda Saraf New NormalPeter PrastBelum ada peringkat
- Rancangan Aktualisasi IndahDokumen55 halamanRancangan Aktualisasi IndahPeter PrastBelum ada peringkat
- Modul Nyeri KepalaDokumen24 halamanModul Nyeri KepalaPeter PrastBelum ada peringkat
- Format DRH NIDN UnsoedDokumen2 halamanFormat DRH NIDN UnsoedPeter PrastBelum ada peringkat
- Daftar Riwayat HidupDokumen2 halamanDaftar Riwayat HidupPeter PrastBelum ada peringkat