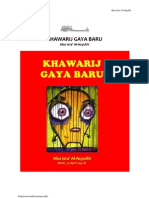Iman dan Kufur Menurut Aliran Khawarij dan Lainnya
Diunggah oleh
Iqbal Taufiqurrochman0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
994 tayangan9 halamanRingkuman dari dokumen tersebut adalah:
1. Beberapa aliran Islam memiliki pandangan berbeda tentang iman dan kufur
2. Khawarij menganggap pelaku dosa besar sebagai kafir, sedangkan Murji'ah menganggapnya tidak mempengaruhi iman
3. Mu'tazilah menganggap pelaku dosa besar bukan beriman atau kafir tetapi berada di antara keduanya
Deskripsi Asli:
teosofi
Judul Asli
Iman Dan Kufur Menurut Menurut Aliran Khawarij
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniRingkuman dari dokumen tersebut adalah:
1. Beberapa aliran Islam memiliki pandangan berbeda tentang iman dan kufur
2. Khawarij menganggap pelaku dosa besar sebagai kafir, sedangkan Murji'ah menganggapnya tidak mempengaruhi iman
3. Mu'tazilah menganggap pelaku dosa besar bukan beriman atau kafir tetapi berada di antara keduanya
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
994 tayangan9 halamanIman dan Kufur Menurut Aliran Khawarij dan Lainnya
Diunggah oleh
Iqbal TaufiqurrochmanRingkuman dari dokumen tersebut adalah:
1. Beberapa aliran Islam memiliki pandangan berbeda tentang iman dan kufur
2. Khawarij menganggap pelaku dosa besar sebagai kafir, sedangkan Murji'ah menganggapnya tidak mempengaruhi iman
3. Mu'tazilah menganggap pelaku dosa besar bukan beriman atau kafir tetapi berada di antara keduanya
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 9
Iman dan Kufur Menurut Menurut Aliran Khawarij
Awal kemunculan sebuah aliran terkadang mendahului bangunan
pemikiran di dalamnya, akan tetapi setelah ia mampu
mempertahankan eksistensinya dikancah pergolakan pemikiran
dengan sejumlah pendukungnya, maka lahirlah tokoh dengan
mengusung bangunan pemikiran yang apik.[2]
Sebentuk ideologi yang mengukuh dan mengokoh menjadi
mazhab resmi tentunya tidak meraksasa begitu saja. Butuh
proses dan waktu yang membuatnya kian besar hasil akumulasi
pergumulan pemikiran, Demikian halnya yang terjadi dalam
kubuh khawarij.
Aliran ini merumuskan dasar-dasar pemikirannya untuk berdiri
tegak ditengah pergolakan, baik yang sifatnya external maupun
internal aliran. Hal ini mengindikasikan adanya perpecahan
dalam kubuh khawarij, namun tetap memiliki kesamaan
mengenai pokok-pokok ajaran. Diantara pokok ajaran tersebut
ialah persoalan pelaku dosa besar.[3]Berbicara masalah dosa
besar maka secara tidak langsung hal itu berkaitan dengan
persoalan Iman dan Kufur.
Khawarij, terlepas dari pelbagai aliran di dalamnya, menganggap
bahwa menjalankan perintah agama seperti shalat, puasa,
kejujuran, serta menegakkan keadilan merupakan bagian dari
iman. Menurut pandangan mereka, iman tidak hanya terbatas
pada keyakinan dalam hati. Maka ketika seseorang meyakini
keesaan Allah dan nabi Muhammad sebagai rasul tetapi tidak
menjalankan perintah agama dan melakukan dosa besar maka
menurut pandangan Khawarij mereka termasuk dalam kategori
kafir.[4]
Hal itu tidak mengherankan, karena kebanyakan penganut aliran
tersebut dari kalangan Arab baduwi sehingga As-syahrastani
memberikan gelar kepada mereka sebagai golongan yang taat
berpuasa dan shalat serta seringkali mengucilkan pembohong
dan pelaku maksiat.[5]
Mereka beranggapan bahwa iman adalah pengakuan hati serta
penuturan lidah mengenai keesaan Allah dan Muhammad adalah
rasulnya, menunaikan kewajiban serta menghindari perbuatan
dosa besar.[6] Meskipun subsekte Khawarij yang sangat ekstrim,
Azariqah menggunakan istilah yang lebih mengerikan daripada
kafir yaitu musyrik bagi siapa saja yang berada diluar golongan
mereka. Sedangakan pelaku dosa besar telah beralih
keimanannya menjadi kafir millah dan kekal di neraka.
Begitu halnya dengan subsekte Najdah yang memberikan
predikat musyrik bagi pelaku dosa kecil secara
berkesinambungan dan predikat kafir bagi pelaku dosa besar
yang tidak dilakukan secara kontinyu.[7] Berdasarkan hal
tersebut, yang menjadi titik temunya ialah Khawarij menilai
orang yang melakukan dosa besar keimanannya serta merta
akan hilang dan orang yang kehilangan keimanannya itu berarti
termasuk dalam golongan kafir.
Namun, tak bisa dipungkiri adanya subsekte Khawarij yang
tergolong moderat yaitu Ibadiyah. subsekte ini berpendapat
bahwa pelaku dosa besar tetap sebagai muwahhid (yang
mengesakan Tuhan), tetapi bukan mukmin. Ia tetap disebut kafir
tapi hanya merupakan kafir nikmat (mengingkari nikmat) bukan
kafir millah (agama). Siksaan yang akan mereka terima di akhirat
nanti adalah kekal di dalam neraka bersama orang-orang kafir
lainnya.[8]
Iman dan Kufur Menurut Menurut Aliran Al-Murjiah
Pandangan Murjiah dalam hal iman dan kufur ada keterkaitan
dengan kesenjangan yang terjadi dalam kubuh umat Islam
setelah peristiwa pembunuhan khalifah ketiga Usman bin Affan
r.a. Berbeda dengan beberapa aliran lainnya yang berakar politik
dan kemudian membentuk bangunan pemikiran teologi, faham
Murjiah sebagai gerakan non blok yang tidak memihak kepada
kelompok tertentu.
Kata Murjiah itu sendiri merupakan derivasi dari kata arjaa yang
mempunyai makna yang beragam. Diantaranya berarti
mengakhirkan sesuatu. Berdasarkan makna ini, maka Murjiah
ialah faham yang menganggap bahwa perselisihan yang terjadi
dikalangan umat Islam terkait pembunuhan Usman bin Affan,
keputusannya di tangguhkan hingga hari kiamat.
Kata arjaa juga berarti membangkitkan sebuah harapan.
Berangkat dari makna ini, maka Murjiah adalah mereka yang
berkeyakinan bahwa perkara iman dan kufur adalah perkara hati.
Sehingga slogan mereka ialah
Dosa tidak berarti apa-apa selama masih ada iman.
Demikian halnya ke-kufuran tidak berarti apa-apa selama masih
ada ketaatan.
Ibnu Asakir menguraikan pandangan kelompok Murjiah terkait
fitnah kubra yang terjadi dikalangan sahabat bahwa setelah
mereka kembali ke Madinah dari peperangan dan seusai
peristiwa terbunuhnya khalifah ketiga, mereka mengatakan
pada saat kami meninggalkan Madinah kalian dalam keadaan
bersatu dan tak ada perpecahan diantara kalian. Setelah kami
kembali, kalian dalam keadaan berselisih.
Diantara kalian ada yang menganggap bahwa Usman bin Affan
yang merupakan sahabat yang paling adil terbunuh. Sebagian
menganggap Ali merupakan sahabat yang paling benar. Kami
(Murjiah) tidak meragukan kejujuran para sahabat. Kami tidak
memihak atau menyalahkan salah satu diantara mereka. Perkara
itu kami serahkan kepada Allah.[9]
Dalam hal ini, Mereka menilai bahwa keimanan ialah keyakinan
terhadap Allah dan Rasulnya. Maka barangsiapa yang
mengikrarkan dalam hati kalimat syahadat, maka hal itu sudah
cukup untuk memasukkan mereka kedalam barisan orang-orang
yang beriman meskipun ia mengaku kafir, menyembah berhala
dan mati dalam keadaan tersebut meskipun tidak
mendemonstrasikannya dalam ucapan maupun tindakan.
Demikian halnya Perbuatan dosa tidak dapat menciderai
keimanan, sebagaimana ketaatan pun tidak memberi pengaruh
terhadap keimanan. Dalam pandangan mereka, iman sifatnya
statis dan tidak terpengaruh oleh prilaku seseorang karena
prilaku bukan bagian dari Iman.
Iman dan Kufur Menurut Menurut Aliran Al-Mutazilah
Mutazilah merupakan salah satu aliran yang paling menonjol
dikancah pemikiran Islam. Ia mengkristal dengan bangunan
pemikirannya di akhir abad pertama hijriah. Pentas pemikiran
saat itu tidak sunyi dari berbagai pemikiran lainnya yang ikut
mewarnai langit pemikiran saat itu. Dalam kondisi demikian,
Mutazilah hadir dengan lima tiang dasar pemikirannya. Al-adl,
at-tauhid, al-wadu wa al-waid, al-manzilah bain al-manzilatain,
al-amr bi al-maruf wa an-nahyu an al-munkar.[10]
Berdasarkan al-Ushul al-Khamsah ini. Khususnya Al-wadu wa al-
waid, Mutazilah menganggap bahwa iman tidak hanya sekedar
pengakuan hati akan tetapi harus disertai perbuatan yang
merupakan bukti pengakuan hati. Dalam hal ini mereka sejalan
dengan khawarij yang juga mendefenisikan keimanan sebagai
sesuatu yang tidak hanya sekedar keyakinan tanpa wujud nyata
dalam pengamalan nilai.
Adapun persoalan pelaku dosa besar. mereka menolak
pandangan Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Juga
murjiah yang menganggap dosa besar tidak sedikitpun
mengeruhkan keimanan seseorang, serta pendapat gurunya
Hasan al-Bashri yang menggolongkan pelaku dosa besar sebagai
munafik.
Dalam pandangan Mutazilah, pelaku dosa besar tidak termasuk
dalam kategori beriman dan tidak pula termasuk golongan kafir
ataupun munafik akan tetapi fasik. mereka berada diantara
golongan orang beriman dan kafir, ia kekal dalam neraka
sebagaimana halnya orang kafir. Akan tetapi siksaan yang
mereka dapatkan di neraka derajatnya lebih rendah
dibandingkan dengan siksaan terhadap orang kafir.[11]
Ini berarti, disatu sisi terdapat kemiripan antara Khawarij dan
Mutazilah mengenai makna iman. Kedua aliran tersebut
menganggap bahwa iman memiliki tiga rukun. Yang pertama
pembenaran hati, yang kedua pengakuan lisan dan yang ketiga
pembuktian melalui perbuatan. Oleh karena itu iman dalam
pandangan kedua aliran tersebut tidaklah statis sebagaimana
yang diyakini oleh Murjiah.
Namun juga terdapat perbedaan yang tipis antara Khawarij dan
Mutazilah mengenai pelaku dosa besar. Khawarij menganggap
orang yang tidak menunaikan kewajiban termasuk dalam
golongan kafir. Sedangkan Mutazilah tidak menganggapnya
beriman ataupun kafir. Akan tetapi mereka berada diantara
keduanya.
Iman dan Kufur Menurut Menurut Aliran Asyariyah
Sangat sulit untuk memahami makna iman dalam pandangan
Abu Al-Hasan Al-Asyari, sebab didalam karya-karyanya seperti
dalam kitab Maqalat, Al-Ibanah, Al-Luma, ia mendefenisikan
iman secara berbeda-beda. Dalam Maqalat dan Al-Ibanah, ia
menyebutkan bahwa iman adalah qawl dan amal (ucapan dan
perbuatan), dapat bertambah dan berkurang.
Dalam Al-Luma, iman diartikannya sebagai tashdiq bi Allah.
Argumentasinya, bahwa kata mukmin seperti disebutkan dalam
al-Quran surat Yusuf ayat 7 memiliki hubungan makna dengan
kata shadiqin dalam ayat itu juga. Dengan demikian, menurut al-
Asyari, iman adalah tashdiq bi al-qalb (pembenaran dengan
hati).
Diantara defenisi iman yang dimaksudkan al-Asyari dijelaskan
oleh Asy-Syahrastani, salah seorang teolog Asyariah. Asy-
Syharastani mengatakan:
Al-Asyari berkata, iman (secara esensial) adalah tashdiq bi
al-janan (pembenaran dengan hati). Sedangakan pembuktian
secara lisan dan melakukan berbagai kewajiban utama (amal bi
al-arkan) hanyalah merupakan furu (cabang-cabang) iman. Oleh
sebab itu, siapa pun yang membenarkan keesaan Tuhan dan
utusan-utusannya beserta apa yang dibawanya dengan kalbu,
maka iman semacam itu adalah iman yang sahih, dan keimanan
seseorang tidak akan hilang kecuali jika ia mengingkari salah
satu dari hal-hal tersebut.
Keterangan Asy-Syahrastani tersebut, disamping
mengonvergensikan kedua defenisi yang berbeda yang diberikan
oleh al-Asyari dalam Maqalat, al-Ibanah dan al-luma kepada
satu titik pertemuan, juga menempatkan ketiga unsur iman
(tashdiq, qawl, dan amal) pada posisinya masing-masing. Jadi,
bagi Al-Asyari dan juga Asyariah, persyaratan minimal untuk
adanya iman hanyalah tashdiq yang jika diekspresikan secara
verbal berbentuk syahadatain.[12]
Pernyataan Asy-Syahrastani ini tidak mengherankan, karena
seperti halnya setiap aliran, konsep iman dalam pandangan
Asyariah sangatlah berkaitan dengan term mengenai kekuatan
akal dan fungsi wahyu. Mereka berkeyakinan bahwa akal
manusia tidak dapat memahami Tuhan secara independen
sebelum adanya syariat yang menjelaskan hal tersebut.
Berdasarkan hal tersebut, Asyariah beranggapan bahwa orang
yang tidak sampai kepadanya risalah, jika ia tidak beriman, maka
ia tidak akan mendapat siksa atas hal tersebut. Dengan
mengutip dalil al-Quran, Surah al-Isra:15. Kami tidak akan
menyiksa (seseorang), hingga kami mengutus kepadanya
seorang rasul.[13] Olehnya, iman bukan merupakan marifah
ataupun amal. Manusia dapat mengetahui hal tersebut
berdasarkan wahyu. Wahyulah yang menerangkan kepada
manusia mengenai kewajiban mengetahui Tuhan, dan manusia
harus menerima kebenaran berita ini.
Oleh karena itu, iman dalam pandangan Asyariah adalah al-
tasdiq bi Allah.[14] Dengan kata lain, hilangnya sesuatu yang
bukan merupakan syarat wujud sesuatu tidak serta merta
menghilangkan esensinya.[15] Berdasarkan hal ini, maka dosa
besar, tidak serta merta menghilangkan keimanan seseorang
dan hal tersebut tidak menyebabkannya kafir. Karena dalam
pandangan Asyariah perbuatan bukan merupakan syarat iman
akan tetapi sebagai penyempurna. oleh karena itu, maka
frekwensi keimanan seseorang tidak bersifat statis, akan tetapi
bersifat dinamis sesuai amal perbuatan seseorang.
Iman dan Kufur Menurut Menurut Aliran Al-Maturidiyah
Munculnya aliran al-Maturidi pada dasarnya memiliki kesamaan
dengan aliran Asyariyah. Kedua tokoh aliran tersebut memiliki
persamaan dalam hal perkembangan pemikiran kalamnya.
Keduanya sama-sama dihadapkan pada pemikiran kalam yang
cukup menggoncangkan spritualitas ideologi umat Islam kala itu,
terlebih setelah peristiwa al-Mihnah.[16]
Dalam masalah iman, aliran Maturidiyah Bukhara mempunyai
faham yang sama dengan kaum Asyariah. Keduanya
beranggapan bahwa akal tidak dapat sampai kepada kewajiban
mengetahui adanya Tuhan. Olehnya itu iman tidak bisa
mengambil bentuk marifah atau amal, tetapi haruslah
merupakan tasdiq bi al-qalb wa al-lisan.[17] Adapun pengertian
iman menurut Maturidiah Samarkand, iman adalah tashdiq bi al-
qalb, bukan semata-mata iqrar bi al-lisan.
Apa yang diucapkan oleh lidah dalam bentuk pernyataan iman,
menjadi batal bila hati tidak mengakui ucapan lidah. Namun,
lebih dari itu, menurutnya tasdiq harus diperoleh dari marifah.
Tasdiq hasil dari marifah ini didapatkan melalui akal, bukan
sekedar berdasarkan wahyu. Ia mendasari pandangannya pada
dalil naqli surat al-Baqarah ayat 260.
Surat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim meminta kepada
Tuhan untuk memperlihatkan bukti dengan menghidupkan orang
yang sudah mati. Dalam pandangan al-Maturidi, permintaan
tersebut tidaklah berarti bahwa Nabi Ibrahim belum beriman.
Akan tetapi ia mengharapkan agar iman yang telah dimilikinya
dapat meningkat menjadi iman hasil marifah. Meskipun
demikian, marifah menurutnya sama sekali bukan esensi iman,
melainkan faktor kehadiran iman.
Mengenai fluktuasi iman, al-Maturidi tidak memberikan
pandangan secara jelas. Namun, komentarnya terhadap al-Fiqh
al-Akbar, karya Abu Hanifah, tentang fluktuasi iman, cukup
memberi isyarat penolakan Al-Maturidi terhadap fluktuasi iman.
Berbeda dengan Abu Hanifah, al-Maturidi mengamini perbedaan
individual dalam hal iman. Hal itu dibuktikan dengan
penerimaannya terhadap hadis Nabi yang menyatakan bahwa
skala iman Abu Bakr lebih berat dan besar daripada skala iman
seluruh manusia. Sedangkan Maturidiyah Bukhara
mengembangkan pendapat yang berbeda.
Anda mungkin juga menyukai
- Kontroversi MusikDokumen44 halamanKontroversi MusikMuhammad Fathoni Abu FaizBelum ada peringkat
- Per 9 Fuzzy 1 PDFDokumen43 halamanPer 9 Fuzzy 1 PDFMuhammad Farhan FauzanBelum ada peringkat
- Materi Eko. X Smt.1 Revisi 2020Dokumen99 halamanMateri Eko. X Smt.1 Revisi 2020Olivia BalikpapanBelum ada peringkat
- MODUL Teknik Digital 2022 FIXDokumen96 halamanMODUL Teknik Digital 2022 FIXAde aldi GantengBelum ada peringkat
- Pertemuan 13 - Pengantar Logika FuzzyDokumen32 halamanPertemuan 13 - Pengantar Logika FuzzyRasya NurmalaBelum ada peringkat
- Resistansi Dan Hukum OhmDokumen20 halamanResistansi Dan Hukum OhmnasmaBelum ada peringkat
- Mengukur Suhu Dan Kelembaban Dengan Sensor DHT11Dokumen5 halamanMengukur Suhu Dan Kelembaban Dengan Sensor DHT11Reno Manoca KrisnantoBelum ada peringkat
- Sensor PIRDokumen3 halamanSensor PIRMuhammad RuslyBelum ada peringkat
- Jobsheet Sensor IR Dan Serial MonitorDokumen3 halamanJobsheet Sensor IR Dan Serial MonitorZainal AbidinBelum ada peringkat
- Engertian Waqaf Dan WashalDokumen24 halamanEngertian Waqaf Dan WashalnurislamiahBelum ada peringkat
- LOGIKA FUZZYDokumen70 halamanLOGIKA FUZZYYoon ElfinitizefriendBelum ada peringkat
- Pengantar Ekoonomi IiDokumen29 halamanPengantar Ekoonomi IiPutri TribuanaBelum ada peringkat
- ILMU NAWAWIDokumen3 halamanILMU NAWAWIwandiBelum ada peringkat
- Dialog Ibnu Abbas Dengan Kaum KhawarijDokumen9 halamanDialog Ibnu Abbas Dengan Kaum KhawarijbisnisweblogBelum ada peringkat
- Khawarij Gaya BaruDokumen71 halamanKhawarij Gaya BaruHelmon ChanBelum ada peringkat
- Hikayat Iblis VS RasulullahDokumen15 halamanHikayat Iblis VS RasulullahKristyanBelum ada peringkat
- Android Berbasis Pemantauan Kualitas Udara di Industri GulaDokumen108 halamanAndroid Berbasis Pemantauan Kualitas Udara di Industri GulaRobi MulyadiBelum ada peringkat
- Jaringan Syaraf Tiruan 2Dokumen32 halamanJaringan Syaraf Tiruan 2ramadhani prasetyaBelum ada peringkat
- Teknik Dasar ListrikDokumen33 halamanTeknik Dasar ListrikAnonymous mZJFhcBelum ada peringkat
- Fiqh QurbanDokumen50 halamanFiqh QurbanRovvy OcktoraBelum ada peringkat
- 153 PDFDokumen75 halaman153 PDFnanumnetBelum ada peringkat
- Makalah Mikro EkonomiDokumen93 halamanMakalah Mikro EkonomiEl Muflih100% (1)
- Bulughul Maram - Terj IndonesiaDokumen852 halamanBulughul Maram - Terj IndonesiaAchmad Lucky Baluqia100% (1)
- Fix Sop Lomba Masak FinalDokumen2 halamanFix Sop Lomba Masak FinalAnis hikmatulBelum ada peringkat
- E-Book Gratis Belajar Qurban Sesuai Tuntunan Nabi - Muhammad Abduh Tuasikal PDFDokumen58 halamanE-Book Gratis Belajar Qurban Sesuai Tuntunan Nabi - Muhammad Abduh Tuasikal PDFNoorAhmadBelum ada peringkat
- Terjemah Majmu Syarah Muhadzdzab 11Dokumen846 halamanTerjemah Majmu Syarah Muhadzdzab 11Muhammad SayaBelum ada peringkat
- Ushul AtsalasahDokumen60 halamanUshul AtsalasahHusnul Ma'arifBelum ada peringkat
- Hukum OHMDokumen15 halamanHukum OHMjachle'sBelum ada peringkat
- SYAFAATDokumen13 halamanSYAFAATGeron DumyBelum ada peringkat
- Dasar Manajemen InvestasiDokumen34 halamanDasar Manajemen InvestasisingatesBelum ada peringkat
- 500 Ulama Mengkafirkan MerekaDokumen3 halaman500 Ulama Mengkafirkan MerekaAbu Nabila As SundawyBelum ada peringkat
- Hukum Orang Yang Meninggalkan SholatDokumen41 halamanHukum Orang Yang Meninggalkan SholatIlyazBelum ada peringkat
- SYARAH BULUGHUL MARAM 7 by Abdullah Bin Abdurrahman Al BassamDokumen701 halamanSYARAH BULUGHUL MARAM 7 by Abdullah Bin Abdurrahman Al BassamFadhila zulfaBelum ada peringkat
- DETEKSI GERAKDokumen11 halamanDETEKSI GERAKReyhan AdamBelum ada peringkat
- Modul Audit K3Dokumen68 halamanModul Audit K3PuryBelum ada peringkat
- KITAB AL-ADZKARDokumen19 halamanKITAB AL-ADZKARAkhmad SaikuddinBelum ada peringkat
- Akreditasi Program Studi Teknik Perkapalan UIDokumen113 halamanAkreditasi Program Studi Teknik Perkapalan UISandy Yansiku100% (1)
- Bab 7 Neuron - MC CUlloch Pitts PDFDokumen25 halamanBab 7 Neuron - MC CUlloch Pitts PDFNURAINI WIDYA NINGSIH 190534646415Belum ada peringkat
- Harut Dan Marut Adalah Antara Malaikat Yang Diciptakan Oleh AllahDokumen17 halamanHarut Dan Marut Adalah Antara Malaikat Yang Diciptakan Oleh AllahSyafiqah Akmal0% (1)
- KESABARAN MENERIMA PENYAKITDokumen67 halamanKESABARAN MENERIMA PENYAKITEdy ArfandyBelum ada peringkat
- Pemikiran Teologi Al-Khawarij Dan Al-Murji'AhDokumen27 halamanPemikiran Teologi Al-Khawarij Dan Al-Murji'AhayuBelum ada peringkat
- (Fathi Yakan) Rintangan Perjuangan PendakwahDokumen81 halaman(Fathi Yakan) Rintangan Perjuangan PendakwahKuyokuyo Ebook100% (1)
- SEKOLAH ELEKTRONIKA DAYADokumen42 halamanSEKOLAH ELEKTRONIKA DAYAtryvenavalentinetBelum ada peringkat
- Aliran KhawarijDokumen4 halamanAliran KhawarijAndri HerdiantoBelum ada peringkat
- HAIKAL ALUMAM (ILMU KALAM) Arti Iman, Kufur, Fasik, Munafik, Dan MurtadDokumen8 halamanHAIKAL ALUMAM (ILMU KALAM) Arti Iman, Kufur, Fasik, Munafik, Dan MurtadDayana HusnaBelum ada peringkat
- Makalah Tentang Ilmu KalamDokumen5 halamanMakalah Tentang Ilmu KalamQuranic TubabaBelum ada peringkat
- Ilmu Kalam Kel. 7Dokumen12 halamanIlmu Kalam Kel. 7iqlima Nazihatul mu'tamarohBelum ada peringkat
- Iman dan Kufur Menurut AliranDokumen10 halamanIman dan Kufur Menurut AliranNur HalimahBelum ada peringkat
- MAKALAH Ilmu KalamDokumen9 halamanMAKALAH Ilmu Kalamroihah jannahBelum ada peringkat
- Konsep Kufur Dan ImanDokumen11 halamanKonsep Kufur Dan ImanResty SetiawanBelum ada peringkat
- Pelaku Dosa 2Dokumen9 halamanPelaku Dosa 2Zahiruddin ZaherBelum ada peringkat
- Makalah Iman Dan KufurDokumen13 halamanMakalah Iman Dan KufurKadir MunirBelum ada peringkat
- Perbandingan Aliran Pelaku Dosa Besar dan Iman Menurut TeologDokumen6 halamanPerbandingan Aliran Pelaku Dosa Besar dan Iman Menurut TeologMuktoharohBelum ada peringkat
- MurjiahDokumen6 halamanMurjiahNISABelum ada peringkat
- Iman dan Kufur Menurut Aliran Ilmu KalamDokumen13 halamanIman dan Kufur Menurut Aliran Ilmu KalamKhoir Ibnu khoirBelum ada peringkat
- Iman Menurut MurjiahDokumen8 halamanIman Menurut MurjiahMierja Van Zura0% (1)
- Kalam Murji'ah Dan Pengaruhnya Di Sejarah IslamDokumen15 halamanKalam Murji'ah Dan Pengaruhnya Di Sejarah IslamAldi Fajar NugrahaBelum ada peringkat
- Iman Dan KufurDokumen11 halamanIman Dan KufurNur WahidBelum ada peringkat
- Pemikiran para Teolog Tentang Pelaku Dosa BesarDokumen30 halamanPemikiran para Teolog Tentang Pelaku Dosa Besarmuhammad nur haqiqiBelum ada peringkat
- Aliran MurjiahDokumen7 halamanAliran MurjiahHafiz MuthoharohBelum ada peringkat
- Bab IDokumen3 halamanBab IIqbal TaufiqurrochmanBelum ada peringkat
- Distribusi Peluang DiskritDokumen26 halamanDistribusi Peluang DiskritIqbal TaufiqurrochmanBelum ada peringkat
- Distribusi Peluang LengkapDokumen32 halamanDistribusi Peluang LengkapIqbal TaufiqurrochmanBelum ada peringkat
- Kelompok 9 Pembenaran Ilmu: Ghina K.D (15610087)Dokumen18 halamanKelompok 9 Pembenaran Ilmu: Ghina K.D (15610087)Iqbal TaufiqurrochmanBelum ada peringkat
- PEMBAHASANDokumen2 halamanPEMBAHASANIqbal TaufiqurrochmanBelum ada peringkat
- KELOMPOK 9 Hari KiamatDokumen24 halamanKELOMPOK 9 Hari KiamatIqbal TaufiqurrochmanBelum ada peringkat
- Perkembangan Pemikiran Fiqih Di IndonesiaDokumen11 halamanPerkembangan Pemikiran Fiqih Di IndonesiaIqbal TaufiqurrochmanBelum ada peringkat
- UTS UmarDokumen3 halamanUTS UmarIqbal TaufiqurrochmanBelum ada peringkat
- POST TEST Uji HipotesisDokumen1 halamanPOST TEST Uji HipotesisIqbal TaufiqurrochmanBelum ada peringkat
- Install WinrarDokumen1 halamanInstall WinrarIqbal TaufiqurrochmanBelum ada peringkat
- Daftar PustakaDokumen1 halamanDaftar PustakaIqbal TaufiqurrochmanBelum ada peringkat
- Install WinrarDokumen1 halamanInstall WinrarIqbal TaufiqurrochmanBelum ada peringkat
- UTS Analisis DataDokumen2 halamanUTS Analisis DataIqbal TaufiqurrochmanBelum ada peringkat
- BlockDokumen1 halamanBlockIqbal TaufiqurrochmanBelum ada peringkat
- 6 Rantai Markovklasifikasi StateDokumen54 halaman6 Rantai Markovklasifikasi StateLa Lauda SeptianaBelum ada peringkat
- Modul 9 Dist Peluang KontinuDokumen11 halamanModul 9 Dist Peluang KontinuIqbal TaufiqurrochmanBelum ada peringkat
- Aplikasi Minitab Dalam Perancangan Percobaan MarzukiDokumen44 halamanAplikasi Minitab Dalam Perancangan Percobaan MarzukiIwd AliscandelBelum ada peringkat
- 10 Buku Rancob Uji LanjutanDokumen32 halaman10 Buku Rancob Uji LanjutanHanung Puspita Aditya SBelum ada peringkat
- PELURUHAN RADIOAKTIFDokumen11 halamanPELURUHAN RADIOAKTIFMawardi Jalil Masri100% (1)
- OPTIMASI PDB NUMERIKDokumen15 halamanOPTIMASI PDB NUMERIKAstrid HerawatiBelum ada peringkat
- Makalah Anfar 2Dokumen10 halamanMakalah Anfar 2Erik MelanoBelum ada peringkat
- Pengambilan Sampel dalam PenelitianDokumen19 halamanPengambilan Sampel dalam PenelitianHajja DewantiBelum ada peringkat
- Makalah RalDokumen11 halamanMakalah RalIqbal TaufiqurrochmanBelum ada peringkat
- Perla KuanDokumen4 halamanPerla KuanIqbal TaufiqurrochmanBelum ada peringkat
- Teori Himpunan DasarDokumen4 halamanTeori Himpunan DasarRizki HaryBelum ada peringkat
- Ermainan TradisionalDokumen6 halamanErmainan TradisionalIqbal TaufiqurrochmanBelum ada peringkat
- SahamDokumen23 halamanSahamIqbal TaufiqurrochmanBelum ada peringkat