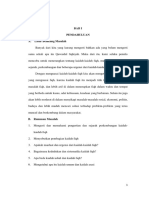Akhlak Atau Etika Dalam Perspektif Filsafat Barat
Diunggah oleh
Nurul AzaliaJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Akhlak Atau Etika Dalam Perspektif Filsafat Barat
Diunggah oleh
Nurul AzaliaHak Cipta:
Format Tersedia
Akhlak atau Etika dalam Perspektif Filsafat Barat
Etika pada umumnya diidentikkan dengan moral (atau moralitas). Namun, meskipun sama
terkait dengan baik-buruk tindakan manusia, etika dan moral memiliki perbedaan pengertian.
Secara singkat, jika moral lebih condong kepada pengertian “nilai baik dan buruk dari setiap
perbuatan manusia itu sendiri”, maka etika berarti “ilmu yang mempelajari tentang baik dan
buruk”. Jadi, bisa dikatakan, etika berfungsi sebagai teori dari perbuatan baik dan buruk
(ethics atau ‘ilm ul-akhlaq), dan moral (akhlaq) adalah praktiknya. Dalam disiplin filsafat,
ter-kadang etika disamakan dengan filsafat moral.
Garis merah yang jelas antara etika dan moral dari definisi yang diberikan oleh Haidar Bagir
di atas, berarti etika adalah teori (teoritis, al-nadariyah) dan moral adalah praktik (praktis, al-
‘amaliyah). Sedangkan filsafat itu ada pa-da tataran teori atau pemikiran. Jadi pada akhirnya
pun etika sebagai teori ditarik kepada bagian dari filsafat, di sana dibicarakan tentang nilai,
norma dan atau ukuran secara toeritis (al-nadariyah) dari etika itu sendiri.
Dalam khazanah pemikiran Islam etika bersama-sama dengan politik dan ekonomi biasa
dimasukkan ke dalam apa yang disebut sebagai filsafat praktis (al-hikmah al-‘amaliyah).
Filsafat praktis itu sendiri berbicara tentang segala sesuatu “sebagaimana seharusnya”.
Walaupun demikian, ia mesti didasarkan pada filsafat teoretis (al-hikmah al-nadariyah).
Yakni pembahasan mengenai segala sesuatu “sebagaimana adanya”, termasuk di dalamnya
metafisika.
Pada umumnya, pandangan-pandangan mengenai etika yang berkem-bang di belahan
dunia ini dikelompokkan menjadi tiga golongan, yakni; etika hedonistik, utilitarian, dan
deontologis.
Hedonisme mengarahkan etika kepada keperluan untuk menghasilkan sebanyak-
banyaknya kesenangan bagi manusia. Etika utilitaristik mengoreksinya dengan
menambahkan bahwa kesenangan atau kebahagiaan yang di-hasilkan oleh suatu etika yang
baik adalah kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang dan bukan kesenangan atau
kebahagiaan individual – yang di sisi lain, mungkin justru menimpakan kesengsaraan bagi
orang lain yang justru jauh lebih banyak lagi jumlahnya dibandingkan dengan yang
mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Sementara etika deontologis (berasal dari ka-
ta deon yang mempunyai arti kewajiban) memandang bahwa sumber bagi perbuatan etis
adalah rasa kewajiban. Sejalan dengan itu, aliran ini mem-percayai bahwa sikap etis bersifat
fitri dan, pada saat yang sama, tidak (mur-ni) rasional. Pada kenyataannya, hasil pemikiran
para filosof Barat berkena-an dengan etika seringkali merupakan irisan dari ketiga aliran
besar itu. De-ngan kata lain, pemikiran dan pandangan masing-masing mereka bisa
mengandung prinsip-prinsip lebih dari satu aliran besar tersebut di atas. Adapun pemikiran
dan pandangan masing-masing mereka adalah
1. Teori yang Bersifat Fitri
Teori etika yang bersifat fitri (innate nature) ini dikemukakan oleh Socrates, tokoh
filsafat pertama dan ternama yang mendapat julukan sebagai Bapak Filsafat Yunani Klasik,
tokoh yang dihukum mati karena filsafatnya ber-tentangan dengan adat budaya bangsanya
dengan hukuman minum racun, sebagaimana disampaikan oleh muridnya, Plato. Teori ini
menyatakan bah-wa moratilas itu bersifat fitri (innate nature). Yakni, pengetahuan yang
berke-naan dengan baik dan buruk atau dorongan untuk berbuat baik sesungguh-nya telah ada
pada sifat alami (pembawaan) manusia (fitrah atau innate na-ture).
Teori kefitrian ini sepertinya sejalan dengan pemikiran Islam, yang menegaskan bahwa
ketika manusia lahir dalam keadaan fitri (nature). Secara jujur, hati nurani sering mengatakan
kebenaran itu, bahkan–mungkin–sampai saat ini hati nuranilah yang masih dalam keadaan
fitri, ia tidak terkontaminasi oleh lingkungan yang buruk, hanya saja ia sering tertutupi oleh
nafsu manusia yang telah sangat kotor dan penuh oleh debu-debu ketidak-benaran.
2. Teori yang Bersifat Empirik Klasik
Seorang murid Plato, Aristoteles atau yang lebih dikenal dengan julukannya sebagai
Bapak Logika, berpendapat bahwa etika merupakan suatu keterampilan semata dan tidak ada
kaitannya sama sekali dengan alam Idea Platonik yang bersifat supranatural. Dimana
keterampilan tersebut, menurutnya diperoleh dari hasil latihan dan pengajaran. Seseorang
yang berlatih dan belajar untuk berbuat baik, maka ia pun akan menjadi seorang yang
bermoral.
Lebih dari itu, Aristoteles, peletak landasan peripaterisme, dan Guru Pertama yang
dikenal dengan teorinya yang berkenaan dengan moderasi (hadd ul-wasath) tersebut,
mengatakan bahwa moral yang baik sesungguhnya iden-tik dengan memilih segala sesuatu
yang bersifat “tengah-tengah”. Pada dasarnya, setiap perbuatan bersifat netral. Hakikatnya
ketakutan tidaklah lebih jelek. Begitu pun dengan keberanian. Keberanian qua keberanian
tidak mutlak bagus. Demikian pula, ketakutan tidak mutlak buruk. Keduanya bisa disebut
baik jika ditempatkan di posisi yang moderat atau proporsional–tidak berlebihan, tidak
kekurangan. Jika keduanya tidak ditempatkan pada posisi moderat, akan ada suatu saat yang
di dalamnya sesuatu yang umumnya dikenali sebagai baik berubah menjadi jelek dengan
sendirinya, dan sebaliknya. Bagi Aristoteles, pada puncaknya tujuan dari tindakan-tindakan
etis itu adalah untuk mendapatkan kebahagiaan intelektual (eudemonia).
3. Teori Etika Modernisme
Bapak dari filsafat modernisme ini adalah Rene Descartes, seorang filo-sof abad ke-15
yang terkenal dengan pemikiran filsafat cogito ergo sum (aku berfikir maka aku ada) sebagai
sebuah pemikiran filsafat–yang kami sebut dengan filsafat–keraguan. Dalam persoalan etika,
corak pemikiran modernisme berbeda dari dua teori di atas. Akan tetapi, pada saat yang
sama, mereka justru mempercayai adanya satu etika yang bersifat rasional, absolut, dan
universal – yakni bisa disepakati oleh semua manusia.[5]
Secara jelas pemikiran tokoh utama filsafat modernisme ini terdapat dalam
bukunya Discours de la Methode[6] yang dirumuskannya menjadi tiga atau empat prinsip
moral sementara. Yaitu:
1. Mematuhi undang-undang dan adat istiadat negeri, sambil berpegang teguh kepada agama.
2. Bersikap setegas dan semantap mungkin dalam tindakan, dan mengikuti pendapat yang
paling meragukan secara sama mantapnya sebagaimana mengikuti pendapat yang sangat
meyakinkan, bila telah memutuskan untuk mengikutinya.
3. Selalu berusaha mengalahkan diri sendiri daripada menunggu nasib; mengubah keinginan-
keinginan sendiri, dan bukannya merombak tata-nan dunia, serta membiasakan diri untuk
meyakini bahwa tidak ada satu pun yang berada di bawah kekuasaan individu sepenuhnya
kecuali pi-kiran individu tersebut.
4. Teori Etika Immanuel Kant
Menurut Immanuel Kant, etika itu bersifat fitri, meskipun demikian sumbernya tidak bersifat
rasional ataupun teoretis. Bahkan menurutnya, ia bukanlah urusan “nalar murni”. Akan tetapi
justru, apabila manusia meng-gunakan nalarnya dalam berusaha merumuskan etika, ia dengan
sendirinya tidak akan sampai pada etika sesungguhnya. Di samping bakal berselisih satu
sama lainnya mengenai mana yang baik dan mana yang buruk, “etika” yang bersifat rasional
sudah bukan lagi etika, melainkan bisa terjebak ke dalam perhitungan untung dan rugi. Di
mana dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perbuatan etis itu dapat menghasilkan
keuntungan bagi si pelaku, dan akan tetapi bisa juga mengakibatkan kerugian baginya. Kant
mengatakan bahwa etika adalah urusan “nalar praktis”. Artinya, pada dasarnya nilai-nilai
moral itu telah tertanam pada diri manusia sebagai sebuah kewajiban (imperatif kategoris).
Kecenderungan untuk berbuat baik, misalnya, sebenarnya telah ada pada diri manusia.
Manusia pada intinya hanya menunaikan kecenderungan diri dalam setiap perbuatannya.
Dengan kata lain, perbuatan etis bersifat deontologis dan berada di balik nalar
5. Teori Bertrand Russel
Bertrand Russel berpendapat bahwa perbuatan etis itu bersifat rasional, ini sangat berbeda
dengan apa yang dikatakan oleh Immanuel Kant. Artinya, justru karena manusia itu sendiri
memang rasional, sehingga dia melihat perlunya bertindak secara etis. Mengapa demikian?
Karena bertindak secara etis itu pada akhirnya pastilah akan mendukungnya dalam
pencapaian interest (kepentingan) sang pelaku itu sendiri, baik itu interest yang bersifat
material maupun yang bersifat nonmaterial. Yang dengan istilah lain dapat dikatakan sebagai
nilai-nilai etis sekaligus pragmatis atau utiliristik.
6. Teori Etika Post-modernisme
Era post-modernisme secara umum dapat dicirikan dengan hilangnya kepercayaan terhadap
“narasi-narasi besar” (teori-teori yang diandaikan berlaku secara indiskriminatif dan absolut)
yang mencirikan modernisme. Para tokoh post-modernis memandang bahwa kebenaran
bersifat relatif, terhadap waktu, tempat, budaya dan sebagainya. Yang mungkin hanyalah
teori-teori yang memiliki keberlakuan terbatas. Bukan saja narasi-narasi besar itu tak bisa
memiliki kebenaran dan bisa menyesatkan, pemaksaannya untuk menjelaskan berbagai
fenomena secara indiskriminatif mengandung potensi menindas. Dengan kata lain, akan ada
pemaksaan agar obyek disesuaikan dengan teori. Termasuk di dalamnya teori tentang hukum,
ekonomi, sejarah ataupun etika. Oleh karena itu, harus dirumuskan secara lokal dan
kontekstual untuk kepentingan sebanyak mungkin kelompok manusia yang di dalamnya etika
itu dirumuskan
Anda mungkin juga menyukai
- Perkembangan Filsafat Dari Zaman Ke ZamanDokumen10 halamanPerkembangan Filsafat Dari Zaman Ke Zamanindraputu85100% (1)
- Macam Macam Aliran Filsafat Islam Dan Corak PemikirannyaDokumen7 halamanMacam Macam Aliran Filsafat Islam Dan Corak PemikirannyaIndaBelum ada peringkat
- Kel8 Syariat, Thariqat, Hakikat, Ma'rifat PDFDokumen11 halamanKel8 Syariat, Thariqat, Hakikat, Ma'rifat PDFsaturnus wen100% (2)
- Pengertian FiqihDokumen16 halamanPengertian FiqihDyn PertiwiBelum ada peringkat
- Ulumul Qur'an (Mukjizat Dan Macam-Macamnya)Dokumen6 halamanUlumul Qur'an (Mukjizat Dan Macam-Macamnya)FahmiBelum ada peringkat
- 4 Penyebab Runtuhnya Kerajaan PersiaDokumen5 halaman4 Penyebab Runtuhnya Kerajaan PersiaAnonymous zbJr0cBelum ada peringkat
- Makalah Studi IslamDokumen12 halamanMakalah Studi IslamAkh SakuriBelum ada peringkat
- Kelompok 8 (Metode Tafsir Qur'an) - Ulumul Qur'an 3C-1Dokumen18 halamanKelompok 8 (Metode Tafsir Qur'an) - Ulumul Qur'an 3C-1Muhammad ZainuddinBelum ada peringkat
- Erbandingan Perbuatan Tuhan Dan Perbuatan ManusiaDokumen6 halamanErbandingan Perbuatan Tuhan Dan Perbuatan ManusiaMiftahur RahmanBelum ada peringkat
- Makalah Akhlak Masyrakat LiberalDokumen12 halamanMakalah Akhlak Masyrakat Liberalanau 123Belum ada peringkat
- Sejarah Tentang PlatoDokumen8 halamanSejarah Tentang PlatoRyan SukrawanBelum ada peringkat
- Etika PragmatisDokumen14 halamanEtika PragmatisTlogotunggal PpsBelum ada peringkat
- Turats Dan Hadatsah.1Dokumen10 halamanTurats Dan Hadatsah.1Sultan MahasinBelum ada peringkat
- Makalah (Aksiologi Hukum Islam)Dokumen8 halamanMakalah (Aksiologi Hukum Islam)Soma GustiandaBelum ada peringkat
- Kosmologi Dalam IslamDokumen6 halamanKosmologi Dalam IslamIkmal SnevalBelum ada peringkat
- Makalah Baik Dan BurukDokumen10 halamanMakalah Baik Dan BurukUkhti Fee0% (1)
- Akhlak Dan Adab PDFDokumen15 halamanAkhlak Dan Adab PDFDila LaBelum ada peringkat
- Makaalah Antar Aliran Tentang Kehendak Mutlak TuhanDokumen9 halamanMakaalah Antar Aliran Tentang Kehendak Mutlak TuhanYulia Citra DewiBelum ada peringkat
- Akhlak, Moral, Etika Dan SusilaDokumen20 halamanAkhlak, Moral, Etika Dan SusilaShizaya-yuuBelum ada peringkat
- MAKALAH Pendekatan Teologis Dan Pendekatan Filosofis Dalam Kajian IslamDokumen20 halamanMAKALAH Pendekatan Teologis Dan Pendekatan Filosofis Dalam Kajian IslamAbdul Rozak50% (2)
- Tugas Islam Dan Budaya LokalDokumen11 halamanTugas Islam Dan Budaya LokalRiska PermatasariBelum ada peringkat
- Jawaban Soal tasawuf-WPS OfficeDokumen17 halamanJawaban Soal tasawuf-WPS OfficeFikiwijayanti Fiki67% (3)
- Rukun NikahDokumen8 halamanRukun NikahMir Lien DankBelum ada peringkat
- 9 Pertanyaan Dan JawabanDokumen20 halaman9 Pertanyaan Dan JawabanRangga Kusuma NegaraBelum ada peringkat
- Studi Islam Dengan Pendekatan Sejarah PDFDokumen12 halamanStudi Islam Dengan Pendekatan Sejarah PDFFarabi Ahmad0% (1)
- BAB I Ilmu AkhlakDokumen8 halamanBAB I Ilmu AkhlakULFA UTARI100% (1)
- Etika Akademik Ipb PDFDokumen3 halamanEtika Akademik Ipb PDFIam IlhamRizkiBelum ada peringkat
- Resume Pengantar Filsafat Ilmu PDFDokumen32 halamanResume Pengantar Filsafat Ilmu PDFnur fuadBelum ada peringkat
- Unsur-Unsur PenalaranDokumen5 halamanUnsur-Unsur Penalaranfiandra arganiBelum ada peringkat
- Orientasi Keilmuan Islam FiksDokumen12 halamanOrientasi Keilmuan Islam FiksShaury FiyanBelum ada peringkat
- Beberapa Pendekatan Dalam Studi Agama IslamDokumen24 halamanBeberapa Pendekatan Dalam Studi Agama IslamArdian PulunganBelum ada peringkat
- MAKALAH AKHLAQ DAN TASAWUF-dikonversiDokumen8 halamanMAKALAH AKHLAQ DAN TASAWUF-dikonversiZaenal ArifinBelum ada peringkat
- Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Manajemen Pendidikan IslamDokumen58 halamanMetodologi Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Manajemen Pendidikan Islamajeng rizky99Belum ada peringkat
- Makalah MSI (Metodologi Studi Islam) Islam Normatif Dan Islam Historis - JALAN LURUSDokumen10 halamanMakalah MSI (Metodologi Studi Islam) Islam Normatif Dan Islam Historis - JALAN LURUSFirmansahPratamanBelum ada peringkat
- Makalah Filsafat Plato Dan AristotelesDokumen13 halamanMakalah Filsafat Plato Dan AristotelesIrpan Ilmi100% (2)
- Makalah Pengembangan Pembinaan Akhlak SiswaDokumen15 halamanMakalah Pengembangan Pembinaan Akhlak SiswaDen Zumad Van HellenBelum ada peringkat
- Pendekatan Normatif Dan Deskriptif Dalam Studi IslamDokumen43 halamanPendekatan Normatif Dan Deskriptif Dalam Studi IslamDewy SundaryBelum ada peringkat
- Makalah Pengembangan KurikulumDokumen14 halamanMakalah Pengembangan KurikulumMuhamad nur muhsinBelum ada peringkat
- Ketatanegaraan Pada Masa Bani AbbasDokumen15 halamanKetatanegaraan Pada Masa Bani Abbasrafki sandrikaBelum ada peringkat
- Islam Normatif Dan HistorisDokumen11 halamanIslam Normatif Dan HistoristowewewBelum ada peringkat
- Aliran-Aliran Dalam Teologi IslamDokumen53 halamanAliran-Aliran Dalam Teologi IslamulfiBelum ada peringkat
- Etika Keilmuan Dalam Filsafat Pendidikan IslamDokumen7 halamanEtika Keilmuan Dalam Filsafat Pendidikan IslamLuicy Anggri Via100% (2)
- Kelompok 1 Turjaman Al-MustafidDokumen12 halamanKelompok 1 Turjaman Al-MustafidHilman AnbariBelum ada peringkat
- Konsekuensi Dari Penerapan Akhlak Mulia Dan Akhlak BurukDokumen4 halamanKonsekuensi Dari Penerapan Akhlak Mulia Dan Akhlak BurukGuntur RahmandhitoBelum ada peringkat
- Pengertian Hadits, Kedudukan, Dan Kehujjahan HaditsDokumen12 halamanPengertian Hadits, Kedudukan, Dan Kehujjahan HaditsmarindaBelum ada peringkat
- Pentingnya Belajar Ilmu TajwidDokumen2 halamanPentingnya Belajar Ilmu TajwidMuhammad Iqbal NstBelum ada peringkat
- Perkembangan Pemikiran IslamDokumen34 halamanPerkembangan Pemikiran Islamyusvera100% (1)
- Makalah Rasm Al'QuranDokumen13 halamanMakalah Rasm Al'QuranNauval AribBelum ada peringkat
- Dasar Hukum Sholat Wajib Dan SunahDokumen3 halamanDasar Hukum Sholat Wajib Dan Sunahputri nandaBelum ada peringkat
- Pembagian Ilmu FiqhDokumen9 halamanPembagian Ilmu FiqhRidwanBelum ada peringkat
- Akhlak Pada Ibadah HajiDokumen24 halamanAkhlak Pada Ibadah HajiDini MardhiyaniBelum ada peringkat
- Alinea Atau ParagrafDokumen8 halamanAlinea Atau ParagraferickcarloBelum ada peringkat
- 3-Makalah Siri Dan Etos KerjaDokumen11 halaman3-Makalah Siri Dan Etos KerjaAndi MuammalBelum ada peringkat
- Analisa Tafsir Mahmoed YoenoesDokumen32 halamanAnalisa Tafsir Mahmoed YoenoesBebasBerekspresiBelum ada peringkat
- Makalah Hubungan Hak, Kewajiban Dan Keadilan Dengan AkhlakDokumen13 halamanMakalah Hubungan Hak, Kewajiban Dan Keadilan Dengan AkhlakIrwansyah SHIBelum ada peringkat
- Makalah Perkembangan Pemikiran Dalam Akhlak IslamDokumen16 halamanMakalah Perkembangan Pemikiran Dalam Akhlak IslamDella AprilianaBelum ada peringkat
- Syariah, Hakikat, Thariqat, Dan MarifatDokumen15 halamanSyariah, Hakikat, Thariqat, Dan MarifatNesi AprilianiBelum ada peringkat
- BAB II Mekanisme Pasar Dan Teori Harga Dalam Ekonomi SyariahDokumen5 halamanBAB II Mekanisme Pasar Dan Teori Harga Dalam Ekonomi SyariahMaria Reviyona TosBelum ada peringkat
- Moral Dalam Perspektif Barat Dan IslamDokumen9 halamanMoral Dalam Perspektif Barat Dan IslamFahrilBelum ada peringkat
- Makalah Kode Etik AuditorDokumen19 halamanMakalah Kode Etik AuditorHarris FadhillahBelum ada peringkat
- Bab V Persamaan Diferensial Orde 2 Homogen Dengan Koefisien KonstanDokumen5 halamanBab V Persamaan Diferensial Orde 2 Homogen Dengan Koefisien KonstanNurul Azalia100% (1)
- Draft Surat Pernyataan Terdampak Covid LiaDokumen4 halamanDraft Surat Pernyataan Terdampak Covid LiaNurul AzaliaBelum ada peringkat
- Buku Saku RPPDokumen20 halamanBuku Saku RPPSarjana MudaBelum ada peringkat
- Administrasi PembelajaranDokumen23 halamanAdministrasi PembelajaranNurul AzaliaBelum ada peringkat
- 04 Kata Kerja Operasional Kko Edisi Revisi Teori BloomDokumen4 halaman04 Kata Kerja Operasional Kko Edisi Revisi Teori BloomEdy Tahir MattoreangBelum ada peringkat
- Silabus Matematika SMA Wajib Versi 110216Dokumen26 halamanSilabus Matematika SMA Wajib Versi 110216Shul KifliBelum ada peringkat
- 04 Kata Kerja Operasional Kko Edisi Revisi Teori BloomDokumen4 halaman04 Kata Kerja Operasional Kko Edisi Revisi Teori BloomEdy Tahir MattoreangBelum ada peringkat
- Essay Nurul Azalia (17011079)Dokumen6 halamanEssay Nurul Azalia (17011079)Nurul AzaliaBelum ada peringkat
- Makalah Bandongan Kelompok 3Dokumen8 halamanMakalah Bandongan Kelompok 3Nurul AzaliaBelum ada peringkat
- Essay Lia (17011079)Dokumen5 halamanEssay Lia (17011079)Nurul AzaliaBelum ada peringkat
- Tugas 7Dokumen3 halamanTugas 7Nurul AzaliaBelum ada peringkat
- Bahasa IndonesiaDokumen16 halamanBahasa IndonesiaNurul AzaliaBelum ada peringkat
- 04 Kata Kerja Operasional Kko Edisi Revisi Teori BloomDokumen4 halaman04 Kata Kerja Operasional Kko Edisi Revisi Teori BloomEdy Tahir MattoreangBelum ada peringkat
- CoverDokumen1 halamanCoverNurul AzaliaBelum ada peringkat
- CoverDokumen1 halamanCoverNurul AzaliaBelum ada peringkat
- LAMPIRANDokumen13 halamanLAMPIRANNurul AzaliaBelum ada peringkat