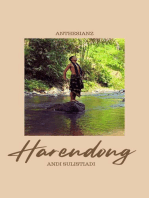Unsur Kebudayaan
Unsur Kebudayaan
Diunggah oleh
SMAN1BARABAIJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Unsur Kebudayaan
Unsur Kebudayaan
Diunggah oleh
SMAN1BARABAIHak Cipta:
Format Tersedia
Unsur Kebudayaan
http://yusmabjm.blogspot.com/2009/02/sistem-mata-pencaharian-suku-banjar.html
Sistem Mata Pencaharian
Orang Banjar dikenal dengan julukan masyarakat air (`the water people') karena
adanya pasar terapung, tempat perdagangan hasil bumi dan kebutuhan hidup sehari-
hari di sungai-sungai kota Banjarmasin, ibukota Propinsi Kalimantan Selatan.
Sebagian besar mereka hidup bertani dan menangkap ikan. Sekarang banyak pula
yang bergerak dalam bidang perdagangan, transportasi, pertambangan,
pembangunan, pendidikan, perbankan, atau menjadi pegawai negeri. Selain itu,
mereka mempunyai keahlian menganyam dan membuat kerajinan permata yang
diwariskan secara turun temurun. Upacara-upacara adat masih dipertahankan.
Sistem kekerabatan suku Banjar adalah bilateral.
Kekayaan alam dan kesuburan tanah tempat orang Banjar ternyata tidak otomatis
meningkatkan taraf hidup mereka. Hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana
transportasi (kondisi jalan dan angkutan) yang terbatas menyebabkan produk
pertanian dan non pertanian mereka sulit untuk dipasarkan. Selain itu, kesulitan
mendapat modal juga mengurangi ruang gerak mereka.
A. Pertanian Pada Suku Banjar
Sistem kearifan lokal secara netral dan dinamik di kalangan dunia barat biasanya
disebut dengan istilah Indigenous Knowledge (Warren, dalam Adimiharja, 2004).
Konsep kearifan lokal atau kearifan tradisional atau sistem pengetahuan lokal
(indigenous knowledge system) adalah pengetahuan yang khas milik suatu
masyarakat atau budaya tertentu yang telah berkembang lama sebagai hasil dari
proses hubungan timbal-balik antara masyarakat dengan lingkungannya (Marzali,
dalam Mumfangati, dkk., 2004). Jadi, konsep sistem kearifan lokal berakar dari
sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal atau tradisional. Karena hubungan yang
dekat dengan lingkungan dan sumber daya alam, masyarakat lokal, tradisional, atau
asli, melalui “uji coba” telah mengembangkan pemahaman terhadap sistem ekologi
dimana mereka tinggal yang telah dianggap mempertahankan sumber daya alam,
serta meninggalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap merusak lingkungan.
Dalam konteks pengembangan rawa lebak, kearifan lokal dalam pemanfaatan lahan
rawa lebak ini cukup luas meliputi pemahaman terhadap gejala-gejala alam atau ciri-
ciri alamiah seperti kemunculan bintang dan binatang yang menandakan datangnya
musim hujan/kemarau sehingga petani dapat tepat waktu dalam melakukan kegiatan
usaha taninya serta kebiasaan dalam budidaya pertanian, termasuk perikanan dan
peternakan seperti dalam penyiapan lahan, konservasi air dan tanah, pengelolaan air
dan hara, pemilihan komoditas, perawatan tanaman, pengembalaan dan
pemeliharaan ternak (itik, kerbau rawa), dan upaya pengembangbiakannya yang
meskipun masih bersifat tradisional, merupakan pengetahuan lokal spesifik yang
perlu digali dan dikembangkan (Noorginayuwati dan Rafieq, 2004; Furukawa, 1996).
Sistem pertanian yang dipraktekkan oleh petani Banjar di lahan rawa (lahan pasang
surut, lebak, dan gambut) Kalimantan bagian selatan terutama di kawasan Delta
Pulau Petak oleh para ahli, misalnya Collier, 1980: Ruddle, 1987; van Wijk, 1951; dan
Watson, 1984, disebut sebagai Sistem Orang Banjar (Banjarese System) (Leevang,
2003). Salah satu penemuan petani Banjar adalah ilmu pengetahuan teknologi dan
kearifan tradisional dalam pembukaan (reklamasi), pengelolaan, dan pengembangan
pertanian lahan rawa. Lahan rawa lebak telah dimanfaatkan selama berabad-abad
oleh penduduk lokal dan pendatang secara cukup berkelanjutan. Menurut Conway
(1985), pemanfaatan secara tradisional itu dicirikan oleh (Haris, 2001):
· Pemanfaatan berganda (multiple use) lahan, vegetasi, dan hewan. Di lahan rawa,
masyarakat tidak hanya menanam dan memanen padi, sayuran, dan kelapa, tetapi
juga menangkap ikan, memungut hasil hutan, dan berburu hewan liar.
· Penerapan teknik budidaya dan varietas tanaman yang secara khusus disesuaikan
dengan kondisi lingkungan lahan rawa tersebut.
Teknik-teknik canggih dan rendah energi untuk transformasi pertanian yang berhasil
pada lahan rawa lebak di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah telah
dikembangkan dan diperluas dalam beberapa dekade oleh orang-orang Banjar,
Bugis, dan migran dari Jawa. Ketiga kelompok ini mempergunakan sistem yang
hampir seluruhnya berdasarkan model yang dikembangkan oleh orang Banjar
(Ruddle, dalam Haris, 2001).
Sistem orang Banjar merupakan sistem pertanian tradisional lahan rawa yang akrab
dan selaras dengan alam, yang disesuaikan dengan situasi ekologis lokal seperti
tipologi lahan dan keadaan musim yang erat kaitannya dengan keadaan topografi,
kedalaman genangan, dan ketersediaan air. MacKinnon et al. (1996) menilai sistem
ini sebagai sistem multicropping berkelanjutan yang berhasil pada suatu lahan
marjinal, sistem pertanian yang produktif dan self sustaining dalam jangka waktu
lama. Hal ini terlihat dari penerapan sistem surjan Banjar dan pola suksesi dari
pertanaman padi menjadi kelapa–pohon, buah-buahan–ikan yang diterapkan petani
Banjar (Haris, 2001).
Pertanian lahan rawa lebak yang dilakukan oleh Orang/Suku Banjar di Kalimantan
Selatan dan Kalimantan Tengah umumnya masih dikelola secara tradisional, mulai
dari persemaian benih padi, penanaman, pemeliharaan, pengendalian hama,
penyakit dan gulma, pengelolaan air, panen, hingga pasca panen. Fenomena alam
dijadikan indikator dan panduan dalam melaksanakan kegiatan bercocok tanam.
Ketergantungan pada musim dan perhitungannya pun masih sangat kuat. Apabila
menurut perhitungan sudah waktunya untuk bertanam, maka para petani akan mulai
menggarap sawahnya. Sebaliknya, apabila perhitungan musim menunjukkan
kondisinya kurang baik, maka umumnya para petani akan beralih pada pekerjaan
lainnya.
Sebagai upaya penganekaan tanaman, petani memodifikasi kondisi lahan agar sesuai
dengan komoditas yang dibudidayakan. Petani membuat sistem surjan Banjar
(tabukan tembokan/tukungan/baluran). Dengan penerapan sistem ini, di lahan
pertanian akan tersedia lahan tabukan yang tergenang (diusahakan untuk
pertanaman padi atau menggabungkannya dengan budidaya ikan, mina padi) dan
lahan tembokan/tukungan/baluran yang kering (untuk budidaya tanaman palawija,
sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman tahunan dan tanaman industri). Pengolahan
tanah menggunakan alat tradisional tajak, sehingga lapisan tanah yang diolah tidak
terlalu dalam, dan lapisan pirit tidak terusik. Dengan demikian, kemungkinan pirit
itu terpapar ke permukaan dan teroksidasi yang menyebabkan tanah semakin
masam, dapat dicegah. Pengolahan tanah dilakukan bersamaan dengan kegiatan
pengelolaan gulma (menebas, memuntal, membalik, menyebarkan) yang tidak lain
merupakan tindakan konservasi tanah, karena gulma itu dikembalikan ke tanah
sebagai pupuk organik (pupuk hijau). Selain sebagai pupuk, rerumputan gulma yang
ditebarkan secara merata menutupi permukaan lahan sawah juga berfungsi sebagai
penekan pertumbuhan anak-anak rumput gulma (Idak, dalam Haris, 2001).
B. Kearifan Lokal Petani Lahan Rawa Lebak
Sajian di bawah ini aku ambil dari tulisannya Pak Achmad Rafieq yang berjudul
“Sosial Budaya dan Teknologi Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengembangan
Pertanian Lahan Lebak di Kalimantan Selatan”.
Sebagian besar penduduk yang bermukim di wilayah rawa lebak di Kalimantan
Selatan bergelut di sektor pertanian secara luas, yaitu sebagai petani holtikultura,
padi, dan palawija, sebagai penangkap ikan, serta peternak itik atau kerbau rawa.
Sebagian penduduk lainnya bergerak di sektor perdagangan, kerajinan, dan jasa yang
hampir seluruhnya berhubungan erat dengan pemanfaatan sumberdaya lahan rawa
lebak.
Pada mulanya rawa lebak hanya dijadikan tempat tinggal sementara para penebang
kayu dan pencari ikan. Semakin lama komunitasnya semakin bertambah banyak,
sementara kayu yang ditebang mulai berkurang sehingga masyarakat berupaya untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mencoba menanam padi dan
mengembangkan keterampilan. Semakin lama mereka semakin memahami
fenomena lahan rawa sehingga mampu mengembangkan beragam komoditas
pertanian. Dalam berinteraksi dengan alam mereka tidak berupaya untuk menguasai
atau melawannya tetapi berusaha untuk menyesuaikan dengan dinamika lahan rawa.
Usaha tani padi yang dikembangkan di lahan rawa lebak sebagian terbesar
merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Sebagian besar hanya
bertanam sekali setahun pada musim kering (banih rintak) dan sebagian kecil dapat
bertanam dua kali dalam setahun (banih surung dan banih rintak). Mereka yang
bertanam dua kali setahun umumnya sawahnya berkisar antara 10-20 borongan
(0,3-0,6 ha) dengan produktivitas sebesar 3,5 ton/ha. Petani di Negara selalu
menanam padi rintak setiap tahun sedangkan padi surung tergantung pada keadaan
air. Penanaman padi rintak paling sedikit seluas 0,3 ha sedangkan padi surung paling
sedikit setiap 0,6 ha. Pada daerah yang ditanami padi sekali dalam setahun, luas
tanam setiap keluarga mencapai rata-rata 1 ha permusim dengan produktivitas
mencapai 4,2 ton/ha.
Petani lokal di lahan rawa lebak Kalimantan Selatan umumnya masih memerhatikan
fenomena alam seperti bintang atau binatang untuk melihat peluang keberhasilan
usaha tani, termasuk waktu tanam. Fenomena alam yang menjadi pertanda musim
kering di antaranya sebagai berikut:
1. Apabila ikan-ikan mulai meninggalkan kawasan lahan rawa lebak (turun) menuju
sungai merupakan pertanda akan datangnya musim kering. Gejala alam ini biasanya
terjadi pada bulan April atau Mei. Pada saat ini suhu air di lahan lebak sudah
meningkat dan ikan turun untuk mencari daerah yang berair dalam. Kegiatan usaha
tani yang dilakukan adalah persiapan semaian.
2. Apabila ketinggian air semakin menyusut tetapi masih ada ikan saluang yang
bertahan maka menunjukkan bahwa lahan rawa lebak masih tidak akan kekeringan.
Biasanya masih akan ada air sehingga kedalaman air di lahan rawa lebak kembali
meningkat, baik sebagai akibat turunnya hujan di lahan rawa lebak atau kiriman air
di dataran tinggi yang mengalir melalui beberapa anak sungai. Kegiatan usaha tani
yang dilakukan adalah persiapan semaian.
3. Bintang karantika muncul di ufuk barat pada senja hari hingga sesudah waktu
maghrib menandakan air di lahan rawa lebak akan mulai kering. Bintang karantika
merupakan gugusan bintang yang susunannya bergerombol (bagumpal) membentuk
segi enam. Kemunculan bintang ini di ufuk barat merupakan peringatan kepada
petani untuk segera melakukan penyemaian benih tanaman padi (manaradak). Saat
kemunculan bintang ini hingga 20 hari kemudian dianggap merupakan waktu yang
ideal untuk melakukan penyemaian benih padi. Apabila telah lewat dari waktu
tersebut maka petani akan terlambat memulai usahatani padinya dan diperkirakan
padi di pertanaman tidak akan sempat memperoleh waktu yang cukup untuk
memperoleh air.
4. Bintang baur bilah yang muncul 20 hari kemudian juga dijadikan pertanda bagi
datangnya musim kering dan dijadikan patokan dalam memperkirakan lama
tidaknya musim kering. Bintang ini muncul di ufuk barat berderet tiga membentuk
garis lurus. Apabila bintang paling atas terlihat terang, terjadi musim kemarau
panjang. Sebaliknya, jika bintang paling bawah terlihat terang, kemarau hanya
sebentar. Juga bila bintang paling kiri paling terang, terjadi panas terik pada awal
musim, sebaliknya jika paling kanan terang, maka terik di akhir musim.
5. Tingginya air pasang yang datang secara bertahap juga menjadi ciri yang
menentukan lamanya musim kering. Apabila dalam tiga kali kedatangan air pasang
(pasang-surut, pasang-surut, dan pasang kembali), ketinggian air pasang pada
tahapan pasang surut yang ketiga lebih tinggi dari dua pasang sebelumnya biasanya
akan terjadi musim kering yang panjang.
6. Ada juga yang melihat posisi antara matahari dan bintang karantika. Apabila
matahari terbit agak ke sebelah timur laut dibandingkan posisi karantika berarti
akan terjadi musim kemarau panjang (landang).
7. Apabila burung putuh (kuntul = sejenis bangau) mulai meletakkan telurnya di
semak padang parupuk merupakan tanda air akan menyurut (rintak). Burung putih
mengharapkan setelah telurnya menetas air akan surut sehingga anaknya mudah
mencari mangsa (ikan).
8. Ada pula petani yang meramalkan kemarau dengan melihat gerakan asap
(mamanduk). Apabila asap terlihat agak tegak (cagat) agak lama berarti kemarau
panjang dan sebaliknya.
Fenomena alam sebagai pertanda akan datangnya air di lahan rawa lebak di
antaranya sebagai berikut:
1. Munculnya fenomena alam yang disebut kapat, yaitu saat suhu udara mencapai
derajat tinggi. Diceritakan, orang yang mengetahui waktu terjadinya kapat dapat
menunjukkan bahwa air yang diletakkan dalam suatu tempat akan memuai. Kapat
ini biasanya mengikuti kalender syamsiah dan terjadi pada awal bulan Oktober.
Empat puluh hari setelah terjadinya kapat maka biasanya air di lahan rawa lebak
akan dalam kembali (layap).
2. Setelah terjadi fenomena kapat, akan muncul fenomena alam lain yang ditandai
dengan beterbangannya suatu benda yang oleh masyarakat disebut benang-benang.
Munculnya benda putih menyerupai benang-benang yang sangat lembut,
beterbangan di udara dan menyangkut di pepohonan dan tiang-tiang tinggi ini
disebutkan sebagai pertanda datangnya musim barat, yaitu tanda akan dalam
kembali air di lahan lebak (layap). Fenomena alam ini biasanya terjadi pada bulan
Oktober sampai Nopember.
3. Apabila kumpai payung (papayungan) yang tumbuh di tanah yang agak tinggi
mulai menguning dan rebah maka pertanda air akan dalam (basurung). Ada pula
tumbuhan yang disebut pacar halang yang berbuah kecil seperti butir jagung. Apabila
buahnya memerah (masak) dan mulai berjatuhan maka air sudah mulai
menggenangi lahan rawa lebak.
4. Untuk menentukan lama tidaknya musim basah, petani menjadikan keladi lumbu
(gatal) sebagai indikator. Bila tanaman ini mulai berbunga berarti itulah saat
pertengahan musim air dalam. Apabila rumput pipisangan daunnya bercahaya agak
kuning maka pertanda air akan lambat turun (batarik).
5. Apabila ikan-ikan yang masih bisa ditemukan di lahan lebak mulai bertelur maka
pertanda air akan datang (layap). Fenomena ini biasanya terlebih dahulu ditandai
dengan hujan deras, lalu ikan betok berloncatan (naik) melepaskan telurnya, setelah
itu akan panas sekitar 40 hari lalu air akan datang dan telur ikan akan menetas.
Selain pengetahuan yang berhubungan dengan peramalan iklim, petani di lahan rawa
lebak juga mempunyai kearifan lokal mengenai kesesuaian tanah dengan tanaman,
baik ditinjau dari ketinggiannya maupun kandungan humus dan teksturnya. Mereka
menanami tanah yang tinggi dengan semangka, jagung, kacang, dan ubi negara,
sedangkan tanah yang rendah ditanami padi.
Bagi petani di lahan rawa lebak, tanah bukaan baru dan dekat hutan umumnya
dianggap sangat subur dan tidak masam, tetapi bila banyak tumbuh galam pertanda
tanah itu masam. Ciri tanah masam lainnya adalah apabila di batang tanaman tersisa
warna kekuning-kuningan begas terendam (tagar banyu) dan ditumbuhi oleh kumpai
babulu dan airnya berwarna kuning. Tanah masam ini maih dapat ditanami ubi
nagara atau bila ingin ditanami semangka maka tanah dilakukan pengapuran
terlebih dahulu. Bila telah ditanami beberapa kali keasaman akan berkurang karena
sisa-sisa rumput yang tumbuh dan mati menjadi humus. Apabila keasaman tanah
tidak bisa ditingkatkan maka petani akan meninggalkannya dan menganggap tanah
tersebut sebagai tanah yang tidak produktif (tanah bangking). Tanah yang baik
adalah tanah yang tidak banyak ditumbuhi oleh jenis tanaman liar (taung) seperti
parupuk, mengandung humus yang banyak dari pembusukan kumpai, serta
mempunyai aliran sungai yang dalam. Sungai ni berfungsi untuk pembuangan air
masam sehingga sejak dahulu petani membuat dan memelihara ray yang dibuat
setiap jarak 30 depa.
Pada masa lalu pengembangan dan penerapan kearifan lokal ini merupakan otoritas
perangkat kampung yang disebut Kepala Padang. Kepala Padang biasanya orang
yang mempunyai pengetahuan yang luas mengenai silsilah kepemilikan lahan dan
peramalan iklim. Ketentuan suatu kampung memulai melakukan aktivitas pertanian
biasanya ditentukan oleh Kepala Padang berdasarkan indikator gejala alam yang
diamatinya. Pada saat ini sudah jarang desa yang dilengkapi perangkat Kepala
Padang.
Sistem Religi
PERKEMBANGAN KEPERCAYAAN SUKU BANJAR
Orang-orang Banjar memang beragama Islam, dan sejak lama Islam
menjadi ciri masyarakat Banjar. Namun, ternyata tidak hanya Islam yang
ada disana, melainkan ajaran Hindu. Sisa-sisa kepercayaan dan praktik-
praktik Hindu disanyalir oleh Matsoff (1888) ditemukan di daerah
Kabupaten Tabalong akhir abad lalu.
Bentuk-bentuk kepercayaan dan praktek keagamaan yang
sebagaimana yang dianut oleh nenek moyang Banjar tatkala mereka mula-
mula menetap disini, tidak ada keterangan yang bisa diperoleh. Barangkali
aspek religius dari kehidupan masyarakat Bukit yang mendiami
pegunungan Meratus adalah merupakan sisa-sisa yang masih tertinggal
dari kepercayaan mereka itu. Tentu saja dengan mengingat adanya
pengaruh dari agama Hindu dan Islam. Mungkin pula religi nenek moyang
orang Banjar pada zaman purba itu dapat ditelusuri dikalangan suku
Murba yang hidup di daerah Sumatera (Riau dan Jambi) dan Semenanjung
Malaya (sekarang Malaysia Barat) pada saat ini. dengan demikian kita bisa
memperkirakan bahwa religi mereka berdasarkan pemujaan nenek moyang
dan adanya makhluk-makhluk halus di sekitar manusia (animisme).
Mungkin bentuk-bentuk pemujaan nenek moyang dan aspek animisme
dari kehidupan keagamaan masyarakat Banjar, yang kadang-kadang masih
muncul, adalah sisa-sisa dari agama mereka terdahulu.
Tentang agama yang dianut oleh raha-raja cikal bakal sultan-sultan
Banjar, Hikayat Banjar barangkali dapat dijadikan landasan. Empu
Jatmika pada waktu mendirikan Keraton Negaradipa konon menyuruh
pula membangun sebuah candi, yang dinamakan “candi Agung”, yang
bekas-bekasnya masih ada di kota Amuntai, tidak jauh dari oertemuan
antara sungai Balangan dan Tabalung. Candi lainnya adalah candi Laras,
yang bekas-bekasnya ditemukan jauh di hilir sungai Negara, yaitu dekat
kota Margasari. Di lokasi candi yang terakhir ditemukan sebuah batu, yang
dikeramatkan penduduk setempat dan dinamakan “batu babi”,
diidentifikasikan sebagai patung Nandi. (Daud Alfani, 1997: 47)
Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa agama yang dianut di
Negaradipa ialah salah satu bentuk agama Syiwa, mungkin sekali dalam
bentuk sinkretisme Syiwa Budha. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa
keagamaan kerajaan menjadi patokan agama penduduk yang berada disana
pada zaman dahulu, sehingga dapat dinyatakan bahwa bentuk agama di
kerajaan ini menjadi agama pula pada penduduk.
Sementara itu agama Kristen diperkenalkan sekitar tahun 1688 oleh
seorang pastor Portugis. Namun, penyebaran agama Kristen secara intensif
dilakukan dikalangan orang Dayak di kawasan ini, sedangkan orang-orang
Bukit baru terjamah oleh kegiatan pengkristenan pada permulaan abad
sekarang. (Daud Alfani, 1997: 53)
3. ISLAM SUKU BANJAR
Daud Alfani menjelaskan bahwa pembentukan suku Banjar tidak
terlepas dari pembauran orang-orang Arab yang datang ke Kalimatan
Selatan. Orang-orang Arab mungkin banyak berdatangan mulai zaman
Islam, yaitu sekitar abad ke-15 atau 16.
Sejak pangeran Samudera dinobatkan sebagai Sultan Suriansyah di
Banjarmasin, yaitu kira-kira 400 tahun yang lalu, Islam menjadi agama
resmi kerajaan menggantikan agama Hindu. Namun, tentu saja dapat
diduga, bahwa jauh sebelumnya pemeluk Islam sudah ada di kota-kota
pelabuhan atau di pemukiman-pemukiman yang lebih dekat dengan pantai.
Sejak masa Suriansyah proses Islamisasi berjalan cepat, sehingga dalam
waktu yang relatif tidak terlalu lama, yaitu sekitar pertengahan abad ke-18,
Islam telah menjadi identitas orang Banjar. Proses pembanjaran yang
terjadi juga berakibat pada orang-orang Dayak, baik pria maupun wanita
untuk memeluk agama Islam. (Daud Alfani)
Sementara tentang ajaran Islam itu sendiri di kalangan orang-orang
Banjar dapat diketahui dari ajaran ritual Islam dalam kehidupan mereka
sehari-hari:
a. Kegiatan Ibadah Suku Banjar
Kegiatan ibadah pada orang-orang Banjar seperti kegiatan ibadah
Islam pada umumnya, yakni ibadah wajib; shahadat, shalat, bersuci secara
ritual, puasa, zakat, naik haji, ibadah sunnah; shalat berjamaah, shalat hari
raya, puasa sunnah, dan ibadah sunnah lainnya, ajaran Islam dalam bidang
lainnya; perkawinan seperti yang ada dalam Islam, perceraian, sistem
pewarisan, dan sebagainya.
Semua rangkaian ibadah diatas dilaksanakan seperti yang telah
digariskan dalam ajaran Islam pada umumnya, terlepas dari tatacara yang
dianut masing-masing aliran organisasi Islam yang ada di Indonesia; NU,
Muhammadiyah, dan lembaga kecil lainnya.
b. Pewarisan Ajaran Islam
Adapun pewarisan ajaran Islam pada masyarakat suku Banjar
menurut Daud Alfani dengan cara mengaji, pengajaran pengetahuan Islam
dan praktek keagamaan sehari-hari. Sejak umur 6 atau 7 tahun anak-anak
sudah mulai belajar membaca huruf-huruf hijaiyyah (al-Qur’an). Anak-
anak diajar satu persatu, sementara anak-anak yang telah lancar mengaji
ditunjuk untuk mengajar anak-anak lainnya yang belum lancar mengaji.
Untuk guru mengaji sendiri tidak diberikan upah tertentu. Biasanya,
sebagai ganti upah para murid akan membelikan minyak lampu
penerangan, dan pada waktu panen tiba seorang ibu akan menyuruh
anaknya membawakan sedikit hasil panen itu untuk guru mengajinya.
(Daud Alfani) Selain belajar membaca al-Qur’an, biasanya juga diadakan
pengajian terhadap rukun iman, dan aspek terpenting lainnya dalam Islam.
Ketika mengaji, anak-anak diberikan pelajaran pokok tentang ajaran
Islam. Cara-cara dan bacaan shalat sehari-hari, puasa, dan sebagainya.
Namun, ajaran-ajaran tersebut tidak sampai disana, setiap anak diwjibkan
untuk mengahfal dan mempraktekkan apa-apa yang telah dipelajari ketika
mengaji.
Tekanan-tekanan untuk menghafal bacaan-bacaan shalat menjadi
aspek dominan tentang bagaimana teori para guru agar anak muridnya
dapat mengaplikasikan pelajaran agama yang telah didapatkan ketika
mengaji. Selain itu, anak-anak yang telah berumur 7 atau 8 tahun, anak-
anak telah dibimbinh untuk mengerjakan ibadah puasa dalam bulan
ramadhan.
4. KEPERCAYAAN DAN RITUAL DALAM SUKU BANJAR
a. Kepercayaan dan Tindakan
Kepercayaan pada orang Banjar dapat dibedakan menurut asal-
usulnya, kepercayaan dalam Islam, dan kepercayaan asal kebudayaan
masyarakat setempat. Detail-detail kepercayaan Islam diperoleh ketika
seorang anak mengaji, secara tidak langsung diajarkan oleh kerabatnya,
dan diperoleh disekolah. Kepercayaan asal lokal terutama diperoleh oleh
adanya dongeng-dongeng yang beredar dalam masyarakat tentang asal-
usul sultan-sultan kawasan ini, dan adanya cerita-cerita orang tua tentang
daerah-daerah tertentu dan makhluk-makhluk halus yang dipercayai
menghuninya. Kepercayaan terhadap makhluk halus menjadi aspek
dominan dalam kepercayaan lokal.
Kepercayaan ini terlepas dari kepercayaan makhlus halus yang
diajarkan oleh Islam (malaikat, jin, iblis), masyarakat Banjar percaya
adanya makhluk halus, yakni berbagai jenis hantu. Orang gaib, yang
dipercaya sebagai jelmaan manusia yang wafat, konon hidup berkeluarga
dan bermasyarakat dalam perkampungan mereka seperti halnya manusia,
dan beberapa tokoh mengatakan bahwa hidup orang gaib lebih lama
dibanding manusia. Kemudian kepercayaan yang lainnya adalah bahwa
setiap manusia lahir setidak-tidaknya membawa empat makhlus halus.
(Daud Alfani, 1997: 556)
Kemudian tindakan yang mereka lakukan terhadap kepercayaan
tersebut mengharuskan mereka untuk melakukan upacara bersaji setahun
sekali, dimana orang-orang gaib dan nenek moyang mereka tersebut
kemudian diundang untuk diberi sesaji. Hal tersebut bertujuan agar
makhluk halus dan arwah nenek moyang tersebut tetap bersahabat
(memberi keselamatan), dan supaya tidak mengganggu kegiatan mereka
sehari-hari, terutama berkenaan dengan perolehan rezeki dengan pertanian.
Sesajian tersebut mereka lakukan bukan tanpa landasan, sebab
mereka sering kali diserang makhluk gaib (yang mereka sebut
dengan kapuhunan atau kesurupan), seperti secara tidak terduga seseorang
terpeleset, tertimpa pohon runtuh, jatuh dari atas pohon, dan sebagainya.
Kesemuanya itu tidak terlepas dari kemarahan dan teguran dari arwah
nenek moyang dan orang gaib yang tinggal disekitar mereka.
b. Ritual Orang Banjar
Masyarakat (orang-orang) Banjar melakukan berbagai ritual,
kebanyakan dari ritual tersebut masih memasukkan unsur Islam, namun
didalam beberapa ritual mereka masih memakai cara-cara tradisional yang
berkaitan dengan kepercayaan mereka terdahulu;
1. Pengobatan gangguan orang gaib
Berbagai gangguan orang gaib yang konon disebabkan karena
melakukan kesalahan-kesalahan terhadap orang-orang gaib, meskipun
tanpa ada kesengajaan untuk itu, wujudnya mungkin ringan saja. Usaha
penyembuhan biasanya meminta bantuan tabib. Biasanya yang terkena
gangguan meminta maaf atas kesalahan-kesalahan warga yang sakit oleh
tabib, biasanya dengan mempersiapkan syarat-syarat yang konon diminta
oleh tokoh gaib bersangkutan, seperti dinyatakan oleh tabib, dan
dilaksanakan dalam suatu upacara selamatan yang khusus diadakan untuk
keperluan tersebut. Adakalanya terdapat dua versi yang menyatakan sebab
penyakit tersebut. Pertama, yang menjadi sebab sakitnya ialah ketika lewat
disuatu tempat yang dihuni oleh orang gaib secara tidak sengaja telah
menyebabkan marahnya tokoh gaib tersebut. Kedua, menyatakan
penyebab sakitnya ialah karena telah dilalaikannya pelaksanaan upacara
tahunan yang wajib bagi kerabat keturunan yang bersangkutan, meskipun
tanpa disadarinya tentang adanya kewajibannya itu, karena sebenarnya
selama beberapa generasi kerabatnya tidak pernah melaksanakannya.
Penyembuhannya ialah dengan mengucapkan kaul akan melaksanakan
upacara tahunan yang dituntut dengan menempatkan suatu benda, dan
mewujudkan kaul tepat pada waktunya, seperti yang telah diajarkan
tabibnya.
2. Mengetam Padi
Sebelum padi diketam secara beramai-ramai, biasa pula dilakukan
upacara bamula. Untuk memulai mengetam ini keluarga-keluarga petani
dilaporkan meminta bantuan seorang tua yang dipandang “ahli”. Pada sore
hari akan diadakan upacara, upacara tersebut bertujuan untuk
mengumpulkan semangat padi dan guna memastikan agar padi tidak
terlihat orang gaib, dan dengan demikian konon bila dituai kelak tidak ada
yang ketinggalan dan dihindari pula bahaya dituai orang gaib. Untuk
keperluan ini pelaksana upacara membawa sebuah upat (suluh terbuat dari
kulit bunga kelapa yang sudah kering dan dipilah-pilah). Upacara dimulai
dengan berdiri ditengah-tengah sawah dan mengucapkan
“mamangan” ditengah kepulan asap upat, yang selalu dijaga agar tidak
menyala. Isi mamangan ialah memberi salam kepada semangat padi
bahwa besok pagi akan dijemput dan ditempatkan dalam gadung
tujuh. Setelah meletakkan upat dipinggir sawah, pelaksana upacara
berkeliling sambil menepung tawari rumpun-rumpun padi
dengan minyak likat boboreh yang telah dicampur dengan parutan kencur.
(Daud Alfani, 1997: 442)
KESIMPULAN
Suku Banjar merupakan kelompok mayoritas yang mendiami
wilayah Kalimantan Selatan. Pada awalnya kelompok ini banyak
menempati wilayah pesisir dengan mata pencaharian utama berdagang.
Namun belakangan, suku Banjar juga mulai menempati wilayah-wilayah
pedalaman di sekitar pegunungan Meratus untuk menjalani kehidupan
sebagai petani karet atau berladang sebagaimana yang dilakukan oleh
masyarakat Meratus pada umumnya.
Islam merupakan agama mayoritas pada orang Banjar. Namun dalam
prakteknya terdapat beberapa kepercayaan dan ritual yang
menggambarkan sinkretisme ajaran Islam dan kepercayaan animisme yang
ada sebelumnya. Hal ini terdapat pada kepercayaan terhadap hantu yang
berupa orabg gaib, menghormati roh nenek moyang, dan beberapa
penyakit yang dihadirkan oleh orang gaib dan roh nenek moyang.
Namun terlepas dari itu semua hal terpenting yang dapat penulis
simpulkan adalah bahwa setiap peradaban bermula dari suatu peradaban
yang dianggap aneh oleh peradaban dewasa ini. Hal tersebut tidak dapat
dipungkiri, tapi lantas kita tidak boleh meremehkan kepercayaan dan
peradaban terdahulu, sebab dari sana pokok pikiran dan budaya kita
sekarang alhir dan berkembang. Apapun yang terjadi kepercayaan
animisme dan dinamisme (meskipun kuno) ia tetap menjadi identitas
bangsa Indonesia yang sepatutnya kita hormati.
http://mengsleheuheu3.blogspot.com/2018/01/kepercayaan-urang-banjar-di-
kalimantan.html
Anda mungkin juga menyukai
- Jurnal Analisis Pencucian Sarang Burung WaletDokumen15 halamanJurnal Analisis Pencucian Sarang Burung WaletSMAN 1 PANAI TENGAHBelum ada peringkat
- Kepentingan Hutan Paya BakauDokumen8 halamanKepentingan Hutan Paya BakauArab Mosa100% (1)
- Kearifan Lokal Dalam Pemanfaatan Lahan Lebak Untuk Pertanian Di Kalimantan SelatanDokumen16 halamanKearifan Lokal Dalam Pemanfaatan Lahan Lebak Untuk Pertanian Di Kalimantan Selatanmutia aBelum ada peringkat
- Masyarakat Undau MauDokumen8 halamanMasyarakat Undau MaubudimagBelum ada peringkat
- Kelompok 10Dokumen17 halamanKelompok 10Benvica Regita CahyaniBelum ada peringkat
- Aspek Sosiokultural Kearifan Lokal Masyarakat Pada Lingkungan LahanDokumen10 halamanAspek Sosiokultural Kearifan Lokal Masyarakat Pada Lingkungan LahanRayhan Hafizh100% (3)
- Kehidupan Masyarakat SungaiDokumen15 halamanKehidupan Masyarakat SungaiAhmad SuhaimiBelum ada peringkat
- Masyarakat Undau MauDokumen9 halamanMasyarakat Undau MauMoegie Mugz Mugz100% (2)
- Bab III Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Pesisir Dan NelayanDokumen18 halamanBab III Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Pesisir Dan Nelayanmohammadyunus1992Belum ada peringkat
- Adaptasi Manusia Dalam Berladang Dan BersawahDokumen7 halamanAdaptasi Manusia Dalam Berladang Dan BersawahDzulismi Ayuninda SBelum ada peringkat
- BAB 3 Potensi Dan Masalah Pemanfaatan Lahan Rawa LebakDokumen7 halamanBAB 3 Potensi Dan Masalah Pemanfaatan Lahan Rawa Lebaktasha_abollaBelum ada peringkat
- Bab IDokumen12 halamanBab IFatimah Yushar IskandarBelum ada peringkat
- Iodiversitas Dan Kearifan Lokal Dalam Pertanian Lahan GambutDokumen7 halamanIodiversitas Dan Kearifan Lokal Dalam Pertanian Lahan GambutDewi Sagita SasaBelum ada peringkat
- Ppt. Ips Putri Meida Sari (0306202043)Dokumen15 halamanPpt. Ips Putri Meida Sari (0306202043)Faza Rezky AshifahBelum ada peringkat
- Revitalisasi Adat MelayuDokumen17 halamanRevitalisasi Adat MelayuYandra WindesiaBelum ada peringkat
- Lahan Basah Danau Dan Lahan Basah BuatanDokumen7 halamanLahan Basah Danau Dan Lahan Basah BuatanIqbal Julian ArrizkyBelum ada peringkat
- Kelompok 2 - Lahan Rawa Pasang SurutDokumen9 halamanKelompok 2 - Lahan Rawa Pasang SurutBayu Muhaimin ChaniagoBelum ada peringkat
- Budaya Lahan KeringDokumen14 halamanBudaya Lahan Keringelvhynd bei100% (2)
- Almanik Suryo Kuncoro (1810112210020) Proposal PenelitianDokumen23 halamanAlmanik Suryo Kuncoro (1810112210020) Proposal PenelitianIrfan Maulana Pradana skrillexborneoBelum ada peringkat
- Ekologi - Keseimbangan LingkunganDokumen13 halamanEkologi - Keseimbangan LingkunganHantinifitriBelum ada peringkat
- Suku Talang MamakDokumen14 halamanSuku Talang MamakTaman ArengkaBelum ada peringkat
- Kearifan Lokal Masyarakat Dayak, Lingkungan Hidup Masyarakat Dayak, Kalimantan TengahDokumen15 halamanKearifan Lokal Masyarakat Dayak, Lingkungan Hidup Masyarakat Dayak, Kalimantan Tengahfidelis_harefaBelum ada peringkat
- Perkembangan Manusia Dalam Sistem Mata PDokumen6 halamanPerkembangan Manusia Dalam Sistem Mata PBayu SugaraBelum ada peringkat
- Mata Pencaharian Suku Dayak Di Kalimantan Tengah Dan Suku JawaDokumen2 halamanMata Pencaharian Suku Dayak Di Kalimantan Tengah Dan Suku JawaSi IprikitiwBelum ada peringkat
- Ciri-Ciri Pertanian LokalDokumen9 halamanCiri-Ciri Pertanian LokalStella Marmah Suhatril0% (1)
- 42 78 1 SMDokumen11 halaman42 78 1 SMeka prasetyaBelum ada peringkat
- Tradisi Mulaka NgerbahDokumen25 halamanTradisi Mulaka NgerbahWidya SyawalBelum ada peringkat
- Ekologi Kelompok 5 Keseimbangan Ekologis Kehidupan ManusiaDokumen13 halamanEkologi Kelompok 5 Keseimbangan Ekologis Kehidupan ManusiaPuskesmas Harapan MulyaBelum ada peringkat
- Isi Laporan Gangguan ManusiaDokumen6 halamanIsi Laporan Gangguan ManusiaLeni FirdayantiBelum ada peringkat
- Nur Indah SariDokumen12 halamanNur Indah SariAbdul RahmanBelum ada peringkat
- Kearifan Lokal Dalam Budaya Nasional IndonesiaDokumen4 halamanKearifan Lokal Dalam Budaya Nasional IndonesiaSiloam MatausejaBelum ada peringkat
- Budaya Lahan Kering KepulauanDokumen12 halamanBudaya Lahan Kering KepulauanDewi Lita Endra Wati67% (3)
- Kearifan LokalDokumen8 halamanKearifan LokalGiska ManikasariBelum ada peringkat
- Konsep Dan Teknik Sea Ranching Pada Kerang AbalonDokumen5 halamanKonsep Dan Teknik Sea Ranching Pada Kerang AbalonDicki CountThreeBelum ada peringkat
- PLLB Adaptasi Budaya Masyarakat Di Lahan BasahDokumen3 halamanPLLB Adaptasi Budaya Masyarakat Di Lahan BasahAhmad Najib NajmuddinBelum ada peringkat
- Kebudayaan Pertanian KalselDokumen8 halamanKebudayaan Pertanian KalselAkbar Budi LaksonoBelum ada peringkat
- Aren Sulawesi Tengah PDFDokumen7 halamanAren Sulawesi Tengah PDFHariyanto Abdee NegoroBelum ada peringkat
- Review Jurnal KonservasiDokumen19 halamanReview Jurnal Konservasiennotien100% (1)
- p3264073 PDFDokumen7 halamanp3264073 PDFHidayat Brigit 3112Belum ada peringkat
- Laporan Agroforestri Tradisional-1Dokumen8 halamanLaporan Agroforestri Tradisional-1Patricia SuhartonoBelum ada peringkat
- Aris PonimanDokumen15 halamanAris PonimanAgung Nugroho ZainiBelum ada peringkat
- Pengantar Lahan Basah Kel. 10Dokumen17 halamanPengantar Lahan Basah Kel. 10WordBelum ada peringkat
- Kegiatan Ekonomi Tradisional Melayu (SEM3)Dokumen2 halamanKegiatan Ekonomi Tradisional Melayu (SEM3)TheStalkerZone 51Belum ada peringkat
- VickoDokumen13 halamanVickoTeuku GilangBelum ada peringkat
- Manfaat LamunDokumen7 halamanManfaat LamunshintadspBelum ada peringkat
- Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Lahan GambutDokumen8 halamanKearifan Lokal Dalam Pengelolaan Lahan GambutadhenancBelum ada peringkat
- Laporan PKLP Baluran FixDokumen135 halamanLaporan PKLP Baluran FixASA 29Belum ada peringkat
- 10 NgahumaDokumen41 halaman10 NgahumaRezvira EdrianiBelum ada peringkat
- Kearifan Lokal Di MalukuDokumen6 halamanKearifan Lokal Di Malukuaurelio hendriksz100% (1)
- PesisirDokumen10 halamanPesisirAidafajriyaNot Zhacto-chazze Affaffoo-HorazzBelum ada peringkat
- Makalah Pip AkmalDokumen5 halamanMakalah Pip AkmalAkmal FikriawanBelum ada peringkat
- Apartemen IkanDokumen14 halamanApartemen IkanPenyu LuhBelum ada peringkat
- Makalh Ekologi KeseimbanganDokumen25 halamanMakalh Ekologi KeseimbanganAndi SmartBelum ada peringkat
- Sumber Daya Alam Yang Memiliki Sifat GabunganDokumen8 halamanSumber Daya Alam Yang Memiliki Sifat GabunganTupai LoncatBelum ada peringkat
- 10.INSANI TUPAHIL SATINDO (181210665) Kearifan LokalDokumen5 halaman10.INSANI TUPAHIL SATINDO (181210665) Kearifan LokalNabila TrianaBelum ada peringkat
- Laporan Teknis - Kajian Kehati Partisipatif - Draft0Dokumen54 halamanLaporan Teknis - Kajian Kehati Partisipatif - Draft0Naufal AthayasedaBelum ada peringkat
- Pengelolaan Tambak Intensif Berwawasan LingkunganDokumen8 halamanPengelolaan Tambak Intensif Berwawasan LingkunganRiky ArisandiBelum ada peringkat
- Poli KulturDokumen6 halamanPoli KultursenoscribdBelum ada peringkat
- 145-File Utama Naskah-468-1-10-20180815Dokumen10 halaman145-File Utama Naskah-468-1-10-20180815anon_509992240Belum ada peringkat