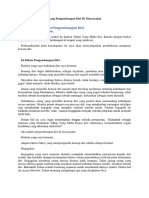Avisena, Etika 4c
Diunggah oleh
AvisenaDeskripsi Asli:
Judul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Avisena, Etika 4c
Diunggah oleh
AvisenaHak Cipta:
Format Tersedia
Nama: Avisena
Nim: 11210331000077
Kelas: AFI 4C
Matakuliah: Etika AFI 4C (12:45)
1. Dalam menyikapi berbagai masalah konflik yang dihadapi, baik itu konflik kepentingan
maupun dilema, setidaknya sampai sekarang, saya cenderung berhaluan utilitarian sekaligus
menganut etika kantian dilain pihak. Dalam kasus konflik kepentingan misalnya; “saya lebih
mengutamakan my time dibandingan merelakan kesehatan psikis untuk keperluan orang
lain”. Dalam hal ini, corak utilitarian justru saya tempatkan (mengutamakan) pada diri sendiri
untuk melihat ‘akibat’ kepada orang lain. Alasanya sederhana saja, saya pikir banyak orang
diluar sana, yang bertentangan dengan nilai moral universal seperti; membunuh, berbohong,
mencuri dll, berawal dari kesehatan mental yang dialami. Jika saya terus merelakan
kesehatan mental saya demi melayani orang lain (saya memahaminya sebagai tuntutan
sebagai makhluk sosial), yang mana bisa mengakibatkan ‘stres’ yang berat, maka saya pikir
akan menimbulkan masalah yang lebih banyak dibandingkan kebaikan yang saya berikan.
Berawal dari kondisi ‘stres’ yang dialami, mengakibatkan kondisi yang tidak stabil, tidak
fokus pada sesuatu yang dikerjakan, seperti misalnya; teman saya meminta bantuan untuk
mengerjakan tugasnya, karena kondisi yang lelah, kurang waktu untuk istirahat, kondisi yang
tidak stabil, mengakibatkan tugas yang saya bantu bisa saja salah atau keliru, dan bahkan
bisa mengakibatkan yang lebih parah lagi dalam ranah sosial. Dilain pihak, saya juga percaya
bahwa ‘membantu’ itu merupakan hal yang baik, semakin banyak membantu maka semakin
banyak juga hal baik yang dilakukan. Bukan karena alasan tertentu, tapi karena kebaikan
adalah ‘baik’ itu sendiri.
2. Dalam menanggapi fenomena ‘Idul Fitri’, jika pertanyaannya adalah keutamaan
‘memaafkan’ dan ‘meminta’ maaf, saya menempatkan diri saya sebagai orang yang
beragama Islam. Bahwa, dalam konteks ‘memaafkan dan ‘meminta maaf’ merupakan dua
nilai yang setara dalam kualitas kebaikannya (dalam konteks tertentu). Dalam ajaran Islam,
ketika dihadapkan dengan permasalahan hubungan antara manusia, misalnya; saya
bertengkar dengan kakak saya karena persoalan pembagian piket kebersihan, saya
mendapatkan jadwal pagi dan kakak di sore hari. Tapi karena ada kondisi yang mendesak di
pagi hari, yang mengharuskan untuk mengganti jadwal piketnya di pagi hari dan
mengerjakannya di sore hari. Dalam konteks itu, Islam mengajarkan bahwa ketika ada
pertengkaran antara dua orang atau lebih, “maka diharamkan untuk saling mendiami selama
tiga hari. Dan yang lebih utama adalah dari mereka adalah orang yang menyapa terlebih
dahulu”. Disini saya memahami sikap ‘menyapa’ sebagai bentuk memafaankan dan
permintaan maaf (karena bisa saja itu berawal dari kesalahpahaman atau miskomunikasi).
(Lihat: HR. Bukhori dan Muslim). Tetapi dalam konteks tertentu saya pikir bahwa
‘memaafkan’ mempunyai kedudukan lebih setingkat daripada ‘meminta maaf’, karena,
seringkali kita merasa berat untuk memaafkan dibandingkan meminta maaf. Misalnya dalam
konteks mencuri, seringkali susah memaafkan orang yang telah mencuri barang kita
(meskipun ia dalam keadaan mendesak) walaupun ia sudah meminta maaf kepada kita.
Karena tantangannya lebih berat, maka kemuliaannya atau kebaikannya juga lebih
dibandingkan hanya meminta maaf saja. Dalam konteks ini, jika saya menempatkan diri saya
sebagai seorang utilitarian, maka, saya akan memaafkan dengan keutamaannya; karena jika
saya tidak memaafkannya, mungking si pencuri tersebut akan merasa bahwa tidak ada lagi
harapan untuk dia berubah. Jika demikian, karena perasaan ‘tidak ada kesempatannya untuk
berubah’ memungkinkan untuknya mengulangi perbuatan yang sama pada orang lain dilain
waktu. Dalam hal ini, saya sebagai kantian tidak mengartikan ‘memaafkan’ sebagai bentuk
‘melupakan’ tetapi sebaliknya, bahwa perbuatan salah tetap salah. Tetapi bagaimana cara
menjadikannya pelajaran agar menghasilkan keutamaan bagi pribadi dan orang banyak,
bukan karena alasan tertentu, tapi melainkan itu adalah kebaikan itu sendiri.
3. Contoh kasus yang bisa saya berikan dalam kehidupan pribadi, ketika menasehati diri saya
dan saudara saya tentang malas kebersihan. Dalam persoalan fiqih, tidak ada hukum
tertentu yang mengatur tentang rasa malas; menjaga kebersihan, bersikap tidak ramah, dan
persoalan etis lainya, tapi melainkan membahas apa perbuatan yang nyata dan hukumnya
(mana yang boleh dan mana yang tidak secara hukum). Analoginya seperti rambu lalu-lintas,
fiqih hanya membahas tentang orang-orang yang melanggar lalu-lintas; tidak memakai helm,
menerobos lampu merah dll, tetapi tidak membahas apakah dia malas (tidak memakai helm,
malas menunggu lampu merah dll). Tapi dalam konteks soal yang diberikan, setidaknya
sampai sekarang, pemahaman saya antara ranah fiqih dan etika masih saja beririsan.
Mengenai kebersihan, memang tidak diatur dalam fiqih tapi dalam ruang lingkup syariah itu
semua diatur (etika, etos, akhlak, perasaan, estetika dll). Dalam kajian syariah, bermalas-
malasan itu tidak dibenarkan. Memang dalam hal ini ilmu fiqih tidak membahas secara
langsung ‘hukum malas’. Tetapi ketika seorang terlambat mengerjakan ibadah lima waktu,
maka ada hukum fiqihnya. Lepas dari apa yang menjadi dasar keterlambatannya, apakah
malas mandi, malas bangun dll, fiqih menitik beratkan bahwa kewajiban shalat tidak gugur
karena sikap malas, melainkan orang itu wajib mengqadha’ shalatnya.
Anda mungkin juga menyukai
- Makalah Tentang Makna Berbuat Baik Dalam Kehidupan ManusiaDokumen6 halamanMakalah Tentang Makna Berbuat Baik Dalam Kehidupan ManusiaEdi Karang PendetaBelum ada peringkat
- Pengertian Sifat Hakikat ManusiaDokumen4 halamanPengertian Sifat Hakikat ManusiaNobody QuesBelum ada peringkat
- Analisis Kasus Carl Rogers - WPS OfficeDokumen5 halamanAnalisis Kasus Carl Rogers - WPS Officedewi fortunaBelum ada peringkat
- Etika Akhlak Dan MoralDokumen4 halamanEtika Akhlak Dan MoralBagus PutraBelum ada peringkat
- SILATURAHImDokumen4 halamanSILATURAHImDwi SetyawanBelum ada peringkat
- Tugas PPT PaiDokumen12 halamanTugas PPT PaiArini NuriBelum ada peringkat
- Latar BelakangDokumen6 halamanLatar BelakangovieBelum ada peringkat
- Guna Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Ilmu Kalam/tauhid Yang BerjudulDokumen13 halamanGuna Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Ilmu Kalam/tauhid Yang BerjudulHauzzan FelgiansyahBelum ada peringkat
- Konsep Etika Dalam Pandangan IslamDokumen16 halamanKonsep Etika Dalam Pandangan IslamSarah Ristika67% (3)
- Dia Itu Gitu, Kenapa Gak Kayak AkuDokumen3 halamanDia Itu Gitu, Kenapa Gak Kayak AkuRehab Napza RSJSBelum ada peringkat
- Contoh Teks PidatoDokumen10 halamanContoh Teks PidatoTiffanAzhimiMarsenoBelum ada peringkat
- Saling Menghormati Dan MenghargaiDokumen9 halamanSaling Menghormati Dan Menghargaiahgase snxxsnxxBelum ada peringkat
- Mantiq PDFDokumen156 halamanMantiq PDFAmirul Bahri100% (3)
- Essai KAMMIDokumen4 halamanEssai KAMMIsalman alfarisiyBelum ada peringkat
- Pengertian Budi PekertiDokumen19 halamanPengertian Budi PekertiDeu Dinul Damai Sworo100% (1)
- (Etika) Alfian Tri Laksono - 1201010007Dokumen4 halaman(Etika) Alfian Tri Laksono - 1201010007alfiantrilaksono378Belum ada peringkat
- Thomas ScanlonDokumen4 halamanThomas ScanlonHEMAWATHY A/P ARUMUGAMBelum ada peringkat
- TUGAS PPT PAIDokumen11 halamanTUGAS PPT PAIArini NuriBelum ada peringkat
- Agama Sebagai MotivatorDokumen3 halamanAgama Sebagai MotivatorNanda RastaBelum ada peringkat
- Alia Rohani - Tugas Aktualisasi DiriDokumen7 halamanAlia Rohani - Tugas Aktualisasi DirialiaBelum ada peringkat
- Manusia Dan Hubungan Horizontal Dan VertikalDokumen2 halamanManusia Dan Hubungan Horizontal Dan Vertikalbi YuenBelum ada peringkat
- Uas Etika Kristen YosuaDokumen4 halamanUas Etika Kristen YosuaPatri MallisaBelum ada peringkat
- Tugas Agama Hindu Tugas 2Dokumen14 halamanTugas Agama Hindu Tugas 2Dewa YudiBelum ada peringkat
- Artikel Fikri MahmudDokumen9 halamanArtikel Fikri MahmudMee Lye FtrBelum ada peringkat
- Berakhlak Mulia Dalam Masyarakat Digital Saat Ini PDFDokumen6 halamanBerakhlak Mulia Dalam Masyarakat Digital Saat Ini PDFfiqih maulanaBelum ada peringkat
- AltruismeDokumen6 halamanAltruismeACC ARKBelum ada peringkat
- Makalah Meningkatkan Prilaku MenolongDokumen15 halamanMakalah Meningkatkan Prilaku MenolongWiwin HandayaniBelum ada peringkat
- Bagaimana Anda Menjadi Orang Yang Bertanggung Jawab Multazam AkbarDokumen2 halamanBagaimana Anda Menjadi Orang Yang Bertanggung Jawab Multazam Akbar230802098Belum ada peringkat
- (REV) Teks Pidato Tanggung Jawab - Wilson CorneliusDokumen3 halaman(REV) Teks Pidato Tanggung Jawab - Wilson CorneliusLAILATUL NURJANAHBelum ada peringkat
- Makalah AgamaDokumen10 halamanMakalah AgamaDevita Rahmawati Sutrasno100% (1)
- Pertemuan Ke-3 Bab 1 (Ukhuwah)Dokumen4 halamanPertemuan Ke-3 Bab 1 (Ukhuwah)yusufBelum ada peringkat
- Makalah Perilaku Tanggung JawabDokumen23 halamanMakalah Perilaku Tanggung JawabLeniBelum ada peringkat
- Tugas Akhir EtikaDokumen2 halamanTugas Akhir Etikaalda SindhyBelum ada peringkat
- FilsafatDokumen17 halamanFilsafatDwi Haryadi NugrahaBelum ada peringkat
- C2C020036 - Etika Budaya JawaDokumen17 halamanC2C020036 - Etika Budaya JawaLala SosoBelum ada peringkat
- Prinsip Asas KemoralanDokumen4 halamanPrinsip Asas KemoralanThaevakumari AnndyBelum ada peringkat
- Tugas Pai 2Dokumen3 halamanTugas Pai 2F12Mifthachul Nur Ihza.ABelum ada peringkat
- Teologi MoralDokumen4 halamanTeologi MoralAlifia Putri RamadhaniBelum ada peringkat
- Tugas Kelompok 3 (Minggu 8 / Sesi 12) : 2301962465 - Ismi Tania 2301961840 - Nurmalia SafitriDokumen3 halamanTugas Kelompok 3 (Minggu 8 / Sesi 12) : 2301962465 - Ismi Tania 2301961840 - Nurmalia SafitriNurmalia SafitriBelum ada peringkat
- Kesalahan LogikaDokumen19 halamanKesalahan LogikaTolere Daeng PalingeBelum ada peringkat
- Esei MoralDokumen15 halamanEsei MoralRajasree Karunamoorthy0% (1)
- Refleksi TeologiMoraDokumen5 halamanRefleksi TeologiMoraYosep ValenBelum ada peringkat
- Menakar Proyek Nahi Munkar Lintas AgamaDokumen4 halamanMenakar Proyek Nahi Munkar Lintas AgamaAhmad A. Na'im-iBelum ada peringkat
- Kepedulian SosialDokumen10 halamanKepedulian SosialMirrah MeGhaBelum ada peringkat
- RESUME 2 Filsafat Moral - Anis Sonia - 19500022Dokumen4 halamanRESUME 2 Filsafat Moral - Anis Sonia - 19500022AnisBelum ada peringkat
- Pembentukan Insan Bermoral Secara TerpimpinDokumen22 halamanPembentukan Insan Bermoral Secara TerpimpinGeethu Princess100% (1)
- Husnudzon Dan UkhuwahDokumen7 halamanHusnudzon Dan Ukhuwahayazka100% (1)
- Soalan Tutorial Pengenalan Kepada Pendidikan MoralDokumen6 halamanSoalan Tutorial Pengenalan Kepada Pendidikan MoralLooi Hooi ChenBelum ada peringkat
- Moral EseiDokumen18 halamanMoral EseiPatrick Wong Pak Ying50% (4)
- Pandangan HidupDokumen12 halamanPandangan Hiduptwin fitersya S.EiBelum ada peringkat
- Bersilaturahmi DanDokumen6 halamanBersilaturahmi Dansyifa syifaBelum ada peringkat
- RikaDokumen2 halamanRikaJuatno PendungBelum ada peringkat
- Pengertian AqidahDokumen15 halamanPengertian AqidahGis Gidamee100% (1)
- Tugasan 1 MPU3102 Pengenalan Kepada Pendidikan MoralDokumen8 halamanTugasan 1 MPU3102 Pengenalan Kepada Pendidikan MoralPeggy WongBelum ada peringkat
- Tugas EtikaDokumen6 halamanTugas EtikaPrianka Dwi Pangestika0% (1)
- EtSos Tapi B Indo - Hati NuraniDokumen30 halamanEtSos Tapi B Indo - Hati NuraniNabiel Bayu Al GamarBelum ada peringkat
- Harvard Business Review's 10 Must Reads: Pengurusan Diri Sendiri (Edisi Bahasa Melayu)Dari EverandHarvard Business Review's 10 Must Reads: Pengurusan Diri Sendiri (Edisi Bahasa Melayu)Penilaian: 3.5 dari 5 bintang3.5/5 (12)
- Manajemen konflik dalam 4 langkah: Metode, strategi, teknik-teknik penting, dan pendekatan operasional untuk mengelola dan menyelesaikan situasi konflikDari EverandManajemen konflik dalam 4 langkah: Metode, strategi, teknik-teknik penting, dan pendekatan operasional untuk mengelola dan menyelesaikan situasi konflikBelum ada peringkat
- Resume Makalah Agama Dunia, AvisenaDokumen3 halamanResume Makalah Agama Dunia, AvisenaAvisenaBelum ada peringkat
- RPP 99505Dokumen24 halamanRPP 99505AvisenaBelum ada peringkat
- Tulisan AvisenaDokumen2 halamanTulisan AvisenaAvisenaBelum ada peringkat
- HINDUISME, Aida Intan LestariDokumen14 halamanHINDUISME, Aida Intan LestariAvisenaBelum ada peringkat
- EstetikaDokumen1 halamanEstetikaAvisenaBelum ada peringkat
- Makalah Kel.5, Agama HinduismeDokumen39 halamanMakalah Kel.5, Agama HinduismeAvisenaBelum ada peringkat
- UAS PFI (Resensi Buku)Dokumen3 halamanUAS PFI (Resensi Buku)AvisenaBelum ada peringkat
- Avisena, Filsafat IslamDokumen2 halamanAvisena, Filsafat IslamAvisenaBelum ada peringkat
- Filsafat RenainssanceDokumen3 halamanFilsafat RenainssanceAvisenaBelum ada peringkat
- TUGAS ILMU MANTIK AvisenaDokumen1 halamanTUGAS ILMU MANTIK AvisenaAvisenaBelum ada peringkat
- Pertemuan 10, AvisenaDokumen1 halamanPertemuan 10, AvisenaAvisenaBelum ada peringkat
- Maqamat, Avisena 11210331000077Dokumen2 halamanMaqamat, Avisena 11210331000077AvisenaBelum ada peringkat
- AhwalDokumen3 halamanAhwalAvisenaBelum ada peringkat
- Tasawuf Akhlaki J AvisenaDokumen3 halamanTasawuf Akhlaki J AvisenaAvisenaBelum ada peringkat
- Tugas Pengantar Ilmu TasawufDokumen3 halamanTugas Pengantar Ilmu TasawufAvisenaBelum ada peringkat
- Avisena, Bahasa Arab, Afi 2cDokumen1 halamanAvisena, Bahasa Arab, Afi 2cAvisenaBelum ada peringkat
- PengantarFilsafat IslamDokumen2 halamanPengantarFilsafat IslamAvisenaBelum ada peringkat