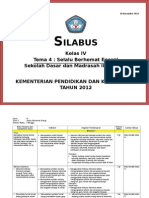Makalah Hubungan Kurikulum Dan Pembelajaran Kelompok 2
Makalah Hubungan Kurikulum Dan Pembelajaran Kelompok 2
Diunggah oleh
Sri RahayuJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Makalah Hubungan Kurikulum Dan Pembelajaran Kelompok 2
Makalah Hubungan Kurikulum Dan Pembelajaran Kelompok 2
Diunggah oleh
Sri RahayuHak Cipta:
Format Tersedia
lOMoARcPSD|19983118
Makalah Hubungan Kurikulum dan Pembelajaran Kelompok 2
Kurikulum Dan Pembelajaran (Universitas Pendidikan Indonesia)
Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Sri Rahayu (sr482676@gmail.com)
lOMoARcPSD|19983118
Hubungan Kurikulum dan Pembelajaran Secara Umum
MAKALAH
Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata
kuliah Kurikulun dan Pembelajaran Kode DK303
Dosen Pengampu: Dr. Lutfi Nur, S.Pd., M.Pd.
Ika Fitri Apriani, S.Pd., M.Pd.
oleh:
Kelompok 6
Kelas 2C
Adinda Novita Andhini (1901781)
Ajeng Anisatu Rahmah (1904794)
Nuri Aprilia Muharoni (1904103)
Milah Nur Zaqi (1909408)
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
KAMPUS TASIKMALAYA
2021
Downloaded by Sri Rahayu (sr482676@gmail.com)
lOMoARcPSD|19983118
KATA PENGANTAR
Puji serta syukur kehadirat Alloh swt, yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya
kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan
kepada Nabi Muhammad Saw.
Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan tugas Mata Kuliah Kurikulum
dan Pembelajaran mengenai “Hubungan Kurikulum dan Pembelajaran Secara
Umum” tepat pada waktu yang telah ditentukan.
Melalui penulisan makalah mengenai “Hubungan kurikulum dan
Pembelajran Secara Umum” ini, kiranya dapat menjadi bahan pembelajaran untuk
kita sebagai pelaksana pendidikan, dalam kegiatan belajar baik di dalam
lingkungan pendidikan maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Tak ada gading yang tak retak. Penulis menyadari bahwa makalah ini
masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kontribusi
pemikiran pembaca sehingga makalah ini bermanfaat bagi kita semua.
Tasikmalaya, Februari 2021
Penyusun,
ii
Downloaded by Sri Rahayu (sr482676@gmail.com)
lOMoARcPSD|19983118
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................................ii
DAFTAR ISI..........................................................................................................iii
BAB I
PENDAHULUAN...................................................................................................1
1.1 Latar Belakang...................................................................................................1
1.2 Rumusan Masalah..............................................................................................1
1.3 Tujuan Penulisan................................................................................................2
1.4 Manfaat..............................................................................................................2
BAB II
ISI.............................................................................................................................3
2.1 Kajian Pustaka....................................................................................................3
2.2 Pembahasan........................................................................................................4
BAB III
PENUTUP.............................................................................................................17
3.1 Simpulan..........................................................................................................17
3.2 Saran.................................................................................................................17
DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................18
iii
Downloaded by Sri Rahayu (sr482676@gmail.com)
lOMoARcPSD|19983118
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Masa depan bangsa terletak dalam tangan generasi muda. Mutu bangsa di
kemudian hari bergantung pada pendidikan yang dikecap oleh anak-anak
sekarang, terutama melalui pendidikan formal yang diterima di sekolah. Apa yang
akan dicapai di sekolah, ditentukan oleh kurikulum sekolah itu. Dengan kata lain,
kurikulum menjadi penentu nasib masa depan bangsa ini. Maka dapat dipahami
bahwa kurikulum sebagai alat yang begitu vital bagi perkembangan bangsa
dipegang oleh pemerintahan suatu negara. Dapat pula dipahami betapa pentingnya
usaha mengembangkan kurikulum itu. Oleh sebab itu, setiap guru merupakan
kunci utama dalam pelaksanaan kurikulum, maka ia harus pula memahami seluk
beluk kurikulum.
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kurikulum adalah apa yang akan
diajarkan, sedangkan pembelajaran (instruction) adalah bagaimana
menyampaikan apa yang akan diajarkan tersebut. Dengan perkataan lain,
kurikulum adalah suatu program, tindakan belajar-mengajar, dan presentasi.
Setiap pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di kelas, selalu berangkat dari
landasan-landasan pembelajaran yang tertulis dalam kurikulum. Setiap
pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru merupakan bagian utama dari
pendidikan formal yang syarat wajib dari pelaksanaannya adalah adanya
kurikulum sebagai pedoman atau kitab suci dari terlaksananya proses belajar dan
mengajar di kelas.
Hubungan antara kurikulum dan pembelajaran seperti dua sisi mata uang
logam yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Di satu sisi, kurikulum
merupakan rancangan dan pengaturan belajar-mengajar, sementara di sisi yang
lainnya pembelajarannya, yang tidak lain adalah pelaksanaan dari rancangan yang
sudah dibuat sebelumnya. Perbedaan kedudukan tersebut dapat dilihat dari
fungsinya. Kurikulum berfungsi sebagai landasan yang memberikan arah dan
tujuan pendidikan, serta isi yang harus dipelajari, sedangkan pembelajaran adalah
proses yang terjadi dalam interaksi belajar dan mengajar antara guru dan siswa.
Mengingat pentingnya peranan kurikulum dan pembelajaran di dalam
pendidikan dan dalam perkembangan kehidupan manusia, maka dalam
pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran tidak bisa dilakukan tanpa
menggunakan landasan yang kokoh dan kuat. Oleh karena itu, makalah ini akan
mengungkapkan hubungan antara kurikulum dan pembelajaran.
1.2 Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dari makalah ini, di antaranya:
1.2.1 Apa pengertian dari kurikulum?
Downloaded by Sri Rahayu (sr482676@gmail.com)
lOMoARcPSD|19983118
1.2.2 Apa fungsi kurikulum?
1.2.3 Apa peranan dari kurikulum?
1.2.4 Apa saja komponen kurikulum?
1.2.5 Apa hakekat dari pembelajaran?
1.2.6 Apa saja rinsip-prinsip pembelajaran?
1.2.7 Bagaimana hubungan kurikulum dan pembelajaran secara umum?
1.3 Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penulisan makalah
ini, yaitu:
1.3.1 Untuk mengetahui pengertian dari kurikulum
1.3.2 Untuk mengetahui fungsi kurikulum
1.3.3 Untuk mengetahui peranan dari kurikulum
1.3.4 Untuk mengetahui komponen yang membentuk kurikulum
1.3.5 Untuk mengetahui hakekat dari pembelajaran
1.3.6 Untuk mengetahui prinsip-prinsip pembelajaran
1.3.7 untuk mengetahui bagaimana hubungan dan pembelajaran secara umum
1.4 Manfaat
Adapun manfaat dari penulisan makalah ini yaitu dapat mengetahui
pengertian kurikulum dan pembelajaran, serta mengetahui bagaimana hubungan
mengenai kurikulum dan pembelajaran secara umum.
Downloaded by Sri Rahayu (sr482676@gmail.com)
lOMoARcPSD|19983118
BAB II
ISI
2.1 Kajian Pustaka
Istilah kurikulum (curriculum), yang pada awalnya digunakan dalam dunia
olahraga, berasal dari kata curir (pelari) dan curere (tempat berpacu). Pada saat
itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari
mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali/ penghargaan. Kemudian,
pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata
pelajaran (subjects) yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai
akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah.
Dari pengertian tersebut, dalam kurikulum terkandung dua hal pokok, yaitu (1)
adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa, dan (2) tujuan utamanya
yaitu untuk memperoleh ijazah. Dengan demikian, implikasi terhadap praktik
pengajaran yaitu setiap siswa harus menguasai seluruh mata pelajaran yang
diberikan dan menempatkan guru dalam posisi yang sangat penting dan
menentukan. Keberhasilan siswa ditentukan oleh seberapa jauh mata pelajaran
tersebut dikuasainya.
Sedangkan pembelajaran adalah proses sistematis di mana semua
komponen, antara lain guru, siswa, material dan lingkungan belajar merupakan
komponen penting untuk keberhasilan belajar hal tersebut diungkapkan oleh Dick
& Carey (1990: 2). Hal ini berarti bahwa pembelajaran adalah proses
transaksional (saling memberikan timbal balik) di antara komponen-komponen
sistem pembelajaran, yakni pendidik, peserta didik, bahan ajar, media, alat,
prosedur dan proses belajar guna mencapai suatu perubahan yang komprehensif
pada diri peserta didik. Perubahan yang komprehensif tersebut berarti perubahan
yang mendalam dan esensial pada perilaku, sikap, pengetahuan dan kemampuan
pemaknaan pada peseta didik yang dapat berguna untuk menyelesaikan
tugas/kewajibankewajiban dalam hidupnya, sehingga melalui sebuah kegiatan
pembelajaran yang berkelanjutan, seluruh kebutuhan hidup peserta didik tersebut
sebagai seorang insan manusia akan dapat terpenuhi.
Kurikulum dan pembelajaran mempunyai kedudukan yang sangat sentral
(penting) dalam pendidikan. Kurikulum sebagai bahan tertulis atau program
pendidikan (ideal curriculum) dengan lebih menekankan pada operasional proses
pembelajaran (real curriculum). Kurikulum berhubungan dengan isi/materi yang
harus dipelajari sedangkan pembelajaran berkaitan dengan cara mempelajarinya.
Tanpa kurikulum sebagai rencana, maka pembelajaran tidak akan efektif,
demikian juga sebaliknya tanpa pembelajaran sebagai implementasi sebuah
rencana, maka kurikulum tidak akan memiliki arti apa-apa. Kurikulum bertujuan
sebagai arah, pedoman, atau sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan proses
Downloaded by Sri Rahayu (sr482676@gmail.com)
lOMoARcPSD|19983118
pembelajaran (belajar mengajar). Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas
pembelajaran demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan.
2.2 Pembahasan
2.2.1 Kurikulum
Istilah kurikulum (curriculum), pada awalnya digunakan dalam dunia
olahraga, berasal dari kata curir (pelari) dan curere (tempat berpacu). Pada saat
itu kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari
mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan.
Kemudian, pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi
sejumlah mata pelajaran (subject) yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari
awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh ijazah.
Dari pengertian tersebut, dalam kurikulum terkandung dua hal pokok,
yaitu (1) adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa, dan (2) tujuan
utamanya yaitu untuk memperoleh ijazah. (Hermawan A.H. & Susilana, R., hlm.
2)
Kurikulum pada dimensi pertama mengandung makna bahwa pada
dasarnya kurikulum itu terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh
siswa. Dalam hal ini, kurikulum selalu berorientasi pada penguasaan isi atau
materi pelajaran sebagai sasaran akhir proses pendidikan (content oriented). Isi
atau materi pelajaran yang harus dikuasai siswa tersebut pada hakikatnya
merupakan ilmu pengetahuan yang terkait dengan setiap mata pelajaran. Dimensi
pengertian kurikulum sebagai mata pelajaran ini dianggap pandangan yang terlalu
sempit dan sederhana, namun demikian, pada kenyataannya masih banyak
diterapkan dalam praktik pelaksanaan pendidikan dewasa ini.
Kurikulum pada dimensi kedua tidak hanya dibatasi sebagai sejumlah
mata pelajaran saja, tetapi mencakup semua pengalaman belajar (learning
experiences) yang dialami siswa dan memengaruhi perkembangan pribadinya.
Dengan demikian, pengertian kurikulum itu mencakup seluruh kegiatan yang
dilakukan oleh siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat Zaputri (2019) bahwa
kurikulum ialah program pendidikan dan bukan program pengajaran, sehingga
program itu direncanakan dan dirancang sebagai bahan ajar dan juga pengalaman
belajar.
Menurut undang - undang no. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 19 tentang
sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah
“seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan
pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelengggaran kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan tertentu.”
Downloaded by Sri Rahayu (sr482676@gmail.com)
lOMoARcPSD|19983118
Menurut Anjarsari (2014) kurikulum merupakan dokumen rencana
pembelajaran dan memberikan acuan apa yang akan diajarkan. Sedangkan
menurut Fujiawati (2016: 17) kurikulum adalah perangkat pengalaman belajar
yang akan didapat oleh peserta didik selama ia mengikuti suatu proses pendidikan.
Dari semua pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kurikulum
adalah serangkaian program, rencana, dan dokumen tertulis yang dijadikan alat
atau media untuk menyukseskan pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat
tercapai dengan baik. Oleh karena itu keberhasilan dari suatu kurikulum yang
ingin dicapai sangat bergantung pada faktor kemampuan yang dimiliki oleh
seorang guru, artinya guru adalah orang yang bertanggung jawab dalam upaya
mewujudkan segala sesuatu yang telah tertuang dalam suatu kurikulum resmi.
Dapat dikatakan, guru berperan sebagai ujung tombak implementasi kurikulum.
2.2.2 Fungsi Kurikulum
Alexander Inglish, dalam bukunya Principles of Secondary Education
(dalam Oemar Hamalik, 2009) mengatakan bahwa fungsi kurikulum sebagai
berikut:
1. Fungsi penyesuaian (the adjustive or adaptive function)
Fungsi penyesuaian mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat
pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well adjusted,
yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik
maupun lingkungan sosial. Lingkungan itu sendiri senantiasa mengalami
perubahan dan bersifat dinamis. Oleh karena itu, siswa harus memiliki
kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di
lingkungannya.
2. Fungsi integrasi (the integrating function).
Fungsi integrasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan
harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Siswa pada dasarnya
merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat. Oleh karena itu, siswa
harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi
dengan masyarakatnya.
3. Fungsi diferensiasi (the differentiating function)
Fungsi diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat
pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu
siswa. Setiap siswa memiliki perbedaan, baik dari aspek fisik maupun psikis, yang
harus dihargai dan dilayani dengan baik.
Downloaded by Sri Rahayu (sr482676@gmail.com)
lOMoARcPSD|19983118
4. Fungsi persiapan (the propaedeutic function)
Fungsi persiapan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat
pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke
jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu, kurikulum juga diharapkan dapat
mempersiapkan siswa untuk dapat hidup dalam masyarakat seandainya ia karena
sesuatu hal, tidak dapat melanjutkan pendidikannya.
5. Fungsi pemilihan (the selective function)
Fungsi pemilihan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat
pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih
program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Fungsi
pemilihan ini sangat erat hubungannya dengan fungsi diferensiasi karena
pengakuan atas adanya perbedaan individual siswa berarti pula diberinya
kesempatan bagi siswa tersebut untuk memilih apa yang sesuai dengan minat dan
kemampuannya. Untuk mewujudkan kedua fungsi tersebut, kurikulum perlu
disusun secara lebih luas dan bersifat fleksibel (luwes/lentur).
6. Fungsi diagnostik (the diagnostic function)
Fungsi diagnostik mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat
pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat
memahami dan menerima kekuatan (potensi) dan kelemahan yang dimilikinya.
Apabila siswa sudah mampu memahami kekuatan-kekuatan dan kelemahan-
kelemahan yang ada pada dirinya maka diharapkan siswa dapat mengembangkan
sendiri potensi/kekuatan yang dimilikinya atau memperbaiki kelemahan-
kelemahannya. Keenam fungsi yang sudah dikemukakan harus dimiliki oleh suatu
kurikulum lembaga pendidikan secara menyeluruh (komprehensif). Dengan
demikian kurikulum dapat memberikan pengaruh bagi pertumbuhan dan
perkembangan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.
2.2.3 Peranan Kurikulum
Kurikulum memiliki kedudukan dan posisi yang sangat sentral dalam
keseluruhan proses pendidikan, bahkan kurikulum menjadi syarat mutlak dan
bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan itu sendiri. Menurut Oemar Hamalik
pada tahun 1990 (dalam Hernawan, Tanpa Tahun, hlm. 10) terdapat tiga peranan
kurikulum yang dinilai sangat penting, yaitu peranan konservatif, peranan kreatif,
dan peranan kritis/evaluatif berikut penguraiannya.
1. Peranan Konservatif
Peranan konservatif menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai
sarana untuk men-transmisi-kan atau mewariskan nilai-nilai budaya masa lalu
Downloaded by Sri Rahayu (sr482676@gmail.com)
lOMoARcPSD|19983118
yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda, dalam hal
ini para siswa sekolah dasar. Dengan demikian, peranan konservatif ini pada
hakikatnya menempatkan kurikulum yang berorientasi ke masa lampau. Peranan
ini sifatnya menjadi sangat mendasar, disesuaikan dengan kenyataan bahwa
pendidikan pada hakikatnya merupakan proses sosial, di mana salah satu tugas
pendidikan, yaitu memengaruhi dan membina perilaku siswa sesuai dengan nilai-
nilai sosial yang hidup di lingkungan masyarakatnya.
2. Peranan Kreatif
Peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan
sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-
kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Kurikulum
harus mengandung hal-hal yang dapat membantu setiap siswa mengembangkan
semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan-
pengetahuan baru, kemampuan-kemampuan baru, serta cara berpikir baru yang
dibutuhkan dalam kehidupannya.
3. Peranan Kritis dan Evaluatif
Peranan ini dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan
budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan sehingga
pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan
kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Selain itu, perkembangan yang terjadi
pada masa sekarang dan masa mendatang belum tentu sesuai dengan apa yang
dibutuhkan oleh siswa. Oleh karena itu, peranan kurikulum tidak hanya
mewariskan nilai dan budaya yang ada atau menerapkan hasil perkembangan baru
yang terjadi, melainkan juga memiliki peranan untuk menilai dan memilih nilai
dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan tersebut. Dalam hal ini,
kurikulum memiliki peranan sebagai kontrol atau filter sosial. Nilai-nilai sosial
yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tuntutan masa kini dihilangkan dan
diadakan modifikasi atau penyempurnaan-penyempurnaan. (Hernawan, Tanpa
Tahun, 10-11)
2.2.4 Komponen-Komponen Kurikulum
Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan memiliki komponen
pokok yang saling berkaitan, berinteraksi dalam rangka mendukung tercapainya
tujuan. Kurikulum memiliki lima komponen utama, yaitu (1) tujuan; (2) materi;
(3) strategi pembelajaran; (4) organisasi kurikulum, dan (5) evaluasi. Kelima
komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan.
Berikut ini adalah uraian mengenai tiap-tiap komponen kurikulum tersebut.
1. Komponen tujuan
Downloaded by Sri Rahayu (sr482676@gmail.com)
lOMoARcPSD|19983118
Menurut Ibrahim (2012, hlm. 8) Kurikulum merupakan suatu program yang
dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan itulah yang dijadikan
arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Berhasil atau
tidaknya program pengajaran di sekolah dapat diukur dari seberapa jauh dan
seberapa banyaknya pencapaian tujuan-tujuan tersebut.
Pratt (dalam Hernawan dan Andriyani, Tanpa Tahun, hlm.13) mengemukakan
tujuh kriteria yang harus dipenuhi dalam merumuskan tujuan kurikulum adalah
seperti berikut.
a. Tujuan kurikulum harus menunjukkan hasil belajar yang spesifik dan dapat
diamati.
b. Tujuan harus konsisten dengan tujuan kurikulum, artinya, tujuan-tujuan khusus
itu dapat mewujudkan dan sejalan dengan tujuan yang lebih umum.
c. Tujuan harus ditulis dengan tepat, bahasanya jelas sehingga dapat memberi
gambaran yang jelas bagi para pelaksana kurikulum.
Tujuan kurikulum biasanya terbagi atas tiga level atau tingkatan, yaitu sebagai
berikut.
a. Tujuan Jangka Panjang (aims)
Tujuan ini, menggambarkan tujuan hidup yang diharapkan serta didasarkan
pada nilai yang diambil dari filsafat. Tujuan ini tidak berhubungan langsung
dengan tujuan sekolah, melainkan sebagai target setelah anak didik menyelesaikan
sekolah, seperti; “bertanggung jawab sebagai warga negara”, “bangsa berbangsa
Indonesia” dan sebagainya.
b. Tujuan Jangka Menengah (goals)
Tujuan ini merujuk pada tujuan sekolah yang berdasarkan pada jenjangnya,
terdapat tujuan sekolah SD, SMP, SMA dan lain-lainnya.
c. Tujuan Jangka Pendek (objective)
Tujuan yang dikhususkan dicapai pada pembelajaran di kelas, misalnya; siswa
dapat mengerjakan perkalian dengan betul, siswa dapat mempraktekkan sholat,
dan sebagainya.
2. Komponen isi/materi
Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik
dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum
meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program tiap-tiap bidang
studi tersebut. Bidang-bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis, jenjang
maupun jalur pendidikan yang ada.
Downloaded by Sri Rahayu (sr482676@gmail.com)
lOMoARcPSD|19983118
Kriteria yang dapat dijadikan pertimbangan agar isi kurikulum efektif dan
efisien, antara lain sebagai berikut.
a. Kebermaknaan (signifikasi): kebermaknaan suatu isi/materi diukur dari
bagaimana esensi atau posisinya dalam kaitan dengan isi materi disiplin ilmu yang
lain. Konten kurikulum dalam wujud konsep dasar atau prinsip dasar mendapat
prioritas utama dibandingkan dengan konsep atau prinsip yang kurang
fundamental.
b. Manfaat atau kegunaan: adapun parameter kriteria kebermanfaatan isi adalah
seberapa jauh dukungan yang disumbangkan oleh isi/materi kurikulum bagi
operasionalisasi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.
c. Pengembangan manusia: kriteria pengembangan manusia mengarah pada nilai-
nilai demokratis, nilai sosial, atau pada pengembangan sosial. (Ibrahim, 2012,
hlm. 11)
Materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis, dalam bentuk fakta,
konsep, generalisasi, prinsip, prosedur, hukum, istilah, contoh/ilustrasi, definisi,
dan postulat. Zais (dalam Hernawan dan Andriyani, Tanpa Tahun, hlm.15)
menentukan empat kriteria dalam melakukan pemilihan isi/materi kurikulum,
yaitu sebagai berikut.
a. Isi kurikulum memiliki tingkat kebermaknaan yang tinggi (significance).
b. Isi kurikulum bernilai guna bagi kehidupan (utility).
c. Isi kurikulum sesuai dengan minat siswa (interest).
d. Isi kurikulum harus sesuai dengan perkembangan individu (human
development).
3. Komponen media (sarana dan prasarana)
Media merupakan sarana perantara dalam pengajaran. Media merupakan
perantara untuk menjabarkan isi kurikulum agar lebih mudah dipahami oleh
peserta didik. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pemakaian media dalam
pengajaran secara tepat terhadap pokok bahasan yang disajikan pada peserta didik
akan mempermudah peserta didik dalam menanggapi, memahami isi sajian guru
dalam pengajaran.
4. Komponen strategi pembelajaran
Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang
digunakan dalam pengajaran. Pembicaraan strategi pengajaran tergambar dari cara
yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, mengadakan penilaian,
pelaksanaan bimbingan dan mengatur kegiatan, baik yang secara umum berlaku
maupun yang bersifat khusus dalam pengajaran.
Downloaded by Sri Rahayu (sr482676@gmail.com)
lOMoARcPSD|19983118
Sudjana pada tahun 1988 (dalam Hernawan dan Andriyani, Tanpa Tahun, hlm.
17) mengemukakan bahwa strategi pembelajaran pada hakikatnya adalah tindakan
nyata dari guru dalam melaksanakan pembelajaran melalui cara tertentu yang
dinilai lebih efektif dan lebih efisien.
Menurut Undang-undang Nomor 20/2003, strategi pembelajaran di kelas
hendaknya dilakukan dengan cara olah hati, olah raga, olah rasa, dan olah otak.
Strategi pembelajaran yang demikian menyiratkan bahwa strategi yang digunakan
harus mampu melakukan pemberdayaan terhadap seluruh potensi siswa.
5. Komponen proses belajar mengajar
Keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar merupakan indikator
keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Kecenderungan proses pembelajaran adalah
terjadi perubahan paradigma dan mengajar ke pembelajaran. Perubahan yang
dimaksud ditandai dengan terjadi perubahan sebagai berikut.
a. Berpusat pada guru beralih ke pembelajaran yang berpusat pada siswa
b. Berorientasi disiplin (mapel tertentu) beralih ke pembelajaran yang integratif.
c. Berorientasi topik tertentu beralih ke pembelajaran berorientasi masalah.
d. Pembelajaran mengikuti alur tertentu (standardized) beralih ke pembelajaran
dengan alternatif-alternatif.
6. Komponen Kurikulum
Evaluasi kurikulum dimaksudkan sebagai evaluasi program, untuk mengakses
kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator
kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga
relevansi, efisiensi, kelaikan (feasibility) program. Salah satu komponen
kurikulum penting yang perlu dievaluasi adalah berkenaan dengan proses dan
hasil belajar siswa.
Sukmadinata (dalam Ibrahim, 2012 hlm. 14) mengemukakan tiga pendekatan
dalam evaluasi kurikulum, yaitu: (a) pendekatan penelitian (analisis komparatif);
(b) pendekatan obyektif; dan (c) pendekatan campuran multivariasi. Di samping
itu, terdapat beberapa model evaluasi kurikulum, diantaranya adalah Model CIPP
(Context, Input, Process, dan Product) yang diuraikain sebagai berikut:
a. Context; yaitu situasi atau latar belakang yang mempengaruhi jenis-jenis tujuan
dan strategi pendidikan yang akan dikembangkan dalam program yang
bersangkutan.
b. Input; bahan, peralatan, fasilitas yang disiapkan untuk keperluan pendidikan,
seperti: dokumen kurikulum, dan materi pembelajaran yang dikembangkan, staf
10
Downloaded by Sri Rahayu (sr482676@gmail.com)
lOMoARcPSD|19983118
pengajar, sarana, dan prasarana, media pendidikan yang digunakan dan
sebagainya.
c. Process; pelaksanaan nyata dari program pendidikan tersebut, meliputi :
pelaksanaan proses belajar mengajar, pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh
para pengajar, pengelolaan program, dan lain-lain.
d. Product; keseluruhan hasil yang dicapai oleh program pendidikan, mencakup:
jangka pendek dan jangka lebih panjang.
2.2.5 Hakikat Pembelajaran
Pembelajaran adalah proses menciptakan kondisi, scaffolding, dan
pemotivasian yang dilakukan oleh guru terhadap siswa agar mereka menjadi
mandiri dan menjadi peserta didik yang dapat melakukan pengaturan diri. Pada
pengertian tersebut berarti bahwa di dalam proses pembelajaran siswa harus
aktif,serta pada penyampaian ”informasi jadi” tidak mendapat penekanan. Pada
pembelajaran yang aktif ini siswa menemukan sendiri informasi dengan
merangkai pengalaman. Para ahli konstruktivis menyatakan bahwa pembelajaran
merupakan proses aktif merangkai pengalaman untuk membangun pemahaman
baru di dalam benaknya.
Dari pengertian tersebut, pembelajaran memiliki dua peran penting, yaitu
membangun pemahaman pada siswa melalui aktivitas mereka sendiri dan
sekaligus menerampilkan siswa melakukan proses belajar. Pendapat ini
didasarkan pada dua asumsi: yang pertama bahwa ilmu dan pengetahuan tidak
tetap melainkan selalu berubah,dan ilmu itu bersifat individual. Meskipun kepada
siswa diajarkan hal yang sama, setiap siswa akan memiliki pengetahuan dan
pemahaman serta interpretasi yang berbeda terhadap hal yang diajarkan tadi.
Asumsi yang kedua adalah bahwa yang paling penting seharusnya dipelajari oleh
siswa adalah Bagaimana belajar tentang belajar. Berdasarkan pada uraian di atas,
hakikat pembelajaran adalah menyiapkan siswa untuk belajar sepanjang hayat,
belajar secara mandiri dan menjadi pembelajaran yang mandiri. Seorang peseta
didik yang mandiri memiliki beberapa ciri (Arends, 2000): (a) mampu memilih
strategi yang cocok dalam belajar, (b) mampu memonitor proses belajarnya, dan
(c) melaksanakan proses belajarnya secara konsisten sampai apa yang
dipelajarinya tercapai.
Pembelajaran adalah Proses Menciptakan Kondisi
Pembelajaran berarti menciptakan kondisi agar siswa dapat belajar. Untuk itu,
pengalaman yang diberikan kepada siswa sebaiknya bersifat kontekstual, yaitu
sesuai dengan latar di mana proses pembelajaran itu terjadi. Kontekstual juga
berarti bahwa pembelajaran itu berlangsung alami dan siswa sendiri yang
mengalaminya.
11
Downloaded by Sri Rahayu (sr482676@gmail.com)
lOMoARcPSD|19983118
Penciptaan kondisi agar siswa bisa belajar, dilakukan oleh guru, misalnya
dengan (a) mengajukan pertanyaan yang menuntut siswa berpikir, (b)
memfasilitasi interaksi antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, (c)
menyediakan alat dan bahan yang digunakan siswa dalam proses belajarnya, (d)
menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, (d) membangun hubungan
guru siswa yang saling menghargai dan menghormati, (e) menggunakan metode
dan strategi pembelajaran yang menuntut siswa berperan aktif, dan sebagainya.
Pembelajaran adalah Scaffolding
Menurut Arends (2000) yang mengutip pendapat Vygotsky, scaffoldding
berarti bimbingan yang diberikan oleh orang yang lebih tahu (Guru/siswa yang
lain) kepada orang (siswa) yang kurang tahu yang mula-mula bimbingan itu
diberikan secara ketat, kemudian berangsur-angsur dikurangi dan pada akhirnya
tanggung jawab belajar diambil alih oleh siswa yang belajar Scaffolding sangat
membantu siswa belajar. Interaksi siswa yang satu dengan siswa yang lain
membantu siswa menyelesaikan masalah-masalah sulit yang tidak dapat
diselesaikan secara sendiri-sendiri. Dengan scaffolding kemampuan siswa
meningkat sedikit lebih tinggi dari pada kemampuan aktualnya.. Konsep
Scaffolding, jika dibimbing dengan benar siswa mampu mencapai kemampuan
potensialnya. Kemampuan potensial adalah kemampuan seseorang sedikit di atas
kemampuan aktualnya.
Pembelajaran adalah Pemotivasian
Motivasi amat penting artinya di dalam pembelajaran. Motivasi adalah
penyebab terjadinya tingkah laku pada organisme, atau alasan mengapa suatu
organisme itu melakukan aktivitas. Pada manusia, motivasi meliputi conscious
and unconscious drives. Teori-teori psikologi menyatakan bahwa tingkat utama
terjadinya motivasi adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan,
oksigen, dan air. Level kedua motivasi adalah memenuhi kebutuhan sosial seperti
kejuaraan dan prestasi. Level kebutuhan pertama harus dipenuhi terlebih dahulu
sebelum seseorang memenuhi kebutuhan kedua (sekunder). Ahli psikologi
Amerika Serikat Abraham Maslow membagi ada enam tingkatan hierarkis tingkah
laku manusia menurut teori ini, yang menentukan tingkah laku manusia. Maslow
meranking kebutuhan manusia sebagai berikut: (1) psikologis; (2) keamanan dan
keselamatan; (3) rasa cinta dan perasaan memiliki; (4) kompetensi, prestise, dan
percaya diri; (5) dorongan diri; dan (6) rasa ingin tahu dan kebutuhan untuk
memahami. Tidak ada satu pun teori motivasi yang dapat diterima secara
universal.
Salah satu strategi pemotivasian di dalam pembelajaran adalah strategi ARCS
yang diperkenalkan oleh Keller, M (1987). Strategi motivasi ini dikembangkan
sebagai jawaban atas suatu keinginan untuk menemukan cara efektif
12
Downloaded by Sri Rahayu (sr482676@gmail.com)
lOMoARcPSD|19983118
meningkatkan motivasi belajar siswa, dan untuk menemukan cara sistematis
mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan dengan motivasi belajar.
Keller (1987:2) mengungkapkan: “The ARCS Model is a method for
improving the motivational appeal of instructional materials. It has three
distinctive features. First, it contains four conceptual categories that subsume
many of the specific concepts and variables that characterize human motivation.
Second, it includes sets of strategies to use to enhance the motivational appeal of
instruction. And third, it incorporates a systematic design process, called
motivational design, that can be used effectively with traditional instructional
design model”
Menurut kutipan tersebut, motivasi model ARCS adalah suatu metode untuk
meningkatkan motivasi terhadap bahan pengajaran. Model ARCS mempunyai tiga
ciri khusus. Pertama, berisi empat kategori konseptual yang meliputi banyak
variabel dan konsep yang menandai motivasi manusia. Kedua, meliputi
seperangkat strategi untuk meningkatkan motivasi dalam pengajaran. Ketiga,
menyertakan suatu proses perancangan yang sistematis, disebut desain
motivasional (Keller, 1987), yang dapat digunakan secara efektif dengan model
desain pengajaran tradisional. Strategi pemotivasian model ARCS ini dapat
dimasukkan dalam rencana pelajaran yang dibuat oleh guru.
Motivasi model ARCS dilandasi oleh teori motivasi dan desain pembelajaran
yang dikembangkan oleh Keller (Kardi, 2002:1). Model ini didasarkan pada teori
expectancy-value (nilai yang diharapkan). Teori nilai yang diharapkan berasumsi
bahwa orang-orang termotivasi terlibat dalam suatu aktivitas jika ia merasa
dihubungkan kepada kepuasan akan kebutuhan pribadinya (aspek nilai), dan jika
ia merasa ada suatu pengharapan positif untuk berhasil (aspek pengharapan).
Selanjutnya, kedua aspek tersebut diperluas menjadi empat komponen strategi
motivasi yaitu attention (perhatian), relevance (relevansi), confidence (percaya
diri), dan satisfaction (kepuasan).
Dengan perkataan lain menurut teori itu, siswa akan termotivasi jika
pembelajaran itu menarik perhatian siswa, relevan dengan kebutuhannya serta
menyebabkan rasa percaya dirinya meningkat dan mereka menjadi puas. Oleh
karena itu, karena pembelajaran adalah proses pemotivasian, sudah selayaknyalah
di dalam pembelajaran mengakomodasi 4 aspek motivasi tersebut.
2.2.6 Prinsip Pembelajaran
Berdasarkan uraian mengenai pembelajaran di atas ada sejumlah prinsip
yang harus diperhatikan ketika mengelola kegiatan pembelajaran sebagai berikut
ini.
Pembelajaran Berpusat pada Siswa
13
Downloaded by Sri Rahayu (sr482676@gmail.com)
lOMoARcPSD|19983118
Pada dasarnya yang belajar adalah siswa. Oleh karena belajar bersifat aktif,
maka seharusnya yang aktif adalah siswa itu sendiri. Siswa aktif merangkai
pengalaman membangun pemahaman tentang apa yang dipelajarinya. Siswa
mengalami sendiri, menggunakan seluruh inderanya untuk melakukan eksplorasi
terhadap alam. Dengan perkataan di dalam melalui prinsip berpusat pada siswa,
pembelajaran sekaligus berlangsung melalui melakukan (learning by doing).
Kualitas keterlibatan siswa di dalam proses belajar sangat mempengaruhi
kualitas hasil belajar yang diperoleh siswa. Siswa yang belajar dengan melihat
tentu hasilnya lebih baik daripada hanya mendengar. Anda dapat membandingkan
manakah yang lebih utuh penerimaan Anda akan sebuah informasi bila Anda
hanya mendengar radio ataukah menonton televisi?
Pembelajaran Mengembangkan Transferable Skill
Pembelajaran adalah pemberdayaan siswa agar dia mampu belajar secara
mandiri. Oleh karena itu, pembelajaran harus mampu memberikan bekal
kecakapan yang dapat digunakan saat mereka belajar secara mandiri tadi.
Kecakapan yang dimaksud adalah transferable skill. Transferable skill juga
dikenal sebagai kecakapan kunci atau kecakapan inti, atau kecakapan umum, yaitu
suatu kecakapan yang dikembangkan di dalam suatu situasi tertentu, kemudian
dapat digunakan pada situasi yang lain. Kecakapan semacam itu meliputi
kemampuan bekerja di dalam tim, kemampuan memecahkan masalah,
kemampuan melakukan perencanaan, kemampuan berkomunikasi secara lisan dan
sebagainya.
Pembelajaran Mengembangkan Kreativitas
Kreativitas adalah sifat yang dimiliki oleh manusia yang kreatif dan inovatif.
Prinsip pembelajaran haruslah dilaksanakan untuk mendorong siswa menjadi
kreatif dan inovatif. Melalui pembelajaran isi pelajaran yang dirancang
sedemikian rupa mampu mengembangkan kreativitas. Dengan kreativitas yang
dimiliki siswa mampu belajar isi pelajaran lebih baik dan lebih luas. Bahkan
dengan kreativitas, siswa dapat menemukan hal-hal yang baru (inovatif).
Kemampuan kreatif merupakan bekal yang diperlukan di dalam persaingan.
Dengan perkataan lain, pembelajaran yang menganut prinsip mengembangkan
kreativitas berarti pembelajaran yang menyiapkan siswa untuk memiliki
kemampuan kompetitif dan komparatif.
Pembelajaran Mengembangkan Keingintahuan, Imajinasi, dan Fitrah
Siswa
Secara fitrah setiap orang yang lahir telah memiliki rasa ingin tahu. Dengan
rasa ingin tahunya orang melakukan eksplorasi terhadap apa yang dijumpainya,
14
Downloaded by Sri Rahayu (sr482676@gmail.com)
lOMoARcPSD|19983118
eksplorasi terhadap alam dan lingkungannya. Dari eksplorasi yang dilakukan
secara aktif itu terjadilah proses belajar. Seseorang memperoleh informasi dari
eksplorasinya dan menemukan jawaban terhadap pertanyaannya. Oleh karena itu,
pembelajaran yang dilakukan harus mampu mengembangkan fitrah rasa ingin
tahu ini.
Lebih dari pada itu, pembelajaran juga harus mengembangkan dan
menumbuhkan imajinasi. Tidak kurang dari Einstein mengatakan bahwa imajinasi
lebih penting dari pada pengetahuan. Kalau kita anggap bahwa pengetahuan
merupakan hasil belajar, maka imajinasi itu lebih penting dari hasil. Imajinasi
akan menginspirasi seseorang untuk belajar lebih daripada apa yang sudah
diketahuinya. Tanpa imajinasi dan rasa ingin tahu, pengembangan pengetahuan
menjadi berhenti. Jadi, untuk mengembangkan masyarakat yang selalu belajar
maka pembelajaran harus mampu mengembangkan rasa ingin tahu dan imajinasi
tersebut.
Mengembangkan Kemampuan Menggunakan Ilmu dan Teknologi
Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan amat pesat. Oleh karena itu,
siswa harus disiapkan untuk mampu memanfaatkan hasil-hasil perkembangan
ilmu dan teknologi tersebut untuk meningkatkan taraf hidupnya. Di dalam
kehidupan sekarang, setiap orang tidak dapat memisahkan diri dari teknologi.
Ketergantungan manusia terhadap hasil perkembangan teknologi sangat tinggi.
Kalau dahulu belum tentu setiap rumah memiliki pesawat telepon, pada saat
sekarang setiap orang memiliki telepon seluler bahkan lebih dari satu buah. Tanpa
kemampuan menggunakan hasil teknologi tentu kita akan mengalami kesulitan di
dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan sehari-hari.
Pembelajaran Menumbuhkan Kesadaran sebagai Warga Negara yang Baik
Pembelajaran harus mampu membangun manusia secara utuh sehingga
memiliki pengetahuan, keterampilan serta sikap termasuk moral dan budi pekerti.
Pembelajaran harus membuat siswa bangga sebagai bangsa Indonesia. Manusia
yang sadar sebagai bangsa Indonesia memiliki kesadaran terhadap aturan dan
norma kemasyarakatan. Pembelajaran yang mendidik harus mampu membuat
manusia Indonesia yang bermoral tinggi dan patuh terhadap aturan yang sudah
disepakati. Pembelajaran yang dilaksanakan harus membuat siswa sadar akan hak
dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.
2.2.7 Hubungan Kurikulum dan Pembelajaran Secara Umum
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kurikulum adalah apa yang akan
diajarkan, sedangkan pembelajaran (instruction) adalah bagaimana
menyampaikan apa yang akan diajarkan tersebut. Dengan perkataan lain,
15
Downloaded by Sri Rahayu (sr482676@gmail.com)
lOMoARcPSD|19983118
kurikulum adalah suatu program, tindakan belajar-mengajar, dan presentasi.
Dengan demikian peranan kurikulum di dalam system pendidikan amat penting
dan sangat strategis dan bahkan sangat tidak bisa dipisahkan dari suatu sistem
pendidika khususnya pendidikan formal.
Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua ssitem yang berbeda, namun
saling keterkaitan satu dengan yang lainnya secara terus-menerus dalam suatu
siklus. urikulum dapat mempengaruhi pembelajaran dan begitupun sebaliknya.
Artinya, pembelajaran tanpa kurikulum sebagai rencana tidak akan efektif, atau
bahkan bisa keluar dari tujuan yang telah dirumuskan, kurikulum tanpa
pembelajaran pun akan menghasilkan sesuatu yang tidak berguna.
Kurikulm sendiri berfungsi sebagai perencana tentang pengalaman belajar
apa yang akan diberikan kepada peserta didik. Pembelajaran sendiri merupakan
implementasi dari kurikulum yang telah dibuat dan untuk mencapai tujuan yang
sudah ditetapkan. Pembelajaran adalah upaya guru untuk merupah tingkah laku
siswa. Agar tingkah laku siswa dapat berubah, maka siswa diharuskan untuk
melakukan dan mengalami. Kurikulum berhubungan dengan isi/materi yang harus
dipelajari sedangkan pembelajaran berkaitan dengan cara mempelajarinya. Tanpa
kurikulum sebagai rencana, maka pembelajaran tidak akan efektif, demikian juga
sebaliknya tanpa pembelajaran sebagai implementasi sebuah rencana, maka
kurikulum tidak akan memiliki arti apa-apa. Kurikulum bertujuan sebagai arah,
pedoman, atau sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan proses pembelajaran
(belajar mengajar). Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pembelajaran
demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan.
16
Downloaded by Sri Rahayu (sr482676@gmail.com)
lOMoARcPSD|19983118
BAB III
PENUTUP
3.1 Simpulan
Kurikulum adalah serangkaian program, rencana, dan dokumen tertulis
yang dijadikan alat atau media untuk menyukseskan pembelajaran agar tujuan
pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Oleh karena itu keberhasilan dari suatu
kurikulum yang ingin dicapai sangat bergantung pada faktor kemampuan yang
dimiliki oleh seorang guru, artinya guru adalah orang yang bertanggung jawab
dalam upaya mewujudkan segala sesuatu yang telah tertuang dalam suatu
kurikulum resmi. Dapat dikatakan, guru berperan sebagai ujung tombak
implementasi kurikulum. Sedangkan pembelajaran adalah proses yang disengaja
dirancang untuk menciptakan terjadinya aktivitas belajar dalam diri peserta didik.
Jadi pembelajaran merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dan sengaja
dirancang untuk mendukung terjadinya proses belajar dari dalam diri peserta
didik. Dapat disimpulkan, hubungan keduanya adalah saling berkaitan satu sama
lain dan tidak dapat dipisahkan karena kurikulum bertugas sebagai perencana dan
pembelajaran bertugas sebagai pengaplikasi perencanaan tersebut dan terciptalah
suatu proses pendidikan yang utuh.
3.2 Saran
Materi mengenai hubungan kurikulum dengan pembelajaran secara umum
cakupannya sangat luas. Semoga pembaca tidak cepat merasa puas setelah
membaca makalah ini dan diharapkan untuk mencari informasi lebih atau
informasi tambahan dari sumber literasi lain. Saran dan masukan sangat berguna
untuk kemajuan pembuatan makalah kedepannya.
17
Downloaded by Sri Rahayu (sr482676@gmail.com)
lOMoARcPSD|19983118
DAFTAR PUSTAKA
Anjarsari, P. (2014). Literasi Sains dapam Kurikulum dan Pembelajaran IPA
SMP. Proaiding Semnas Pensa VI "Peran Literasi Sains"
Fujiawati, F.S. (2016). Pemahaman Konsep Kurikulum dan Pembelajaran dengan
Peta Konsep bagi Mahasiswa Pendidikan Seni. Jurnal Pendidikan dan
Kajian Seni, 1(1) hlm. 16-28
Hernawan, A. H. dan Andriyani, D. (Tanpa Tahun). Pengembangan Kurikulum
dan Pembelajaran Ekonomi dan Koperasi. Pustaka Universitas Terbuka.
[Online] Diakses dari: https://www.google.com/url?
sa=t&source=web&rct=j&url=http://reposito pada tanggal 11 Februari
2021
Hernawan, A.H. dan Susilana, R. (Tanpa Tahun). Konsep Dasar Kurikulum. File
UPI Edu. [Online] Diakses dari: https://www.google.com/url?
sa=t&source=web&rct=j&url=http://file.upi. pada tanggal 11 Februari
2021
Ibrahim, M. (2012). Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Biologi.
Pustaka Universitas Terbuka. [Online] Diakses dari :
http://repository.ut.ac.id/4283/1/PEBI4303-M1.pdf
pada tanggal 11 Februari 2021
Nasution, S. (1987). Pengembangan Kurikulum. Bandung : Alumni.
Nn. (1988). Pengembangan Kurikulum. Jakarta : P2LPTK.
Prasetyo, Z. (Tanpa Tahun). Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Fisika.
Pustaka Universitas Terbuka. [Online] Diakses dari :
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://reposito
pada tanggal 11 Februari 2021
Sulfemi, W.B. (2018). Manajemen Kurikulum di Sekolah. Bogor: Visi Nusantara
Maju.
Sukirman, D. dan Nugraha, A. (Tanpa Tahun). Kurikulum dan Bahan Belajar TK.
18
Downloaded by Sri Rahayu (sr482676@gmail.com)
lOMoARcPSD|19983118
Pustaka Universitas Terbuka. [Online] Diakses dari :
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://reposito
pada tanggal 11 Februari 2021
Syam, A.R. (2017). Posisi Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran dalam
Pendidikan. MUADDIB, 7 (1) hlm. 33-46.
Tim Pengembangan MKDK. (2002). Kurikulum dam Pembelajaran. Bandung :
Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan FIP UPI
Undang-undang No. 20 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Zaputri, N. S. (2019). Kurikulum. https://doi.org/10.31227/osf.io/8xfcw
19
Downloaded by Sri Rahayu (sr482676@gmail.com)
Anda mungkin juga menyukai
- Makalah Etika Profesi KeguruanDokumen14 halamanMakalah Etika Profesi KeguruanDion Damansari100% (1)
- Modul Pengembangan Pembelajaran PPKN SD Berbasis Project MethodDokumen231 halamanModul Pengembangan Pembelajaran PPKN SD Berbasis Project Methodputri nurrasidahBelum ada peringkat
- Laporan Mini Riset Manajemen Kelas-Kelompok 6Dokumen16 halamanLaporan Mini Riset Manajemen Kelas-Kelompok 6Inri Maranata GultomBelum ada peringkat
- Learning and Innovation Skills Dalam Pembelajaran Abad Ke-21 Belajar Dan Berkreasi BersamaDokumen12 halamanLearning and Innovation Skills Dalam Pembelajaran Abad Ke-21 Belajar Dan Berkreasi BersamaFirman Ma'rufBelum ada peringkat
- Analisis Observasi Kelas Dikaitkan Dengan Teori Pembelajaran Bahasa IndonesiaDokumen8 halamanAnalisis Observasi Kelas Dikaitkan Dengan Teori Pembelajaran Bahasa IndonesiaAlsa Sukma Pradani alsasukma.2019Belum ada peringkat
- Kel 4 Pembelajaran Tematik SDDokumen34 halamanKel 4 Pembelajaran Tematik SDZurotulBelum ada peringkat
- Landasan Pembelajaran Tematik Terpadu - DoDokumen20 halamanLandasan Pembelajaran Tematik Terpadu - DoAldinoBelum ada peringkat
- Hots Dan TpackDokumen11 halamanHots Dan TpackAyiidaFitriBelum ada peringkat
- Kurikulum Terpadu Pada Jenjang Pendidikan DasarDokumen17 halamanKurikulum Terpadu Pada Jenjang Pendidikan DasarRony WirachmanBelum ada peringkat
- 3C - Kelompok 1 - Makalah Problematika Pembelajaran SDDokumen17 halaman3C - Kelompok 1 - Makalah Problematika Pembelajaran SDZulfa Alfin NikmahBelum ada peringkat
- MAKALAH KELOMPOK 5-Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Bimbingan BelajarDokumen22 halamanMAKALAH KELOMPOK 5-Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Bimbingan BelajaraldizaBelum ada peringkat
- Model Jaring Laba-Laba Kelompok 2 B 2018Dokumen12 halamanModel Jaring Laba-Laba Kelompok 2 B 2018Nur HamidahBelum ada peringkat
- Modul Ajar MTK Unit 4 Kelas 4 Semester 1Dokumen24 halamanModul Ajar MTK Unit 4 Kelas 4 Semester 1ElizabethMellaBhektiBelum ada peringkat
- RPP - Tema 9 Subtema 1 Pembelajaran 3Dokumen19 halamanRPP - Tema 9 Subtema 1 Pembelajaran 3sintya pradnyawatiBelum ada peringkat
- Makalah STM 1Dokumen18 halamanMakalah STM 1Laily UsmaliaBelum ada peringkat
- Macam Penelitian (Bidang Garapan Dan Sifat) - 1Dokumen12 halamanMacam Penelitian (Bidang Garapan Dan Sifat) - 1DerhmenaBelum ada peringkat
- Makalah Kahoot SiakomDokumen13 halamanMakalah Kahoot Siakomhanrohana92Belum ada peringkat
- Kelas 3 Tema 3 Subtema 1Dokumen16 halamanKelas 3 Tema 3 Subtema 1Dio AlphardBelum ada peringkat
- Model Pembelajaran Team Games TournamentDokumen36 halamanModel Pembelajaran Team Games TournamentSulastina Thytin LatonroBelum ada peringkat
- KepramukaanDokumen14 halamanKepramukaanIka AyuBelum ada peringkat
- KELOMPOK 3 - PENDIDIKAN MULTIKULTURAL JRDokumen13 halamanKELOMPOK 3 - PENDIDIKAN MULTIKULTURAL JRInviolata ManaBelum ada peringkat
- RPP SPDPDokumen6 halamanRPP SPDPAZHARIBelum ada peringkat
- Makalah Pemb TematikDokumen15 halamanMakalah Pemb TematikYahrifBelum ada peringkat
- Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013Dokumen6 halamanRencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013Febriyanto TarnandoBelum ada peringkat
- Proposal PenelitianDokumen47 halamanProposal PenelitianLuthfita chairaniBelum ada peringkat
- Proposal Bahasa IndonesiaDokumen40 halamanProposal Bahasa IndonesiaAndii LaathiifaaBelum ada peringkat
- Makalah Keterampilan Pembuka Dan Penutup Pelajaran - KEL 1Dokumen15 halamanMakalah Keterampilan Pembuka Dan Penutup Pelajaran - KEL 1S KrtikaBelum ada peringkat
- Pentingnya Pengelolaan Manajemen Kelas Dalam Pembelajaran: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng MeulabohDokumen10 halamanPentingnya Pengelolaan Manajemen Kelas Dalam Pembelajaran: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng MeulabohTati RohBelum ada peringkat
- Makalah Inklusi Kel 5Dokumen20 halamanMakalah Inklusi Kel 5Eni SusilawatiBelum ada peringkat
- Tugas Model Networked-DewiSitiPatimahDokumen16 halamanTugas Model Networked-DewiSitiPatimahDewi SPBelum ada peringkat
- INOVASI DALAM BIDANG KETENAGAAN DAN HAMBATAN INOVASI (Al-Amin)Dokumen16 halamanINOVASI DALAM BIDANG KETENAGAAN DAN HAMBATAN INOVASI (Al-Amin)Muhammad SetiawanBelum ada peringkat
- Silabus Selalu Berhemat EnergiDokumen11 halamanSilabus Selalu Berhemat EnergimuthiahfnBelum ada peringkat
- Upaya Meningkatkan Kompetensi Belajar Siswa Pembelajaran PPKN Dengan Menggunakan Media ElektronikDokumen28 halamanUpaya Meningkatkan Kompetensi Belajar Siswa Pembelajaran PPKN Dengan Menggunakan Media ElektronikAlwi SiregarBelum ada peringkat
- Proposal Penelitian Emi YuskaDokumen33 halamanProposal Penelitian Emi YuskaOver LordBelum ada peringkat
- Ujian Akhir Semester Mahasiswa PGSD Matakuliah Manajemen Kelas SEMESTER GANJIL 2021/2022Dokumen2 halamanUjian Akhir Semester Mahasiswa PGSD Matakuliah Manajemen Kelas SEMESTER GANJIL 2021/2022elisa mawarBelum ada peringkat
- Makalah Kelompok 4 Model Pembelajaran TematikDokumen11 halamanMakalah Kelompok 4 Model Pembelajaran Tematikirma anggrainiBelum ada peringkat
- CiliataDokumen52 halamanCiliatawindragunawanBelum ada peringkat
- Ips Kelompok 10Dokumen23 halamanIps Kelompok 10Prin CessBelum ada peringkat
- Penilaian Berpikir GeometrisDokumen30 halamanPenilaian Berpikir GeometrisChika PrimatoyovaBelum ada peringkat
- MA - Bahasa Indonesia - Fase BDokumen10 halamanMA - Bahasa Indonesia - Fase BIcha LarasatiBelum ada peringkat
- Tari Caping - Susanti - 1401418334Dokumen11 halamanTari Caping - Susanti - 1401418334susanti shantyBelum ada peringkat
- Makalah Inovasi Pendidikan Kelompok 3 PGSD A 2019Dokumen22 halamanMakalah Inovasi Pendidikan Kelompok 3 PGSD A 2019Rizqie Dwiyanti AyuningtiasBelum ada peringkat
- LKPD BHS Indonesia Bab 2 Kelas 4Dokumen3 halamanLKPD BHS Indonesia Bab 2 Kelas 4ghitaBelum ada peringkat
- Model SharedDokumen8 halamanModel SharedSofia SetiaBelum ada peringkat
- Makalah Produk Pengembangan Kurikulum Sekolah Dasar Dan Rencana PembelajaranDokumen16 halamanMakalah Produk Pengembangan Kurikulum Sekolah Dasar Dan Rencana PembelajaranChoirulBelum ada peringkat
- Ips Kel 3 Makalah KoperasiDokumen24 halamanIps Kel 3 Makalah KoperasiNIDAUL HASANAH100% (1)
- Makalah Desain Kurikulum Kelompok 4Dokumen15 halamanMakalah Desain Kurikulum Kelompok 4Diajeng AvitaBelum ada peringkat
- 1 Konsep Dasar PKNDokumen15 halaman1 Konsep Dasar PKNRohis KurniawanBelum ada peringkat
- Konsep Dasar Belajar Dan PembelajranDokumen13 halamanKonsep Dasar Belajar Dan Pembelajranfirman ardiansyah bjsBelum ada peringkat
- Rangkuman Kapita Selekt1Dokumen16 halamanRangkuman Kapita Selekt1x-crusaidersBelum ada peringkat
- Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)Dokumen6 halamanRencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)Dheny ElkamparyBelum ada peringkat
- Makalah Tugas Guru Dan KlasifikasinyaDokumen12 halamanMakalah Tugas Guru Dan KlasifikasinyaMukti Sasi KironoBelum ada peringkat
- Makalah Media Pembelajaran Ipa Kel.8Dokumen35 halamanMakalah Media Pembelajaran Ipa Kel.8rosa widiastutiBelum ada peringkat
- Pendidikan Seni Musik SDDokumen4 halamanPendidikan Seni Musik SDCassandra PutriBelum ada peringkat
- 03 - Ilma - Inovasi Pendidikan Dalam Konteks Pendekatan Dan Metode PembelajaranDokumen13 halaman03 - Ilma - Inovasi Pendidikan Dalam Konteks Pendekatan Dan Metode PembelajaranIlma Amalia100% (1)
- Penerapan Pembelajaran Kooperatif Model TGT Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Terhadap Konsep FPB Dan KPK Di Kelas Vi SDDokumen20 halamanPenerapan Pembelajaran Kooperatif Model TGT Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Terhadap Konsep FPB Dan KPK Di Kelas Vi SDInokasay SimanjuntakBelum ada peringkat
- Makalah PIT Model Shared Dan IntegratedDokumen12 halamanMakalah PIT Model Shared Dan Integratedayu711Belum ada peringkat
- Pendidikan Budi Pekerti Dalam Proses Edukasi Dan TranformasiDokumen4 halamanPendidikan Budi Pekerti Dalam Proses Edukasi Dan TranformasiFajar KusumaBelum ada peringkat
- Kel.6 Hakikat, Dimensi Kurikulum, Peranan & FungsiDokumen15 halamanKel.6 Hakikat, Dimensi Kurikulum, Peranan & FungsiNajibahBelum ada peringkat
- Kel.6 Komponen KurikulumDokumen23 halamanKel.6 Komponen KurikulumNajibahBelum ada peringkat
- Makalah Kriteria Pmilihan Media PembelajaranDokumen12 halamanMakalah Kriteria Pmilihan Media PembelajaranSri RahayuBelum ada peringkat
- ARTIKEL DikonversiDokumen5 halamanARTIKEL DikonversiSri RahayuBelum ada peringkat
- Vanna Kelompok PKNDokumen15 halamanVanna Kelompok PKNSri RahayuBelum ada peringkat
- Makalah Perang Sikh&indianmunityDokumen17 halamanMakalah Perang Sikh&indianmunitySri RahayuBelum ada peringkat
- Bab 2Dokumen16 halamanBab 2Sri RahayuBelum ada peringkat
- Sejarah Asia SelatanDokumen78 halamanSejarah Asia SelatanSri RahayuBelum ada peringkat
- Kel.6 Makalah Salsa Wawan RezaDokumen12 halamanKel.6 Makalah Salsa Wawan RezaSri RahayuBelum ada peringkat