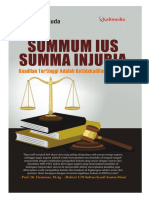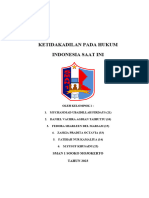Hakim, Putusan, Dan Tuah Buku
Diunggah oleh
roziq0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
10 tayangan2 halamanHak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
10 tayangan2 halamanHakim, Putusan, Dan Tuah Buku
Diunggah oleh
roziqHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 2
Hakim, Putusan, dan Tuah Buku
Oleh Achmad Fauzi
Wakil Ketua Pengadilan Agama Penajam, Kalimantan Timur
Artikel ini dimuat di Harian Jawa Pos tanggal 12 Juni 2016
Perbincangan seputar hakim dan mahkota putusannya sudah jamak didengar di ruang publik. Ketika
putusan hakim dianggap mencederai keadilan masyarakat pasti menjadi topik pembicaraan oleh banyak
kalangan. Namun, ada dimensi lain yang jarang diulas soal relasi hakim dengan buku. Aspek ini menarik
dicuatkan karena suatu alasan. Buku dan hakim ibarat kemelekatan ruh dengan jasad. Jika buku telah
ditahbiskan sebagai kebutuhan intelektual hakim, masyarakat akan menemukan kedalaman pertimbangan
putusan yang di dalamnya terhampar nilai keadilan, kebijaksanaan, kepastian dan kemanfaatan bagi
peradaban. Hakim tanpa (membaca) buku menyebabkan putusannya gersang dari ratio decidendi.
Istilah ratio decidendi dalam dunia peradilan acap dimaknai sebagai alasan hakim dalam menjatuhkan
putusan. Maksudnya, sebelum menjatuhkan putusan ada pertimbangan hakim yang mengandung
argumentasi dan nalar ilmiah yang berpijak kepada sebuah fakta. Pudjosewojo (1976) mendefinisikan ratio
decidendi sebagai faktor esensial yang harus dipenuhi karena menjadi ruh dari putusan hakim. Berarti
perumusan ratio decidendi itu penting sekali keberadaannya karena menentukan kualitas putusan hakim.
Basuki Rekso Wibowo (2011) bahkan menyatakan hakim dalam merumuskan putusannya hendaknya
jangan sekadar berkutat pada silogisme formal dan menafsir secara mekanis saja. Putusan hakim sebagai
pekerjaan intelektual membutuhkan analisis dan penafsiran secara komprehensif, argumentatif dan
dilengkapi penalaran hukum (legal reasoning) yang memadai sehingga tergambar tingkat kecermatan dan
intelektualitasnya.
Di negara-negara yang menganut sistem common law hakim terikat kepada putusan hakim yang terdahulu
(precedent). Sehingga ratio decidendi yang terdapat dalam putusan sifatnya mengikat untuk kasus serupa
yang terjadi di masa mendatang. Namun demikian, bukan berarti putusan hakim di negara yang menganut
tradisi civil law system seperti Indonesia tidak memerlukan ratio decidendi. Di negara manapun putusan
hakim idealnya mengandung argumentasi yang memadai dengan merujuk kepada prinsip hukum, moral,
filsafat, politik dan sosial sehingga masyarakat memahami secara komprehensif alasan hakim dalam
memutus perkara.
Urgensi ratio decidendi dalam putusan erat kaitannya dengan pemaknaan sosiologis asas res judicata pro
varitate habetur (setiap putusan hakim harus dianggap benar dan dihormati). Mustahil putusan hakim
sekonyong-konyong dihormati begitu saja sebagai sebuah kebenaran jika di dalamnya tidak memiliki
pertimbangan yang kokoh dan meyakinkan. Karena itu, supaya asas res judicata pro varitate
habetur sepenuhnya memiliki legitimasi kuat di tengah masyarakat, pertimbangan hakim yang berorientasi
kepada kemaslahatan masyarakat luas sebagai entitas dari suatu peradaban harus terus dipelihara di dalam
laboratorium nalarnya. Bukankah salah satu fungsi dari hukum sebagai instrumen untuk melindungi
kepentingan manusia? Sebagai pertanggungjawaban peradilan (judicial accountability) upaya yang
dilakukan untuk melindungi kepentingan manusia adalah hukum harus ditegakkan secara layak.
Dalam kasus pemerkosaan, misalnya, perlu memuat pertimbangan yang pengaruh hukumnya memiliki
daya jangkau melindungi segenap kaum perempuan secara keseluruhan yang notabene masih ditindas
kultur patriarki. Jadi perlindungannya bukan sebatas kasus perkasus saja. Sensitivitas putusan hakim harus
memiliki pantulan ke depan dan mampu mengobati dahaga keadilan kaum perempuan. Sehingga putusan
yang demikian dalam tataran fenomenologis nantinya akan berperan ganda: menyelesaikan kasus dan
mengubah peradaban.
Di era tahun 80-an almarhum Bismar Siregar seorang hakim yang dikenal berjiwa keadilan pernah
menghukum seorang laki-laki yang tebar janji akan menikahi gadis. Ceritanya ada seorang laki-laki yang
berpaling dari tanggungjawabnya setelah berhasil merenggut keperawanan pacarnya. Merasa keberatan
sang gadis mengajukan tuntutan ke pengadilan. Meski ketika itu tidak ada hukum yang mengatur tentang
perzinahan namun bagi Bismar hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya belum jelas
atau tidak ada. Bismar tetap memvonis laki-laki tersebut dengan delik penipuan. Bismar menafsirkan
vagina perempuan dengan unsur barang. Sehingga seorang pria yang ingkar janji menikahi pasangannya
namun telah digauli dapat dianggap telah menipu “barang” milik orang lain (Pasal 378 KUHP). Meski
ditentang oleh beberapa kalangan namun Bismar berhasil menjalankan tugasnya sebagai hakim dalam
mengisi kekosongan undang-undang. Dan yang lebih penting lagi, ia telah menorehkan sejarah
perlindungan terhadap kaum perempuan dari penindasan seksualitas kaum lak-laki melalui mahkota
putusannya.
Putusan hendaknya memenuhi dua unsur tujuan hukum, yakni etis (memberikan rasa keadilan kepada yang
berhak) dan utilities (memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat luas). Jika putusan hakim telah
memenuhi dua unsur tersebut maka dengan sendirinya asas res judicata pro varitate habetur di dalam
masyarakat menjadi realitas yang niscaya. Masyarakat tidak lagi karena terpaksa meyakini putusan hakim
sebagai sebuah kebenaran hukum yang wajib dihormati karena di dalamnya telah nyata terhampar nilai-
nilai keadilan yang diidamkan.
Pemaknaan independensi
Saat ini ramai di media sosial gunjingan atas putusan hakim yang oleh sebagian masyarakat dianggap
melukai rasa keadilan. Dalam gunjingan itu mengemuka suatu pertanyaan sejauh mana hakim berlindung
di balik jaminan independensinya dalam memutus perkara. Bagi masyarakat, menjadikan independensi
sekonyong-konyong sebagai tameng di tengah putusan yang tidak adil sungguh suatu sesat pikir dan
kesewenang-wenangan. Karena itu, jaminan independensi harus diimbangi dengan pertanggungjawaban
peradilan. Termasuk di dalamnya peningkatan integritas hakim dan transparansi yang dibangun di atas
prinsip harmonisasi antara tanggungjawab hukum (legal responsibility) dan tanggungjawab
kemasyarakatan (social responsibility). Pertanggungjawaban ini nantinya menjadi alasan bagi masyarakat
untuk tetap mempercayai dan menghormati putusan hakim.
Agar putusan hakim memiliki kedalaman pertimbangan dan dihormati masyarakat, maka mengasah
kepekaan intelektualitas dalam menafsir dan keterampilan menerapkan undang-undang perlu terus
dilakukan dalam kerja yudisial. Alat asahnya tentu adalah buku yang notabene menjadi nutrisi intelektual
bagi hakim. Kebutuhan hakim untuk membaca buku sama dengan kebutuhan asupan makanan untuk daya
tahan tubuh.
Pengembangan cakrawala melalui membaca buku menjadi keharusan profesi karena keilmuan hakim
dituntut selalu linear dengan dinamika perubahan masyarakat. Buku mengasah nalar hakim untuk
melakukan pembaruan hukum, menyimpangi aturan yang jumud (contra legem), dan melakukan judicial
activism sehingga tercipta suatu keadilan. Buku memiliki tuah mengubah pola pikir hakim agar tak sekadar
sebagai cerobong undang-undang (la bouche de la loi). Tapi senantiasa menggali, mengikuti, dan
memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dianggap tahu semua
hukum ( ius curia novit). Ketidaktahuan akan hukum mencelakakan (ignorantia iuris nocet).
PENGALAMAN KEPENULISAN
Aktif menulis di berbagai media nasional maupun lokal, seperti Harian Kompas, Jawa Pos, Koran Tempo,
Majalah Gatra, Media Indonesia, Suara Pembaruan, Jurnal Nasional, Koran Jakarta, Republika, Koran
Kontan, Pikiran Rakyat, Sinar Harapan, Suara Karya, Radar Surabaya, Sriwijaya Post, Banjarmasin Post,
Pontianak Post, Bangka Post, Tribun Kaltim, Kaltim Post, Balikpapan Pos, Lampung Post, Jurnal Millah,
Jurnal La Riba, Jurnal Al Mawarid, Mimbar Hukum, Varia Peradilan, Majalah Komisi Yudisial dan lain-
lain.
BUKU KARYA
Buku Pergulatan Hukum di Negeri Wani Piro (LeutikaPrio, Yogyakarta, 2012)
Anasir Kejahatan Peradilan (LeutikaPrio, Yogyakarta, 2013)
Korupsi dan Pengauatan Daulat Hukum (UII Press, Yogyakarta, 2015)
Anda mungkin juga menyukai
- Tugas Review Jurnal 1Dokumen4 halamanTugas Review Jurnal 1Herman Syah Tri100% (2)
- Legal Justice: The Construction of The Rule of Law by JudgesDokumen13 halamanLegal Justice: The Construction of The Rule of Law by Judgestoby anggaraBelum ada peringkat
- 2Dokumen166 halaman2Alfendry Yusuf54Belum ada peringkat
- 5374 13842 1 PBDokumen13 halaman5374 13842 1 PBAngga SetiawanBelum ada peringkat
- Makalah Hukum Dan Akses KeadilanDokumen19 halamanMakalah Hukum Dan Akses KeadilanGebz Ai BianBelum ada peringkat
- 9 Perbedaan Antara Mochtar Dan RoscoeDokumen8 halaman9 Perbedaan Antara Mochtar Dan RoscoeZiahBelum ada peringkat
- Heurmeuneutik HukumDokumen14 halamanHeurmeuneutik HukumnanangrBelum ada peringkat
- Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Medi PDFDokumen26 halamanPenyelesaian Perkara Pidana Melalui Medi PDFLina izzatul wardah Lina izzatul wardahBelum ada peringkat
- 01 Putu Angga Pramudia Putra 2014101067 3c Uas FilhumDokumen11 halaman01 Putu Angga Pramudia Putra 2014101067 3c Uas FilhumRYAN SAPUTRA NZ 2014101080Belum ada peringkat
- Legal OpinionDokumen4 halamanLegal OpinionikaBelum ada peringkat
- REVISI Sisitem Peradilan Kelompok 12 Friska Sofyan (Repaired)Dokumen17 halamanREVISI Sisitem Peradilan Kelompok 12 Friska Sofyan (Repaired)Friska SaputraBelum ada peringkat
- Musyawarah As Keadilan RestoratifDokumen20 halamanMusyawarah As Keadilan RestoratifKens Aigawa Koro-koroBelum ada peringkat
- Filsafat Hukum KHANIADokumen24 halamanFilsafat Hukum KHANIAKhania ReskyBelum ada peringkat
- Upaya Penegakan HukumDokumen10 halamanUpaya Penegakan HukumWahid Abdulrahman100% (1)
- Penerapan Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di IndonesiaDokumen8 halamanPenerapan Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di IndonesiaAnisa SamwipiBelum ada peringkat
- Keadilan Dalam Ilmu HukumDokumen11 halamanKeadilan Dalam Ilmu HukumBang NawiBelum ada peringkat
- Makalah Pengantar Hukum Indonesia Andi Aditya Tri HandaniDokumen22 halamanMakalah Pengantar Hukum Indonesia Andi Aditya Tri HandaniAHNAF ZACHARBelum ada peringkat
- Problematik Penegakan Hukum 6Dokumen18 halamanProblematik Penegakan Hukum 6adequaat satriaBelum ada peringkat
- Ketidakadilan SosioDokumen13 halamanKetidakadilan SosioUBEED FRDAUUSBelum ada peringkat
- File Makalah Mafia HukumDokumen49 halamanFile Makalah Mafia HukumNeycha_ciayouBelum ada peringkat
- Makalah Ilmu Hukum (Kesadaran Hukum Dan Masyarakat)Dokumen18 halamanMakalah Ilmu Hukum (Kesadaran Hukum Dan Masyarakat)Dian sri rahayuBelum ada peringkat
- Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan MasyarakatDokumen16 halamanTerciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan MasyarakatFitri AuliaBelum ada peringkat
- Tugas Sosiologi Hukum-Kesadaran Hukum Pada Masyarakat-Abdul Wafi-Abdul Wasik-Abdul HolilDokumen10 halamanTugas Sosiologi Hukum-Kesadaran Hukum Pada Masyarakat-Abdul Wafi-Abdul Wasik-Abdul Holilabdwafi260500Belum ada peringkat
- Critical Riview A. SarmadiDokumen7 halamanCritical Riview A. SarmadiBerdi SitorusBelum ada peringkat
- Makalah Paradigma Penemuan HukumDokumen19 halamanMakalah Paradigma Penemuan Hukumkislim.369Belum ada peringkat
- Bab I Pendahuluan: A. Latar BelakangDokumen32 halamanBab I Pendahuluan: A. Latar BelakangWindyBelum ada peringkat
- Makalah MononDokumen14 halamanMakalah MononHenoch DanielBelum ada peringkat
- Teori Hukum 2 - RAHBIAHDokumen20 halamanTeori Hukum 2 - RAHBIAHedi rosandiBelum ada peringkat
- Makalah Keadilan Hukum IwinDokumen11 halamanMakalah Keadilan Hukum IwintikailahudeBelum ada peringkat
- Apsarihadii, 940-950 Cahya PalsariDokumen11 halamanApsarihadii, 940-950 Cahya Palsarieginovia96Belum ada peringkat
- Pentingnya Mentaati HukumDokumen4 halamanPentingnya Mentaati HukumRivie Corleone100% (1)
- Mewujudkan Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim PerdataDokumen12 halamanMewujudkan Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Perdatanawawi84muhammad100% (1)
- Nusantara Vol1No22022 Sandhi - 1Dokumen18 halamanNusantara Vol1No22022 Sandhi - 1rinajulyantyBelum ada peringkat
- Sosialisasi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat: M. Mahrus AliDokumen14 halamanSosialisasi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat: M. Mahrus AliNana YogaBelum ada peringkat
- Penegakkan Hukum Yang Tidak Adil Sebab Rendahnya Moralitas Penegak HukumDokumen11 halamanPenegakkan Hukum Yang Tidak Adil Sebab Rendahnya Moralitas Penegak HukumZulfadli MarsukiBelum ada peringkat
- Fanita AditiaDokumen9 halamanFanita AditiaFanitadtBelum ada peringkat
- Makalah Hukum (KLMPK 5)Dokumen18 halamanMakalah Hukum (KLMPK 5)Nurul Ilmi AzimullahBelum ada peringkat
- JURNAL - Keadilan Dan Kejujuran Dalam Pelaksanaan Hukum Di IndonesiaDokumen10 halamanJURNAL - Keadilan Dan Kejujuran Dalam Pelaksanaan Hukum Di IndonesiapramestiaprilianingrumBelum ada peringkat
- Tugas 1 PTHI UTDokumen12 halamanTugas 1 PTHI UTMuhamad NurridwanBelum ada peringkat
- Makalah PPKNDokumen13 halamanMakalah PPKNHenry BagauBelum ada peringkat
- Upaya Membangun Kesadaran Hukum Di Kalangan Generasi MudaDokumen14 halamanUpaya Membangun Kesadaran Hukum Di Kalangan Generasi MudaAyunindia SofwatunnisaBelum ada peringkat
- BAB V BUDAYA HUKUM KLP SoshumDokumen28 halamanBAB V BUDAYA HUKUM KLP Soshumnadhia auliaBelum ada peringkat
- Penegakkan Hukum Progresif Di IndonesiaDokumen28 halamanPenegakkan Hukum Progresif Di IndonesiaMuhammad Fikkri Fakih NashuhaBelum ada peringkat
- Teks PidatoDokumen4 halamanTeks PidatoYasmin RahmadewiBelum ada peringkat
- ID Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Advokat Dalam Mendampingi Klien Dalam PerkaraDokumen22 halamanID Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Advokat Dalam Mendampingi Klien Dalam PerkaraShintia WindiastutiBelum ada peringkat
- Fungsi Hukum Dalam Era GlobalisasiDokumen22 halamanFungsi Hukum Dalam Era GlobalisasiQia Kian CemilanBelum ada peringkat
- Tugas 6 Kwn-Nabila Urningsih-A1a020166Dokumen12 halamanTugas 6 Kwn-Nabila Urningsih-A1a020166Lala NadilaxxBelum ada peringkat
- Uas Masalah Kemiskinan Dan Keadilan Sosial - Fintania Vellinda - 8051901011Dokumen9 halamanUas Masalah Kemiskinan Dan Keadilan Sosial - Fintania Vellinda - 8051901011fintania vellindaBelum ada peringkat
- 1499 2919 1 SMDokumen35 halaman1499 2919 1 SMJulius Tere NababanBelum ada peringkat
- Hukum Merupakan Bagian Yang Tidak Dapat Dipisahkan Dari MasyarakatDokumen5 halamanHukum Merupakan Bagian Yang Tidak Dapat Dipisahkan Dari MasyarakatDimass SoesenoBelum ada peringkat
- 1Dokumen14 halaman1ardiyanti arisBelum ada peringkat
- 1 PBDokumen9 halaman1 PBImam SafiiBelum ada peringkat
- Makalah PKN KehakimanDokumen14 halamanMakalah PKN KehakimanannisaBelum ada peringkat
- Teori Hukum Progresif Dari Satjipto RahardjoDokumen17 halamanTeori Hukum Progresif Dari Satjipto RahardjoadelinaBelum ada peringkat
- Filsafat Hukum - Aliran Hukum BebasDokumen5 halamanFilsafat Hukum - Aliran Hukum BebasTaufikBelum ada peringkat
- UAS HukmasDokumen8 halamanUAS HukmasWitty catBelum ada peringkat
- Makalah HAPTUNDokumen16 halamanMakalah HAPTUNZakky MuharrirBelum ada peringkat
- klp7 Legislasi Hukum IslamDokumen14 halamanklp7 Legislasi Hukum IslamNur AlmaBelum ada peringkat
- Putusan - 142 - PDT.P - 2023 - PN - PMK - 20231203162915 Akta KematianDokumen8 halamanPutusan - 142 - PDT.P - 2023 - PN - PMK - 20231203162915 Akta KematianroziqBelum ada peringkat
- 3574K PDT 2000Dokumen44 halaman3574K PDT 2000roziqBelum ada peringkat
- 111K Ag 1998Dokumen38 halaman111K Ag 1998roziqBelum ada peringkat
- 137K Ag 2007Dokumen10 halaman137K Ag 2007roziqBelum ada peringkat
- 3277K PDT 2000Dokumen13 halaman3277K PDT 2000roziqBelum ada peringkat
- Fajar Tugas 2Dokumen6 halamanFajar Tugas 2roziqBelum ada peringkat
- Fajar Tugas 1Dokumen4 halamanFajar Tugas 1roziqBelum ada peringkat
- Tugas 5Dokumen6 halamanTugas 5roziqBelum ada peringkat
- Tugas 4Dokumen5 halamanTugas 4roziqBelum ada peringkat
- Tugas 3Dokumen6 halamanTugas 3roziqBelum ada peringkat
- Tugas 2Dokumen5 halamanTugas 2roziqBelum ada peringkat
- Tugas 1Dokumen7 halamanTugas 1roziqBelum ada peringkat
- Tugas 4Dokumen7 halamanTugas 4roziqBelum ada peringkat
- SEMA Nomor 07 Tahun 2011Dokumen2 halamanSEMA Nomor 07 Tahun 2011roziqBelum ada peringkat
- Tugas 16Dokumen9 halamanTugas 16roziqBelum ada peringkat
- Tugas 15Dokumen9 halamanTugas 15roziqBelum ada peringkat
- Tugas 14Dokumen8 halamanTugas 14roziqBelum ada peringkat
- SEMA Nomor 02 Tahun 2011Dokumen4 halamanSEMA Nomor 02 Tahun 2011roziqBelum ada peringkat
- Sema Nomor 3 Tahun 2014Dokumen3 halamanSema Nomor 3 Tahun 2014roziqBelum ada peringkat
- Sema Nomor 09 Tahun 2010Dokumen1 halamanSema Nomor 09 Tahun 2010roziqBelum ada peringkat