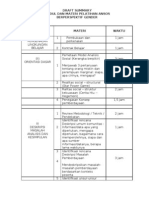Media Kapitalis
Diunggah oleh
rezafajriHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Media Kapitalis
Diunggah oleh
rezafajriHak Cipta:
Format Tersedia
Pers Indonesia dan Imperialisme Media Oleh IDI SUBANDY IBRAHIM TATKALA angin reformasi berhembus dengan kencang,
koridor demokrasi pun perlahan tetapi pasti mulai terkuak. Ruang publik yang sebelumnya penuh dengan jaring laba-laba kekuasaan yang setiap saat bisa membelenggu kebebasan pers, tiba-tiba sirna dan mengubah wajah pers Indonesia. Suara-suara alternatif yang sekian lama mengendap di balik bilik kebisuan publik tiba-tiba menyeruak, seperti burung yang lepas dari sangkarnya, terbang ke sana kemari. Dalam suatu kesempatan ilmuwan komunikasi dari Bandung, K.H. Jalaluddin Rakhmat dengan bagus pernah melukiskan bagaimana wajah pers Indonesia pascaSoeharto. Menurut Kang Jalal, seperti kuda lepas dari kandangnya, pers Indonesia kini meloncat-loncat, berlari tanpa arah dan mendengus-dengus ke mana saja. Kalau kita coba lukiskan perkembangan pers Indonesia akhir-akhir ini, paling tidak ada beberapa hal penting yang menunjukkan perubahan wajah pers pasca-Soeharto. Pertama, deregulasi media yang dilakukan rezim pasca-Soeharto, seperti ditandai dengan dipermudahnya memperoleh izin dan dicabutnya sistem SIUPP telah menyebabkan maraknya penerbitan pers. Sayangnya peningkatan kuantitas media, belum dengan sendirinya disertai oleh perbaikan kualitas jurnalismenya. Dalam dunia media cetak, kini mulai muncul tanda-tanda ada di antara media yang hanya menjual gosip alias desas desus dengan warna pemberitaan yang kental keberpihakan atau penyudutan kepada suatu tokoh/golongan/partai tertentu. Sementara media yang cenderung partisan terus melakukan "sensasionalisme bahasa" seperti tampak lewat pemilihan judul (headlines) yang bombastis atau desain cover yang norak, majalah dan tabloid hiburan justru melakukan "vulgarisasi" dan "erotisasi" informasi seks. Menyambut semakin banyaknya stasiun TV akhir-akhir ini kita layak prihatin dengan persoalan kualitas budaya TV kita. Karena tayangan TV tampaknya masih terjebak dengan logika keseragaman (homogenitas) mata acara. Kalau suatu stasiun dianggap berhasil menayangkan kuis, dangdut, telenovela Amerika Latin, serial romantika India atau serial laga Mandarin, dan adu jotos di tengah malam buta, maka stasiun yang lain pun bisa dipastikan akan mengikuti kemudian. Begitupun dengan sistem bintang di layar kaca. Kita akan melihat logika keseragaman ini. Acara-acara baik kuis, sinetron, atau pun drama komedi hanya berputar di sekitar artis yang itu-itu saja. Yang lebih menggelikan lagi, untuk acara kuis justru hanya sekadar gonta-ganti peran beberapa artis saja. Pada suatu acara, seorang artis yang kebetulan lagi laris menjadi pembawa acara, pada acara lain, dia sebagai pesertanya. Kedua, Maraknya apa yang disebut sebagai "media baru" (new media) di kalangan masyarakat kita akhir-akhir ini. Untuk menyebut di antaranya adalah Internet dan teknologi multimedia yang semakin canggih. Akses Internet membawa budaya baru dalam pemanfaatan waktu luang (leisure time). Dengan Internet, batas-batas ruang dan waktu telah hancur. Anak-anak begitu mudah mengakses jenis informasi apapun yang mereka inginkan. Baik yang bisa kita kategorikan informasi yang positif maupun yang negatif. Semakin banyak mereka menghabiskan waktu di depan komputer, semakin berkurang waktu mereka untuk melakukan aktivitas lain. Ketiga, Menguatnya fenomena apa yang dikenal sebagai tesis "imperialisme media".
Fenomena ini disebabkan globalisasi media transnasional dan invasi produk hiburan impor yang menguasai pasar media dalam negeri. Selain dominasi film-film Hollywood yang biasanya sarat seks dan kekerasan, akhir-akhir ini serial telenovela Amerika Latin dan serial laga Mandarin serta serial romantika India tampaknya masih mendominasi tayangan acara stasiun TV di Tanah Air. Untuk jenis sinetron atau film, misalnya, kini lebih dari 60% masih diisi oleh produk impor. Kalaupun kita melihat produk lokal, yang kita saksikan adalah wajah yang tidak jauh dengan gaya kemasan produk impor ini. Akhir-akhir ini, fenomena "imperialisme media" juga bisa kita lihat dari kian mengguritanya media yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Sebutlah salah satu contoh saja, "Cosmopolitan". Media jenis ini jelas menawarkan gaya hidup bagi wanita kelas menengah ke atas. Tidak hanya dari segi daya beli atau gaya hidupnya, tapi juga selera budayanya. Ia jelas menawarkan nilai tertentu bagi wanita muda. Dari rubrik dan selera budaya yang ditawarkannya, kita bisa memastikan corak kelas menengah macam apa yang membacanya. Membaca iklan spanduknya saja sudah cukup serem bagi ukuran rata-rata budaya kita. Ia menawarkan tip-tip panas dengan sensasi foto dan vulgarisasi bahasa yang menjanjikan kepuasan seks bagi pasangan dalam bercumbu, bercinta atau berhubungan badan. Tapi, jangan lupa, majalah dan tabloid dalam negeri pun sudah banyak yang melampaui ideologi selera seks yang ditawarkan "Cosmopolitan". Narkotisasi dan Masyarakat Jenuh MediaPara ahli menyebut budaya dan masyarakat mutakhir sebagai masyarakat yang jenuh dengan media (media saturated society). Masyarakat mutakhir adalah masyarakat yang dilimpahi dengan informasi berupa gambar, teks, bunyi, dan pesan-pesan visual. Masyarakat mutakhir adalah masyarakat yang dibanjiri informasi dan pesan-pesan komersial. Masyarakat yang jenuh media ternyata juga telah menyebabkan narkotisasi media bagi masyarakat. "Narkotisasi" (narcotization) adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan efek negatif atau efek menyimpang (dysfunction) dari media massa. Istilah ini sebenarnya berasal dari Paul F. Lazarsfeld dan Robert K. Merton. Dalam eseinya, "Mass Communication, Popular Taste and Organized Social Action" (1948), mereka menggunakan istilah "Narcotizing Dysfunction" untuk menyebut konsekuensi sosial dari media massa yang sering diabaikan. Media massa mereka pandang sebagai penyebab apatisme politik dan kelesuan massa. Media massa dipandang telah menyebabkan berkurangnya aktivitas dan keadaan "pingsan" (stupor) yang dialami khalayak. Seperti Lazarsfeld dan Merton yang melihat bahwa meningkatnya proporsi penggunaan waktu yang dicurahkan oleh orang Amerika saat itu terhadap media, alih-alih akan memberdayakan mereka, malah banjir informasi itu telah membius mereka ke dalam apatisme massa. Media massa dianggap sangat efektif untuk membuat orang kecanduan, karena media massa telah menjadi "narkotika sosial yang paling efisien dan paling bisa diterima". Informasi media pun mempunyai efek tak ubahnya seperti efek obat bius atau narkotika. Dengan media, orang merasa akan semakin banyak memiliki informasi tentang dunia dan peristiwa di sekitar mereka, tetapi pengetahuan itu sebenarnya hanyalah permukaan. Dengan informasi yang melimpah, orang seakan-akan bisa menjadi serbatahu segala hal, tapi sebenarnya mereka hanya dapat pengetahuan yang dangkal dan terpenggal-penggal. Orang mengonsumsi sebanyak-banyaknya informasi apapun bukan karena butuh, tapi karena memang itulah yang terus menerus disuguhkan kepada mereka.
Akhirnya, orang-orang menjadi kurang tercerahkan dan berkurang pula minatnya untuk terlibat dengan hal-hal yang bersifat aktual. Atau, dalam kata-kata Lazarsfeld dan Merton, "increasing dosages of mass communications may be inadvertently transforming the energies of men from active participation into passive knowledge." (Meningkatnya dosis komunikasi masa dengan kurang hati-hati bisa saja mengubah energi manusia dari partisipasi aktif menjadi pengetahuan pasif). Masyarakat yang jenuh media ternyata juga adalah masyarakat yang setiap hari dihibur dengan bujuk rayu iklan. Dalam hidup sehari-hari, nyaris mustahil kita terbebas dari kepungan iklan. Pesan-pesan komersial setiap saat menyapa, membujuk, menggoda, dan bahkan memaksa kita untuk tergiur dengan janji-janji dan mimpi-mimpi dalam masyarakat komoditas. Setiap hari TV membawa ratusan bahkan ribuan iklan ke dalam rumah tangga kita. Coba bandingkan apa yang kini tengah kita alami dengan data di AS yang memperlihatkan bahwa saat seseorang menyelesaikan sekolah lanjutan, ia telah menghabiskan waktu sekitar 11.000 jam di sekolah, 15.000 jam di depan TV, 10.500 jam mendengar musik pop, dan saat itu ia telah diterpa oleh jutaan iklan. Menurut American Medical Association, nonton TV merupakan aktivitas nomor satu setelah pulang sekolah bagi anak-anak usia sekolah. Mereka akan menyaksikan 14.000 referensi yang berhubungan dengan seks, 20.000 pesan-pesan komersial setiap tahun, dan menyaksikan lebih dari 200.000 tindakan kekerasan sebelum usia 18 tahun. Lebih dari itu, iklan tidak hanya menjual barang, tetapi juga menawarkan nilai, yakni nilai masyarakat konsumer. Nilai dan gaya hidup yang ditanamkannya adalah agar kita selalu menyukai kebaruan. Kita dipaksa untuk mengganti apa saja yang kita pakai/miliki dengan sesuatu yang baru. Sehingga kita tidak pernah bosan berbelanja dan terus mengonsumsi. Iklan menawarkan gaya hidup hedonis dan ideologi materialisme yang memuja penampilan dan pemilikan benda-benda. Jadilah kita terpenjara dalam budaya konsumtif. Selain itu, dalam masyarakat yang jenuh media ini kita merasakan kian longgarnya kriteria nilai dan norma yang dipegang teguh dalam masyarakat. Kini semakin banyak saja media (majalah dan tabloid) pop yang mengumbar informasi (gambar dan teks) seronok, yang mengeksploitasi sikap suka pamer tubuh sebagian artis atau calon artis dan bintang iklan yang memang dengan berbagai cara terus memburu popularitas di pentas kebudayaan pop. Tampaknya apapun akan mereka lakukan asal tetap laris di pasar pemberitaan media. Sementara menyaksikan tayangan beberapa sinetron dan iklan di beberapa stasiun TV swasta akhir-akhir ini sudah tampak kian berani dan terang-terangannya mereka mempertontonkan adegan ciuman di layar kaca. Penanaman nilai dan budaya serba-boleh (permisif) seperti ini begitu halus dan menawan serta dibungkus dengan cantik lewat trik iklan atau intrik dalam sinetron. Karena ditayangkan secara berulang-ulang teranglah akan berakibat bagi perilaku dan gaya hidup anak muda. Baik cara berpakaian maupun bergaul jelas kini kian longgar di sebagian anak muda, termasuk di kalangan mahasiswa. Kalau menyimak tema-tema sinetron akhir-akhir ini, ada kecenderungan kuat mulai berkembangnya ideologi kelas menengah yang hanya menjual mimpi dan budaya penyelesaian gampangan (budaya instan) atas persoalan kompleks dalam dunia rumah tangga. Misalnya, dalam beberapa sinetron tampak ditanamkannya nilai yang secara halus mulai membenarkan hubungan yang longgar antara suami istri. Tema-tema diseputar perselingkuhan dan penghianatan terhadap kesetiaan pasangan yang kini mulai
menjadi isu trendi di kalangan kelas menengah kota adalah nilai baru yang ikut ditanamkan secara gampangan oleh para pembuat sinetron. Memang ada juga sinetron-sinetron yang bertema religius, dengan memperlihatkan figur-figur serba berkerudung dan suka sembahyang, tapi tetap tanpa meninggalkan kebiasaan suka diskotek dan hura-huranya. Sayangnya tema-tema ini belum menyentuh substansi, masih terjebak dalam formalisme agama atau masih menunjukkan kesalehan simbolik. Membentuk Masyarakat Melek MediaBagaimanakah kita menghadapi efek jangka panjang dari narkotisasi media yang menyebabkan masyarakat terus terbius dengan pesan-pesan media? Jawabannya, tak lain jalan satu-satunya yang harus mulai ditempuh adalah menggalakkan apa yang dikenal sebagai Program "Media Literacy" atau Pendidikan Melek Media. Pendidikan Melek Media mempunyai arti penting, karena ia meletakkan titik berat perhatian kepada upaya pemberdayaan khalayak media. Memang selama ini masyarakat sudah mempercayakannya kepada lembaga seperti Media Watch atau Ombudsman untuk mewakili khalayak sebagai lembaga pemantau atau pengawas kinerja media. Akan tetapi, pertanyaan yang muncul kemudian; Apakah lembaga seperti ini bisa sepenuhnya netral? Apakah lembaga ini juga mandiri secara finansial dan terbebas dari vested interest? Bagaimana pula kalau lembaga pemantau itu berada di bawah payung sebuah media atau ia didirikan oleh orang pers? Apakah mereka akan bersikap kritis dan terbuka kalau sudah menyangkut kepentingan media mereka sendiri? Seberapa jauh kepentingan khalayak media akan diperjuangkannya? Lantas, apakah lembaga ini benar-benar akan tulus dalam memberdayakan mayoritas pembaca/pemirsa? Singkat kata, kemungkinan sebuah lembaga sehebat Media Watch atau Ombudsman untuk tidak netral jelas bisa saja terjadi. Inilah yang membedakannya dengan program Media Literacy. Pendidikan Melek Media mengembalikan titik berat upaya pemberdayaan sepenuhnya pada diri si khalayak media (pembaca, pendengar, dan pemirsa). Orangorang yang Melek Media (Media Literate People) jelas akan senantiasa jeli dan kritis terhadap media, terutama manakala kepercayaan terhadap lembaga-lembaga pemantau atau pengawas yang diragukan kenetralan dan independensinya sudah mulai merosot. Sebagai sebuah istilah "Media Literacy" jelas tergolong masih bayi di Indonesia. Untuk tidak mengatakan belum cukup dikenal luas di kalangan praktisi dan teoretisi media dan komunikasi di Tanah Air. Sejauh pengamatan saya, sampai saat tulisan ini dirampungkan, belum satu pun tulisan yang dihasilkan baik berupa buku, jurnal, atau artikel di media massa yang membahas topik Media Literacy. Selain memang literaturnya masih langka dalam studi media dan komunikasi di Tanah Air, juga tampaknya orang masih lebih terpesona dengan lembaga seperti Media Watch atau Ombudsman. Sesungguhnya istilah "Media Literacy" memang masih tergolong baru bahkan untuk negara maju seperti Jepang dan AS. Kini para teoretisi dan praktisi Media Literacy di AS juga mengakui dan menyesali keterlambatan mereka dalam merespons dampak media yang begitu luar biasa terhadap anak muda di AS. Sementara di Jepang, baru pada 1990-an akhir, pentingnya program Media Literacy mulai dibicarakan secara serius. Namun, di Kanada, Australia, dan Inggris yang bisa dikatakan sebagai pelopor Media Literacy, gerakan ini sudah cukup memasyarakat sejak sekitar 1980-an. Di Kanada, misalnya, ia digunakan untuk memberikan pandangan kritis terhadap dampak media Amerika. Ia digunakan sebagai bagian dari gerakan menentang imperialisme
budaya Amerika yang disebarkan lewat media seperti CNN dan industri film Hollywood. Di Inggris, Pendidikan Media (Media Education) sudah diajarkan sejak tingkat SMP dan pendidikan Media Literacy sudah begitu terprogram dengan baik, sehingga sudah menjadi semacam gerakan budaya. Mengapa pendidikan Melek Media amat penting kita sosialisasikan di kalangan masyarakat Indonesia? Jawabannya jelas, karena dengan begitu banyaknya media, kini masyarakat telah dilimpahi beraneka informasi. Informasi yang bagai banjir itu membuat kapasitas untuk berrefleksi dan berimajinasi kian menumpul. Kini semakin sulit membedakan mana informasi yang penting dan sampah atau bahkan mana yang benar dan menyesatkan juga sudah sama-sama dikemas dengan cantik. Karena itu, Jean Baudrillard sudah mengingatkan dalam eseinya, "The Implosion of Meaning in the Media" (1983): "Kita berada dalam sebuah alam semesta yang begitu banyak informasi, tetapi begitu hampa makna." Program Media Literacy dimaksudkan mendidik khalayak supaya senantiasa bersikap kritis terhadap informasi apapun yang ia terima dari media. Media Literacy juga menanamkan pentingnya kebiasaan untuk bersikap selektif atas setiap mata acara yang akan ditonton atau setiap berita yang akan dibaca. Sebab orang-orang yang kurang terdidik dalam memahami medialah yang lebih rentan bagi bentuk-bentuk manipulasi yang halus. Karena itu, ada yang memandang Media Literacy sebagai suatu keahlian (skill) atau kesanggupan (ability). Seperti dari Aspen Institute's National Leadership Conference on Media Literacy (1992), sebuah yayasan yang didedikasikan untuk memperbaiki kehidupan sosial dan budaya warga AS, yang memandang Media Literacy sebagai "Kesanggupan seorang warga negara untuk mengakses, menganalisis, dan memproduksi informasi untuk tujuan-tujuan tertentu." Dalam konteks yang lebih praktis, Art Silverblatt, ilmuwan media yang cukup terkemuka, dalam bukunya Media Literacy: Keys to Interpreting Media Messages (1999), mengidentifikasi paling tidak lima unsur yang fundamental dalam Pendidikan Media Literacy. Yakni, kesadaran terhadap dampak media; Pemahaman terhadap proses komunikasi massa; Strategi untuk menganalisis dan mendiskusikan pesan-pesan media; Pemahaman terhadap isi media sebagai teks yang menyajikan pandangan bagi kehidupan dan budaya kita; dan Kesanggupan untuk menikmati, memahami, dan mengapresiasi isi media. Selain itu, ada juga yang menganggap bahwa program Media Literacy sebagai perjuangan untuk meraih kekuasaan (struggle for power). Di sini pendidikan Melek Media memiliki agenda yang jelas untuk melakukan perlawanan terhadap hidden agenda atau agenda terselubung yang ada di balik media. Media Literacy diyakini sebagai jalan menuju ke arah pembebasan masyarakat dari manipulasi pikiran atau propaganda media. "Media literacy harus membantu orang-orang membangun kesadaran dan pemahaman yang diperlukan untuk membuat keputusan-keputusan yang bebas dari pengaruh luar. Pendidikan ini adalah keharusan, jika kita ingin memiliki sebuah masyarakat demokrasi yang sejati," demikian ujar Chris Rosequist dalam "How Media Literacy can Make You Millions!" (1995). Walhasil, Pendidikan Media atau Media Literacy sudah seyogianya masuk kurikulum pendidikan nasional, menjadi mata ajar di tingkat menengah hingga perguruan tinggi. Kampanye Media Literacy juga harus mulai kita sosialisasikan di rumah, di sekolah, di tempat ibadah, dan di lembaga-lembaga sosial umumnya.
Inilah sebenarnya muara dari Pendidikan Media Literacy: Pemberdayaan khalayak berarti pula pemberdayaan media! *** Penulis adalah pengamat dan peneliti media dan kebudayaan pop; Redaktur "Jurnal Komunikasi", diterbitkan ISKI (Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia).
Anda mungkin juga menyukai
- Media Dan Pornografi + PassDokumen60 halamanMedia Dan Pornografi + PassRaka AmadaBelum ada peringkat
- Berbagai Wawancara Dari Sebuah Dekade Yang Singkat: Mengenal Lebih Dekat Tokoh-Tokoh Terkemuka Abad Ke-20 Dari Dunia Politik, Budaya, Dan SeniDari EverandBerbagai Wawancara Dari Sebuah Dekade Yang Singkat: Mengenal Lebih Dekat Tokoh-Tokoh Terkemuka Abad Ke-20 Dari Dunia Politik, Budaya, Dan SeniBelum ada peringkat
- POP BUDAYADokumen7 halamanPOP BUDAYADandung CornettoBelum ada peringkat
- Keragaman Budaya Dan Gaya Hidup Luar RuanganDokumen37 halamanKeragaman Budaya Dan Gaya Hidup Luar Ruanganfeby darsjeb96Belum ada peringkat
- Apa Itu Budaya MassaDokumen5 halamanApa Itu Budaya MassaEven TamaelaBelum ada peringkat
- A. Masalah-Masalah SosialDokumen60 halamanA. Masalah-Masalah SosialHen DyBelum ada peringkat
- Pertemuan 12 - Budaya PopulerDokumen12 halamanPertemuan 12 - Budaya PopulerRIFKY ANAN KURNIAWANBelum ada peringkat
- Pidato Kebudayaan Taufiq IsmailDokumen8 halamanPidato Kebudayaan Taufiq IsmailevisanBelum ada peringkat
- Budaya Baru PDFDokumen42 halamanBudaya Baru PDFLiko Pah TuafBelum ada peringkat
- Teori Cultural ImperialismDokumen4 halamanTeori Cultural ImperialismВера ОткровенияBelum ada peringkat
- Makalah Ilmu NegaraDokumen9 halamanMakalah Ilmu NegaraFbyBelum ada peringkat
- Makalah Kajian Budaya Popular Kel.2Dokumen17 halamanMakalah Kajian Budaya Popular Kel.2Randy SaputraBelum ada peringkat
- 187-311-1-SMDokumen21 halaman187-311-1-SMmichelle mabelleBelum ada peringkat
- Review7 Muhammad Khadafi BudayaPopulerDokumen4 halamanReview7 Muhammad Khadafi BudayaPopulerMuhammad KhadafiBelum ada peringkat
- Menjual Si MiskinDokumen13 halamanMenjual Si MiskinAgam Imam PratamaBelum ada peringkat
- Tugas Teori Komunikasi 2Dokumen4 halamanTugas Teori Komunikasi 2zeckomanisBelum ada peringkat
- BUDAYA MASSA DAN POSMODERNISME DALAM IKLAN TVDokumen15 halamanBUDAYA MASSA DAN POSMODERNISME DALAM IKLAN TVSeany SukmawatiBelum ada peringkat
- Budaya Populer ModernDokumen8 halamanBudaya Populer ModernNadiah AprilianiBelum ada peringkat
- Fungsi dan Disfungsi Komunikasi MassaDokumen6 halamanFungsi dan Disfungsi Komunikasi Massaayu_roisterBelum ada peringkat
- Menjamurnya Budaya Populer Dan Lunturnya Budaya LokalDokumen8 halamanMenjamurnya Budaya Populer Dan Lunturnya Budaya Lokalrakayekajata14Belum ada peringkat
- Peranan Media CetakDokumen5 halamanPeranan Media CetakStpmTutorialClassBelum ada peringkat
- Kesan Program Realiti Terhadap MasyarakatDokumen18 halamanKesan Program Realiti Terhadap MasyarakatSyarifah SakinahBelum ada peringkat
- JURNALISTIK DAN DEHUMANISASI AlfinaDokumen13 halamanJURNALISTIK DAN DEHUMANISASI AlfinaFinza OlsopBelum ada peringkat
- MEDIA DAN BUDAYA POPDokumen12 halamanMEDIA DAN BUDAYA POPTeddyBelum ada peringkat
- 492 952 1 SMDokumen16 halaman492 952 1 SMDwi PutraBelum ada peringkat
- BudayaPopulerDokumen13 halamanBudayaPopulerErnesto Che GujizUyeahBelum ada peringkat
- Analisa Representasi Gaya Hidup Pada Iklan Ditinjau Dari Sisi Etika PeriklananDokumen8 halamanAnalisa Representasi Gaya Hidup Pada Iklan Ditinjau Dari Sisi Etika Periklananshania ekaBelum ada peringkat
- Review5 - Muhammad Khadafi - Industri BudayaDokumen2 halamanReview5 - Muhammad Khadafi - Industri BudayaMuhammad KhadafiBelum ada peringkat
- UTS-Muhammad Fatih Ainul Haqqi-204103010024-KommasDokumen12 halamanUTS-Muhammad Fatih Ainul Haqqi-204103010024-Kommasanjasbadas693Belum ada peringkat
- Budaya PopulerDokumen8 halamanBudaya PopulerTinon Al-audiyBelum ada peringkat
- Kajian Media Dan Budaya PopulerDokumen12 halamanKajian Media Dan Budaya PopulerQuest 14Belum ada peringkat
- Konsumerisme Sebagai Dampak Dari GlobalDokumen16 halamanKonsumerisme Sebagai Dampak Dari GlobalGustixyanBelum ada peringkat
- Riset Iklan IIDokumen11 halamanRiset Iklan IIAhmad FauzanBelum ada peringkat
- Posmodernitas, Degradasi Komunikasi, Dan HOAX: Wahyu Budi NugrohoDokumen4 halamanPosmodernitas, Degradasi Komunikasi, Dan HOAX: Wahyu Budi NugrohonanangsusetyoBelum ada peringkat
- Budaya Populer Unk WEB StkipDokumen3 halamanBudaya Populer Unk WEB Stkip281067Belum ada peringkat
- Counter To Public SphereDokumen14 halamanCounter To Public SphereCicilia SinabaribaBelum ada peringkat
- Artikel KerenDokumen10 halamanArtikel KerenRiyani RenzBelum ada peringkat
- Kebebasan Pers Di IndonesiaDokumen2 halamanKebebasan Pers Di IndonesiaMulyadiRaBelum ada peringkat
- Kelompok 3 - Komunikasi Publik Dan MassaDokumen7 halamanKelompok 3 - Komunikasi Publik Dan MassaRozanatu Dzil IzzatiBelum ada peringkat
- Mengkaji Dampak Mistisme MediaDokumen5 halamanMengkaji Dampak Mistisme MediaYulia AngeloBelum ada peringkat
- Post TruthDokumen15 halamanPost TruthsetiawanBelum ada peringkat
- Peran MediaDokumen7 halamanPeran MediaIvana Octaria PanjaitanBelum ada peringkat
- Makalah Hukum PersDokumen11 halamanMakalah Hukum PersNabillah SariekideBelum ada peringkat
- 20.96.2246 SOSIOLOGI KOMUNIKASIDokumen4 halaman20.96.2246 SOSIOLOGI KOMUNIKASIYanti beraniBelum ada peringkat
- Budaya Massa di Media TelevisiDokumen4 halamanBudaya Massa di Media TelevisiNezabrellBelum ada peringkat
- TEORI ANTROPOLOGI 2Dokumen8 halamanTEORI ANTROPOLOGI 2firlizzle manizzleBelum ada peringkat
- Mewaspadai Televisi - Neil PostmanDokumen13 halamanMewaspadai Televisi - Neil PostmanFaris Muhammad HanifBelum ada peringkat
- Folk, High, Pop, MassDokumen8 halamanFolk, High, Pop, MassRumpoko adiBelum ada peringkat
- Mimetisme Dan Etika KomunikasiDokumen4 halamanMimetisme Dan Etika Komunikasiaina al firdausBelum ada peringkat
- MAKALAH PANCASILA KELOMPOK 3-WPS OfficeDokumen11 halamanMAKALAH PANCASILA KELOMPOK 3-WPS OfficeTnaaBelum ada peringkat
- Kesan Media Cetak Dan Media Elektronik Dalam Kehidupan Sekarang Dan Dunia Sejagat Sangat Mencabar. Bahaskan Kenyataan Ini.Dokumen14 halamanKesan Media Cetak Dan Media Elektronik Dalam Kehidupan Sekarang Dan Dunia Sejagat Sangat Mencabar. Bahaskan Kenyataan Ini.silvia li92% (12)
- Gar A PanDokumen6 halamanGar A PanKenzhi Kharisma Hemas AgityaBelum ada peringkat
- Studi Kasus Komunikasi MassaDokumen5 halamanStudi Kasus Komunikasi MassaAlia MulinaBelum ada peringkat
- Fenomena Tayangan Infotainment Di IndonesiaDokumen3 halamanFenomena Tayangan Infotainment Di IndonesiaUman SchatziBelum ada peringkat
- Media Dan Isu Kontemporer - Penggunaan Dan ImplikasinyaDokumen18 halamanMedia Dan Isu Kontemporer - Penggunaan Dan Implikasinyaizzaku100% (1)
- Aktivisme Sosial Remaja Antara Budaya Dan KritisDokumen9 halamanAktivisme Sosial Remaja Antara Budaya Dan KritisFarhadShameelBelum ada peringkat
- Modul Pertemuan Xiii Komunikasi MassaDokumen9 halamanModul Pertemuan Xiii Komunikasi MassaAlfi NikmatinBelum ada peringkat
- INFOTAINMENTDokumen24 halamanINFOTAINMENTruthlintangBelum ada peringkat
- Gereja dan Tantangan MediaDokumen6 halamanGereja dan Tantangan MediaYusuf MauyesBelum ada peringkat
- Kritik Yang Berwawasan Humor Dalam KarikaturDokumen2 halamanKritik Yang Berwawasan Humor Dalam KarikaturrezafajriBelum ada peringkat
- Menuangkan Ide Melalui TulisanDokumen2 halamanMenuangkan Ide Melalui TulisanrezafajriBelum ada peringkat
- Menuangkan Ide Dalam Tulisan (HIMA)Dokumen1 halamanMenuangkan Ide Dalam Tulisan (HIMA)rezafajriBelum ada peringkat
- Model AnsosDokumen4 halamanModel AnsosrezafajriBelum ada peringkat
- Penulisan Resensi BukuDokumen1 halamanPenulisan Resensi BukurezafajriBelum ada peringkat
- Teknik Ar TikelDokumen3 halamanTeknik Ar TikelrezafajriBelum ada peringkat
- Undang Undang PersDokumen7 halamanUndang Undang PersrezafajriBelum ada peringkat
- Pers Baru Dapat Dipidana Apabila Ada Unsur KengajaanDokumen2 halamanPers Baru Dapat Dipidana Apabila Ada Unsur KengajaanrezafajriBelum ada peringkat
- Plot Dan StilistikaDokumen11 halamanPlot Dan StilistikarezafajriBelum ada peringkat
- Teknik Investigasi 2Dokumen2 halamanTeknik Investigasi 2rezafajriBelum ada peringkat
- Peran Dan Eksistensi NovelisDokumen5 halamanPeran Dan Eksistensi NovelisrezafajriBelum ada peringkat
- Media Massa Dari Politik Ke BisnisDokumen2 halamanMedia Massa Dari Politik Ke BisnisrezafajriBelum ada peringkat
- Ringkasan Modul CTDokumen2 halamanRingkasan Modul CTrezafajriBelum ada peringkat
- Menumpulkan Pers Atau MemberdayakannyaDokumen4 halamanMenumpulkan Pers Atau MemberdayakannyarezafajriBelum ada peringkat
- Sket Proposal Materi Penulisan NovelDokumen4 halamanSket Proposal Materi Penulisan NovelrezafajriBelum ada peringkat
- Sekilas IndikatorDokumen5 halamanSekilas IndikatorrezafajriBelum ada peringkat
- TOR Penulisan NovelDokumen1 halamanTOR Penulisan NovelrezafajriBelum ada peringkat
- Nurdin Kalim - Sekadar PengantarDokumen5 halamanNurdin Kalim - Sekadar PengantarrezafajriBelum ada peringkat
- Memahami Alur Liputan InvestigatifDokumen6 halamanMemahami Alur Liputan InvestigatifrezafajriBelum ada peringkat
- Sepuluh Jurus Menulis Berita EkonomiDokumen15 halamanSepuluh Jurus Menulis Berita EkonomirezafajriBelum ada peringkat
- Teknik WawancaraDokumen4 halamanTeknik WawancararezafajriBelum ada peringkat
- JurnalDokumen9 halamanJurnalrezafajriBelum ada peringkat
- Silabus Diskusi Milis Litbangnas PPMI 2004Dokumen3 halamanSilabus Diskusi Milis Litbangnas PPMI 2004rezafajriBelum ada peringkat
- Missing Link Gerakan Mahasiswa IndonesiaDokumen5 halamanMissing Link Gerakan Mahasiswa IndonesiarezafajriBelum ada peringkat
- Jurnalisme EmpatiDokumen3 halamanJurnalisme EmpatirezafajriBelum ada peringkat
- Nyanyian Cinta Persma Dan PergerakanDokumen4 halamanNyanyian Cinta Persma Dan PergerakanrezafajriBelum ada peringkat
- Mahasiswa Dan Tradisi BerpikirDokumen3 halamanMahasiswa Dan Tradisi BerpikirrezafajriBelum ada peringkat
- Persma Dan Dinamika PendidikanDokumen2 halamanPersma Dan Dinamika PendidikanrezafajriBelum ada peringkat
- Pers Mahasiswa Bukan Journalism SchoolDokumen4 halamanPers Mahasiswa Bukan Journalism SchoolrezafajriBelum ada peringkat